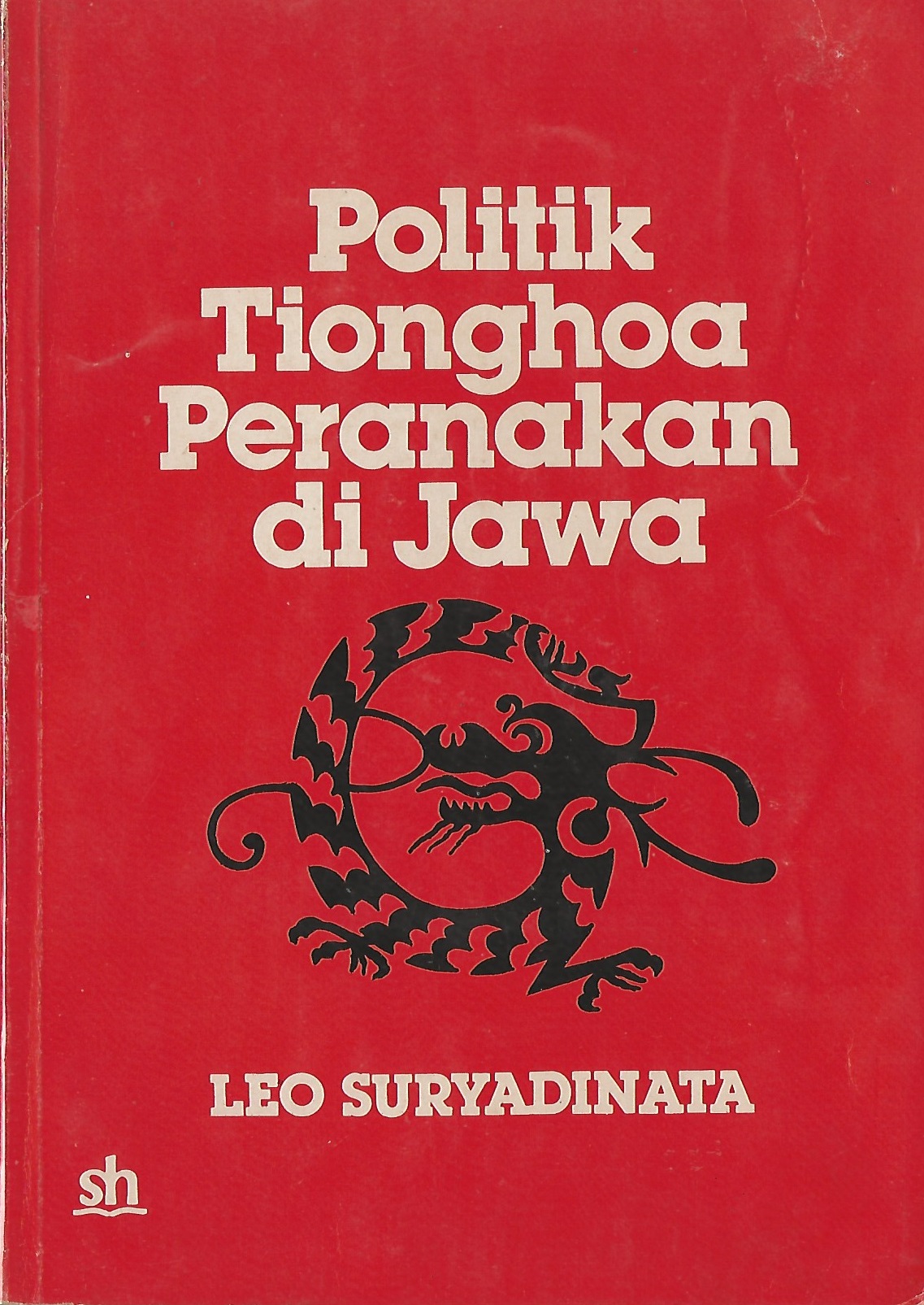Judul: Politik Tionghoa Peranakan di Jawa
Penulis: Leo Suryadinata
Tahun Terbit: 1986
Penerbit: Sinar Harapan
Tebal: 195
ISBN:
Saya lahir dan dibersarkan di era Orde Baru sebagai anak Tionghoa Peranakan di pedesaan Jawa. Sebagai orang yang lahir dimasa awal orde baru (saya kahir tahun 1965) dan sampai dengan selesai S-1 hidup dalam alam Orde Baru, maka mau tidak mau cara berperilaku dan berpikir saya sangat dipengaruhi oleh Orde Baru. Saya tidak bisa sama sekali bahasa Mandarin dan bahasa Hokian. Saya tidak mengenal sama-sekali budaya Tiongkok. Saya lebih tahu tentang barongan daripada barongsay. Saya lebih kenal wayang kulit daripada kisah Sik Jin Kwie. Saya lebih paham langgam Jawa daripada musik-musik Mandarin.
Dalam hal identifikasi diri, saat remaja dan awal masa muda, saya pernah ingin menghilangkan sisi ke-Tionghoa-an saya. Saya pernah benci menjadi orang Tionghoa Peranakan. Kebencian saya ini disebabkan karena saya di-bully karena dianggap “ora Jowo” oleh teman-teman etnis Jawa dan dianggap tidak Jawa karena kulit saya yang lebih terang dan mata saya yang lebih sipit. Saya juga dibuly oleh saudara-saudara dan teman-teman saya dari etnis Tionghoa yang berasal dari kota karena tidak paham ceban, gocing. Saya sangat fasih berbahasa Jawa halus, saya paham dan menerapkan unggah-ungguh. Jadi kurang Jawa bagaimana saya? Saya punya marga, saya punya nama Tionghoa. Jadi kurang Tiongha apa saya ini?
Setelah berhasil memaafkan diri, saya menulis buku yang menggambarkan bagaimana saya mencari jati diri. Sejak itu saya lebih rajin mencari tahu pergumulan orang Tionghoa Peranakan dalam upayanya menjadi Indonesia. Saya berteman dengan orang-orang yang lebih dulu menggumuli topik ini. Saya membaca buku-buku yang berhubungan dengan Tionghoa dan Tiongkok.
Salah satu buku yang memberi pengetahuan mendalam tentang posisi politik orang Tionghoa di masa sebelum kemerdekaan adalah buku “Politik Orang Tionghoa Peranakan di Jawa” karya Leo Suryadinata. Buku ini menggambarkan bagaimana dinamika orang-orang Tionghoa di era politik etis, post politik etis sampai dengan menjelang kedatangan Jepang ke Hindia Belanda. Tulisan yang disusun secara kronologis dan diakhiri dengan sebuah bab kesimpulan, membuat saya sadar bahwa pergumulan orang Tionghoa Peranakan di Indonesia tidak hanya saya alami sendiri. Para pendahulu juga mengalami pergumulan, yang ternyata lebih hebat dari yang saya alami.
Dari buku ini saya belajar bahwa kecenderungan politik orang Tionghoa di Hindia Belanda tidaklah tunggal. Orang Tionghoa mempunyai kecondongan politik yang berbeda-beda. Ada yang menerima menjadi kawula (warga) Hindia Belanda, ada yang mengidentifikasi diri sebagai warga Tiongkok, namun ada pula yang pro kemerdekaan Indonesia. Sikap politik warga Tionghoa juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik saat itu. Tiga kondisi politik yang sangat berpengaruh kepada sikap politik warga Tionghoa adalah: (1) Bangkitnya nasionalisme China, (2) Politik kewargaan Belanda (Undang-Undang Kawula Negara Belanda), dan (3) Bangkitnya rasa nasionalisme orang Indonesia.
Populasi orang Tionghoa di Hindia Belanda didominasi oleh peranakan; yaitu warga Tionghoa yang lahir dan tinggal sudah beberapa generasi di Nusantara. Orang peranakan ini pada umumnya berdarah campuran, karena pada awalnya hanya kaum lelaki yang migrasi dari Tiongkok ke Nusantara. Setelah populasinya cukup besar, mereka kawin-mawin di antara mereka dan membentuk etnis Peranakan Tionghoa. Etnis peranakan ini membaur dengan baik dengan suku-suku dimana mereka tinggal. Namun, pada abad 20, imigram baru dari Tiongkok cukup banyak.
Etnis Peranakan mengalami pemisahan status kewargaan di Hindia Belanda. Belanda memisahkan warganya menjadi tiga golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (termasuk Peranakan Tionghoa) dan Bumi Putera. Peraturan-peraturan turunan dari peraturan tentang warga Hindia Belanda ini sangat menggencet Peranakan Tionghoa. Sumber ekonomi mereka dibatasi dan mereka dilarang memiliki tanah.
Kondisi ini membuat para pemimpin Peranakan Tionghoa menoleh kepada Nasionalisme Tiongkok yang sedang tumbuh. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari warga Tiongkok. Mereka mendirikan perhimpunan China Raya seperti Tiong Ha Hwee Koan (THHK). Berdirinya organisasi ini disusul dengan munculnya surat khabar- surat khabar yang didirikan oleh orang Peranakan. Selain dari organisasi dan press, Peranakan Tionghoa di Jawa juga mendirikan kamar dagang (Siang Hwee). Kemudian disusun berdirinya sekolah-sekolah berbahasa China. Gerakan-gerakan China Raya ini kebanyakan dipimpin oleh para imigran baru (Totok).
Pada saat yang sama, anak-anak dari Tionghoa Peranakan yang mendapat pendidikan barat mulai berperan. Perubahan peraturan kewargaan, dimana beberapa peraturan melonggar, membuat para pemimpin dari etnis peranakan yang mendapat pendidikan Barat ini lebih memihak kepada Belanda daripada kepada Tiongkok.
Ketika dilakukan konperensi di Semarang, kelompok yang memihak kepada Belanda ini mendapatkan kemenangan. Kan Hok Hoei (H.H Kan) terpilih menjadi pemimpin orang Tionghoa di Hindia Belanda. Orientasi H.H Kan adalah setuju untuk mengirim wakil Tionghoa dalam Volksraad (parlemen). Namun kelompok yang tidak menyetujui orang Tionghoa menjadi bagian dari Hindia Belanda menolak gagasan orang Tionghoa punya wakil di Volksraad. Melalui Koran Sin Po, mereka menyatakan bahwa orang Tionghoa adalah orang asing, sehingga mereka tidak perlu mengirimkan wakilnya di parlemen. Sampai dengan tahun 1928, dua aliran inilah yang mendominasi aliran politik orang Tionghoa di Hindia Belanda.
Saat kesadaran kebangsaan Indonesia semakin menguat, kelompok orang Tionghoa yang menganggap dirinya adalah bagian dari kaula Hindia Belanda ada yang mengidentifikasi dirinya menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Mereka mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) di Surabaya. Aliran ketiga ini secara terus terang mendukung bumi putera yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Jika dilihat dari wilayah dimana tiga aliran ini berada, bisa dikatakan bahwa Batavia pada umumnya didominasi oleh orang-orang Tionghoa yang pro Belanda. Semarang pada umumnya mendukung aliran politik Tionghoa sebagai orang asing dan tidak perlu terlibat dalam pertikaian politik Hindia Belanda. Sedangkan Surabaya pada umumnya mendukung orang Tionghoa menjadi bagian dari Indonesia yang sedang diperjuangkan.
Buku karya Leo Suryadinata ini juga dilengkapi dengan tokoh-tokoh Tionghoa dan organisasi-organisasi serta penerbitan-penerbitan dari ketiga aliran tersebut. Buku ini juga memuat polemik yang muncul di koran-koran terbitan orang-orang Tionghoa Peranakan. Penjelasan tentang tokoh, organisasi dan penerbitan dari masing-masing aliran, serta polemik keputusan politik yang dimuat di surat-surat khabar saat itu memudahkan saya untuk memahami dinamika politik orang Tionghoa Peranakan di Jawa.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.