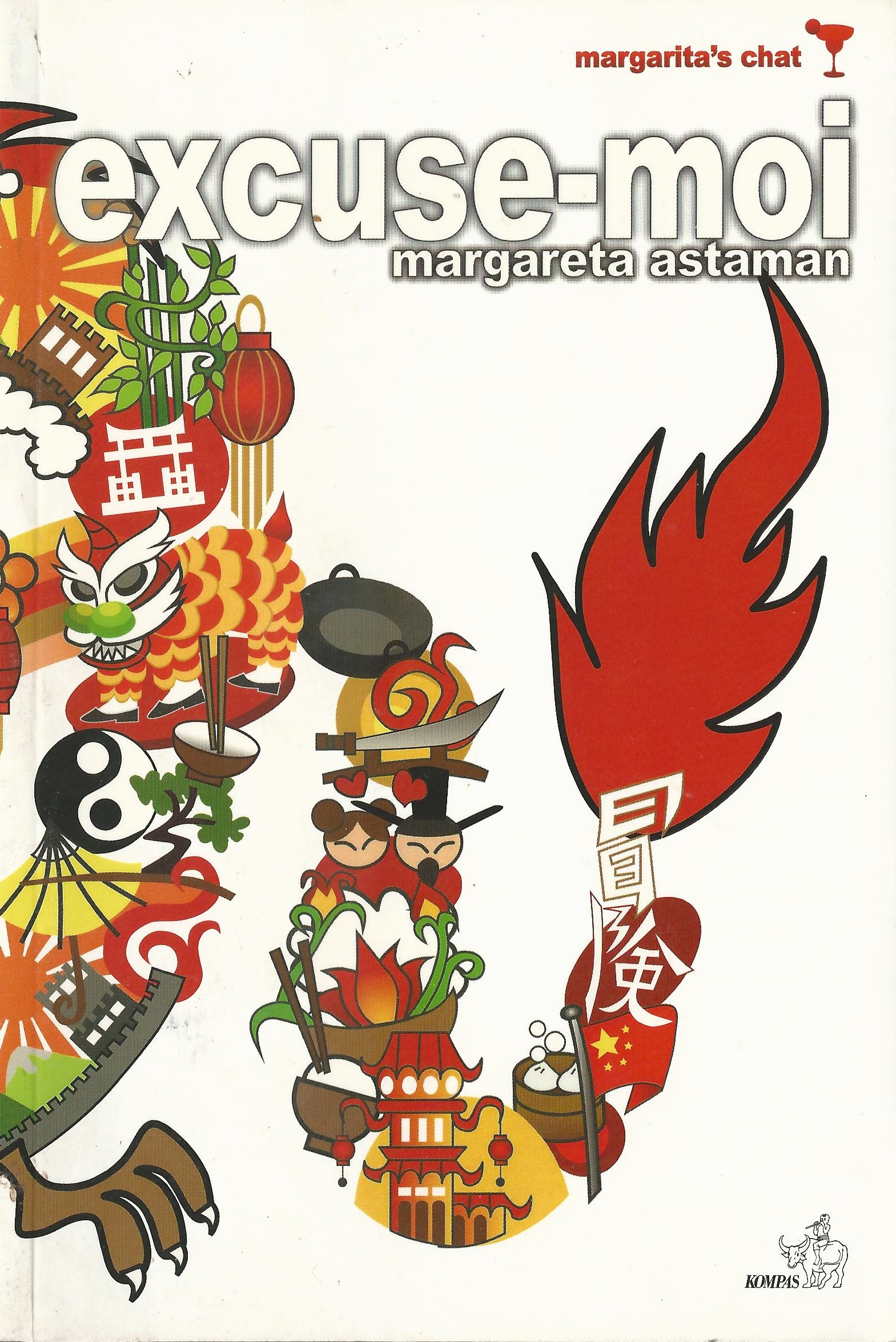Judul: Excuse-Moi
Penulis: Margareta Astaman
Tahun Terbit: 2011
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Tebal: vi + 138
ISBN: 978-979-709-545-1
Perjumpaan antarbudaya senantiasa menimbulkan dinamika yang luar biasa. Kadang-kadang perjumpaan tersebut menimbulkan saling memperkaya, kadang bisa berdampingan tanpa saling mengusik, namun kadang juga menimbulkan prahara. Kadang terjadi yang satu menindas yang lain. Pihak yang ditindas pun seringkali memilih diam dan mengalah. Sikap mengalah ini adalah cara untuk menghindari konflik terbuka. Semacam bentuk pertahanan secara pasif.
Namun demikian kadang pihak yang ditindas berani mengungkapkan perasaannya sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi bisa dibicarakan dan dicarikan pemecahan yang tidak persekutif. Bukankah salah satu langkah dalam teori pemecahan konflik, kedua belah yang berkonflik harus secara terbuka dan presisi menyampaikan posisinya?
Namun mengungkapkan perasaan secara apa adanya sering menimbulkan gelitik, bahkan gemeretak gigi. Itulah sebabnya, sebelum gelitik membuat marah, sang penulis buku ini sudah meminta maaf sejak di halaman judul. Exuce-moi. Permisi. Ijinkan daku. Memang Margareta (Margie) mengungkapkan perasaannya tentang perjumpaan budaya dengan apa adanya. Ia tak berupaya menutupi apa yang dipikirkan. Ia tidak melunakkan pikirannya dengan pembelokan bahasa. Apa adanya. Makanya ia meminta permisi sebelum para pembaca menelan apa yang disajikannya.
Persoalan yang ditampilkan Margie adalah persoalan keturunan Tionghoa di Indonesia. Saya senang Margie menggunakan kata Cina daripada Tionghoa yang dianggap lebih sopan. Sebab konon kata Cina adalah kata yang memuat kebencian dan ketidaksukaan. Namun bukankan memang banyak pihak yang masih tidak suka dan bahkan benci kepada keturunan Tionghoa di Indonesia? Jadi untuk apa kata diganti jika kondisi memang belum terganti?
Lagi pula penggantian kata terbukti tidak efektif untuk menunjukkan status. Mari kita belajar tentang kata “pembantu.” Dulu kita memakai kata babu, yang artinya adalah ibu. Namun babu banyak dianggap sebagai budak yang bisa dieksploitasi tenaganya sesuka majikannya. Maka orang Betawi menggantinya dengan kata “bibi” dan keluarga Jawa menggantinya dengan kata “mbak.” Namun, apakah nasibnya berbuah? Tidak!
Selanjutnya, supaya statusnya lebih bergengsi, kata “pembantu” dianugerahkan kepadanya. Nasibnya pun tidak berubah. Bahkan para Pembantu Rektor, kini mengganti namanya menjadi Wakil Rektor, supaya derajatnya tidak merosot bersama dengan kata “pembantu” yang disematkan kepada babu. Kini, upaya untuk mengangkat status sang babu terus diupayakan dengan menyebutnya sebagai “asisten rumah tangga.” Apakah nasibnya akan berubah. Tentu saja tidak. Demikian pun dengan penggantian istilah Cino menjadi Cina, menjadi China, menjadi Tionghoa.
Sebagai orang yang dilahirkan di Negara Republik Indonesia yang menganut aliran ius sole dalam penentuan kewarga-negaraan, Margie mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Indonesia. Sebab ia memang lahir di Indonesia. Bahkan beberapa generasi yang menjadi nenek moyang Margie lahir di Indonesia. Jika pun Indonesia menganut ius sanguinis, Margie bisa membuktikan bahwa darah Betawi ada mengalir di tubuhnya.
Namun apa daya Ke-Indonesia-an Margie dipermasalahkan oleh banyak pihak. Matanya yang sipit, kulitnya yang kuning dan rambutnya yang lurus, selurus run-way bandar udara menyebabkan ia harus mengakui bahwa ia adalah Cina. Apalagi saat ia kuliah di Singapore, dimana identitas seseorang dikelompokkan berdasarkan ras (tetapi tidak rasis), membuat Margie semakin yakin bahwa ia adalah Cina. Namun ia adalah 100% Indonesia. Makanya ketika mereka bilang Margie Cina, ia dengan santai menjawab: “Emang!” Bukankah mempunyai darah Cina berarti pandai berhitung dan jago berdagang?
Apakah Margie benar-benar Indonesia? Tentu. Ia berpikir dan berbicara dalam Bahasa Indonesia. Ia tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokian. Ia suka makanan Indonesia. Saat belajar di Singapore ia memilih Indonesia sebagai identitasnya. Bahkan dalam sebuah diskusi tentang apakah ia akan membela negaranya saat Indonesia diserang musuh, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia akan mengangkat senjata mempertahankan tanah air. Jadi, kurang Indonesia bagaimana?
Nah upaya apa lagi yang harus dilakukan oleh Margie dan manusia sejenisnya untuk menjadi Indonesia? Apakah harus operasi plastik untuk melebarkan kelopak mata, melakukan tato alis, memasang implant pada payudara supaya tidak lagi setipis telor ceplok, berpakaian tertutup, berjalan lebih pelan untuk mempraktikkan budaya alon-alon waton kelakon – lambat-lambat asat telat? Atau lebih banyak makan sawo daripada makan nanas supaya kulitnya semakin sawo matang? Atau mengikuti agama mayoritas? Tidak! Margie memilih untuk menjadi Indonesia dengan cara mengamalkan Pancasila. Nah masalahnya, bagaimana kalau orang-orang yang merasa lebih Indonesia itu sendiri malah tidak mengamalkan Pancasila?
Di bagian kedua buku ini Margie membahas tentang perbedaan ras yang tidak rasis. Perbedaan ras tentu tak bisa dihindari. Sebab memang demikianlah dunia menjadikan kita. Menggunakan ras sebagai sebuah alat identifikasi tidaklah salah. Yang salah adalah saat kita menggunakan pembedaan ras untuk tujuan kebencian. Stereotiping adalah alamiah. Semua kita melakukan stereotyping kepada liyan. Namun menggunakan stereotyping untuk menggerakkan kebencian adalah salah.
Dalam buku ini Margie juga membahas pernikahan antaragama. Ia tidak setuju dengan pernikahan antaragama, tetapi ia menghargai mereka yang berani melakukannya. Margie menyampaikan pendapatnya tentang betapa sulitnya hidup bersama dengan orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda. Pernikahan bagi Margie adalah mengajak pasangan untuk berbagi masalah pribadi, tradisi, budaya dan kepercayaan. Tidak mudah untuk menyatukan hal-hal tersebut.
Kesimpulan saya sebagai orang yang juga beretnis Cina setelah membaca buku ini adalah bahwa kita harus berani mengakui siapa diri kita apa adanya. Kita tidak perlu merasa bahwa kita adalah pendatang dan bukan 100% Indonesia. Sebagai orang Cina yang 100% Indonesia, kita harus berupaya membangun negeri tempat kita berada.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.