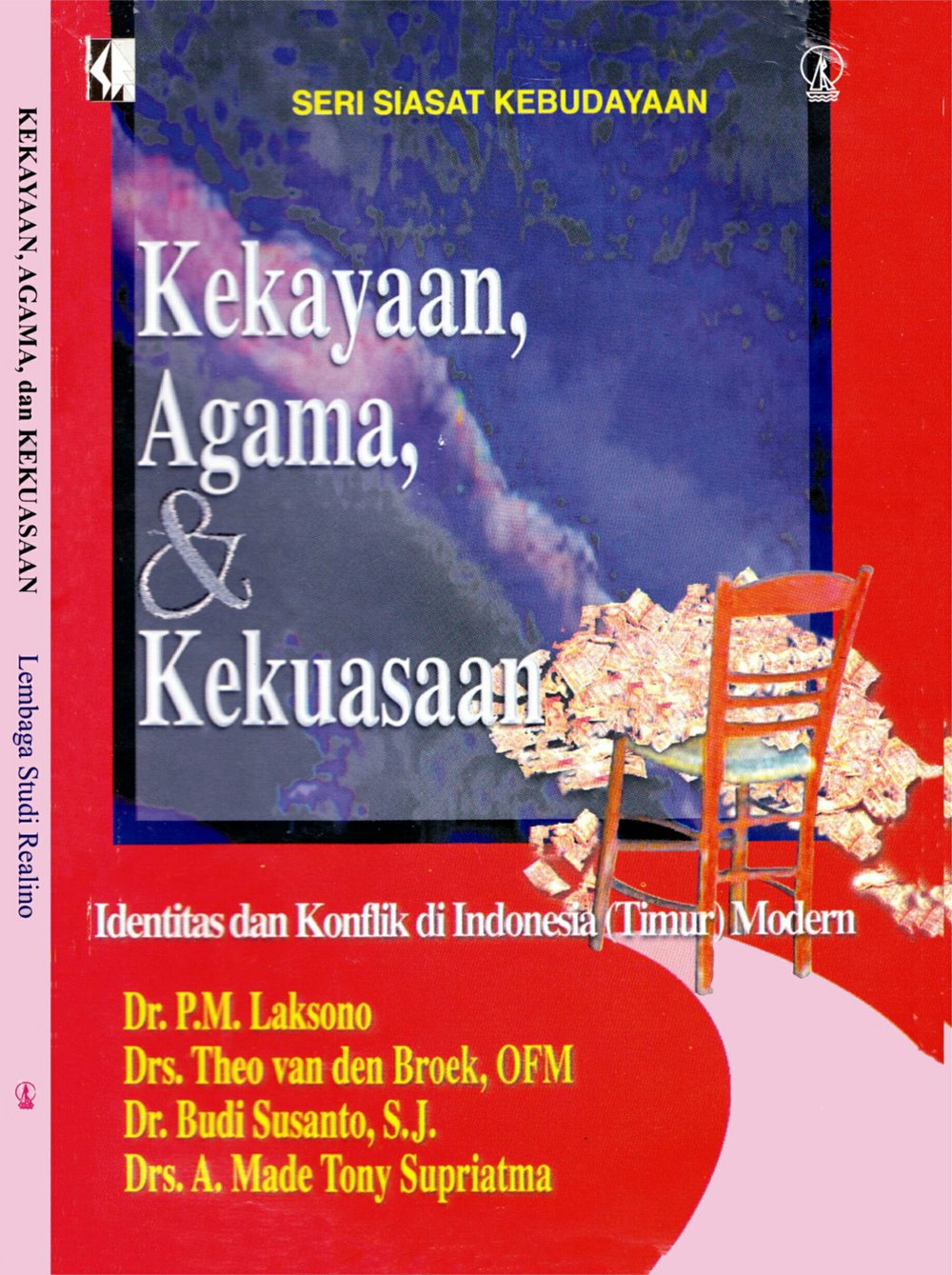Pernyataan Rohaniawan Franz Magnis Suseno bahwa Papua tidak sama dengan Timor-Timur (https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/18221011/franz-magnis-jangan-kira-papua-sama-dengan-timor-timur) dan tak ada jalan untuk referendum Papua merdeka (https://www.inews.id/news/nasional/romo-magnis-tak-ada-jalan-untuk-referendum-papua-merdeka) menarik untuk ditanggapi. Sebab apa yang dinyatakan itu seolah-olah mengabaikan fakta sejarah bahwa Timor-Timur pernah menjadi bagian sah dari Indonesia. Hanya masalahnya, sejak 20 Mei 2002 Timor-Timur memperoleh kemerdekaannya melalui sebuah referendum pada 30 Agustus 1999. Tapi, baik Papua maupun Timor-Timur, sama-sama merupakan konstruk dari historiografi Indonesia.
Sayangnya, historiografi Indonesia yang berkait dengan Papua dan Timor-Timur tampaknya hanya dihadirkan dalam berbagai narasi yang berhubungan dengan orang besar, peristiwa penting politik atau kenegaraan belaka. Itulah mengapa narasi tentang Papua dan Timor-Timur seakan-akan tak pernah lepas hal dan masalah yang hanya memiliki arti penting dan signifikan secara sosial (socially important and significant).
Narasi tentang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 di Papua, atau Referendum 1975 dan 1999 di Timor-Timur, misalnya. Kebanyakan narasi yang ditulis dan diedarkan hanya berdasar versi pihak-pihak yang sedang berkuasa di Indonesia. Masuk akal jika hampir sebagian besar ceritanya berkisah tentang siapa yang menang. Dengan cerita kemenangan itulah dibangun mitos bahwa kekalahan adalah bentuk lain dari kecurangan. Karena itu, jika kekalahan tak terhindari lagi, maka jalan satu-satunya adalah dengan menciptakan kekacauan seperti yang terjadi pada pasca Referendum 1999 di Timor-Timur.
Sementara, kekacauan dalam bentuk lain juga tak jarang direkayasakan. Dengan menamai sejumlah aksi atau gerakan yang mempertanyakan, bahkan menggugat, keabsahan dari sebuah kemenangan sebagai “pemberontak” atau “milisi (gerombolan liar)”, maka mereka yang berkuasa selalu dapat terbebas dari tuduhan atau dugaan sebagai “aktor intelektual”. Dengan demikian, bukan rahasia lagi jika tak ada satupun yang dapat bercerita tentang kekejaman dan kematian yang terjadi akibat peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991 atau pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay pada tahun 2003.
Cerita tentang Papua dan Timor-Timur memang teramat tragis dan traumatis untuk diungkap dan dikaji ulang. Padahal tidak sedikit laporan pengamatan yang telah disajikan dan dijadikan rekomendasi untuk ditindaklajuti. Namun, sebagaimana pernah dinyatakan oleh salah seorang mantan menteri Orde Baru ketika sedang berkunjung ke Amerika (tahun 1999) dan kerap ditanya tentang Timor-Timor, bahwa “Kami tidak tertarik dengan Timor” (Basis No. 03-04, Th. Ke-50, Maret-April 2001). Dan itu artinya, “kematian sekitar 200.000 orang, kerusakan apapun yang dapat dihancurkan dari pulau yang sudah miskin itu, penyiksaan dan perkosaan dari penduduk-penduduknya” sudah tidak dipandang penting dan mendesak lagi untuk segera diselesaikan.
Dalam konteks ini, sosok “Penyambung lidah rakyat” yang di zaman Bung Karno terasa tidak asing, kini justru semakin langka, bahkan terbuang, dari pikiran orang-orang yang sering mengaku bersedia “mengemban amanat rakyat”. Tak heran, Papua yang masih dipandang rawan dengan konflik dan kekerasan hanya dipikirkan sejauh kepentingannya menarik untuk ditampilkan sesuai dengan minat “orang”. Dengan “orang” dimaksudkan mereka yang berhubungan dengan pusat atau yang sedang berkuasa. Maka bukan kebetulan jika pendapat para pejabat berkait dengan kasus rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya tampak begitu dominan.
Beragam pendapat umum dan kebenaran seperti inilah yang telah membuat perhatian terhadap Papua menjadi tidak stabil, bahkan terkesan emosional. Karena dengan ketidakstabilan terus-menerus dari pendapat itulah orang dapat dengan mudah membalikkan punggung terhadap kekejaman-kekejaman. Maka, historiografi Indonesia mengenai Papua seakan-akan telah tersalurkan ke dalam wilayah emosi yang membuat keyakinan terhadap pusat lebih sukar digoyang daripada pengetahuan. Karena itulah, entah Papua ataupun Timor-Timur, sesungguhnya telah menjadi bagian dari historiografi Indonesia yang telah dibuang dari pikiran.
Ikuti tulisan menarik A. Windarto lainnya di sini.