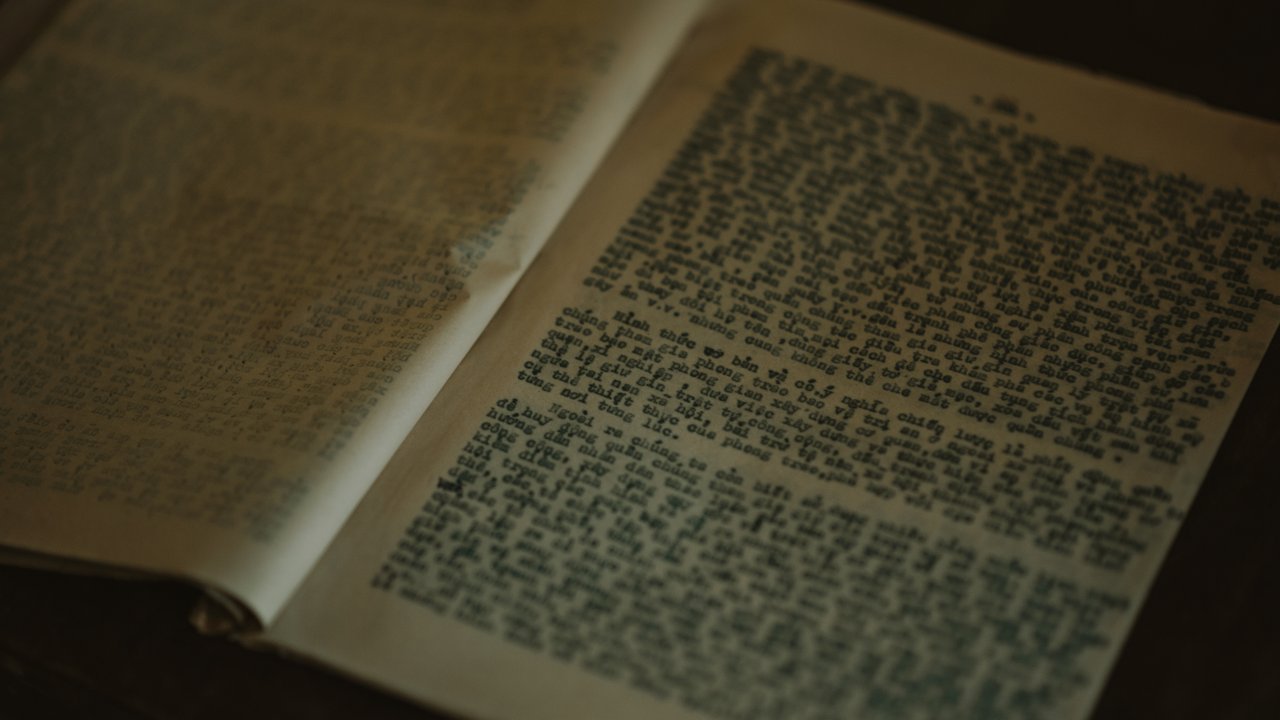“Orang yang paling berdosa adalah orang Indonesia!,” kata pembicara lewat zoom meeting, beberapa pekan lalu. Mendengar itu, saya kaget. Maksudnya apa, yah. Barulah setelah ia menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, saya jadi paham maksudnya.
Ceritanya begini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sekawanan pemuda telah memiliki kesadaran berbangsa. Hal ini tercermin dari kongres Pemuda I tahun 1926. Dua tahun kemudian, tahun 1928, kongres Pemuda II diselenggarakan. Sekumpulan entitas Indonesia berkongres. Diantaranya ada Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Bataks, Jong Celebes dan Jong Ambon. Kali ini, mereka melahirkan Sumpah Pemuda.
Bunyinya cuman tiga bait. Namun jika dibumikan maka akan sedikit berbeda. Indonesia yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, mengaku bertanah air satu. Dari 1.340 suku yang bermukim di 74.958 desa, mengaku berbangsa satu. Yang memiliki kekayaan 652 kosakata bahasa daerah, namun menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia.
Yang disebutkan terakhir yang akan dibahas disini, yaitu perihal sumpah berbahasa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan pernyataan diawal tulisan mengapa warga +62 berdosa. Semacam sikap ahistroris. Sebab telah disumpah berbahasa Indonesia, tapi masih sering menggunakan bahasa asing.
Belakangan memang harus diakui kalau penggunaan bahasa asing mendominasi banyak aspek keseharian. Misalnya di kiriman Instagram, Facebook atau Twitter. Bahkan di media pemberitaan pun, yang notabene mesti menyosialisasikan bahasa Indonesia, masih sering kita temui penggunaan bahasa asing. Lebih enakan menulis Bullying ketimbang perundungan, misalnya, meskipun maknanya setara.
Contoh lainnya yang paling sederhana adalah keseharian kita yang masih menggunakan bahasa gado-gado. Bagi penulis, ini semacam sikap ahistoris yang tidak sejalan dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Mirisnya, sikap ahistoris ini banyak dicontoh dari yang kolonial sampai yang milenial.
Lagipula jika menengok negara lain, taruhlah India yang tidak memiliki bahasa persatuan, maka Indonesia sungguh beruntung. Itu sebabnya tak perlu risau jika kebanyakan warga India dalam tontonan Youtube berbahasa inggris dengan sangat fasih. Ini lantaran mereka menjadikannya sebagai bahasa utama. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang punya bahasa pemersatu.
Perihal sikap ahistoris, ingatan kemudian melayang saat pemerintah menetapkan kebijakan tentang kewajiban berbahasa Indonesia yang mengundang polemik. Tertuang dalam Perpres No 63 Tahun 2019.
Isinya mengatur bahwa pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Baik dalam forum nasional maupun internasional. Jadi kalau ada pidato kenegaraan ke Uganda atau Timur Tengah, seyogyanya mereka menggunakan bahasa Indonesia.
Awalnya saya juga kurang setuju. Soalnya, terkesan dipaksakan. Baru-baru ini saja saya jadi kepikiran dan memang sudah tepat sekali. Selain menjadi amalan dan sikap historis terhadap Sumpah Pemuda, juga untuk merawat identitas bangsa.
Karena itu, memperingati hari sumpah pemuda setiap 28 Oktober harus dibarengi dengan merefleksi kembali perihal penggunaan bahasa. Seperti yang disebutkan diawal, kita disumpah menggunakan bahasa Indonesia, meski belum tentu baik dan benar.
Maksudnya, menguasai bahasa asing tetap dibolehkan. Tapi bukan untuk dijunjung tinggi dan digunakan dalam keseharian. Ada ruang dan waktunya. Sebab, boleh jadi atau tidak, proses asimilasi bahasa ini menuntun Indonesia kehilangan identitas. Pergaulan internasional serta arus globalisasi sangat kejam terhadap bahasa.
Contoh kecilnya kepunahan bahasa lokal. Menurut kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, dikutip dari CNN Indonesia (21/02/2020), sebanyak 11 bahasa daerah sudah punah. 25 bahasa lokal lainnya terancam punah. Artinya, kehilangan penutur berarti kehilangan bahasa. Pertanyaannya kemudian, tanggung jawab siapa?. Yang pasti bukan balai bahasa.
Ikuti tulisan menarik M. Fitrah Wardiman lainnya di sini.