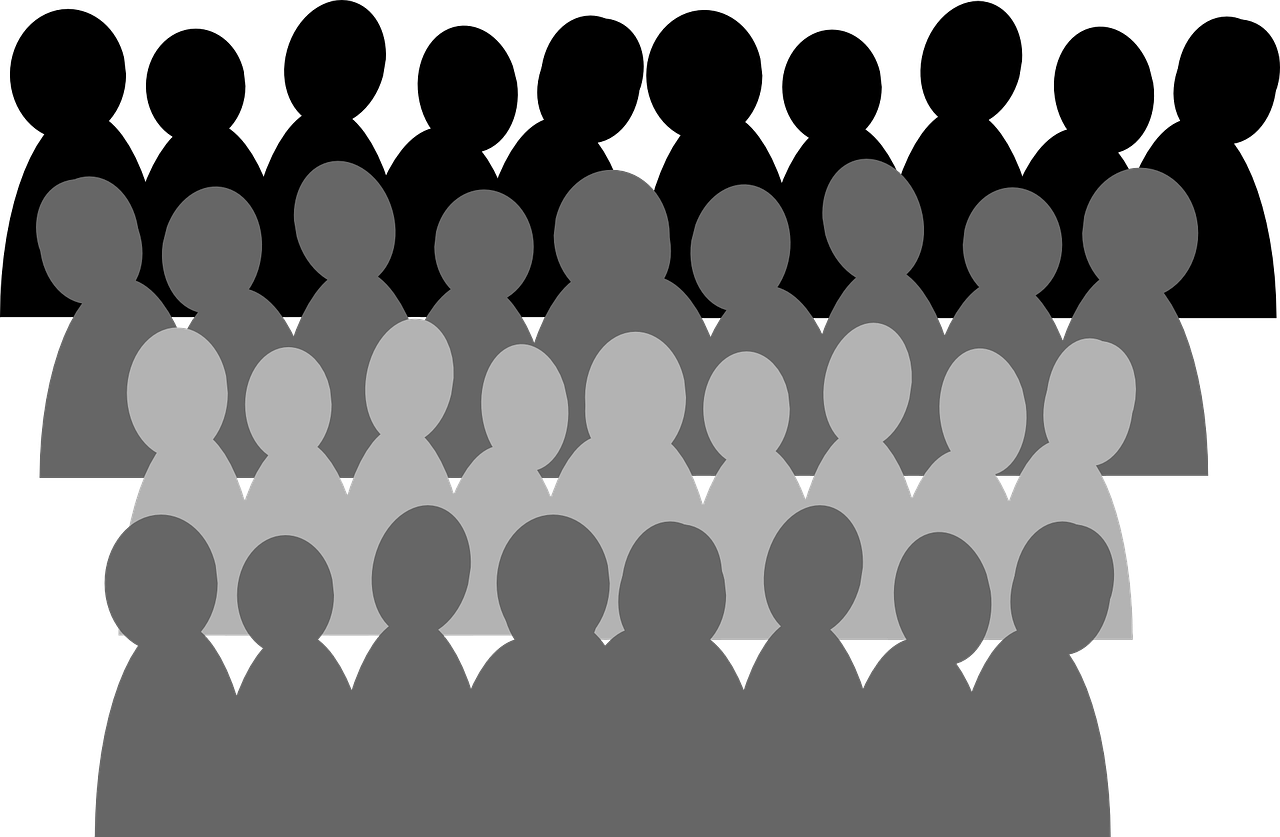Isu rasisme kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Keriuhan ini dipicu oleh unggahan foto dan narasi Ambroncius Nababan, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin, yang dinilai sebagai sikap rasis terhadap Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM. Sikap rasis adalah wujud keangkuhan manusia terhadap sesamanya—sama-sama mahluk Tuhan yang sengaja menciptakan manusia begitu beragam: ada yang berkulit hitam, coklat, putih, hingga kemerahan; ada yang bermata coklat, biru,sipit, belolok, hingga hijau; ada yang pendek, sedang, tinggi, amat jangkung hingga sangat pendek.
Meski begitu beragam, Tuhan sudah menanamkan dalam pikiran manusia: semua itu bukanlah penanda kelebihan satu manusia atas manusia lainnya. Bagi Tuhan, manusia terbaik itu yang mengikuti perintah-Nya; bukan karena kulitnya yang putih, wajahnya yang melankolis, atau tubuhnya yang tegap dengan six-pack yang mengundang decak kagum banyak orang dan karena itu kerap dipamerkan.
Meskipun sudah diingatkan demikian jelas, kita manusia tetap merasa percaya diri lebih baik ketimbang orang lain: merasa lebih tinggi [yang berarti memandang rendah orang yang lebih rendah], merasa berkulit lebih cemerlang [walaupun dibantu aneka rupa kosmetika alias tidak alamiah 100%], merasa lebih bule bahasa asingnya dan meremehkan yang berbahasa asing dengan logat Jawa [padahal dengan logatnya yang khas, Prof. Subroto dulu diakui kehebatannya waktu memimpin OPEC], dan seterusnya.
Apakah semua itu bukan bibit-bibit pikiran rasis atau tunas-tunas rasis yang sadar atau tidak bersemai dalam benak kita? Bolehlah kita bertanya pada diri sendiri: benarkah sama sekali tidak ada pikiran rasis sedikitpun di benak kita terhadap orang lain? Apa yang terlintas dalam benak kita manakala melihat seseorang yang, kebetulan, berbeda dari kita?
Sikap rasis itu bisa termanifestasi secara berbeda-beda, bukan hanya soal warna kulit, tapi juga logat dan dialek, lebar mata, kebiasaan makan, hingga cara memakai sarung. Masing-masing sikap rasis itu tersampaikan dalam kadar yang bergama pula, mulai dari gurauan yang masih bisa diterima hingga yang menimbulkan kegaduhan dan konflik di masyarakat. Ketika masih dapat ditoleransi, gurauan itu dianggap sebagai hiburan yang mengakrabkan, namun bisa menjadi sesuatu yang sensitif bagi orang yang baru kenal.
Gurauan beraroma rasis yang masih bisa diterima itu lazim terjadi jika yang dijadikan objek gurauan adalah diri sendiri atau komunitas sendiri, atau sesama rekan yang sudah akrab pol. Walaupun bisa pula persahabatan jadi ambyar lantaran gurauan rasis yang barangkali terucap pada waktu yang tidak pas.
Bibit atau benih rasis itu barangkali memang ada karena dalam diri kita ada sifat jumawa—merasa lebih dibanding orang lain: bisa lebih kaya, lebih pintar, lebih ganteng, lebih dermawan, dan kelebihan lain menurut ukuran manusia. Misalnya, kita suka menasihati teman atau saudara, eh kalau cari isteri atau suami yang kulitnya putih ya; eh, jangan dia yang jadi bos, logatnya lucu banget alias ndeso. Bukankah itu nasihat dan saran yang beraroma rasis?
Ketika bibit rasis itu kemudian dibiarkan tumbuh semakin besar dan tidak pernah disiangi alias dipangkas gundul, maka muncullah ke permukaan ungkapan-ungkapan rasis pada suatu ketika. Godaan untuk mengekspresikan sikap rasis itu cenderung dipermudah oleh kehadiran media sosial, dari semula sekedar gurauan hingga sebagai penghinaan karena perbedaan pandangan politik.
Bibit itulah yang mesti sering-sering kita siangi. Kita mesti memperlakukan bibit rasisme bak rumput liar yang menggerogoti keindahan taman bunga—maaf, jika ungkapan ini kurang pas, sebab ada pula rumput liar yang bagus. Pendeknya ialah jangan biarkan bibit pikiran dan perasaan yang merendahan orang lain lantaran perbedaan fisik maupun non-fisik. Kita kikis habis pikiran, perasaan, sikap, maupun tindakan yang berpotensi rasis demi menjaga kemanusiaan kita sendiri. Manakala kita bersikap rasis sesungguhnya kita telah merendahkan kemanusiaan kita dan diri kita sendiri. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.