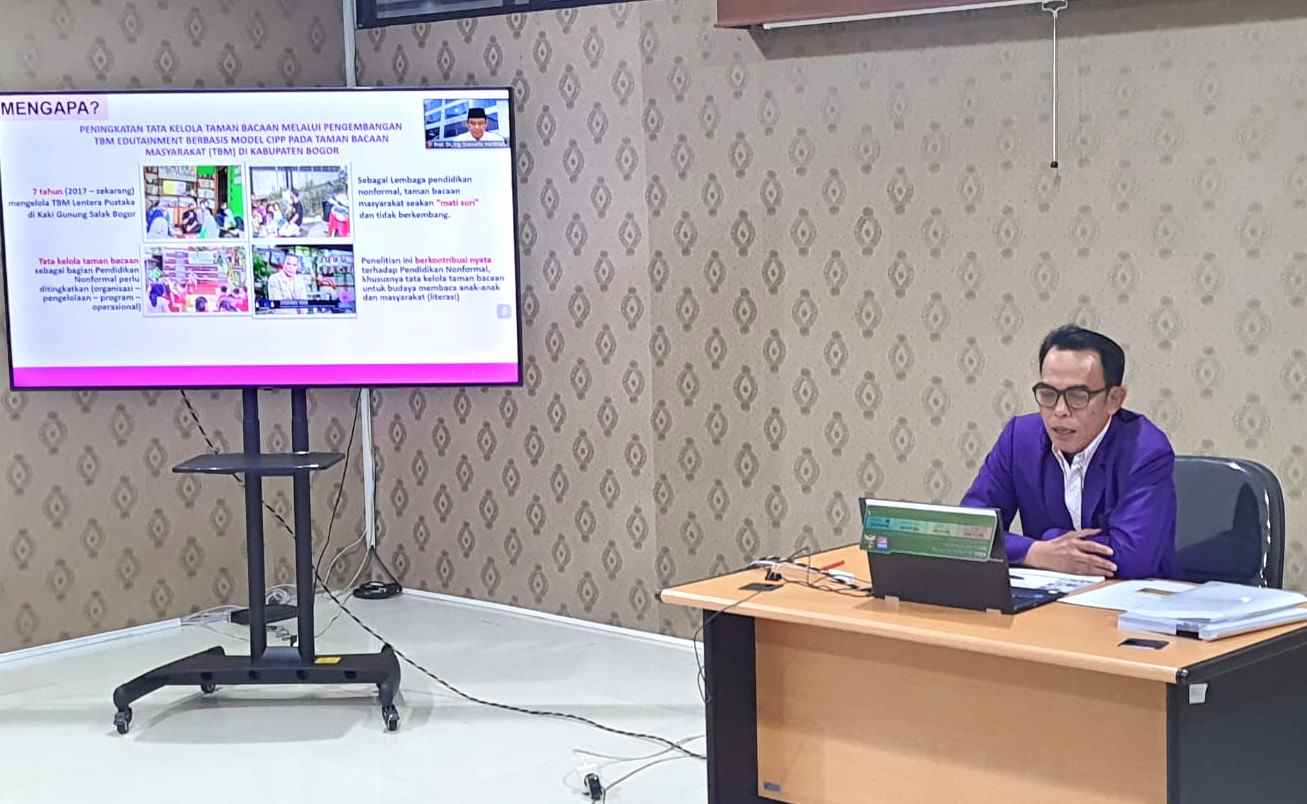Anita Lie, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unika Widya Mandala Surabaya
Sistem pendidikan di Indonesia sudah memperoleh beberapa capaian, di antaranya pemerataan angka partisipasi sekolah yang terus meningkat di berbagai daerah. Pada 2019 angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 99,24% pada jenjang SD, 95,51% pada jenjang SMP, 72,36% pada jenjang SMA/SMK dan 25,21% pada jenjang pendidikan tinggi (https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1054).
Namun harapan bagi para guru untuk membebaskan anak-anak bangsa dari kegelapan masih belum sepenuhnya tercapai. Semua pemangku kepentingan, terutama para guru masih harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diperlihatkan secara kuantitatif dalam berbagai data asesmen tingkat internasional seperti TIMSS, PISA dan Indeks Pembangunan Manusia. Secara kualitatif dalam pengamatan beberapa pelaku dan pengamat pendidikan, prestasi akademik siswa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata.
Pada PISA 2018 yang ditujukan pada anak berusia 15 tahun, Indonesia menempati peringkat 72 pada tes membaca dan matematika, peringkat 70 dalam sains di antara 78 negara. Catatan ini menunjukkan bahwa 40 persen siswa di Indonesia mencapai level 2 atau lebih tinggi dalam bidang sains dibandingkan rata-rata OECD 78 persen. Menurut definisi PISA, pada level 2, siswa bisa menjelaskan fenomena sains dasar dan menilai validitas suatu kesimpulan berdasarkan data yang diberikan.
Indonesia sudah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam dekade terakhir. Namun, masih ada tantangan dalam pembangunan manusia karena perbaikan kualitas manusia sampai dengan saat ini masih memprihatinkan. Selain skor PISA, beberapa studi lain juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Studi mengenai kemampuan matematika yang diangkat dalam Kertas Kerja RISE (A. Beatty dkk, Nov 2018) mencermati 5 gelombang data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) mulai 1993 terhadap lebih dari 30 ribu orang di 13 provinsi dan meneliti keterkaitan antara lama sekolah dan capaian belajar.
Walaupun Indonesia berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, namun masih ada kesenjangan serius antara kemampuan matematika peserta didik dengan apa yang seharusnya menjadi capaian belajar sesuai dengan kurikulum. Hanya 11 persen sampel yang telah lulus dari kelas 12 (SMA/SMK) bisa menjawab soal-soal numerik yang seharusnya diperuntukkan kelas 4. Seperti pembagian 2 digit (56/84), pengurangan pecahan (1/3-1/6), dan desimal (0,76-0,4-0,23). Temuan lain dari studi ini adalah kemungkinan lebih besar anak-anak dengan kemampuan numerik rendah berada di Indonesia Timur, di daerah pedesaan, lebih berumur, dan laki-laki.
Rendahnya prestasi siswa sering dikaitkan dengan rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Lie, 2004, Priyono, 2005 dan Darmaningtyas, 2005).
Namun fenomena rendahnya minat menjadi guru di kalangan orang muda telah berubah setelah 2005. Pada Era Reformasi, salah satu upaya strategis menjadikan profesi guru lebih dihargai dimulai dari Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemberlakuan undang-indang ini menjanjikan perbaikan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi bagi guru yang sudah lulus sertifikasi dan telah mendorong banyak orang muda untuk memilih program studi guru. Ada peningkatan besar-besaran pada pendaftaran program-program studi keguruan sejak 2005.
Sayangnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru ini tidak disertai dengan program menyeluruh untuk reformasi sistemik sehingga belum mencapai tujuan dengan optimal. Banyak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memanfaatkan momentum ini untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tapi tidak cukup serius mengimbangi tindakan pragmatis ini dengan perbaikan proses pendidikan para calon guru. Pemberikan tunjangan sertifikasi tidak diimbangi dengan kinerja guru secara sistematis. Penelitian Bank Dunia terhadap pelaksanaan sertifikasi guru pada 2009, 2011, dan 2012 terhadap 240 SD dan 120 SMP meliputi 3.000 guru dan 90 ribu siswa menunjukkan bahwa program sertifikasi guru oleh pemerintah belum meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan.
Sertifikasi guru hanya efektif meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. Menurut Mae Chu Chang, Head of Human Development Sector Indonesia, “Sertifikasi guru yang semestinya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan di kelas dan sekolah ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Prestasi siswa tak meningkat signifikan” (Napitupulu, 2012).
Program sertifikasi guru yang juga merupakan produk Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada masa itu banyak disorot. Raka Joni (2007) menunjukkan adanya ’cacat ontologik’ dalam konsep kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diturunkan dari Empat Pilar Belajar UNESCO.
Menilai seorang guru dalam 4 kategori sama dengan ’memosisikan keempat kompetensi ortogonal satu sama lain.’ Sebagai ilustrasi, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengembangan peserta didik yang terangkum dalam kompetensi pedagogik akan lepas konteks jika tidak dikaitkan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Demikian juga dengan dua kompetensi yang lain, kompetensi pribadi dan sosial. Tidak pernah jelas bagaimana menilai kompetensi pribadi dan sosial seorang guru.
Sementara itu, persoalan konseptual pendidikan profesional guru masih belum terselesaikan, program sertifikasi melalui portofolio sudah langsung dijalankan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Sungguh sangat absurd tindakan menggunakan berkas-berkas yang dikumpulkan dalam portofolio untuk menilai kompetensi seorang guru. Ketika guru-guru yang beruntung mendapatkan jatah, meraka berlomba-lomba mengumpulkan portofolio untuk memperoleh sertifikasi demi perolehan tunjangan profesi dan fungsional. Berbagai ekses (keikut-sertaan dalam program pendidikan dan pelatihan hanya demi sertifikat, manipulasi berkas, dan kolusi antara pemilik portofolio dan penilai) sangat menodai profesi guru dan bahkan melemparkan guru pada titik nadir dalam perjalanan profesinya.
Kemudian program sertifikasi guru pun mengalami evolusi dari penilaian portofolio menjadi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada 2011 dan selanjutnya pada 2018 menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-Jabatan dan Dalam Jabatan yang berlangsung sampai sekarang. Sampai dengan akhir 2019, PPG Dalam Jabatan yang diselenggarakan oleh 57 LPTK telah melayani 65.506 guru di seluruh Indonesia (Direktorat Pembelajaran, Kemdikbud) dan pada akhir 2020 telah meluluskan 63.470 guru.
Pemerintah tampaknya masih akan melanjutkan program PPG ini dalam beberapa tahun ke depan dan menargetkan penambahan 50 ribu guru profesional baru per tahun. Mengejar target jumlah perlu disertai dengan komitmen perbaikan mutu. Kelanjutan dari kelulusan guru dari PPG perlu dipikirkan dan difasilitasi agar guru bisa merdeka belajar dan menjadi penggerak sepanjang masa profesi mereka melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Beiringan dengan perjalanan PPG, Kemdikbudristek juga meluncurkan Program Guru Penggerak sebagai episode ke 5 Program Merdeka Belajar. Kemdikbudristek menargetkan 405.000 Guru Penggerak di akhir 2024. Sekali lagi, untuk negara sebesar Indonesia dengan populasi (termasuk populsi guru) yang relatif besar, target jumlah memang tidak bisa diabaikan dan sangat perlu dilakukan. Bisa pula dipahami bahwa dalam banyak konteks, target jumlah seringkali berhadapan dengan tuntutan mutu. Segala upaya berupa kegiatan pelatihan dan program pengembangan profesi guru sudah dan masih harus terus dilaksanakan untuk perbaikan mutu guru. Upaya ini akan bisa efektif jika berangkat dari titik kesadaran guru yang mungkin masih harus berhadapan dengan budaya ketakutan yang selama ini sudah bercokol dalam profesi guru.
Mengatasi Budaya Ketakutan
Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan perlu karena melalui perubahan, kehidupan tumbuh dan berkembang. Peran pendidikan dalam pembudayaan umat manusia adalah pembebasan peserta didik untuk melakukan perubahan dan pembaruan demi kehidupan. Perubahan masyarakat seharusnya dimulai di sekolah-sekolah karena di tempat inilah pemilik masa depan sedang dipersiapkan. Namun ironisnya, di sekolah peserta didik tidak banyak diberi kesempatan untuk merekonstruksi masa depan. Mereka bahkan diajar nilai-nilai kepatuhan serta belajar menyesuaikan diri dengan sistem, tatanan, norma, aturan, dan nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Guru diposisikan sebagai perangkat dalam suatu sistem yang tidak cukup memberikan penghargaan bagi upaya pembaruan dan pembebasan, namun justru sangat menghargai tindakan pengukuhan aturan dan sistem.
Pemosisian ini secara sistematis telah menciptakan dan memelihara budaya ketakutan di kalangan guru. Dunia pendidikan telah dibelenggu dan beroperasi dalam budaya ketakutan. Ketakutan guru terjadi secara multidimensional. Ketakutan terhadap sistem dengan segala perangkatnya termasuk penilaian terhadap peserta didik berupa ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkuasa, pengakuan atas profesionalitasnya berupa program sertifikasi, penilaian kinerja yang buruk dari kepala sekolah, jaminan atas kesejahteraan dan keberlanjutan karirnya telah menghambat guru untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh.
Penghapusan Ujian Nasional sebagai Episode Pertama Merdeka Belajar merupakan tonggak penting untuk memutus rantai ketakutan di antara para pemangku kepentingan bidang pendidikan. Pada saat artikel ini ditulis, Asesmen Nasional yang dirancang untuk pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional baru dilaksanakan satu kali pada September-Oktober 2021. Dampak penghapusan Ujian Nasional dan pemberlakuan Asesmen Nasional terhadap perbaikan mutu peserta didik masih perlu dikaji berdasarkan data-data perolehan.
Lebih jauh lagi, keterbelengguan dalam sistem dan ketakutan terhadap kemiskinan juga membatasi guru untuk terus menggali, menjelajahi, dan menemukan nilai-nilai kebenaran dalam bidang ilmu yang diam. Secara lebih mendalam, ketakutan terhadap peserta didik dan dirinya sendiri telah membentengi guru dari panggilan untuk menyapa peserta didik dan membebaskan mereka untuk menemukan diri sendiri. Bahkan, sebagian guru memanfaatkan dan menggunakan ketakutan dalam diri peserta didik untuk mengendalikan proses belajar mengajar. Peserta didik takut terhadap ulangan dan ujian, takut terhadap hukuman, takut menjadi bahan cemooh teman-teman sekelas, dan takut tidak naik kelas.
Ketakutan peserta didik inilah yang dijadikan sumber energi penegakan kekuasaan guru di kelas. Ketakutan peserta didik selanjutnya bergabung dengan ketakutan dari dalam guru sendiri untuk membuka hatinya sendiri dan menyapa hati peserta didiknya. Ketakutan para guru terhadap peserta didik telah mengenakan topeng apatisme terhadap perubahan dan sinisme terhadap kondisi peserta didik (mutu input yang terus merosot dari tahun ke tahun, motivasi belajar yang rendah, latar belakang keluarga yang tidak mendukung, dsb). Ketakutan-ketakutan ini telah memisahkan guru dari peserta didik.
Ketakutan adalah manusiawi dan jarak antara guru dan peserta didik akan selalu ada. Namun, betapapun lebar jarak tersebut, guru seharusnya berkomitmen untuk membangun jembatan dengan peserta didik bukan hanya karena peserta didik membutuhkan guru untuk membimbingnya dalam perjalanan menjadi manusia dewasa tapi juga karena guru membutuhkan pandangan dan enerji dari peserta didik untuk terus memperbaharui kehidupannya sendiri.
Ikuti tulisan menarik Anita Lie lainnya di sini.