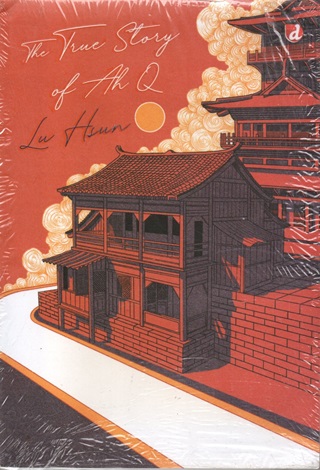Christchurch masih tidur saat pesawat yang menerbangkan kami dari Tullamarine Airport mendarat. Dari jendela pesawat, daratan kota itu tampak seperti gundukan putih yang mengambang di atas permukaan bumi.
Saya takjub bukan main. Hati saya berdebar-debar karena itu pengalaman pertama melihat Selandia Baru. Semakin lama pemandangan berubah jadi pucuk-pucuk putih pegunungan salju. Setiap detiknya seperti mengantarkan saya kepada dongeng masa kecil tentang para kurcaci dan putri salju yang bernyanyi dan menari.
“Oh Tuhan, apakah ini nyata?”
Saking takjubnya, saya menggumam sendiri. Mata saya seperti dua kunang-kunang yang berkejapan. Sesekali saya melirik ke arah istri saya yang duduk di dekat jendela, ia pun sepertinya tidak hendak mengerdipkan mata. Kami sama-sama sedang dipukau oleh apa yang selama ini kami idam-idamkan.
Maskapai Jet Star yang membawa kami dari Adelaide terlebih dahulu harus transit di Melbourne. Pilihan itu harus diambil karena termasuk penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier). Waktu itu harga tiket dari Adelaide ke Christchurch $485.02 AUD (Dollar Australia) atau sekitar Rp 4.800.000 . Cukup terjangkau dan terbilang murah untuk ukuran dua orang.
Di Bandara Tullamarine, emosi kami sempat diuji oleh aksi seorang staf maskapai penerbangan. Drama itu terjadi persisnya saat proses pengecekan paspor dan visa. Peristiwa yang kami hadapi di Tullamarine sesungguhnya dimulai jauh sebelum kami berangkat. Beberapa waktu setelah kami memesan tiket pesawat.
Istri saya memperpanjang paspor melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Dengan kata lain, paspor barulah yang jadi pegangan istri saya dalam menempuh perjalanan. Sementara ketika membeli tiket pesawat, istri saya menggunakan paspor lama. Itulah masalah. Itulah yang dipermasalahkan sehingga menjadi drama yang menjengkelkan.
Saya berusaha menjelaskan secara detail mengapa paspor yang dibawa dengan paspor yang ia gunakan ketika membeli tiket berbeda, tapi drama tidak juga selesai karena petugas pengecekan bersikeras menuntut istri saya untuk memperlihatkan paspor lamanya.
Jujur saja, kami tak kepikiran sama sekali akan hal ini. Tak pernah terbayangkan juga bakal ada kejadian macam ini. Tetapi kami tidak mau terjebak dalam debat kusir yang pada akhirnya akan menguras energi kami.
Kami berdua mencoba tenang. Dingat-ingat lagi oleh kami; rasanya kami pernah men-scan paspor dan filenya masih bersemedi di email kami.
Dengan segera saya membuka laptop. Mungkin di laptop pun ada, pikir saya. Hmmm, dan ternyata benar. Istri saya masih menyimpan scan paspor lamanya di folder yang saya beri nama New Zealand.
Lega rasanya. Setelah seorang staf tadi memverifikasi data yang kami berikan, ia mengangguk dan tersenyum.
***
Pagi di Bandara, hujan. Embusan udara seperti anak-anak kecil yang genit; mencubit-cubit kulit kami. Tak sabar rasanya ingin segera menyantap yang hangat-hangat. Tubuh kami perlu beradaptasi dengan nuansa dingin setajam ini. Kami agak menggigil.
Walau demikian, perasaan kami gembira bukan kepalang. Saya membayangkan selama sembilan hari ke depan bersama istri akan sangat menyenangkan. Menjelajahi tempat-tempat di Selandia Baru adalah sebuah pengalaman yang kami berdua impikan sejak lama.
Saya membentangkan jaket untuk istri saya lalu kami berjalan menuju pintu kedatangan. Tak banyak kesibukan di bandara pagi itu. Saya menyapukan pandangan ke semua sudut gedung. Sejumlah kafe dan mini restoran belum ada yang buka. Situasi tenang itu yang selanjutnya mengantar kami menuju pintu kedatangan.
Saatnya proses pengecekan. Ketatnya pemeriksaan di Selandia Baru bukan rahasia lagi. Sahabat saya pernah didenda lima ratus dolar lantaran kedapatan membawa sebiji apel. Itupun hanya setengahnya karena setengahnya lagi sudah ia makan di atas pesawat.
“Itu adalah buah apel termahal di dunia!” kelakar sahabat saya jika ia ingat kisah pahitnya itu. Hal yang sama pun sebenarnya pernah menimpa bintang sinetron kita – tak elok saya sebut namanya. Ceritanya ia ditahan karena ketahuan menyelundupkan makanan dari Indonesia. Persisnya sambal. Dan jenis makanan serupa memang tak diperbolehkan oleh pihak imigrasi negara setempat.
Dua orang bule memeriksa tas kami. Ikut berjaga-jaga juga bersama mereka anjing-anjing pilihan. Saya dan istri mengikuti semua prosedur. Mata istri saya awas sebab ia takut dengan binatang itu. Begitu pun saya sebenarnya, cuma lelaki tidak boleh memperlihatkan ketakutan. Lagipula saya percaya, anjing-anjing itu sangat profesional. Sekali pun mereka binatang, begitu diberi kepercayaan dan dilatih, mereka akan menjalanan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Eksistensinya untuk membantu manusia, bukan sebaliknya.
Karena kami telah mengumpulkan informasi tentang Selandia Baru, kami tidak membawa makanan dan semua hal yang dilarang. Kami aman- aman saja. Bebas dari penahanan dan tidak didenda.
Kami keluar dari bandara dengan penuh syukur. Dari jauh kami mengirim ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menumpahkan aneka informasi berharga sejak kami masih di Adelaide.
“Hmm, inilah berkah dari sebuah persahabatan,” kata saya dalam hati.
Interaksi yang kami bangun dengan sumber- sumber tertulis atau sumber lisan dari para sabahat terbukti mampu memberi gambaran awal tentang negara ini. Karena bagi kami sebuah perjalanan memang selalu menyimpan rahasia-rahasia tidak terduga. Tetapi setiap perjalanan sudah semestinya dibekali dengan pengetahuan yang memadai agar tidak celaka. Jadi, bukan “jalan dulu, baru tahu”, tapi “ketahui terlebih dahulu baru berjalan”.
***
“Morning Sir. How are you? Can I help you?” sambut seorang pria setengah baya berkulit hitam ketika kami mendekati tempat rental mobil Enterprise.
Dalam hati saya berkata sepertinya pria ini berkebangsaan India, terlihat dari wajah dan dialek English-nya. Senyumnya mengembang. Di depannya kami begitu terkesima. Pembawaan diri yang ramah menghadirkan kesan persaudaraan yang kuat meski baru pertama kali berjumpa.
Saya langsung meresponnya dengan menunjukan bukti pemesanan rental mobil via aplikasi VroomVroomVroom selama tujuh hari ke depan. Nilainya sih $663.66 NZD (Dollar New Zealand). Ya kalau harus dirupiahkan lagi mungkin sekitar enam jutaan. Harga tersebut sudah termasuk asuransi dan bahan bakar.
Udara di bandara yang masih kosong ini terasa dingin. Seorang pria dari negeri Bollywood itu selanjutnya meraih paspor dan SIM dari saya, lalu disalinnya beberapa informasi yang baginya penting. Tak lama berselang, ia pun menyerahkan kunci mobil yang akan kami pakai selama di South Island. Kemudian dengan penuh antusias ia menemani saya dan istri ke tempat dimana mobil ia parkir.
Tuntas dengan urusan sewa mobil, kami pun lega. “Kalau ada apa-apa di jalan, hubungi nomor ini,” pesannya menggunakan bahasa Inggris sebelum ia melepas kami.
Keramahannya menciptakan kesan persaudaraan yang kuat bagi kami berdua yang baru saja menginjakkan kaki di tanah milik Suku Maori tersebut. Sekali lagi, darinya kami mendapat kesan awal bahwa orang di sini sangat ramah.
“Bismillah”, batin saya.
Saya deg-degan, namanya juga mengendarai mobil di negara orang. Bermunculan berbagai pikiran negatif yang coba mengganggu ketenangan saya, tapi tetap harus saya lawan. Jangan sampai mereka – pikiran-pikiran negatif – mengacaukan semua rencana besar kami berdua.
“Tawakkal sajalah pada Tuhan!”, tegas saya dalam hati.
Hal pertama yang kami lakukan setelah meninggalkan bandara yakni belanja kebutuhan perut. Dengan bantuan Google Maps, jarak lima belas menit dari bandara kami menemukan supermarket Countdown, semacam Coles atau Woolworths kalau di Australia. Kami belanja bahan makanan ala kadarnya. Alhamdulillah, mie instan idola rakyat Indonesia ternyata bisa kami temukan di supermarket ini.
Untuk urusan belanja ini itu, istri saya yang pegang kendali utama. Tekadnya bisa meminimalisir pengeluaran. Mampu menahan diri sehingga tak perlu ada konflik antara dompet dan hati, di negara orang lagi. Kami tak punya uang yang banyak. Pun tak punya rumah sanak saudara untuk menginap.
Hujan subuh tadi meninggalkan gerimis tipis. Setelah mengganjal perut dengan pisang dan roti, kami meluncur guna memeriksa keadaan kota. Sebagai driver tunggal hari itu, saya mulai agak tenang. Secara umum kondisi jalan raya di sana mirip dengan di Australia sehingga orang seperti saya tak perlu tunggu lama untuk menyesuaikan diri.
***
Pagi itu hari Minggu, jalan-jalan utama di pusat kota tampak sepi. Di kiri kanan kami hanya ada bangunan-bangunan dengan arsitektur klasik yang masih tegak berdiri. Antik. Meskipun sebagian sempat hancur oleh gempa beberapa tahun silam, jiwa kota ini tetap utuh. Christchurch merupakan kota terbesar di South Island sekaligus kawasan urban terbesar di Selandia Baru setelah Auckland.
Gerimis masih tipis menemani perjalanan kami menyusuri jantung kota yang pucat. Mobil saya parkir di pinggir jalan. Bagi yang ingin tur di kota ini, kalau bisa aturlah perjalanan supaya tiba di Chirstchurch pada hari Minggu. Maksud saya agar dapat parkir gratis di tengah kota. Biasanya berbayar, tapi karena hari Minggu jadinya gratis.
“Lumayan”, kata istri saya.
Di atas jalanan yang basah, kami berdua melempar pandangan ke semua arah. Untuk saat itu kami belum melihat ada seorang warga pun yang berada di jalan. Kami merasa seperti terjebak di tengah kota mati. Sementara dingin dengan gesit menyebar ke seluruh tubuh.
Bersambung......................
Ikuti tulisan menarik Muhammad Hidayat lainnya di sini.