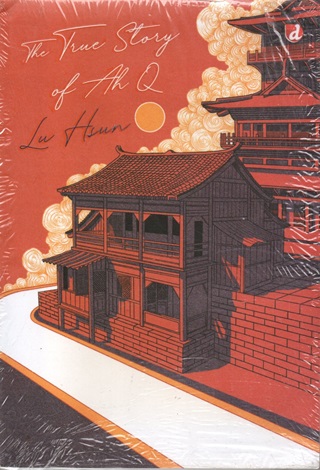Sastra Melayu-Cina di Indonesia tumbuh dan berkembang sebelum munculnya sastra Indonesia modern di akhir abad 19. Nio Joe Lan menyebutnya sebagai sastra Indonesia Tionghoa. Menurut Jakob Sumardjo dalam bukunya yang berjudul Dari Khasanan Sastra Dunia yang diterbitkan pada tahun 1985, jenis sastra Indonesia Tionghoa diawali dengan terjemahan-terjemahan.
Pada awal perkembangangan, karya-karya terjemahan Cina dan Eropa yang terbit dikerjakan oleh Lie Kim Hok, antara lain ialah Kapten Flemberge, Kawanan Bangsat, Pembalasan Baccarat, Rocambole Binasa, dan Genevieve de Vadans. Buku-buku tersebut cukup tebal karena diterbikan secara serial yang panjang serialnya ada yang sampai empat puluh jilid. Setelah masa itu, barulah berkembang karya Melayu Cina asli sampai akhir tahun 1942.
Menurut perhitungan Claudine Salmon, dalam kurun hampir 100 tahun (1870-1960) kesusastraan Melayu Tionghoa memiliki 806 penulis dengan 3.005 buah karya. Lalu menurut catatan A. Teeuw, dalam hampir 50 tahun (1918-1967), kesustraan modern Indonesia asli hanya ada 175 penulis dengan sekitar 400 buah karya. Jika dihitung sampai tahun 1979, ada sebanyak 284 penulisan dan 770 buah karya.
Setelah merdeka, Pramoedya Ananta Toer berulang kali menyebut masa perkembangan kesastraan Melayu Tionghoa sebagai masa asimilasi, masa transisi dari kesusastraan lama ke kesusastraan baru. Tahun 1971, C.W. Watson menyebutnya pendahulu kesusastraan Indonesia modern. Tahun 1977, John B. Kwee menulis disertasi di Universitas Auckland tentang apa yang disebutnya Kesastraan Melayu Tionghoa (Chinese Malay Literature).
Karena adanya kebijakan politik, Sastra Melayu Tionhoa pada masa dulu tidak termasuk ke dalam Sastr Indonesia. Salah satu alasannya karena karya sastra ini menggunakan bahasa Melayu pasar yang dianggap rendah, sementara karya sastra Balai Pustaka menggunakan Bahasa Melayu tinggi yang dianggap sebagai bagian kebudayaan bangsa. Argumentasi di atas terbantah ketika Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, a Provisial Annotated Bibliography (Paris:1981), terbit.
Katalog karya sastra peranakan yang ditulis oleh Claudine Salmon ini memuat 806 penulis dengan 3005 karya yang terdiri dari drama asli, syair asli, terjemahan karya penulis Barat, terjemahan cerita-cerita Tiongkok, novel dan cerita pendek asli. Sebanyak 2757 karya bisa diidentifikasi pengarangnya, sementara 248 lainnya anonim. Claudine bukanlah orang pertama yang menulis tentang kesastraan Melayu-Tionghoa, sebelumnya ada Nio Joe Lan yang pada tahun 1930 pernah menganjurkan agar karya sastra Melayu-Tionghoa dikaji dari bidang sejarah, kesusastraan dan psikologi. Ia menyebutnya Kesastraan Indo-Tionghoa.
Namun melalui karya Claudine, mampu dibuktikan bahwa genre kesastraan ini sebetulnya adalah bagian tidak terpisah dalam sastra Indonesia. A Teeuw bahkan menyatakan, bahwa buku Claudine telah memberi landasan kuat bagi kritik sastra yang sangat diperlukan untuk lebih memajukan penelitian sastra Indonesia modern. “Alasan yang diajukan Salmon itu tak terbantahkan dan begitu meyakinkan, para peneliti perlu melepaskan sikap apriori bahwa Sastra Indonesia awal dan manifestasi satu-satunya sebelum Perang Dunia Kedua adalah novel-novel Balai Pustaka.
Dengan luncurnya buku itu, tidak diragukan lagi bahwa Sastra Peranakan Tionghoa merupakan bagian dari perkembangan Sastra Indonesia masa kini. Dalam penelitian Claudine, ditemukan bahwa Oey Se karya Thio Tjin Boen dan Lo Fen Koei karya Gouw Peng Liang adalah dua prosa asli pertama Kesastraan Melayu-Tionghoa yang terbit di tahun 1903. Ini berarti karya-karya itu telah muncul 20 tahun lebih awal dibandingkan karya Sastra Balai Pustaka yang antara lain ditandai dengan terbitnya novel Azab dan Sengsara: Kisah kehidupan Anak Gadis karya Merari Siregar pada 1920 dan Siti Nurbaya karya Marah Rusli pada tahun 1922.
Dalam buku itu Claudine diperlihatkan bahwa pers Melayu-Tionghoa dan para penulis peranakan Tionghoa memainkan peranan besar dalam menyebarluaskan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia sejak tahun 1890-an. Bahasa Melayu yang digunakan pengarang peranakan tidak ada bedanya dengan bahasa Melayu kaum nasionalis Indonesia awal abad 20. Bahasa inilah yang menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Kemunculan Literature in Malay by the Chinese of Indonesia di tahun 1981 juga menimbulkan pemahaman, bahwa golongan Tionghoa bukanlah seperti apa yang disuguhkan kepada publik di masa itu. Penelitian ini mendorong terbukanya genre sastra Melayu-Tionghoa ke hadapan publik nasional di masa akhir kekuasaan Orde Baru, yang sempat membatasi gerak golongan Tionghoa untuk hanya berkarya di bidang ekonomi.
Karya Sastra Melayu Tionghoa menggambarkan dinamika yang terjadi semasa puncak Pax Nederlandica atau masa keemasan penjajahan Belanda dan beberapa dekade awal kemerdekaan Indonesia. Ada kisah tentang datangnya Raja Siam di Betawi pada tahun 1870, pembuatan jalan kereta api pertama dari Batavia ke Karawang di awal abad 19, biografi seorang petinju masyur, kisah percintaan yang ditentang karena perbedaan, drama berlatar belakang meletusnya Gunung Krakatau sampai kisah keseharian masyarakat pada krisis ekonomi tahun 1930-an. Ada pula Novel Drama di Boven Digoel karya Kwee Tek Hoay yang berani menyentuh masalah pokok masyarakat jajahan pada tahun 1920-an dan secara gamblang mengaspirasikan semangat ke-Indonesiaan. Setting novel ini dianggap luar biasa karena mengangkat peristiwa sejarah Pemberontakan November 1926 yang tidak berani dibahas oleh para pengarang Balai Pustaka.
Seperti karya-karya Thio Tjin Boen yang mempunyai ciri khas penggambaran masyarakat peranakan Tionghoa dalam interaksi dengan etnis lain, seperti Jawa, Sunda, Arab dan sebagainya. Ia bahkan menyatakan konflik antara masyarakat totok yang menyebut dirinya singke’ dengan golongan peranakan, karena adanya sifat, kebiasaan dan pola pikir yang berbeda. Gambaran sejarah lain juga terungkap jelas dalam kisah-kisah tentang perkembangan organisasi Tiong Hoa Hwe Koan (THHK), potret perempuan di zaman kolonial, organisasi perempuan yang sulit berkembang, dan emansipasi kaum perempuan melawan kungkungan tradisi untuk meraih cita-citanya. Sebaliknya literatur golongan Tionghoa peranakan dimulai oleh Liem Kim Hok yang memulai karirenya dengan menulis Siti Akbari, yang menceritakan penyebaran agama Hindu di Hindia. Dalam sejarah pers di Hindia ia pernah menyusun aturan bahasa "Melayu Betawi" yang terbit tahun 1891.
Kemudian disusul oleh Nio Joe Lan yang menyadur Hikayat Sultan Ibrahim, yang mengisahkan penyebaran agama Islam di Hindia. Karya yang lebih maju dari golongan Tionghoa peranakan ditulis oleh Liem Koen Hian dengan judul Ni Hoe Kong Kapitein Tionghoa di Betawi dalem Tahoen 1740 terbit tahun 1912. Tulisan ini menggambarkan peristiwa pembunuhan orang-orang Cina pada tahun 1740. Tulisan-tulisan orang Indo maupun Tionghoa peranakan yang digambarkan secara singkat di atas, masih menampakkan wataknya asimilatif atau pembauran.
Kisah-kisah dalam Karya Sastra Melayu-Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, memuja kolonialisme Belanda atau berusaha menjadi orang Indonesia. Sebuah fakta lagi yang menguak betapa heterogennya masyarakat Tionghoa di Indonesia, dimana sering disamaratakan dengan stereotipe tertentu.
Referensi :
Rosida Erowati & Ahmad Bahtiar. Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta : 2011.
Ikuti tulisan menarik Gita Indah Cahyani lainnya di sini.