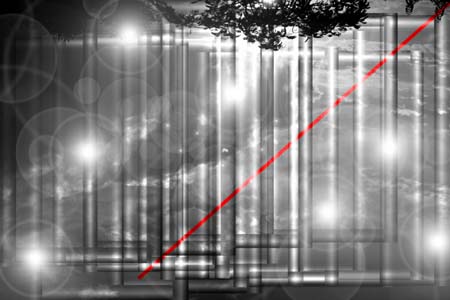Mati Sunyi (6) Episode: Trimatra.
Dia berdoa khusyuk di antara dua nisan. Selesai sudah hidupnya.
Selesai sudah batas kemampuannya. Profesionalisme jadi gelar di tong sampah bagiku kini. Pandir kau! "Ya. Aku pasti si pandir itu," hatinya lusuh, kusut masai.
Selesai sudah segala hakikat atas hak nurani kasih dari segala maha, dia miliki. Mempertahankan, kata, cinta, meski kata itu tak pernah ia pahami sepenuhnya. Kata dari segala sumber bencana. Kata bagi doaku kini.
“Ini saatnya aku menggantung diriku, mati,” hanya itu cara bertemu kamu bersama anak kita. Mengapa batinku berkata seburuk itu.
“Glaarrr!” Petir menyambar sebatang pohon. Tujuh belas depa dari dirinya. Menyadarkan, waktu sore menjelang temaram, ada suara dari rumah ibadah.
Dia dudukan pantatnya di tanah. Belum bisa berdiri, di depan dua pusara, anak-isterinya berdampingan, mungkin kini mereka lebih mengerti dariku, kata, disebut cinta bahagia.
Mereka dilindas kereta, saat menyeberang, tiga malam lalu. Pertanyaan tak perlu lagi. Tak 'kan jelas, hukum sebab akibatnya. Aku tak ingin ingkar berdebat dengan diri sendiri, bakal semakin pandir.
“Poltar, sudah waktunya,” dua petugas kembali memborgol, kedua tanganku. Segala hilang semua kekuatan. Tak kalian borgolpun aku takkan lari, hidupku telah tamat.
Sekelompok anakanak, berlarian, di belakang mereka, mengikuti. Mengajukan berbagai pertanyaan sekenanya. Suara mereka nyaring, polos, tak dijawab, oleh petugas, meminta mereka untuk menjauh.
Di kejauhan, Poltar, merasa mega beriring angin tengah mengolokngolok dirinya. Mobil tahanan menjauh, suara anakanak itupun menghilang. Hanya ada suara, rumahrumah ibadah melekat di lubang telinga, adem di nuraninya.
**
Regu tembak. Peluru menghantam bagianbagian mematikan di tubuhku. Tak ada apapun terasa, kecuali, jantungku bagai pecah, seperti balon berisi air mainan anakku. Lalu, dingin, sejuk nian. Hal tak pernah aku alami sepanjang hidup. Inikah menuju mati.
Kapan aku mati tak pernah di ketahui oleh siapapun termasuk oleh diriku sendiri. Melayang di alam seperti mimpimimpiku dulu, ngawang menuju gerbang raksasa, mungkin ini disebut pintu langit oleh kitabkitab kebijaksanaan.
Tubuhku melayang memasuki ruangan maha luas, labirin raksasa maha dahsyat. Tak aku temukan warna apapun.
Sejuk itu terus, seperti menuju entah tak jua aku kenal apapun, aku melihat semua, sesuatu entah apa, tak satupun aku kenali secara benar, kecuali perasaan bahagia, sebelumnya tak pernah 'ku miliki, untuk aku persembahkan kepada anak-isteriku.
Mungkin ini disebut bahagia, aku tersenyum entah kepada siapa saja sepanjang perjalanan ini. Menyenangkan, tapi itupun masih kurang tepat. Lebih dari perasaan menyenangkan sekalipun bahagia masih terasa asing bagiku, kini.
Ketepatan menggambarkan perasaan ini, aku sulit memahami, untuk menjelaskan kepada anda pembaca. Jika anda pernah bahagia, gelak tawa, gembira bersuka ria, melebihi semua itu. Sungguh suatu perjalanan tidak aku pahami.
Apa namanya ini, begitu ringan, seringan kapas barangkali, tapi, mungkin, itupun kurang tepat. Benda terringan, pernah aku pegang, ya kapas, jadi, seringan itu kirakira.
**
“Poltar?” Aku terkesiap. Suara itu, aku kenal betul, syahdu penuh kesabaran. Tuhan, alangkah cantiknya gadis di hadapanku ini.
Siapa dia gerangan, diakah isteriku terkasih ketika muda dulu? Ya. Alangkah eloknya hatimu untukku adik, baru aku melihatnya kini.
“Ya.” hanya suara itu, keluar dari mulutku. Lidahku berusaha tetap berada di tempatnya.
Diciumnya mulutku mendadak, terlumat olehnya, erat sekali. Amboi! Nikmat kali hidupku ini. Aku tak ingin melepaskan ciuman itu. Takkan pernah.
“Aku menunggumu. Abang, tak juga muncul. Maaf. Adik kemari, menyusulmu, rindu.”
**
Suara memanggil di kejauhan, nyaring sekali. “Poltar!” Aku melihat orang itu jelas sekali.
“Solomo! Kau! Apa kabarmu,” aku menyapa dengan gembira, erat berjabat tangan.
“Satu jam lagi seminar tekno angkasa itu dimulai, kita 'kan jumpa kuantum kelipatan anonim. Kaulah penemu teori itu, bahwa atom tak kekal, imitasi dari materi nyaris serupa jasad renik. Disertasimu disimpan pustaka dunia sobatku Poltar.” Solomo memberi tahu, gembira, kami menuju ruang di samping koridor. Dia masih pencerita nomor wahid sejak di bangku almamater.
“Seingatku, kau berkaca mata sobat.” Segera menyelang kalimatnya, supaya dia jeda sejenak.
“Ya. Masih, tapi sekarang aku tak memerlukannya lagi.” Solomo, memperlihatkan kaca matanya.
**
“Anak bapak perempuan,” suster itu memberi selamat padaku.
“Boleh saya masuk.”
“Belum. Isteri bapak masih lelah, baru melahirkan. Bapak boleh melihat, dari balik pembatas ruangan ini.“ Suster, mempersilakan. Setelah di balik ruang penyekat itu sinaran menyala terang benerang.
Isteriku memperlihatkan makhluk mungil, terbungkus selimut cahaya indah nian di pelukan ibundanya, terang wajahnya. Isteriku memberi tanda bahwa si mungil itu perempuan.
Aku menjawab. “Namanya, Marni saja,” kutulis di penyekat transparan dengan jari telunjukku, muncul seperti cahaya membias lembut membentuk pola nama itu.
**
“Selamat. Kau doktor, lulus dengan nilai luar biasa. Sangat memuaskan. Kau, seorang ahli nuklir. Negaramu pasti bangga.” Marqueste, memberi selamat dengan aksen bahasanya, kental, seperti kopi sedang kami nikmati.
“Hahaha”, kami tertawa menikmati kegembiraan. Bercengkerama berbagai masalah, persoalan peperangan duniawi sampai duren ternikmat di desaku.
Dia masih ingat pula ketika mandi di air terjun di kampung halaman emakku. Bajumu nyaris terlepas merosot lantas kau berlari sembunyi ke huma di balik air terjun itu, memintaku menengadah kelangit seraya membacakan sajak seorang penyair hahaha ...
Gilanya lagi, kau kecup lembut aku dari belakang, bergidik bulu kudukku hahaha ... Kami tertawa lepas.
Matamu, Marqueste, masih hijau indah kebiruan berjuta kenangan di dalamnya, Zaragoza Spain, kota kenangan, dokumen negaraku ada di sana ... Jauh sebelum aku memutuskan meninggalkanmu, demi pengabdian pada emakku. Jodohku telah dipilih.
Terus berlanjut hingga obrolan serangan tsunami menghantam instalasi nuklir negara industri kekinian, sampai pada tontonan komedi alternatif, kami terkekehkekeh.
Labirin maha luas. Menuju entah. Terus menurus berkesinambungan tanpa batas akhir. Barangkali itu gaib semesta. Semoga aku 'kan tiba di surga.
***
Jakarta Indonesiana, Oktober 05, 2022.
Ikuti tulisan menarik Taufan S. Chandranegara lainnya di sini.