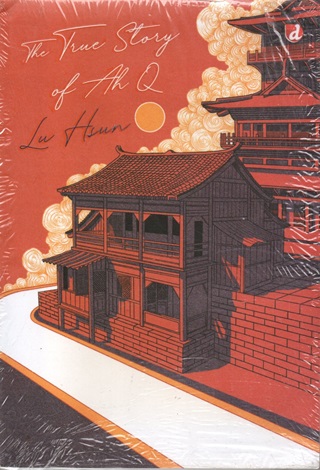Sepanjang petualanganku di dunia kepenulisan, kusadari adanya kecenderungan untuk mengintimkan diri dengan gaya salah satu karya penyair yang berpengaruh dan genre puisi tertentu. Sesuatu yang kusebut sebagai ‘kerja ontologis’, di mana eksperimen tentang gaya diikuti dengan pertanyaan, “Mengapa karya ini ada?”, dan pada akhirnya, “Mengapa aku ada sebagai seseorang yang menulis karya ini?”
Tentang kerja ontologis ini, Milan Kundera mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan manusia di hadapan suatu dunia yang mendahului keberadaannya, diikuti dengan jawaban yang didasari pada kepastian dan asumsi mendasar tentang dunia tersebut. Lebih jelasnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Kafka, “Dunia dalam pandangan Kafka: semesta yang dibirokratisasi.” (Kundera, 2016, hal. 64).
Jauh sebelum tahun 2020, aku sudah menulis puisi seiring dengan kegiatanku di komunitas Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS) di Universitas Pendidikan Indonesia. Hanya saja, karya-karya yang tersimpan dimulai antara tahun 2019 dan 2020, selebihnya terbuang, terlupakan, terurai jadi bit-bit di alam kubur digital, dan ide-ide terbaik kembali pada alam idea platonik – menunggu buat ditemukan kembali. Tetapi justru di tahun ini, sebuah batu fondasi telah diletakan melalui sebuah puisi yang berjudul Tahun Tanpa Puisi. Tentu saja, melalui puisi ini aku melihat, mencium, dan mendengar panggilan laut. Untuk pertama kalinya, kusadari tentang Ruh Kata yang membimbingku memasuki kontemplasi momen puitik di tengah rasa frustrasi, hilangnya tujuan, dan penyadaran bahwa mungkin aku tidak mengerti puisi dan tidak akan pernah bisa menuliskannya. Dan puisi tersebut menjadi monumen penerimaan diri.
Begitu kulihat kembali karya tersebut, kuingat-ingat kembali dari mana dan siapa yang memengaruhiku untuk menulis karya tersebut. Dalam kamus bahasa Inggris terdapat kata ‘conjuration’, kata yang sama dalam dunia video game seringkali digambarkan sebagai teknik sihir yang memanggil mahkluk, senjata astral, atau benda-benda dari dimensi lain. Conjuration dalam pengertian tadi agaknya mendeskripsikan proses kreatifku, baik yang direncanakan atau spontan. Ketika aku hendak menulis sebuah puisi, setidaknya ada kutipan karya yang terngiang, lalu sosok pengarangnya, lalu rangkaian kata yang terucap dalam pikiran untuk dituliskan. Karya yang disebut sebelumnya, terpengaruh oleh konsep Milan Kundera tentang metode menulis secara ‘polifonik’ dan imaji surealisme khas Danarto (meskipun tidak sepenuhnya mirip), selebihnya tentang gaya dan silsilah wujudnya sebagai puisi itu sendiri masih misterius, berbeda dengan karya-karyaku yang selanjutnya.
Tidak lama kemudian aku kembali menulis, kali ini melewati proses conjuration yang lebih intens dari sebelumnya dengan munculnya sosok T.S. Eliot dan Schopenhauer (walaupun sampai hari ini aku tidak mendalami pemikirannya sama sekali, selain dari kritik Nietzsche tentang gagasan pesimismenya). Aku berkenalan dengan T.S. Eliot dari puisi termasyurnya yang berjudul The Waste Land, tepatnya dari fragmen kedua yang berjudul A Game of Chess. Dan sampai hari ini, aku sering kembali membuka dan membaca kembali puisi tersebut walau tidak memunculkan dorongan dan gambaran serupa yang menarikku untuk memasuki momen puitik. Dari Eliot pula, aku berkenalan dengan rubay dan haiku yang tidak hanya memengaruhi penyair berkewarganegaraan Inggris dari abad 20 itu tetapi juga gerakan puisi imajisme di Amerika.
Sebagaimana pendapat Milan Kundera dalam kutipan sebelumnya, keintiman dengan satu karya tersebut membawaku pada petualangan dan sebuah dunia. Sayangnya, aku tidak ada mesin waktu yang bisa kupinjam agar bisa bercakap-cakap dengan keempat Grandmaster haiku: Matsuo Basho (1644-94), Yosa Buson (1716-84), Kobayashi Issa (1763-1827), dan Masaoka Shiki (1867-1902). Tidak pula bisa meminjam beberapa volume karangan R.H Blyth (1898-1964) tentang haiku dari perpustakaan kampus UPI. Jadi, kubangun sendiri dunia dalam semangat Zen tersebut melalui apa yang bisa kubaca dari buku-buku tentang kebudayaan Jepang dan karya sastranya yang kumiliki seperti The Ideal of The East (Okakura, 1997), The Discourse on The Inexhaustible Lamp of The Zen School (Enji, 1996), Ways of Thinking of Eastern Peoples (Nakamura, 1974), The Unffetered Mind (Soho, 2007), Rahasia Hati (Soseki, 1992), Kokoro (Hearn, 1998), novel-novel Haruki Murakami, koleksi haiku Masaoka Shiki, dan sebagai tambahan Tao Te Tjing.
Secara khusus, aku memilih menghayati dan mempelajari karya-karya Shiki karena lebih modern sebagaimana imaji-imaji yang digambarkannya seperti ‘rel kereta’ dan ‘jalan aspal’ (memotret narasi besar tentang era industrial di Jepang), memiliki gaya pengungkapan yang sederhana namun elegan, dan seandainya The Waste Land juga haiku Shiki adalah kopi arabika, keduanya memiliki notes yang mirip.
Akhirnya, semua bahan baku dan resep itu kutuangkan dalam haiku-haiku yang kutulis sejak mulai bekerja sebagai broker di sebuah perusahaan pialang. “Hal kecil dan sederhana yang membuatku tetap waras dan kerasan.” Pikirku, di tengah kejenuhan mencari klien, mengontak mereka satu persatu, menemui mereka di sudut-sudut Kabupaten Bandung Barat yang belum pernah kudatangi, dan terombang-ambing roller coaster market yang seringkali membolak-balikan perasaan. Sebuah karya yang kuharap kelak tersusun dalam antologi berjudul, A Day in The Life. Sebagaimana dalam film yang berkesan, pada babak pertama para penonton semestinya diajak mengenal, mengetahui, dan bersimpati pada si tokoh utama dengan mengikuti kehidupan sehari-harinya.
Meskipun lebih padat dan pendek, nyatanya menulis haiku jauh lebih rumit dan membutuhkan kematangan gagasan agar tersampaikan secara estetik baik dari segi bentuk maupun isi. Wawasan tentang haiku, kebudayaan Jepang, dan semangat Zen memang penting, namun yang sesungguhnya diuji adalah kemampuan kita untuk menuangkan pengalaman sebagai pengalaman itu sendiri ke dalam medium bahasa tanpa membuatnya berubah menjadi sebuah konsep abstrak, petuah, teka-teki, dan hal lain lebih menggugah kerja hemisfer otak kiri kita. Dan jujur saja, aku sendiri belum mampu mencapai tahap tersebut. Untuk saat ini, rasanya aku perlu beradaptasi dengan struktur tradisionalnya (dalam baris pertama tersusun dari 5 silabel, 7 silabel di baris kedua, dan 5 silabel di baris ketiga), walau secara gramatikal dan morfologi bahasa Indonesia sulit untuk diikuti.
Bagaimana hasilnya? Silakan baca dan nikmati koleksi tahun 2019 yang sudah diedit sampai dengan ditulisnya esai ini. Tentu saja tanpa mengubah gagasan utama dari teks aslinya secara radikal. Seperti menulis puisi pada umumnya, aku mencoba memadatkan kembali baitnya dengan pilihan kata yang lebih tepat, menghilangkan kata penanda waktu atau penanda lainnya yang tidak terasa memengaruhi suasana, dan mengubah urutan baitnya jika perlu. Setelah kulihat kembali, sebagai otokritik, di tahun ini aku belum benar-benar menunjukkan unsur Zen yang identik dengan haiku, menerapkan prinsip dasar tentang kireji yang mengarahkan pengalaman pribadi menjadi pengalaman universal, maupun penggunaan juktaposisi yang lebih matang antara baris pertama dan keduanya.
Koleksi Tahun 2019
28 Agustus 2019
Rabu, 13:03
daun hanjuang
dan bulu kuduk bergoyang
sepanjang berdoa
23:56
lalat menyelinap
eh, malah tersesat
di depan kaca
31 Oktober 2019
Kamis, 18:46
malam Hallowen
bulan sabit kemerahan
saat hantu dandan
15 November 2019
Jumat, 14:46
sepanjang jalan
hanya cemara, diam-
diam mengikuti
14:49
bola di tengah
lapangan voli, menanti
teman main
17:54
usai hujan
tak ada pelangi, selain
di genangan jejak truk
17 November 2019
Minggu, 13:13
bayangan gedung
mengundang ke sudut
dengan asap rokok
13:17
mobil mengantri
orang-orang macet
car free day
17:47
kendaraan berbaris
merah, kuning, hijau!
siapa yang pulang duluan?
Referensi:
Kern, Adam L. 2018. The Penguin Book of Haiku. United Kingdom: Penguin Books
Kundera, Milan. 2016. Seni Novel. Yogyakarta: Octopus Publishing House, hal. 64.
Ikuti tulisan menarik Fadzul Haka lainnya di sini.