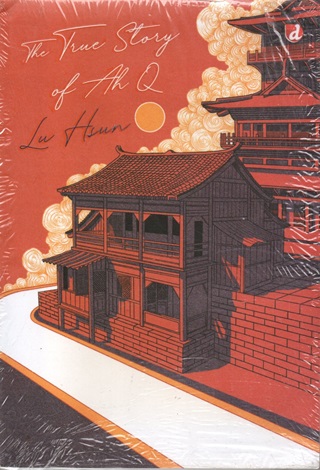Buih putih mengekor panjang membelah biru laut meninggalkan dermaga papan sementara, pada suatu pergantian pagi menuju siang. Kapal motor kapasitas tiga ratusan penumpang menderu menjauh dari daratan Serambi Mekah menuju pulaunya yang terpisah sekaligus penanda tertepi Indonesia, Sabang. September 2006, satu setengah tahunan setelah tsunami, saya, di bangku terdepan Kapal Motor (KM) Pulo Rondo, mengarungi alun dan gelombang besar Selat Benggala tepat puncak Musim Angin Timur.
Ketika Sang Kapten mati-matian mengendalikan laju demi selamat sampai daratan, lima puluh menit ke depan sesuai perkiraan, saya juga sedang berjuang. Sejak kecil, ‘penyakit’ saya kala bepergian adalah mabuk perjalanan. Biasanya, saya mengonsumsi obat anti mabuk, tapi karena kehabisan persediaan sekaligus belum gampang menemukan barang-barang kebutuhan di puing-puing Kota Banda Aceh, yang memang masih hancur waktu itu, saya terpaksa terus tanpa ‘senjata’ andalan.
Perjalanan itu seperti siksaan. Saya mendorong kepala pada sandaran kursi mengalihkan pening sangat akibat mabuk perjalanan yang diperparah hempasan kapal. Sesekali saya memicing menembus jendela di sisi kiri menuruti suami saya yang tengah membanggakan tanah lahirnya. “Lihat itu, indah,” ...lagi, “Lihat itu bagus,”... Ya ya ya...indah dan bagus, ombak laut setinggi kapal. Pusing kepala saya berlipat dua, satu mabuk laut, ditambah ketakutan amuk cuaca ganas. Mabuk saya semakin berat karena beralih-alih pandangan sekaligus pengaruh horor ombak besar.
Pengalaman pertama selalu berkesan, itu hari saya menjelang menjadi penduduk Sabang. Sebulan sebelumnya atau Agustus 2006, saya menikah, dan garis Tuhan membawa saya, yang lahir dan besar di Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya pindah ke Sabang mengikuti suami. Sebagai orang Jawa daratan, saya minim pengalaman naik kapal. Pernah sekali, menyeberang ke Bali dengan feri besar waktu badai. Saya SMA kelas 2 dan itu rombongan darmawisata sekolah.
Pada perjalanan pulang, kami menyeberang malam hari. Kilat-kilat petir adalah cahaya-cahaya putih di gelap malam, gemuruh, dan kapal bergerak naik turun hebat, menyeramkan. Kenangan itu memenuhi pikiran saya tiba-tiba, terkondisi keadaan, dan parahnya, sekaligus membawa saya berpikir pelayaran ini lebih beresiko, karena kapal yang saya tumpangi kecil, artinya akan lebih mudah tenggelam. “Tuhaaaaan.... Mohon selamatkan,” doa saya tiada putus.
Di kepanikan, obat saya melihat suami. Dia tenang di sebelah saya. Berarti, ini badai biasa saja di Sabang, pikir saya. Ternyata Sabang memang langganan badai. Sebenarnya, sama dengan wilayah Indonesia lain, Sabang diterpa dua musim angin atau muson. Bedanya, selama musim angin, teduh dan badai bergantian tanpa henti di Sabang. “Beberapa minggu badai, beberapa minggu teduh,” kata orang Sabang kebanyakan. Pada puncak badai, lalu lintas penyeberangan Sabang-Banda Aceh sering sampai dihentikan menghindari kecelakaan.
Sabang sudah punya pengalaman buruk gara-gara cuaca. Sabang mengalami tragedi pelayaran 1996. 284 orang dinyatakan hilang bersama karamnya Feri Gurita, sementara 94 orang ditemukan, 54 meninggal 40 selamat. Tragisnya, musibah terjadi menjelang Ramadhan atau hari meugang ketika banyak orang Aceh bertradisi mudik berkumpul keluarga untuk menunaikan ibadah selama puasa.
Meski kabarnya kondisi kapal yang tidak layak jalan dan faktor kelebihan muatan menjadi sebab, tapi banyak kesaksian Laut Sabang diamuk badai malam kejadian. Ada monumen kecil setinggi dua meter, kurang lebih, dengan pahatan miniatur KM. Gurita menghias puncak tugu, dibangun di Pelabuhan Balohan Sabang, untuk mengenang.
Empat puluh lima menit setelah keberangkatan, kapal sampai di titik karam KM. Gurita. Selama itu juga, kira-kira, saya ‘tersiksa’ di dalam kapal menuju Sabang dan suami saya belum jera, “Lihat itu … lihat.” Perjalanan-perjalanan berikutnya, yang tanpa mabuk, saya baru bisa akui pemandangan memang indah bagi rekaman saya yang sebelumnya seputar jalan raya jalur aspal, padat kendaraan, gedung, dan rumah-rumah. Menuju Sabang benar-benar berbeda. Ini pengalaman baru, bukan biasa.
Teluk tempat kapal akan menyandar adalah lengkung laut menjorok ke darat dengan barisan gunung kecil. Bukit-bukit merelakan warna aslinya diselimuti pekat belantara. Sejajar horisontal adalah gradasi warna, biru gelap lautan, disambung keabu-abuan ‘kaki’ hutan, lalu rimbun hijau dari tua hingga muda kekuningan tersiram keemasan.
Matahari, entah pagi, entah senja, atau sesuai jadwal lalu lintas kapal penumpang Banda Aceh-Sabang, selalu andil mencorak rona pucuk-pucuk hutan. Sinar Surya mengubah-ubah pencahayaan. Paling atas, putih kapas sering melintas berarak-arak membelakangi latar langit kadang cerah kadang gelap, bisa biru muda, bisa abu-abu tua, tergantung masa cuaca. Sampai hari ini, saya masih sering terkesima pada lukisan alam karya sempurna Sang Maha Indah di Sabang, terutama saat di laut, yang dulu satu-satunya gerbang.
Kapal motor akhirnya bersandar. Terima kasih, Tuhan. Saya lega. Saya berusaha tegak antara pusing belum reda dan kapal turun naik semakin hebat karena mesin telah dimatikan. Bahtera tanpa daya mempertahankan seimbang. Kami antrian ratusan manusia menuju sepasang pintu sempit untuk keluar kapal. Tiba giliran, saya melangkah. Melalui pintu menyusuri balok papan penghubung antara kapal dan tanah Sabang di seberang, saya sampai. Saya menginjakkan kaki di tanah pinggir Barat Indonesia.
Sabang, aku, warga barumu, datang.
Sumber foto : jack-warwer.com
Ikuti tulisan menarik Wulung Dian Pertiwi lainnya di sini.