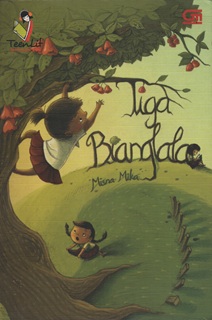Putu Wijaya Dahulu Kala: Tiba-Tiba Malam
Senin, 20 Juni 2022 13:27 WIB
Novel percintaan dengan latar budaya Bali yang ditulis Putu Wijaya dengan gaya konvensional ini justru enak dibaca. Ia menampilkan kompleksitas manusia lebih jauh. Lalu apa itu cinta? Apa artinya kesetiaan?
Upacara pernikahan antara Sunatha, seorang guru SMP yang gemar menyanyikan lagu-lagu tradisional, dengan kembang desa, Utari, menjadi pembicaraan seluruh desa. Kenapa Utari bersedia dinikahi Sunatha. Apalagi esok hari Sunatha harus berangkat ke Kupang untuk mulai mengajar di sana. Aneka gosip bertebaran. “Aku kira Sunatha tadinya wangdu (impoten), akhirnya dapat Utari, hebat juga dia,” ujar salah seorang pemuda di Balai Desa. Dan salah satu yang paling kecewa adalah Ngurah, seorang saudagar muda yang sudah lama menaksir Utari. Ia sudah mempersiapkan segalanya, tapi ternyata Utari memilih Sunatha.
Pada malam hari, di tengah pertunjukan Drama Gong, Renti – pengawal Ngurah—berusaha mencari kesempatan untuk menemui ibu Utari. Kesempatan itu akhirnya didapatnya. Renti mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya dan menyerahkan bungkusan itu. “Mengapa Utari dilepas?” kata Renti. “Bodoh. Sudah dibelikan mobil. Dibikinkan rumah. Apalagi yang kurang? Kok dilepas begitu saja!”
Perempuan itu mulai mengerti. Tapi ia menanggapinya dengan basa-basi. “Wayan sudah dewasa, takut kasep. Ini apa?” kata Ibu Utari sembari mengacungkan bungkusan yang baru saja diterimanya.
“Simpan saja. Nanti kalau sudah sampai di rumah dibuka,” jawab Renti. berusaha memengaruhi ibu Utari, jangan-jangan Utari terkena guna-guna. “Lihat nanti kalau guna-gunanya sudah luntur!”
Pada malam pertama, di dalam kamar, terjadi aneka dialog yang intinya menggambarkan bahwa mereka saling menyintai. “Saya tidak sangsi bahwa kau tidak menganggap perkawinan hanya alat untuk membuat anak, tetapi berjuang...” kata Sunatha dalam salah satu dialognya.
“Dan kamu juga tahu besok pagi saya harus berangkat ke Kupang untuk memikul tugas mengajar di sana. Kamu tidak menyesal?” tanya Sunatha. Utari menggeleng. Sunatha tidak bisa membawa Utari ke Kupang karena di sana belum tersedia perumahan. Ia hanya berjanji akan membawa ke sana jika semuanya sudah siap.
“Besok pagi kita harus bangun pagi-pagi benar, sebab dari sini ke pelabhan memakan waktu enam jam. Saya tidak boleh ketinggalan kapal. Kita harus banyak beristirahat. Saya tidak mau kamu menanggung risiko sepeninggal saya nanti. Jadi apapun kata orang nanti, biarlah kita tidur terpisah malam ini.. nanti kalau kita sudah bersama-sama, kita akan berbuat sebagai suami-istri. Saya minta kamu memahami hal ini,” ujar Sunatha.
Sunatha mencium jidat istrinya. “Tidurlah,” katanya. Lalu dia membaringkan tubuh istrinya di tempat tidur. Kemudian dia sendiri mengambil tikar dan menggelarkannya di lantai. “Saya tidur di sini. Tetapi hati kita telah bersatu,” katanya lagi. Keduanya kemudian lama tak bicara. “Tuhan, saya tahu dia menghendaki lain, tapi apa boleh buat,” gumam Sunatha. Utari menangis sepanjang malam.
Esoknya, keluarga besar kedua mempelai menuju pelabuhan, mengantarkan Sunatha yang hendak ke Kupang. “Kuatkanlah hatimu. Sering-sering kirim kabar,” kata Sunatha. Utari tak menjawab. Sunatha memegang lagi tangan Utari. “Wayan, saya percaya kepadamu. Kamu ingat apa yang saya katakan semalam? Saya minta supaya terus berhati-hati. Kalau ada apa-apa tulislah surat.” Utari tidak menjawab. Waktu sudah habis. Perpisahan itu tidak bisa ditunda. Sunatha berjalan naik ke atas kapal.
Dalam perjalanan pulang, Utari menangis berkepanjangan. Ibu dan bapaknya tidak mampu membujuk. Pengantin itu baru benar-benar sadar apa yang telah terjadi. Ia sedang menyesali apa yang sudah dilakukannya. Meskipun ia masih tetap perawan, toh orang-orang telah menganggapnya sebagai milik orang lain.
“Saya mau pulang. Saya tinggal di rumah saja. Saya sudah diguna-guna,” kata Utari tiba-tiba. Ia menangis makin keras. Akhirnya berteriak-teriak. “Saya tidak mau! Saya mau pulang! Saya sudah diguna-guna!” teriak Utari lagi. Keadaan dalam bus makin kacau.
Di atas kapal, Sunatha bertemu dengan seorang guru yang juga sedang berpindah tugas ke Kupang. Mereka cepat menjadi akrab. “Saya kira saya sudah keliru,” kata Sunatha kepada rekan barunya. “Kalau Anda menjadi saya, apakah Anda akan tega meninggalkan isstri Anda sesudah malam pertama?”
Orang itu tersenyum. “Itu tergantung masing-masing.”
“Apa tali perkawinan cukup menjadi jaminan untuk mengikat?” tanya Sunatha.
“Tentu saja. Kalau memang saling menyintai.”
Sunatha termenung. “Saya sudah lama tidak percaya pada cinta. Justru karena itu saya cepat mengawininya, saya takut dia diserobot orang. Banyak sekali yang ingin dengan dia.”
“Lebih aman kalau bisa saling percaya.”
“Itulah soalnya. Saya tidak percaya pada dia, karena dia cantik dan terlalu muda. Muda sekali, sehingga saya tak mungkin akan menyalahkannya seandainya pun dia tertarik lagi pada orang lain. Dan saya tahu siapa orangnya itu.”
Orang itu menepuk-nepuk Sunatha. “Jangan terlalu dipikir, nanti tidak bisa kerja di sana. Kata orang, wanita tidak pernah akan melupakan lelaki pertama yang menggaulinya. Jadi percaya saja. Anda kan sudah sempat melewatkan malam pertama dengan dia, itu tidak akan mudah dilupakan oleh seorang wanita.....”
Mobil yang mengantar Sunatha sudah kembali ke desa. Utari ternyata masih terus ribut. “Aku tidak mau. Aku mau pulang! Aku sudah diguna-guna!” teriaknya. Ibu dan bapaknya berusaha menenangkan, tapi tidak berhasil Begitu juga Subali, ayah Sunatha, dan istrinya, yang berusaha menenangkan, juga tidak berhasil. “Aku mau pulang. Bawa aku pulang!” teriak Utari.
Orang-orang mulai berkumpul. Subali memegang Utari agak kasar dan hendak menariknya ke dalam rumah. Utari memekik. Ibunya cepat memegang. “Sudahah, biarkan dulu dia pulang, nanti kalau sudah tenang saya bawa lagi kemari,” kata ibunya.
Subali menggeleng. “Ini menantu saya, saya bertanggung jawab. Buruk atau baik, sayalah yang harus memeliharanya selama Sunatha tidak ada.”
“Tapi dia ingin pulang.”
“Rumahnya sekarang di sini. Makan atau tidak makan dia harus di sini.”
Utari meronta. “Aku mau pulang! Aku sudah diguna-guna!”
Subali memegangnya dengan keras. “Diam! Kamu bilang apa! Itu fitnah”
Perang mulut mulai terjadi. Ayah dan Ibu Utari mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pertengkaran antar-keluarga itu tak terelakkan.
Pengawal Ngurah lari untuk mengabarkan hal itu pada Ngurah yang sedang latihan menabuh gamelan di Balai Banjar. Orang semakin banyak berkumpul. Tak sadar Subali menampar menantunya. Ayah Utari segera campur tangan menarik tangan anaknya.
“Baik!” teriak Subali. “Sejak dulu orang selalu menyebar fitnah atas keluargaku. Kamu mau kawin dengan Sunatha secara baik-baik, sekarang kamu tuduh anak saya mengguna-guna, setelah dia tidak ada din sini untuk membela dirinya. Ini pasti ada orang yang campur tangan....”
Utari akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Singkatnya, Utari dan Ngurah kini makin akrab. Kepada bapak-ibunya dan Ngurah, Utari menceritakan bahwa dia belum diapa-apakan oleh Sunatha. “Dia wangdu! Aku tidak mau lagi ke sana. Aku tidak mau!” Ibunya terdiam mendengar pengakuan anaknya.
Sampai di sini, bagi para pengkaji atau kritikus sastra yang senang dengan semiotika, terutama dengan teori Roland Barthes, tentu bisa menerangkan banyak hal dari bahasa-bahasa yang digunakan dalam novel ini, terutama yang digunakan oleh Sunatha dan Utari. Kata atau kalimat sebagai “tanda” memang bisa punya makna yang luas. Tetapi saya mengambil “jalan lain” untuk menikmati dan memahami novel ini.
***
Cerita selanjutnya adalah aneka peristiwa yang terjadi di desa. Tentang percintaan Sunithi dan Weda. Tentang Ngurah yang membawa Utari ke Tabanan. Tentang tradisi kerja bakti di desa. Putu juga menyisipkan tokoh David, orang asing yang selalu mencatat dan memotret semua kejadian yang dilihatnya. Tak cuma itu, David juga sering berdiskusi dengan Subali tentang berbagai hal, termasuk apa yang layak dan tidak layak dijalani dalam hidup Subali. Apa yang dikatakan David benar-benar mempengaruhi kehidupan Subali, sehingga ia dibenci oleh warga desa. Juga cerita tentang surat-surat Sunithi kepada Sunatha. Tentu saja juga tentang hubungan Ngurah dan Utari yang semakin mesra.
***
Sunatha akhirnya pulang. Tapi karena sudah sore, ia terpaksa numpang tidur di cafetaria. Ia mulai akrab dengan Sunari, anak pemilik cafetraia. Malamnya mereka pergi ke pasar malam. Pada malam yang sama, Sunithi menunggu mayat ibunya. Ada beberapa tetangga yang berani datang membantu, termasuk Weda. Anggota banjar yang lain tahu apa yang terjadi, akan tetapi tak ada yang mau datang. Ia sudah berlari ke tukang pukul kentongan. Tetapi orang tua itu menolaknya tatkala tahu yang meninggal adalah istri Subali. Maklum, Subali sudah dikeluarkan dari krama desa.
Pagi-pagi buta, Sunatha naik bus menju Tabanan. Ia tidak henti-hentinya berpikir sepanjang jalan, Sunari yang dikenalnya baru satu hari, telah memberikan pengertian yang begitu dalam. Ia merasa memiliki harga diri kembali.
Dalam perjalanan ke desanya, tiba-tiba Sunatha tertegun. Ia melihat sejumlah kecil orang sedang menggiring mayat ke kuburan. Tidak ada bunyi angklung. Tidak ada yang mengiringi,. Hanya beberapa orang saja yang memikul. Begitu sederhana dan aneh. Sunatha terkesima. Terhenyak. Ia melihat adiknya, bapaknya, dan Weda. Ia cepat mengerti apa yang terjadi. Dadanya tiba-tiba seperti ditebas. Sambil mengangkat kopornya, ia berlari menghampiri.
“Nyomam! Nyoman!”
Sunithi terpekik melihat kedatangan Sunatha. Orang-orang yang dekat di situ sekarang dengan terang-terangan menonton. Mereka memperhatiokan dengan mata melotot. Tidak ada yang merasa kasihan. Mata mereka mengandung kebencian. Mata mereka menaruh dendam.
Penguburan itu akhirnya diteruskan. Sunatha memaklumi apa yang terjadi. Weda ikut membantu menerangkan. Kalau penguburan ditunda lagi, segalanya akan kacau. Sudah jelas penduduk desa tidak akan datang. Tidak seorang pun berniat untuk membantu. Jadi mau tak mau mayat itu, harus diselesaikan seadanya saja.
Sunatha terpaku kehilangan akal. Di atas gundukan tanah. Sunithi memeganginya. Bayangan malam mulai turun. Sore menggelap. Para tetangga yang menolong, setelah menyelesaikan tugasnya, cepat-cepat kembali pulang. Tinggal Subali dan Weda. Waktu itulah Sunatha tidak bisa menahan perasaannya. Ia tidak melihat mertua dan istrinya hadir.
“Jangan ditutup-tutupi lagi Nyoman, mengapa mereka tidak datang?”
Sunithi hanya menunduk. Weda coba untuk bicara. Weda akhirnya menejelaskan bahwa Utari sedang berada di Tabanan untuk berobat bersama Ngurah. “Bangsat,” kata Sunatha. Ia tidak bicara lagi. Ia bergegas pergi, mencari istrinya. Sunithi dan Weda mengikutinya dari belakang.
***
Sunatha langsung saja menggebrak kedua orang tua itu. “Mana istriku! Mana!” teriaknya. Mertuanya itu ketakutan. Mereka tidak bisa menjawab. “Jangan sembunyikan istriku. Mana istriku? Kalau tidak setuju, dari dulu bilang! Saya akan tuntut ini di pengadilan! Melarikan istri orang. Bangsat!”
Sunatha memaki-maki. Kesadarannya sudah mulai hilang. Saat itu Ngurah datang. Guru itu menjadi kalap. Ngurah yang langsung turun untuk mendamaikan, dianggapnya menantang. Sunatha langsung menghajarnya. Akhirnya terjadi perkelahian. Renti yang kemudian datang lalu menghajar Sunatha. Ia bukan lawan yang seimbang buat Sunatha. Untunglah Kepala Desa datang melerai. Penduduk yang datang berkerumun juga beteriak-teriak hendak mengganyang Sunatha. Tapi Ngurah justru menenangkan mereka. Kalau tidak barangkali Sunatha habis saat itu juga.
***
Fajar hampir tiba. Sunithi terbangun dengan badan bersimbah peluh. Ada perasaan aneh menjalari tubuhnya. Ia menengok ke balai-balai. Sunatha masih tidur di situ. Subali tidur sambil duduk di lantai. Weda juga tidur di sudut yang lain. Semuanya tampak lelah. Sunithi merasa kepalanya aneh. Ia mencium bau yang tidak enak.
Sunithi membuka pintu perlahan-lahan. Dingin udara di luar menerobos masuk. Sunithi mencium kembali bau yang aneh itu. Bulu kuduknya berdiri. Seakan-akan nyawa ibunya belum hendak berangkat dari rumah. Ia melemparkan segala kenangan pedih itu. Ditutupnya pintu kembali dengan hati-hati. Ia hendak menjerang air di dapur.
Tiba-tiba ia terhenyak. Di tengah halaman, ada sesuatu. Dadanya memukul kencang-kencang. Ia ketakutan. Seluruh tubunya lemas. Ia tidak bisa bicara sepatah pun. Matanya melotot. Kemudian ia mendorong pintu. Masuk dengan gelagapan. Dibangunkannya Weda.
“Bangun! Bangun!”
Weda tersentak. Sunithi cepat mendorongnya ke pintu. Lelaki itu terhuyung-huyung ke luar. Ia mengusap-usap matanya. Tapi waktu ia menoleh ke halaman, mulutnya jadi ternganga. Seluruh tubuhnya seperti disiram air poanas.
Di tengah halaman itu, menggeletak mayat yang kemarin mereka kubur.
***
Subali menangis tersedu-sedu. Sunatha dengan susah payah bangun. Waktu ia melihat buntalan tubuh ibunya itu, seluruh kekuatannya bangkit kembali. Ia berdiri dengan mata hampir copot. Garang dan meluap-luap. Ia berteriak seperti anjing. “Ini perbuatan Ngurah! Bangsat!”
Dengan galak kemudian ia menyambar kapak yang disampirkan di dapur. Ia berlari ke pintu hendak ke luar pekarangan. Weda dengan cepat menahanya. Sunatha meronta-ronta. Sunithi turut memeganginya. “Lepas! Lepas! Aku bunuh dia!”
“Jangan beli, jangan!”
“Biar!”
Sunatha meronta lagi. Tenaganya sangat kuat. Weda kewalahan memeganginya. Waktu itulah Subali ikut bergerak. Ia ikut memegangi tangan Sunatha.
“Jangan!”
Sunatha jadi lemah mendengar suara bapaknya. Ia berhenti meronta. Lalu Subali mengambil kapak itu dari tangannya. Tubuh Sunatha masih gemetar. Weda berbisik di telinganya, sambil menunjuk ke luar.
“Lihat!”
Sunatha tertegun. Kemudian ia melongok ke luar. Baru jelas apa yang ada di sana. Di sepanjang jalan di depan pintu rumahnya, telah penuh orang. Mereka semuanya membawa senjata. Senjata-senjata tajam, seakan-akan mereka sedang menunggu musuh. Seluruh tubuh Sunatha jadi lemas. Hilang seluruh kemarahannya. Ia menatap semua orang dengan sedih. Kini mulai datang kesadaran.
Orang-orang desa itu, tidak dihasut olehj siapa-siapa. Pemimpin mereka adalah adat yang berlaku dan sama-sama mereka hormati. Subali telah dikeluarkan oleh desa. Berarti ia tidak berhak lagi untuk mempergunakan milik desa. Termasuk tanah kuburan. Ini harus diakui. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun terhadap siapa saja.
Sunatha menarik nafas panjang-panjang. Sekarang kebesaran jiwanya, ketabahannya, kejantanannya sedang diuji. Ia mengangguk kepada bapaknya. Kemudian ia berlajalan perlahan-lahan ke depan orang banyak itu dengan tangan terbuka.
Sepi sekali jalanan, meskipun begitu banyak pasang mata, pasang tangan yang siap mempergunakan senjata. Kalau saja satu orang berteriak, mungkin kesunyian itu akan berubah menjadi air bah. Tetapi muka Sunatha kelihatan begitu tulus. Jujur dan los. Semua orang menantinya dengan diam. Sunatha mencari-cari, kepada siapa ia harus bicazra. Akhirnya ia mengucapkan kata-katanya pada semua orang.
“Saudara-saudara, kawan-kawan semua. Para sesepuh desa, saya dan bapak saya sekeluarga, menyerahkan diri saya untuk diadili oleh desa. Keluarga saya, bapak saya, telah melakukan kesalahan yang besar terhadap adat, sekarang Hyang Widdhi Wasa sudah menjatuhkan hukumannya. Saya terima semua ini dengan penuh pengertian. Seandainya pun belum cukup, ijinkanlah saya meminta maaf, atas kekeliruan bapak saya. Juga kesalahan-kesalahan saya sendiri. Hukumlah kami sesuai dengan kesalahan-kesalahan kami, akan tetapi satu permintaan saya, janganlah buang kami dari pergaulan desa, berikan kami kesempatan sekali lagi. Ini semua adalah pelajaran yang berat bagi kami. Dan ijinkanlah ibu saya beristirahat dengan tenang. Biar saya sendiri sajalah yang memikul semua ini!”
Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanyan lagi. Semua orang terdiam. Subali duduk bersila. Menangis dan menundukkan kepalanya di tengah jalan. Pada saat itu muncul Ngurah. Mukanya benjol-benjol seperti Sunatha. Semua orang terkejut. Mereka menyangka akan terjadi sesuatu. Tetapi sebaliknya dari yang diduga, anak muda itu langsung mendekati Sunatha dan menjabat tangannya. Mereka bersalam-salaman. Kemudian Ngurah berbicara kepada orang banyak.
“Saudara-saudara, ijinkanlah permohonan saudara kita ini. Dia tidak bersalah, keadaan telah begitu rupa, sehingga kita telah sama-sama bodoh. Itulah yang salah,” kata Ngurah.
Kepala Desa kemudian datang juga. Orang tua itu tak banyak berkata-kata. Dia menenangkan orang-orang. “Kawan-kawan,” katanya. “Anak ini telah meminta maaf, kita hormati dia, sebagai orang yang berkelakuan baik. Lihat, bapaknya pun telah menyesal, benar kamu menyesal?”
Subali menganggukkan kepalanya.
“Jadi, mari kita kuburkan dengan sepatutnya, istrinya yang tidak bersalah itu. Hari ini kita sudah banyak belajar, bagaimana caranya hidup bersama-sama sekarang.”
Orang-orang banyak mulai bergerak. Mula-mula mereka bercakap sesamanya. Kemudian Kepala Desa memberikan perintah-perintah. Perdamaian itu mereka sambut dengan baik. Meskipun memang ada juga yang menggerutu. Renti, misalnya.
Hari itu juga, penguburan dilakukan kembali dengan patut.
***
Ada lagi yang lebih sulit buat Sunatha. Ngurah menceritakan semuanya dengan jujur. Sunatha mendengarkan sambil menahan rasa sakit. Tetapi ia mengerti, tak ada lagi yang bisa dicabut setelah terjadi. Ia hanya berusaha menghargai ketulusan Ngurah. :”Sekarang terserah pada Sunatha, bagaimana,” kata Ngurah.
“Saya cuma ingin bertemu sekali lagi dengan Utari.”
“Tapi jangan menyalahkan dia.”
Ngurah membawa Sunatha ke Tabanan. “Dia tidak bersalah. Saya yang bersalah,: kata Ngurah lagi.
“”Saya kira saya bukan mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin melihat dia,” kata Sunatha.
Utari yang semula takut bertemu Sunatha akhirnya bersedia atas bujukan Ngurah. Tadinya Sunatha menyangka akan sanggup bicara banyak. Ia sudah menyiapkan kata-kata bijak. Tetapi begitu melihat perut Utari, hatinya jadi ringsek. Ia tidak bisa bicara lagi. Mereka hanya berdua dalam ruangan. Mereka tidak saling berkata-kata. Akhirnya Sunatha berdiri. Ia memandang lagi perut itu. Lalu bertanya, “Sudah berapa bulan?”
Tak didengarnya jawaban Utari. Sunatha bergerak perlahan-lahan. Rasanya ia telah melepaskan semuanya. Tak ada lagi yang menarik di Tabanan. Tak ada lagi yang mengesankan di desa yang disebut rumah. Tak ada lagi yang pantas mengekang dia untuk tinggal lebih lama.
***
Selepas panen, Sunatha datang ke tempat Ngurah. Gilirannya kini untuk bicara terus terang. Ia telah memutuskan yang terbaik baginya.
“Saya serahkan Utari dengan rela,” ujar Sunatha.
Ngurah menerima pernyataan itu dengan wajar. Ia menjabat tangan Sunatha.
“Benar-benar dengan rela?”
“Ya.”
“Terima kasih, Mudah-mudahan Hyang Widdhy membalas keluhuran budi seperti ini. Saya terima Utari. Saya akan merawat dia sebaik-baiknya.”
“Tapi ada satu permintaan saya.”
“Apa itu?”
Ngurah menatap Sunatha dengan hati berdebar-debar. Tetapi guru itu tenang saja.
“Saya hanya minta supaya Utari dikawin secara resmi.”
Ngurah tersenyum. Ia menyanggupi.
“Saya akan cepat lagi berangkat ke Kupang. Saya ingin menghadiri perkawinan itu,” kata Sunatha lagi.
“Tapi sebelum itu harus ada perceraian.”
“Ya.”
“Apa Sunatha minta syarat?”
“Tidak.”
“Terima kasih. Saya merasa malu karena sikap semacam ini.”
Mereka bersalam-salaman lagi, meskipun hati Sunatha hancur.
***
Upacara pernikahan Utari dengan Ngurah benar-benar dilaksanakan. Sangat meriah. Pemuda-pemuda tidak iri lagi. Karena Utari di tangan seorang yang mereka anggap layak. Tidak seorang pun yang berusaha untuk mengerti bahwa semua itu terjadi karena kebaikan hati Sunatha. Juga tidak ada seorang pun yang membenci Sunatha. Peristiwa itu berjalan dengan wajar. Ini yang lebih menyakitkan hati Sunatha. Tadinya ia menyangka dengan mengikuti segala nasehat rekannya, Badung – untuk membesarkan jiwa – ia akan menerima kehormatan sebagai pahlawan. Sebagai orang bijaksana dan pantas diteladani. Ternyata tidak. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka merasa semuanya itu wajar. Hanya Sunithi, adiknmya, yang benar-benar mengerti apa yang dialami dan dirasakan Sunatha.
Pada malam perkawinan itu, Sunatha menonton Drama Gong. Ia ingat benar bagaimana semuanya mulai. Ingat kata-kata yang ia lepaskan dalam kamar pengantin. Kata-kata itu menjadi kosong. Barangkali Utari bukan orang yang bodoh. Gadis itu hanya menghendaki sesuatu yang lain.
“Wangdu!”
Ia menoleh. Di sana berdiri Renti. Orang itu sengaja melepaskan kata-kata itu di tengah orang banyak. Beberapa wanita yang kebetulan ada di sana cekikikan. Sunatha terbakar. Ia ingin sekali berteriak. Ia ingin sekali membuka celananya dan membantah semua itu. Tapi Sunithi kemudian datang. Ia memegangi kakaknya.
“Biar saja beli,” kata Sunithi.
“Aku akan berangkat secepatnya,” ujar Sunatha.
“Kapan?”
“Besok.”
“Ya, kok cepat sekali.”
“Aku bersumpah aku tidak impoten!”
Sunithi diam saja.
***
Sunatha berada di pelabuhan bersama seluruh keluarganya. Hampir sama seperti dulu. Sunatha menjinjing kopornya. Mukanya kelihatan lebih tua. Di sampingnya ada Weda, Sunithi, dan Subali. Sunatha mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Barangkali uang yang terakhir. Ia memberikan pada Subali. Sunithi hendak bicara, tapi Sunatha memberi isyarat agar diam.
“Sudahlah, tak ada yang harus kita katakan, hidup ini masih panjang, kita jalani saja seadanya tanpa kata-kata besar. Perpisahan ini untuk sementara saja. Tahun depan, mungkin kita belum bisa bertemu, sebab beli harus melakukan tugas-tugas di sana, lagipula sulit sekali rasanya untuk kembali pulang,” kata Sunatha. Ia lalu berpesan agar Weda menjaga Sunithi.
Tiba-tiba Sunatha tersentak. Sebuah sepeda melucur. Seorang gadis langsung turun dan menegur. “Mau berangkat? Sekarang?” kata gadis itu. Ia lalu memperkenalkan diri pada Sunithi. “Nama saya Sunari,” ujarnya. Kemudian ia menjabat tangan Sunatha. Mereka saling berpegangan lama sekali. Sunithi dan Subali meninggalkan mereka berdua. Sunari ini adalah anak pemiliki cafetaria yang ada di dekat pelabuhan. Sejak awal ia menaruh perhatian pada Sunatha.
Sementara dari atas kapal, Kapten menjulurkan kepalanya. Ia melihat Sunatha. Ia mengambil teropong dan mengarahkannya pada Sunari. Kemudian ia mengeluh: “Diincar-incar, yang dapat orang lain.
Selesai.
***
Novel ini bercerita tentang cinta, tentang perjuangan, dengan latar belakang budaya Bali, yang ditulis Putu Wijaya dengan gaya “konvensional” (ditulis tahun 1977). Gaya penulisan seperti dalam novel ini mungkin sulit ditemui lagi dalam cerpen atau novel Putu yang baru.
Tetapi “kesederhanaan” gaya penulisan ini justru mampu memperlihatkan kompleksitas manusia lebih jauh. Kata beberapa filosof, manusia memang penuh misteri. Hubungan antarpersonal juga sering berlangsung rumit. Tentang hubungan dengan sesama ini, kita bisa bertanya, apa sebetulnya arti orang lain bagi kita? Apakah orang lain hanya beban yang menjengkelkan bagi kita?
Dan ketika perceraian makin meningkat, pengkhianatan merajalela, kesetiaan jadi barang langkah, bisa jadi kita pun bertanya: apa itu cinta? Mungkinkah cinta kasih berlangsung selamanya? Apa arti kesetiaan?
Kiranya sudah banyak uraian tentang cinta. Dari kata-kata mutiara, peribahasa, roman picisan, sampai telenovela. Toh, tetap saja masih banyak orang ingin membuka misteri cinta. Bahkan Gabriel Marcel pun ikut berbicara tentang cinta. Filosof asal Prancis ini memang menaruh perhatian serius tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Tentu ia tidak memberi rumus, tetapi menggelar pengertian. Ia mulai dengan istilah "kehadiran" (presence). Jangan salah, "hadir" dalam pengertian Marcel bukan berarti ada di sini, di tempat yang sama, secara konkret. Kata kunci ini tidak boleh dimengerti hanya secara "obyektif" dengan menerapkan kategori ruang dan waktu. Pendeknya, "hadir" tidak selalu harus ada secara fisik.
Sebab bisa saja Anda bersama orang lain di dalam ruang tunggu rumah sakit, pesawat atau kereta api, tetapi belum berarti orang itu "hadir" bagi Anda dan sebaliknya. Bahkan, meskipun Anda dan orang lain itu terjadi komunikasi, omong-omong, belum tentu itu mencapai taraf kehadiran. Sebab belum merupakan kontak yang sungguh-sungguh. Paling-paling komunikasi itu merupakan perjumpaan (recontre) antara "aku" dan "ia" --- orang lain dalam aspek fungsional dan ciri-ciri lainnya, misalnya kondektur, tentara, tinggi, cakep, dan seterusnya.
Dua orang baru hadir yang satu bagi yang lain jika terjadi perjumpaan antara "aku" dan "engkau". Di sini orang lain tidak dipandang sesuai dengan aspek fungsionalnya, tetapi dilihat sebagai sesama manusia, sesama persona. Maka orang lain "hadir" bagi saya jika saya mengadakan kontak yang sungguh-sungguh dengan dia sebagai persona. Tidak sebagai kondektur yang harus melayani saya, atau pejabat yang akan Anda servis.
Dan "kehadiran" ini tampak nyata atau mewujud secara istimewa dalam cinta. Di dalam cinta, "aku" dan "engkau" mencapai taraf "kita", suatu kesatuan yang melebihi dari sekadar penjumlahan satu ditambah satu. Dalam "kita", menurut Marcel, "aku" dan "engkau" diangkat menjadi kesatuan baru yang tidak bisa dipisahkan menjadi dua bagian lagi. Pengikatan diri (engagement) semacam ini mendapat kesempatan paling indah dalam perkawinan, dan memuncak dalam kedudukan sebagai ibu-bapak dengan persatuan cinta keduanya dalam diri anak.
Dalam cinta, "aku" menghimbau kepada "engkau" agar bersedia bersatu sebagai "kita". Begitu juga sebaliknya. Maka "aku" harus bersedia untuk mendengar, menjawab, keluar dari egoisme, untuk membuka diri kepada "engkau". Begitu juga sebaliknya.
Karena kehadiran dalam cinta melebihi ruang dan waktu, maka bisa dimengerti jika sesudah kematian orang yang kita cintai, ia tetap hadir dalam hidup kita. Bisa dimengerti juga bila ada seseorang menunggu dengan setia kekasihnya yang sedang pergi jauh.
Tentu saja relasi semacam itu menuntut keberanian luar biasa dan tetap mengandung risiko. Terutama jika kepercayaan yang satu disalahgunakan oleh yang lain. Sebab godaan untuk berkhianat memang selalu terbuka --termasuk godaan melihat orang lain hanya sekadar sebagai obyek. Maka cinta bisa meleset menjadi eksploitasi. Pendeknya, relasi "aku"--"engkau" ini tetaplah hubungan yang rapuh. Ia mudah jatuh menjadi relasi "aku" -- "ia".
Karena itu, kesetiaan dan kreativitas untuk memelihara cinta mutlak diperlukan. Marcel berharap, kebersamaan dalam cinta tidak terbatas pada suatu saat tertentu saja. Tetapi kebersamaan yang berlangsung terus-menerus. Soalnya adalah, bisakah itu dalam kenyataan? Bukankah banyak faktor lain yang bisa menyebabkan cinta kehilangan cahaya?
Di sinilah cinta tetap tinggal sebagai misteri. Tetapi, kata orang, menyelami misteri cinta bisa membuat hidup lebih berarti.
Selain Gabriel Marcel, diskursus tentang cinta juga diulas panjang lebar oleh Soren Kierkegaard dalam Works of Love. Dalam buku itu Kierkegaard menguraikan soal cinta kepada sesama, cinta dalam agama Kristen, dan tentu saja cinta kepada Tuhan. Juga dalam novel ini, Putu Wijaya berkisah tentang cinta, dengan cara dan gayanya sendiri. Selamat membaca.
- Atmojo adalah penulis yang meminati bidang filsafat, hukum, dan seni.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Drama Nano Riantiarno: Kejujuran dan Penyesalan
Sabtu, 28 Januari 2023 06:50 WIB
Aum Teater Mandiri: Imajinasi yang Meneror
Senin, 9 Januari 2023 18:24 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0


 Berita Pilihan
Berita Pilihan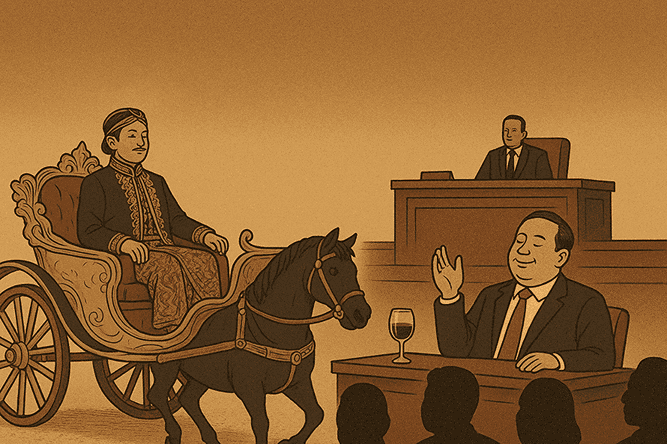






 98
98 0
0