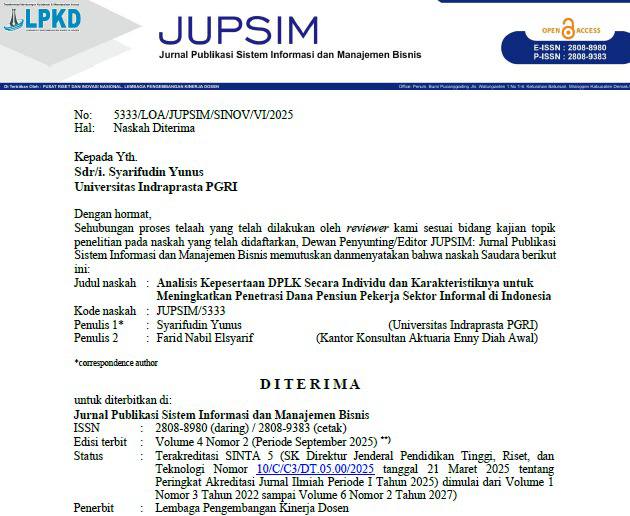Menggugat Malin Kundang
Senin, 15 November 2021 08:42 WIB
“Kalau dongeng itu jangan dibilang ada buktinya. Semua orang yang datang untuk melihat batu Malin Kundang itu pasti kecewa. Kecewa berat, Ma. Batunya ternyata batu bohong-bohongan!”
Memasuki restoran, Rendy menarik tangan Papanya. Rendy mengangkat kepala. Memandang ke atas. Ia menunjuk papan berwarna coklat yang terpasang di tembok samping ruang masuk restoran.
Mengikuti tunjuk anaknya, Mardi menghentikan langkah. Menoleh ke samping kiri. Lalu menoleh pada anaknya.
“Kenapa Malin Kundang namanya?” tanya Rendy melihat tulisan ‘Malin Kundang Resto’ pada papan kecil tertempel di dinding.
“Itu hanya nama restoran,” kata Papanya menjelaskan. Mereka meneruskan langkah. Rendy mengiringi.
“Dia anak durhaka. Mengapa pakai nama dia?”
Mardi tidak menjawab. Sampai di depan meja. Ia menarik dua kursi. Untuk dirinya dan juga Rendy.
Restoran hotel tampak ramai. Sebagian besar meja sudah terisi. Pagi yang dingin memaksa tamu hotel untuk segera menghangatkan kerongkongan dan perut. Dengan segelas kopi atau semangkuk soto padang yang masih mengepulkan asap.
“Kamu mau apa? Nasi goreng atau soto?” tanya Mardi pada anaknya.
“Aku ambil sendiri, Pa,” ujar Rendy. Ia segera berdiri dan berjalan ke meja menu sarapan. Mardi membiarkan. Sudah 10 tahun. Tentu sudah bisa memilih sarapan yang sesuai seleranya. “Hati-hati. Jangan sampai jatuh piringnya.”
Di meja panjang beralaskan kain berwarna biru, teronggok belasan macam menu sarapan pagi. Mulai dari roti tawar berlapis coklat dan mentega, lontong, bubur kacang hijau, lupis dan nasi goreng. Di meja sebelahnya tersusun rapi piring, gelas dan sendok. Di sebelahnya lagi ada water tank air panas. Tersedia cangkir dengan gula dan kopi dalam botol porselen putih kecil. Ada juga creamer sachet dan teh celup.
Rendy sudah ada di depan meja ketika Mardi kembali ke meja. Ia asyik menyuap lupis ketan. Kuahnya bertebaran di pinggir piring dan meja.
“Suka kamu?”
Rendy mengangguk-angguk. Mulutnya pun berlepotan. Lahap sekali.
“Boleh nambah kan, Pa?” tanya Rendy setelah dua lupis di piringnya ludes hanya tersisa kuah.
“Dua lagi?” tanya Mardi.
“Ya, ya,” angguk Rendy cepat.
Mardi memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Meski tanpa suara, Rendy mengerti itu bentuk persetujuan dari Papa. Ia bergegas membawa piring. Tak lama Rendy kembali dengan piring dua lupis di atasnya.
Menghabiskan empat potong lupis dan segelas teh susu, Rendy kekenyangan. Ia menyandarkan badan di kursi. “Mama dan Kak Res kenapa belum turun?” tanyanya. Ia teringat Mama dan kakaknya setelah perutnya kenyang.
Mardi mengakhiri tegukan kopi. “Biasalah mereka. Kalau mandi air panas selalu lama,”
Rendi tertawa. “Oh iya.”
Ketika kemudian Mama dan Resty turun dan mereka pun bergabung di meja untuk sarapan, Rendykembali melanjutkan pertanyaannya yang belum terjawab memuaskan. “Ma, kenapa nama restoran ini Malin Kundang? Dia kan akan durhaka?”
Mama menghentikan suapannya.
“Itu kan hanya nama.” Resty yang menjawab.
“Nama anak jahat kenapa dipakai?”
Mama tersenyum. Melirik Mardi lalu berpindah pada si bungsu. “Malin Kundang itu juga anak yang hebat. Pandai mencari uang. Buktinya ia pulang setelah menjadi pengusaha kaya. Punya kapal sendiri,” jelas Mama.
“Tapi dia anak durhaka,” sanggah Rendy cepat.
“Dia anak yang rajin. Tidak pemalas.”
“Dia jahat sama ibunya!”
Resty menoleh pada Mama. “Itulah, Mama.”
“Kenapa Mama, sayang?”
“Suka ceritain dogeng buruk itu pada dia,” tunjuk Resty dengan dagunya pada Rendy.
“Dongeng buruk?” tanya Papa.
“Iya. Itu cerita yang tidak mendidik. Anak melawan sama orang tua. Eh, orang tua balas mengutuk anaknya. Cerita buruk itu kan,” tandas Resty yang sudah kelas satu SMP.
Papa menggelengkan kepala. Mama menghentikan suapan bubur kacang hijau. Ia tercenung.
*
Seusai menghadiri pesta perkawinan adik sepupu Mama di Lubuk Kilangan, Resty dan Rendy mendesak Papa pergi ke Pantai Air Manis. Mereka mau melihat langsung batu Malin Kundang.
“Kita harus lihat Pa. Batu Malin Kundang itu ada atau tidak. Jangan hanya karangan saja,” ujar Resty yang semenjak kenal dengan cerita dongeng itu ia sudah penasaran.
Jauh-jauh datang dari Dumai tentu bukan hanya untuk menghadiri pesta saja. Mardi sudah janji sama mereka untuk jalan-jalan juga. Di Padang dan Bukittinggi. Semenjak tinggal di Dumai, paling banyak hanya sekali setahun mereka pulang kampung. Pas lebaran. Dan belum pernah pergi ke Pantai Air Manis.
Mobil pun berbelok dan mendaki Bukit Gunung Padang. Lalu kemudian menurun menyusuri Pantai Air Manis.
“Mana batu Maling Kundang itu Pa? Ayo ke sana!” ajak Rendy menarik tangan Papa begitu turun dari mobil.
Rendy dan Papa berjalan duluan. Resty dan Mama mengikut di belakang.
Berada di hamparan batu di pinggir pantai, Resty segera berlari mendekati hamparan batu yang disebutkan sebagai Malin Kundang yang sudah menjadi batu karena dikutuk ibunya.
“Ini batu Malin Kundang itu?” tanyanya heran. Resty memandang tidak percaya.
“Iya. Inilah batu Malin Kundang,” jelas Mama.
Resty membungkuk. Memandangi batu hitam yang sudah berlobang dan pecah-pecah. Tidak jelas lagi wujudnya. Ia menyepak pinggiran batu dengan dengan ujung sepatu. Makin besar pecahnya.
“Bukan, Ma. Ini batu tembok. Tembok biasa,” ujar Resty.
“Inilah batu Maling Kundang itu. Batu yang ada karena kutukan ibu Malin Kundang,” kata Mama lagi.
Resty menggelengkan kepala. “Ini sama dengan batu di belakang rumah. Kena hujan bisa pecah. Lihat ini sudah bolong-bolong. Disepak saja bertebaran pasirnya.” Rendy ikut menyepak-nyepak batu itu.
Papa mendekat. “Cerita Malin Kundang itu hanya dongeng. Cerita dongeng. Ini batu sengaja dibuat untuk dongeng itu,” jelasnya.
“Jadi? Bukan betulan batunya?” tanya Resty. Rendy juga bertanya dengan matanya.
Papa menggeleng.
“Batu ini bukan batu kutukan itu? Bukan yang ada dalam cerita Malin Kundang?” tanyanya lagi dengan mata membulat.
“Bukan.”
“Jadi, Pa. Cerita Malin Kundang itu tidak pernah terjadi? Tidak ada kutukan? Tidak ada batunya?” tanya Resty beruntun.
“Tidak ada.”
“Kenapa dibilang ada batu Malin Kundang di pinggir pantai. Diceritakan ada buktinya batu kutukan itu. Tahu-tahu tidak ada.” Tampak kekecewaan Resty melihat kenyataan berbeda sekali dengan bayangannya.
“Kenapa cerita bohong itu yang Mama ceritakan?” tanyanya kemudian nada kecewa.
Mama dan Papa terdiam. Mereka segera meninggalkan batu di pinggir pantai itu.
“Malas Ires ke Padang lagi,” celetuk Resty saat mereka tengah menyantap kelapa muda di Bukit Gunung Padang.
“Kenapa?”
“Orang sini tukang bohong semua!”
Papa tersedak dengan air kelapa yang tengah diminum. “Heh, kamu itu juga orang Padang,” ujarnya setelah meredakan batuk.
Resty menggeleng. “Kami ini orang Riau, Pa. Bukan orang Padang.”
Papa terdiam.
“Kalian berdua itu orang Padang yang lahir di Riau,” sebut Mama pula.
“Aktenya Riau kan?” tangkis Resty.
Gantian Mama yang terdiam.
Kembali ke hotel, dalam mobil, Resty lebih banyak bermuka muram. Mama yang berada di sebelah, membelai rambutnya. “Kamu kecewa dengan batu Malin Kundang itu?”
“Besok-besok Mama jangan pakai cerita bohong itu lagi. Menyesatkan cerita Malin Kundang itu!”
“Menyesatkan bagaimana?”
“Katanya ada bukti Malin Kundang yang dikutuk sudah menjadi batu. Ada kapalnya juga. Tapi mana ada. Bohong semua. Apa itu tidak menyesatkan?” celoteh Resty dengan jengkel.
“Itu hanya dongeng, sayang.”
“Kalau dongeng itu jangan dibilang ada buktinya. Semua orang yang datang untuk melihat batu Malin Kundang itu pasti kecewa. Kecewa berat, Ma. Batunya ternyata batu bohong-bohongan!” Resty memalingkan muka.
Mama terdiam. Tidak salah juga apa yang disampaikan Resty. Tapi selama ini kenapa tidak menjadi masalah? Tidak ada yang protes.
“Mesti Papa yang protes,” sebut Mama melanjutkan kejengkelan Resty dan Rendy.
“Protes bagaimana?”
“Papa kan suka nulis juga. Papa tulis kalau dongeng Malin Kundang menyesatkan. Mestinya cerita itu tidak dipakai lagi. Jangan dijadikan dongeng anak-anak,” sebut Mama.
“Betul. Betul,” tambah Resty. “Papa tulis di blognya. Di FB atau Twitter. Dongeng Malin Kundang tidak mendidik. Tidak bagus untuk cerita anak-anak. Begitu. Jangan dipakai untuk dongeng anak-anak lagi.”
“Iya, Pa.” Rendy mendukung.
“Atau Papa buat sekalian cerita Malin Kundang lain. Yang ceritanya tidak menyesatkan itu. Tidak ada kutukan itu,” kata Resty pula.
“Aduh, Papa orang Kilang bukan pengarang.”
“Ibu Malin Kundang bukan orang baik ya Ma?” tanya si bungsu pula.
“Kenapa begitu?”
“Masak mengutuk anak menjadi batu. Kalau anaknya salah diberi tahu.”
*
Obrolan di atas mobil dan di Gunung Padang itu menjadi pikiran bagi Mardi. Apa yang disampaikan Resty dan Rendy, ada benarnya juga. Tapi kenapa selama ini ia dan juga orang-orang tidak berpikiran kalau dongeng Malin Kundang itu tidak bagus untuk anak-anak. Orang-orang bahkan sangat membanggakan batu Maling Kundang itu.
Untuk mengingatkan anak-anak agar tidak melawan, tidak durhaka pada orang tua, bisa diterima. Tetapi akhir cerita itu sangat tidak mendidik. Tidak happy ending. Ibu mengutuk anak menjadi batu!
Sepanjang malam, Mardi searching di dunia maya. Mencari-cari adakah orang atau pihak tertentu yang menggugat cerita atau dogeng ke pengadilan. Karena cerita yang tidak baik. Tidak mendidik. Ia juga mencari adakah buku atau novel yang dipermasalahkan hingga sampai pengadilan tersebab isinya. Pun mencari adakah buku-buku yang digugat ke pengadilan.
Mardi berharap ada kasus gugatan terhadap buku karena isinya, kemudian sampai ke pengadilan dan disidangkan. Sebagai sarjana hukum, Mardi melihat ada kemungkinan menggugatkan ke pengadilan. Mempermasalah cerita itu sebagai karya yang tidak baik. Menggugat dongeng Malin Kundang.
Sampai dinihari, sampai tabletnya terasa panas, Mardi tidak mendapatkan apa yang dicarinya. Belum pernah ada orang yang menggugat novel. Apalagi menggugat cerita dongeng. Tidak hanya di negeri ini. Di belahan dunia lain pun tak ada.
Ia tertidur ketika hari sudah berganti nama tiga jam yang lalu.
*
Setengah hari berjalan-jalan di Bukittingi. Setelah makan siang Nasi Kapau mereka melanjutkan perjalanan menuju Payakumbuh untuk kemudian meneruskan menuju Riau. Mardi melawan kantuk habis-habisan sepanjang jalan.
Apalagi ketika melewati jalan tol. Jalan yang lurus dan licin membuat kelopak matanya terasa berat. Sampai di rest area KM 45 Kandis, Mardi tidak turun. Ia lebih memilih tidur dalam mobil. Sementara istri dan anak-anak makan di restoran.
Ia tidak berani tidur dengan mesin mobil hidup untuk menyalakan AC. Mardi segera tertidur dengan mobil terbuka kaca. Dalam tidur ia bermimpi.
Anehnya ia bermimpi jumpa dengan seorang pria. Pria muda yang gagah mendatanginya. Datang ke ruang kerjanya di kantor diantar sekuriti. “Tamu ini mau jumpa Bapak. Heran, namanya Maling Kundang, Pak. Saya lihat KTP-nya memang itu namanya,” jelas sekuriti.
Mardi mempersilahkan masuk. Pria muda itu memperkenalkan diri sebagai Malin Kundang. Mardi percaya. Namun ia tetap bertanya. “Malin Kundang yang mana? Tinggal di mana?”
“Tinggal di Pantai Air Manis. Saya Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu itu,” jelasnya.
“Ada urusan apa dengan saya?” tanya Mardi.
“Tidak benar seperti dongeng itu yang terjadi. Saya pulang dari rantau. Datang ibu menjemput di pelabuhan. Saya pulang membawa istri dan dua orang anak. Ibu terkejut. Rupanya ibu datang bersama seorang gadis yang akan dijodohkan sama saya. Ibu marah-marah. Ia meraung-raung di pelabuhan. Itulah yang terjadi. Saya tidak mencaci ibu. Ibu pun tidak mengutuk saya.”
“Dongeng itu kerjaan pengarang yang terlalu tinggi khayalannya. Mana ada ibu mau mengutuk anaknya. Anak durhaka pada ibu mungkin ada. Tidak ada ibu tega begitu. Mengutuk anaknya menjadi batu! Tidak ada!”
“Saya minta tolong Bapak untuk menggugat pengarangnya. Menggugat penerbit yang memperbanyak buku dongeng yang menyesatkan itu. Menggugat pemerintah Kota Padang yang membangun batu itu!”
“Kenapa minta tolong pada saya?”
“Bapak orang Padang. Tamatan Fakultas Hukum pula.”
Mardi terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada yang memanggil. Ia menggelengkan kepala dan membuka mata. Seorang pria muda di samping pintu mobil. Malin Kundang kah?
“Maaf, Pak. Kami sedang melaksanakan razia narkoba. Tolong SIM dan identitasnya,” ujar pria muda itu.
Mardi merogoh saku bajunya. Bila tengah bawa mobil ia selalu meletakkan dompet kecil berisikan SIM dan surat mobil di suka baju. Biar cepat memperlihatkan pada petugas. Segera diserahkan dompet itu.
“Apa ini, Pak? Kertas apa ini?” tanya pria muda itu.
Dibukanya lipatan kertas itu. Tertulis “Menggugat Maling Kundang”. Pria itu menggelengkan kepala.
“Kami mau SIM dan identitas!”
“Ya itulah semua.”
Pria muda memanggil temannya menyuruh memeriksa mobil. Ia membuka pintu mobil. Membantu Mardi turun dari mobil. "Periksa semuanya!" tegasnya.
“Kita ke pos itu, Pak. Bapak bisa istirahat di sana setelah kita periksa urinenya,” ujar pria itu.
Mardi mengangkat kepala. "Eh, mengapa ke Pos Polisi?" tanyanya. (***)
Penulis Indonesia
0 Pengikut

Menggugat Malin Kundang
Senin, 15 November 2021 08:42 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




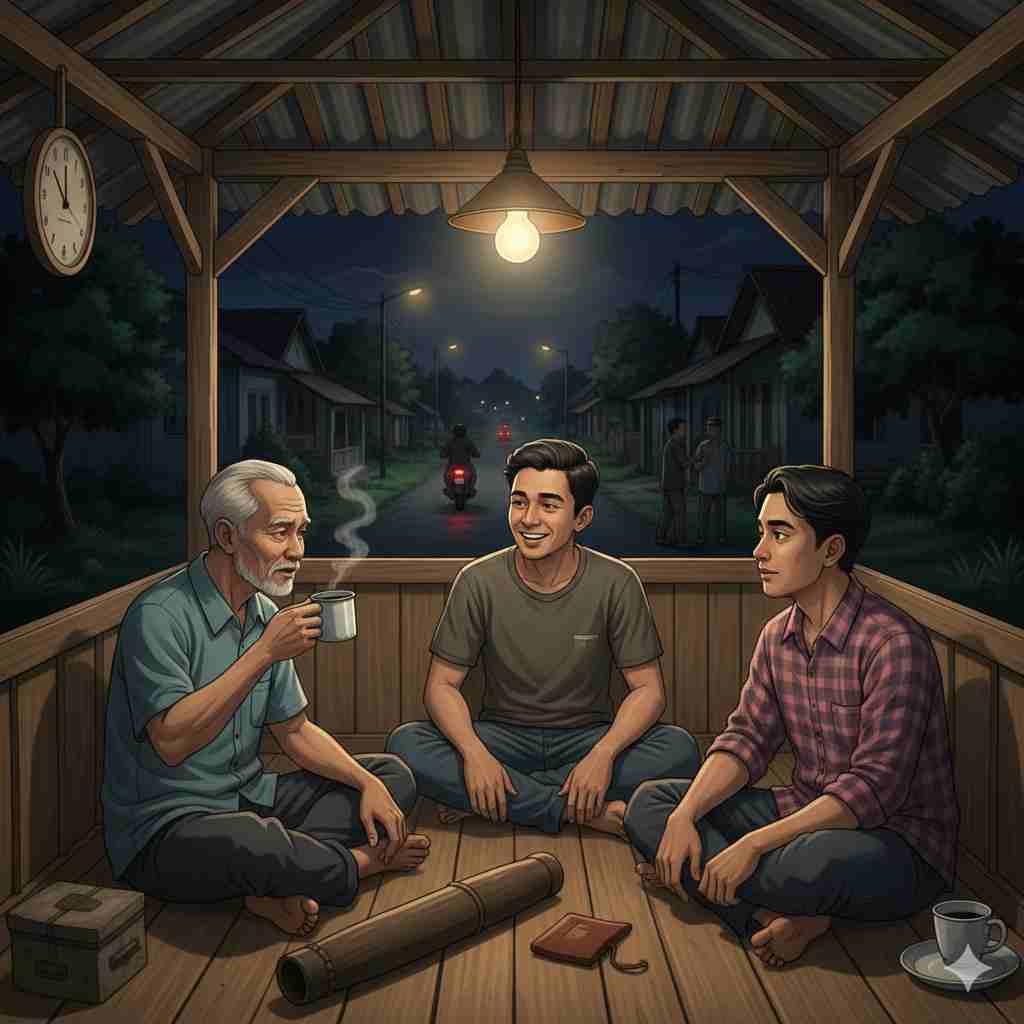

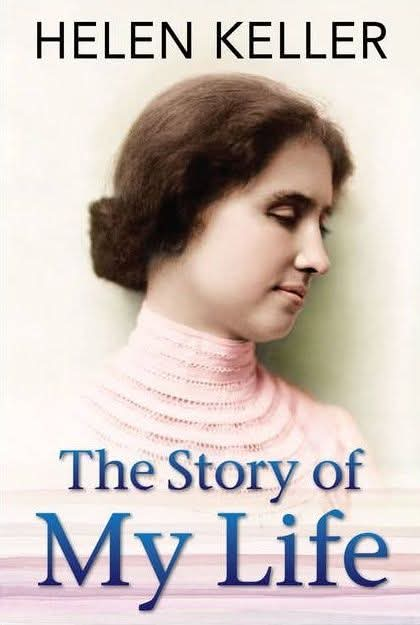
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0