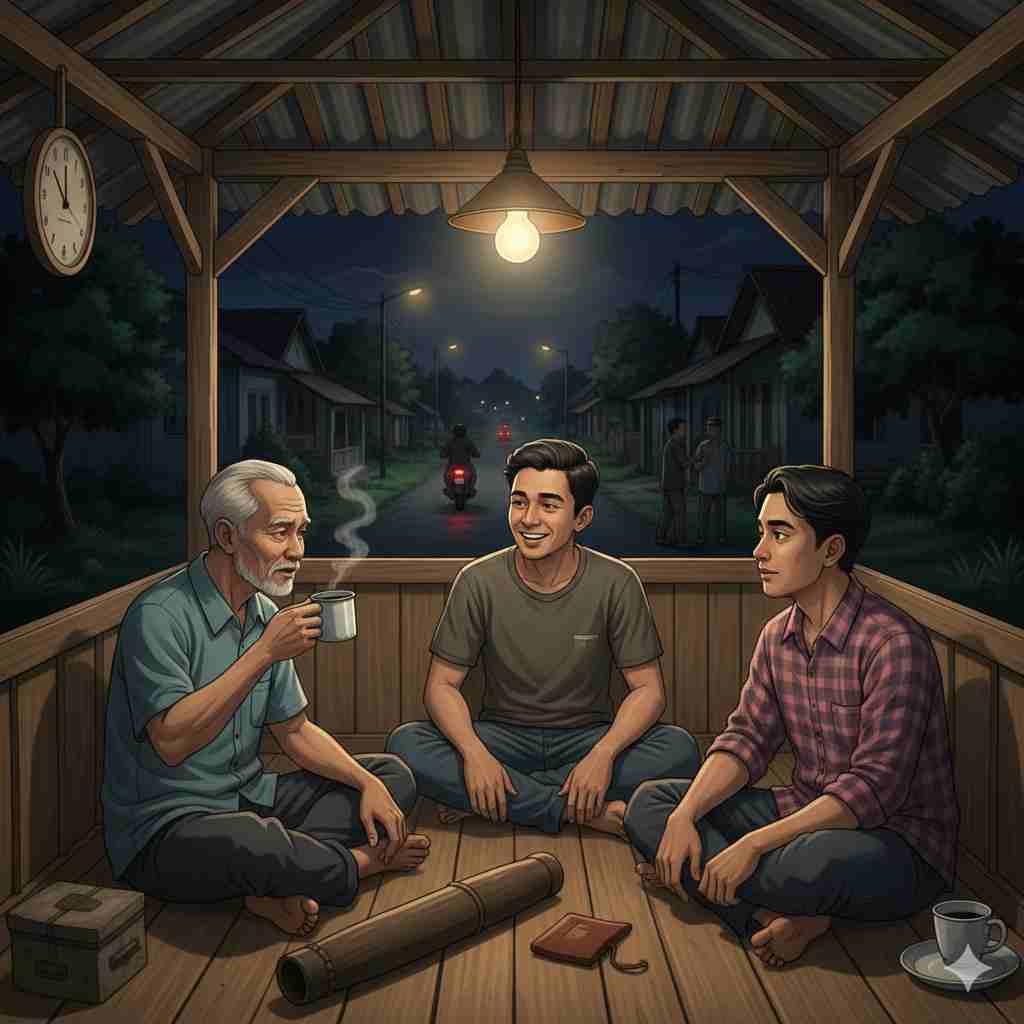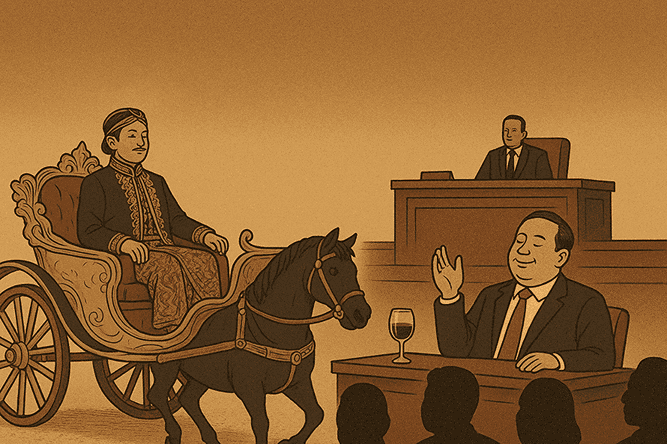The more you take, the more you leave behind.
Apocryphal Stories, Romantisasi dan Kompromi Sejarah
Rabu, 27 November 2024 20:05 WIB
What is history but a fable agreed upon? -- Napoleon Bonaparte (begitulah atribusi umumnya)
***
Setelah menonton kembali film The Last Samurai (2003) yang diperankan dengan apik oleh Tom Cruise, Ken Watanabe, dan sederet aktor/aktris ternama lainnya, saya kembali mengingat bahwa film ini adalah kisah fiktif. Tidak ada latar belakang sejarah aslinya sama sekali. Hanya saja banyak pembelajaran moral yang ingin dititipkan kepada kita yang menontonnya.
Di tengah benturan antara tradisi dan modernisasi, The Last Samurai berhasil menyampaikan kepada audiens tentang pentingnya menjaga nilai-nilai luhur yang membentuk identitas sebuah bangsa. Kita dibawa ikut menjalani perjalanan Kapten Nathan Algren, dimana audiens bisa melihat transformasi seorang pria yang awalnya dipenuhi rasa bersalah gegara tim pasukannya menjadi pelaku langsung pembantaian warga Indian asli, yang di filmnya, ditampilkan korban yang banyak jatuh itu adalah anak-anak dan kaum perempuan, kemudian ia jadi seseorang yang mengalami identity crisis (kehilangan makna hidup).
Long story short, akhirnya ia menjadi seseorang yang memahami makna sejati dari keberanian, penghormatan, dan pengabdian, lewat pembelotannya dari seorang perwira bayaran menjadi samurai kulit putih. Begitulah naratif singkatnya, kurang lebih. Nilai-nilai seperti disiplin, kehormatan, dan kesetiaan yang dipegang teguh oleh para samurai memiliki relevansi abadi, bahkan dalam dunia yang kian cepat berubahnya, karena latar waktu mengambil satu lini masa dengan Revolusi Industri.
Katsumoto, pemimpin samurai, menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus berarti meninggalkan tradisi, melainkan menemukan cara untuk menghormati masa lalu sambil menerima/mengadaptasi era baru, dunia baru, yang bernama masa depan. Sisi paling touching dan memberikan pesan mendalam kalau menurut saya pribadi adalah pada bagian adegan-adegan penghormatan lintas budaya.
Algren, yang berasal dari Barat, belajar menghargai filosofi hidup para samurai yang menempatkan kehormatan di atas segalanya. Bentuk pembelajaran kepada audiens bahwa memahami dan menghormati budaya lain tidak hanya mampu memperkaya batin dari diri sendiri, tetapi juga dapat membantu kita, audiens, menemukan arti hidup yang lebih mendalam. Deep-lah pokoknya. Tapi, balik lagi ke tujuan awal tulisan ini. Apakah itu semua real story? Tidak, jawabannya. Algren itu tidak ada dalam sejarah aslinya. Ia mungkin hanyalah karakter adaptasi dari Jules Brunet. Bagaimana dengan Katsumoto? Juga tidak ada. Dia itu adalah karakter yang diambil dari inspirasi asli Saigō Takamori.
Nah, kisah The Last Samurai itu adalah contoh kecil dari kisah-kisah yang seringkali dianggap memiliki makna budaya atau moral yang kuat, tetapi tidak memiliki bukti sejarah yang dapat diverifikasi. Dengan kata lain, cerita-cerita serupa yang tampil di layar kaca seperti film tersebut mungkin terdengar meyakinkan atau relevan karena mencerminkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh fakta atau catatan sejarah yang valid.
Kisah asli seringnya dibuyarkan oleh romantisasi. Sama halnya seperti kisah The Romance of the Three Kingdoms (Sānguó Yǎnyì) yang merupakan sastra klasik. Produk romantisasi dari kisah asli dari perpecahan politik dari 3 kubu, Wei, Shu, dan Wu, pada periode akhir Dinasti Han.
Ada lagi satu bentuk romantisasi lainnya yang lumayan mendarah daging di berbagai kawasan dan menjadi inspirasi banyak edukator ketika bercerita tentang pentingnya guru dalam pembangunan sebuah bangsa. Salah satunya, yaitu cerita "Kaisar Hirohito bertanya berapa banyak guru yang selamat setelah bom Hiroshima dan Nagasaki". Itu cerita fiktif, ladies and gentlemen.
Cerita itu tidak berasal dari landasan historis asli. Cerita tersebut murni digunakan sebagai spirit booster dan penguat propaganda sakralitas kaisar semata. Agar kepercayaan terhadap kesakralan kaisar, si anak dewa matahari, tidak runtuh, maka dibutuhkan kisah yang bisa menggugah kebangkitan nasional kembali setelah digebuk oleh AS lewat Si Bocah Kecil dan Si Gemoy (tidak ada kaitan dengan karakter perpolitikan di Indonesia ya).
Cerita propaganda itu juga mungkin digunakan untuk menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun kembali masyarakat, tetapi, aslinya, tidak ada bukti kuat bahwa peristiwa bahwa Hirohito bertanya berapa orang guru yang tersisa itu benar-benar terjadi. Cerita seperti ini sering muncul sebagai bagian dari tradisi lisan atau mitos yang memperkuat pesan-pesan yang disebutkan tadi, meskipun aslinya ya tidak benar-benar terjadi.
Sebenarnya ada versi narasi juga yang mengatakan bahwa ada kompromi untuk melindungi posisi kaisar saat Jepang mengangkat bendera putih. Upaya kompromi tersebut adalah agreement dari pemerintah Jepang dan Sekutu (terutama Jenderal Douglas MacArthur) untuk mengubah narasi tentang Hirohito menjadi lebih "manusiawi" dan jauh dari citra pemimpin militer. Hirohito ingin ditampilkan sebagai pemimpin yang tidak terlibat langsung dalam keputusan militer, tetapi lebih sebagai figur pasif dan damai yang mewakili aspirasi rakyat.
Ya, jujur aja malu dong. Udah mulai curi start perang, invasi ke Tiongkok, serangan kejutan ke Pearl Harbour, ekspansi sampai ke daratan Nusantara, eh kekuasaan kaisar terancam juga mau dirombak. Kebayang, ga, kalau Jepang berujungnya jadi Republik?
Itulah sebabnya cerita Hirohito peduli dengan survivabilitas guru adalah sebuah motif narasi yang jelas digunakan untuk melindungi martabat kaisar dan memastikan sistem kekaisaran tetap relevan dalam Jepang modern. Cerita itu pun berujung menjadi produk "propaganda inspirasi moral rakyat". I coined that quote unquote term, by the way.
A lifelong learner, Penulis, Dosen, Investrader,
0 Pengikut

Apocryphal Stories, Romantisasi dan Kompromi Sejarah
Rabu, 27 November 2024 20:05 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
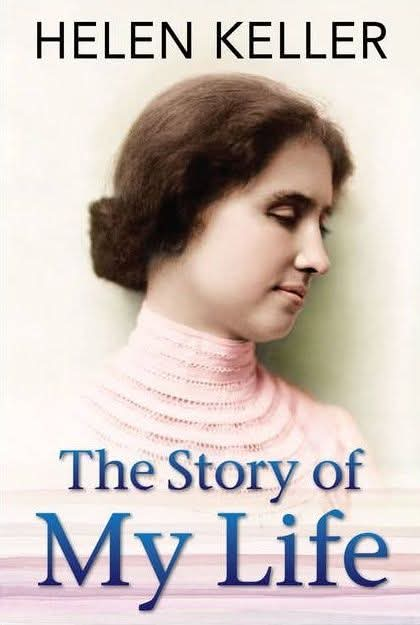
 Berita Pilihan
Berita Pilihan





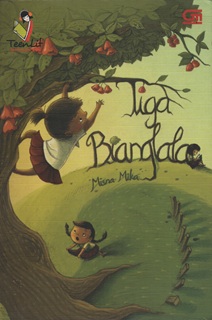

 99
99 0
0