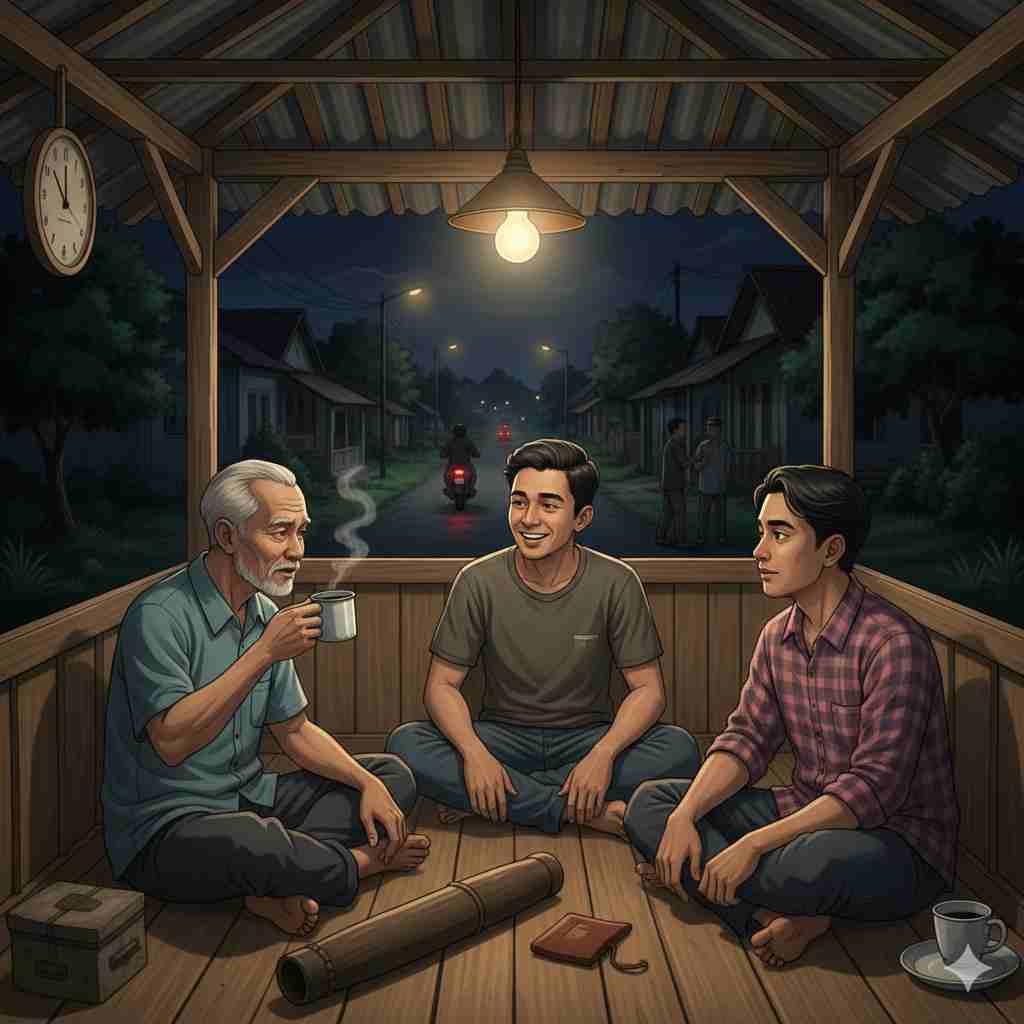Pemerhati politik, hukum, dan demokrasi.
Tragedi Agustus 2025 dan Populisme Politik
5 jam lalu
Ia harus dilihat sebagai kematian cara kita bernegara yang sudah tidak lagi mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan.
***
Republik sedang sakit. Karena itu, ia harus diperiksa apa penyakitnya. Jika kita gagal mengidentifikasi penyakitnya, maka kita juga gagal mengobatinya. Jangan-jangan, selama ini kita gagal mengidentifikasi penyakitnya, sehingga kita juga gagal mengobatinya. Bukannya kita mengobati penyakitnya, tapi malah menambah penyakit baru.
Bongkar pasang sistem dan kelembagaan politik tanpa memperbaiki manusia yang menggerakkannya itu juga hampa, tak hidup. Memperbaiki manusianya tanpa memperbaiki sistem dan kelembagaan politik itu juga tak ideal, tak lengkap.
Good man, good system, and good institution menjadi keharusan. Itu bisa dilakukan mulai dari manusianya, di mulai dari pendidikannya. Dari sistemnya, di mulai dari menutup celah-celah sistem yang kurang. Dari institusinya, di mulai dari membersihkan institusi-institusi yang korup dan feodal. Tanpa melakukan itu semua, sulit untuk mewujudkan tata kelola negara yang baik. Kata Mahfud MD, jangan mengelola negara seperti mengelola warung kopi.
Secara sistem dan kelembagaan, politik kita memang sudah modern, tapi secara mental dan kultur, politik kita masih feodal dan koruptif. Korupsi juga terjadi merupakan akibat dari semua ini. Maka kita harus mulai jujur pada diri kita sendiri, harus mau melihat dari dalam, apa sebenarnya yang terjadi tanpa mengkambinghitamkan kelompok-kelompok kritis.
Tragedi kelam akhir Agustus 2025 harus menjadi pelajaran bersama bagi semua anak bangsa bahwa dalam mengelola negara tidak boleh serampangan, arogan, dan angkuh. Kematian Affan Kurniawan dkk tak bisa hanya dilihat sebagai kematian biologis anak bangsa semata. Ia harus dilihat sebagai kematian cara kita bernegara yang sudah tidak lagi mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Mereka mati dilindas mobil rantis Brimob, di bakar di gedung pemerintahan, dan mati di tangan aparat negara.
Alih-alih melakukan koreksi dari dalam, pemerintah malah membangun narasi ketakutan sambil menggerakkan alat-alat negara, membangun narasi bahwa gerakan itu ditunggangi asing, dibiayai koruptor. Gerakan itu mengarah pada makar dan terorisme. Narasi lama yang di daur ulang untuk mendelegitimasi gerakan dan mempertahankan kekuasaan.
Kita harus mendukung pemerintah membongkar siapa dalang dan yang membiayai gerakan itu, termasuk membongkar akar masalahnya. Kita buka kotak pandoranya. Dengan begitu, kita tahu apa akar masalahnya, siapa yang menunggangi, dan membiayai gerakan itu. Semoga saja bukan orang-orang di sekitar kekuasaan.
Antonio Gramsci menjelaskan, negara bisa hadir dalam dua wajah sekaligus. Ia bisa hadir dalam wajah menakutkan melalui alat-alat negara. Ia juga bisa hadir dalam wajah meneduhkan melalui pendidikan dan agama. Lebih jauh lagi, Karl Marx mengatakan bahwa negara merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme. Alat-alat negara dalam negara adalah untuk menjaga kepentingan kapitalisme. Agama dan pendidikan diproyeksikan sebagai kepentingan kapitalisme dalam negara. Itulah yang disebut sebagai determinisme ekonomi Karl Marx. Determinisme ekonomi Karl Marx itu basisnya ekonomi, suprastrukturnya negara, alat-alat negara, pendidikan, dan agama. Di sini lah, negara bisa hadir dalam dua wajah: keras dan lunak.
Dalam tragedi akhir Agustus 2025, negara mamakai dua cara sekaligus, yakni keras dan lunak melalui alat-alat negara, pendidikan, dan agama. Pemerintah belum menjawab akar persoalan sesungguhnya dari tuntutan rakyat. Tragedi kelam akhir Agustus 2025, tak hanya soal sikap beberapa anggota DPR yang arogan, angkuh, dan tak empati pada kondisi rakyat, malaikan juga akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap perilaku elite-elite politik dan kebijakan pemerintah yang elitis.
Di saat mayoritas rakyat miskin dan pengangguran tinggi, sebagian besar elite-elite politik malah menikmati sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarganya. Ahmad Syafii Maarif (2021) menyebutnya sebagai republik sapi perah, di mana elite-elite politik memeras republik untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Lebih jauh lagi, pendiri bangsa telah mendedikasikan hidupnya untuk republik, penyelenggara negara hari ini mencari makan dari republik (Sukidi, 2021).
Autocratic Legalism
Tragedi kelam akhir Agustus 2025 merupakan cerminan kegagalan negara dalam mengelola negara. Kegagalan mengelola negara tak hanya terlihat pada sikap DPR dan kebijakan pemerintah yang elitis, melainkan juga berakar pada rekrutmen politik, partai politik, dan pemilihan yang terkait langsung dengan ekonomi masyarakat juga pengelolaan negara yang cenderung pada pola autocratic legalism, di mana kebijakan dan produk hukum yang dibuat melewati jalur-jalur politik dan mendapat stempel dari peradilan, namun tidak mendapat legitimasi dari rakyat (Scheppele, 2018). Mereka melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) sebagai prasyarat demokrasi, namun tidak adil dan bebas, bahkan mereka sudah menentukan siapa pemenang Pemilu sebelum dilaksanakan.
Pola autocratic legalism tidak hanya soal mendapat legitmasi rakyat atau tidak dalam kebijakan dan produk hukum yang dibuat, tapi juga bisa diperluas dengan ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi sebagai penyimbang kekuasaan. Atas nama stabilitas politik dan berjalannya pembangunan, mereka mengabaikan check and balance. Akibatnya, sentralisasi kekuasaan eksekutif tak terhindarkan. Hampir seluruh partai politik di parlemen mendukung pemerintah.
Ketiadaan oposisi di satu sisi menumbuhkan gerakan-gerekan oposisi personal-populis atau memunculkan gerakan kelompok-kelompok populis yang tak terhindarkan dan tak terlembagakan dengan baik. Di sisi lain, ketiadaan oposisi telah menciptakan kabinet gemuk di tengah efisiensi karena mengakomodasi semua kepentingan politik. Padahal, dalam sistem presidensial, tak semua kepentingan politik itu harus di akomodasi. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat/menunjuk menteri, dan presiden sulit untuk di impeachment bila tidak dikatakan hampir mustahil. Prosesnya pun panjang.
Itulah Indonesia. Fajrul Falah menyebutnya, di pintu depan presidensial, di pintu belakang parlementer. Alias campur sari.
Pada rekrutmen politik, baik melalui Pemilu maupun melalui panitia seleksi (Pansel) dalam mengisi pos-pos strategis pemerintahan tak terhindarkan dari pengaruh autocratic legalism dan patronase politik. Melalui Pemilu terjadi politik uang dan politik transaksional, yang pada akhirnya berakibat pada korupsi. Melalui Pansel terjadi patronase politik. Rekomendasi ormas, warna bendera, partai politik, dan berbagai kepentingan adalah pola autocratic legalism dan patronase politik yang dibalut secara akademis. Namun, ketika fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR, persoalan sudah menjadi lain: kepentingan dan politis.
Pola autocratic legalism tak berhenti di situ, ia juga bermain pada pengaturan dan budgeting politik atau politik anggaran. Jika MK dan KPK tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah dan DPR, atau mengancam eksistensi elite-elite politik di eksekutif dan legislatif, ia bisa digembosi. Caraanya melalui pengaturan dengan mengubah status lembaga dan pimpinan lembaga melalui revisi UU KPK dan MKdan pengurangan anggaran politik. Pola ini pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada lembaga dan pimpinan lembaga, seperti KPK dan MK.
Populisme Politik
Tragedi kelam akhir Agustus 2025 dan pola autocratic legalism juga berjalin-klindan dengan populisme politik. Francis Fukuyama (2017) mengatakan, tak ada kesepakatan umum untuk mendefinisikan populisme, namun ada tiga ciri utama yang bisa dilihat untuk mengidentifikasinya. Pertama, populisme menerapkan kebijakan jangka pendek yang prorakyat, seperti kebijakan bantuan sosial (Bansos) dan makan bergizi gratis (MBG). Kebijakan ini sering kali tidak mengindahkan stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka panjang suatu negara: menciptakan ketergantungan dan tak memberdayakan.
Kedua, populisme memiliki konsep rakyat yang sempit karena dibatasi identitas, seperti etnis, ras, dan agama. Atau pada pemilih, bukan pada warga negara yang diakui, di jamin, dan di lindungi oleh negara. Donald Trump di Amerika Serikat (AS), Jair Bolsonaro di Brazil, Narendra Modi di India, Jokowi di Indonesia merupakan pemimpin populis prodak dari demokrasi langsung.
Ketiga, populisme membuka jalan bagi otoritarianisme baru. Ketidakpercayaan pada institusi dan polarisasi yang dipicu populisme dapat menciptakan kondisi yang nyaman bagi konsolidasi kekuasaan. Politisi populis dengan popularitas yang tinggi, bisa dengan mudah melumpuhkan institusi demokrasi dan membangun rezim otoriter.
Kita tak ingin menggiring negara ke dalam jurang otoritarianisme baru. Belajar dari tragedi kelam akhir Agustus 2025 agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang sejarah yang sama. Sudah banyak anak bangsa yang di renggut nyawanya, jangan ada lagi korban-korban selanjutnya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Tragedi Agustus 2025 dan Populisme Politik
5 jam laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
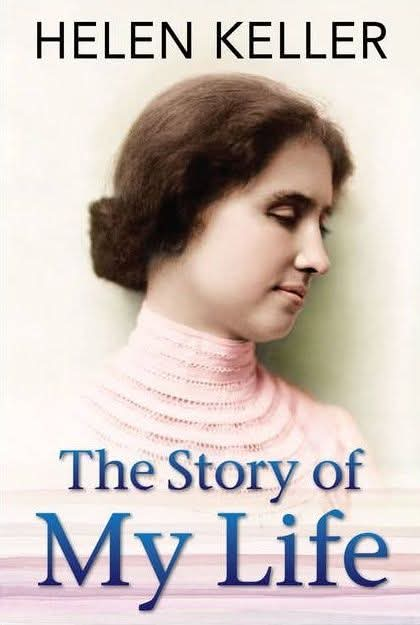
 Berita Pilihan
Berita Pilihan





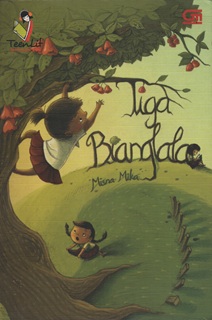

 99
99 0
0