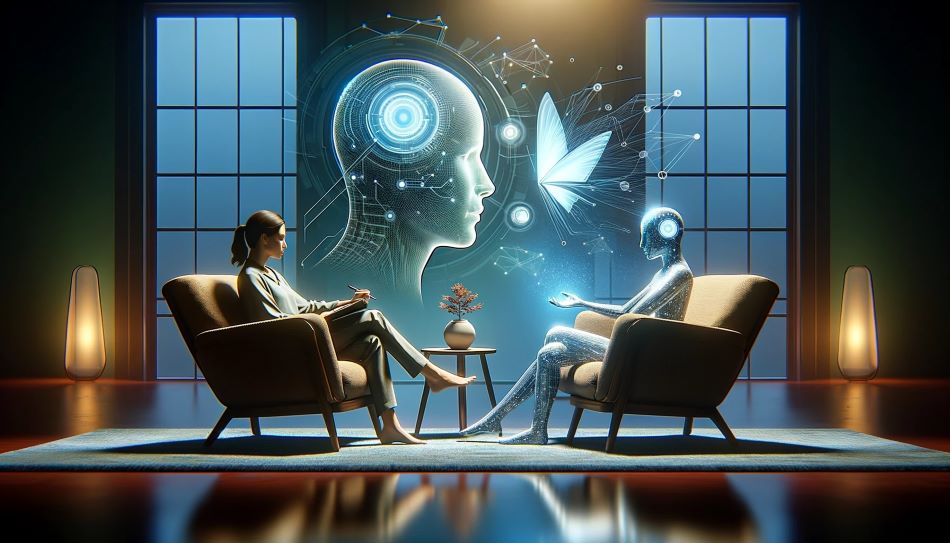Globalisasi, Nasionalisme, Kesukuan
Senin, 9 Maret 2020 13:41 WIB
Buku membabar strategi penyikapan di antara tumpang tindih isu sukuisme, nasionalisme, dan globalisasi. Sehingga, bukan berarti menjadi hilang identitas kesukuannya, tetap membeli produk dalam negeri, dan merancang kerja sama saling menguntungkan dengan orang manca.
Modernitas dan globalisasi, mengandung paradoks. Satu sisi ada lesatan pengetahuan dan inovasi teknologi. Hari ini, seorang yang tinggal di desa terpencil di Jawa Timur, bisa bercakap-tatap muka dengan saudaranya di Arab Saudi. Bertualang di media sosial, sekejap menambah pertemanan dengan siapa pun. Tak terkecuali berinteraksi dengan orang asing. Banyak peristiwa asmara lintas negara-lintas benua terbingkai dari dunia global yang kian menyempit. Menisbikan keterasingan sambil bernarasi dunia memang tak selebar daun kelor.
Ada kebaruan sarana dalam gerak komunikasi. Ketiadaan batas dan sekat geografis sebagai pembeda dari zaman-masa lalu menuai fenomena dengan intensitas interaksi aneka orang, bermacam tipikal adat, serta bahasa-bahasa. Dunia dengan 7,5 milyar penduduk bak aneka makanan yang dihidangkan di satu piring. Pertanyaannya: bisakah menikmati pencampuran kuliner soto khas Indonesia bersama ramen Jepang dan nasi biryani India, sekaligus? Faktanya, pluralitas macam itu kerap menghadirkan konflik; mengkristal dalam dikotomi “orang asli”, “pribumi”, dan pendatang. Tak jarang pula memunculkan kehangatan persaudaraan-persatuan dengan tetap memanggul identitas primordial masing-masing. Atawa, justru meleburkan keberbedaan sehingga membentuk kebudayaan/identitas baru (akulturasi).
Apalagi, hari-hari ini, polemik keberidentitasan kembali menyeruak. Identitas siapa aku; dari mana asal-usulku, serta kaitannya dengan selain aku alias liyan. Negara acap dimaknai sebagai wadah atas keragaman suku dan etnis yang telah mendiami wilayah tertentu. Laiknya Indonesia, negara besar dan luas ini bisa dipahami sebagai imajinasi kebersatuan dalam mencapai cita-cita keluhuran dan penghidupan berkeadilan-berkeadaban. Karena itu, derajat nasionalisme tidak bisa dihadap-hadapkan dengan sentimentil kesukuan. Lantaran, keduanya mempunyai entitas berbeda dan bersifat unik. Idealnya, baik nasionalisme dan kesukuan bisa dirajut sebagai elan berbangsa untuk merajut persatuan tanpa mesti perlu diseragamkan.
Buku tebal ini mengurai sebab-sebab gagal paham cara merajut relasi komunikasi di era globalisasi. Baik surat, telepon, media sosial, adalah sekadar sarana/alat penghubung. Sedangkan, etika dan tata cara berkomunikasi/menanggapi respons liyan, tidak berarti turut menjadi lebih etis-santun. Bukti sahih bisa dilihat dari masih terjadinya stigma superioritas ras/etnis. Sudah berapa banyak pemain sepak bola asal Afrika dilecehkan ketika bermain di lapangan Eropa tersebab soal berkulit hitam legam. Virus Apartheid di Afrika Selatan yang terjadi di abad modern; tahun 1990-an, nyatanya masih tersebar. Konflik berlatar etnis macam Rohingya dan Kurdi, tak kunjung usai di era globalisasi.
Globalisasi memang membuka keterasingan. Jagat kian sesak. Semua orang mesti membuka pintu rumah. Mempersilakan kedatangan tamu dari negeri seberang. Tamu-tamu itu membawa apa yang disebut “ilmu” dan “uang”. Bermodalkan itu, tamu-tamu itu mulai merangsek masuk ke ruang keluarga. Tidur-tiduran di kamar. Memasuki dapur dan kamar mandi. Empunya rumah sebenarnya ingin mempersilakan pulang alias mengusir si tamu lantaran teranggap lancang. Namun, apa daya, si tamu membawa modal banyak (baca: investasi) berniat merenovasi rumah dan membikinkan toko berdalih kerja sama. Saat rumah sederhananya itu telah menjadi ruko megah, si tamu ingin menguasai dan balik mengusir si empu. Konflik pun tak terhindar.
Gambaran inilah yang kerap dijumpa hari ini di banyak tempat berdalih kerja sama ekonomi antarnegara, negara dengan rakyat, dan antarrakyat.
Membincang isu kesukuan, etnisitas, dan nasionalisme, senyatanya selalu aktual sembari butuh pemaknaan baru. Tema-tema tersebut tidak bakal hilang walau terbuncah aneka kesatuan macam Uni Eropa, ASEAN, Liga Arab, dan lain sebagainya. Mengapa? Lantaran tiap manusia lahir di tempat berbeda. Membentuk ciri fisik dan karakter berlainan (hlm: 20). Identitas primordial tersebut terlembaga menjadi budaya yang menyangkut banyak aspek; cara makan hingga penyikapan hidup antara satu suku berbeda dengan suku lain.
Meski demikian, keanekaragaman ini perlu penegasan perihal kesamaan sekaligus sebagai basis kesadaran; bahwa kesemuanya adalah setara dan bersederajat. Buku ini mengurai simpulan bahwa perbedaan tidak perlu dipaksa disatukan. Melainkan lebih kepada kontinyu membuka diri sekaligus membuka ruang mempelajari perbedaan pada diri liyan.
Sehingga, nasionalisme dan kearifan lokal justru perlu terus dihadirkan. Globalisasi mengandaikan ketidakperluan menolak akan datangnya sepatu-sepatu impor. Hanya saja, ada kepastian langkah untuk memosisikan diri perihal amat perlunya mendayagunakan sepatu bikinan anak negeri.
Nasionalisme berkonteks Indonesia yang beranekaragam suku, oleh buku ini, untuk menyorongkan upaya saling memahami dan menghormati nilai-nilai lokalitas masing-masing sembari memegang teguh prinsip kesatuan sebagai orang Indonesia. Lebih penting lagi, buku ini memberikan panduan untuk bersikap moderat dari tumpang tindih globalisasi, nasionalisme, dan kesukuan. Dengan kata lain, orang Jawa, misalkan, tetap perlu menyunggi kejawaannya, meneguhkan keindonesiaannya, dan memerankan sebagai warga dunia secara tepat menyesuaikan konteks dan kondisi di mana ia bertempat tinggal.
Data buku:
Judul: Pengantar Komunikasi Lintas Budaya
Penulis: Prof. Deddy Mulyana, Ph.D
Penerbit: Rosda, Bandung
Cetakan: Agustus, 2019
Tebal: 445 halaman
ISBN: 978-602-446-351-9
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

110 Tahun dari Ranah Minang Membangun Tanah Air
Senin, 16 Maret 2020 07:05 WIB
Globalisasi, Nasionalisme, Kesukuan
Senin, 9 Maret 2020 13:41 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 99
99 0
0