Novel Legendaris Ashadi Siregar: Cintaku di Kampus Biru
Kamis, 18 Agustus 2022 08:35 WIB
Tentang kehidupan kampus dengan keceriaan cinta para mahasiswa dan kepahitan dalam menghadapi realita hidup mereka. Di kampus, cinta berkembang bagai dalam mimpi.
Inilah salah satu novel Ashadi Siregar yang masih dikenang banyak orang sampai sekarang. Novel ini ditulis Ashadi dalam bentuk serial di harian Kompas (1972) dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh Gramedia pada 1974. Sempat difilmkan pada 1976 dengan judul yang sama oleh sutradara Ami Prijono. Pemainnya, antara lain, Roy Marten, Rae Sita, Yati Octavia, dan Farouk Afero. Ami Prijono dianggap berhasil menghadirkan film percintaan di kalangan mahasiswa pada masa itu. Selain itu, secara gambar, Ami juga berhasil mengekspos pilar-pilar dan relung-relung gedung utama rektorat serta pohon-pohon cemara di lingkungan kampus Universitas Gadja Mada (UGM). Maka, sejak film itulah sebutan “kampus biru” melekat pada UGM.
Lalu dari mana datangnya kata “biru” setelah kata “kampus” itu? Warna jaket almamater UGM? Bukan. Untuk mengetahui soal itu, seperti diceritakan Ashadi sendiri, kita mesti kembali ke tahun 1970-an, ketika Indonesia baru saja lepas dari kungkungan Orde Lama (Orla), dan masuk ke Orde Baru (Orba). Ashadi menulis novel ini selepas koran mingguan Sendi dibredel tahun 1972, dan Ashadi selaku penanggung jawab diadili dan dinyatakan bersalah. Pembredelan oleh pemerintahan Orba itu karena koran tersebut dianggap menyebarkan kebencian (penerapan haatzai artikelen KUHP) terhadap Presiden Suharto dan istrinya, Ibu Siti Hartinah Suharto.
Maka, saat itu, menulis novel menjadi pelarian dari kenyataan yang dihadapi Ashadi. Dengan diadili dan divonis bersalah, Ashadi merasa masa depan di bidang pers sudah tertutup. Dalam kepahitan itu Ashadi mengidealisasi kehidupan kampus. Dia membayangkan kehidupan kampus yang ideal sekaligus romantis. Maka dia menulis novel trilogi: “Cintaku di Kampus Biru,” “Kugapai Cintamu”, dan “Terminal Cinta Terakhir.”
Sejak 1970-an, para aktivis mahasiswa perkotaan umumnya memakai celana jin warna biru (blue jean) impor dari Amerika Serikat. Itu pakaian mahal saat itu, populer sebagai celana koboi, dilarang selama di zaman Orla yang anti barat. Sering tentara merazia anak muda bercelana jin dan menggunting kaki celana yang dipakai. Sikap anti barat dari rezim Orla itu lenyap bersamaan dengan tegaknya pemerintahan Orba yang berorientasi pada modal asing.
Celana celana jin biru itu juga mengacu pada gerakan kaum muda Amerika Serikat yang anti perang dan melakukan perlawanan pada kekuasaan mapan (establishment) baik kapitalis maupun komunis yang dianggap mengungkung kebebasan. Demikianlah cerita warna “biru” itu. Jadi, dalam cerita romantis Cintaku di Kampus Biru ini, tema yang tersirat dari celana jin biru adalah simbolisme pemberontakan anak muda pada kekuasaan masa itu. Apalagi, banyak orang muda saat itu -- begitu juga aktivis Indonesia pada 1970-an – juga terpesona dengan gagasan Herbert Marcuse dengan bukunya One-Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (1964). Saya akan kutipkan sebagian dari pemikiran Herbert Marcuse ini di bagian akhir.
***
Kisah novel ini adalah tentang mahasiswa Fakultas Psikologi bernama Anton yang ceria, humoris, cerdas, gemar membaca buku, pandai merayu, dan – tentu saja -- gemar berpacaran. Tetapi Anton juga sedang dihadapkan pada berbagai masalah dalam perkuliahannya. Kehebatannya dalam merayu membuatnya terlibat dalam masalah dengan beberapa wanita. Pada mulanya adalah dengan gadis bernama Marini. Dan novel pun dibuka dengan kisah seperti ini:
Gerumbulan semak itu bergerak-gerak. Bunga-bunga putih dan merah di ujung-ujung ranting ikut bergoyang. Diterpa angin. Dua pasang kaki menjulur dari balik semak itu. Sepasang berbetis putih, jenjang dan mungil, Sandalnya berwarna kuning. Sepasang yang lain, dibalut celana jins biru, Bersandal jepit.
Aroma segar dedaunan ditambah lagi harum bunga, menandakan betapa nyamannya tempat itu. Angin membuat pucuk-pucuk cemara meliuk pelahan. Pohon-pohon flamboyan berbunga. Gedung induk kampus Gadja Mada tertegak sepi. Jalan yang mebelah menuju gedung bertingkat tiga itu dipanggang matahari. Tapi di pinggir, sejuk. Matahari tak bisa menembus dedaunan yang melindungi. Dari balik semak terdengar suara lelaki:
“Aku mau pulang.”
Kaki lelaki itu bergerak, ancang-ancang akan berdiri. Tapi kaki jenjang bersandal warna kuning, menekan kaki lelaki itu.
“Nanti.”
Lelaki itu berusaha melepaskan kakinya dari tindihan. Semak-semak bergoyangan. Di balik semak itu terjadi pergumulan.
“Bah, kau mau memperkosa aku!” suara lelaki itu.
“Brengsek! Diamlah!” suara perempuan.
Lalu suara mulut tersekap: “Hmmmmmm.....”. Tapi suara “hmmm” itu terputus, digantikan suara lelaki dalam napas tersengal.
“Cukup. Aku malas. Awas kakimu. Aku mau pergi.”
“Ah, sshhhhhh...”
“Tidak mau. Jangan tindih aku. Ke sana kau!”
“Bah.”
“Hari ini tiada cinta,” kata lelaki itu.
“Hm, gaya Motinggo. Tapi kurang erotis,” perempuan itu mengejek.
Gerumbulan semak bdergoyangan lagi.
“Ah! Jangan! Aku mau pulang,” suara lelaki.
“Alaa, sok kau.”
“Sudah kubilang, hari ini tak ada cinta. Kepalaku pusing memikirkan ujian, uang kuliah yang belum dibayar, pemilihan dewan mahasiswa, resolusi untuk dosen brengsek....”
“Kau yang brengsek! Sok jadi orang penting.”
“Bah.”
“Bah,” ejek perempuan itu.
“Pokoknya, aku mau pulang. Membaca di dekatmu, hilang konsentrasiku.”
“Dasar!”
“Dasar apa?”
“Dasar lelaki. Dulu menguber-uber. Sekarang berlagak.”
“O, perempuan! Dulu jual mahal. Sekarang menggerogoti waktuku yang berharga.”
“Dulu kenapa kau tak berasa digerogoti. Malah membuang waktu berhari-hari mengejar-ngejar.”
“Lain Bengkulu, lain Semarang. Sekarang, sudahlah. Pokoknya, aku cinta padamu. Tapi kita harus bercinta sedikit metodologis. Pakai logika. Jangan sentimentil.”
“Dasar!” kata perempuan itu.
“Ya, dasar. Sudah? Nah, geser kakimu. Aku mau berdiri.”
“Kau datang atau tidak, nanti malam?” Ada ancaman dalam suara perempuan itu.
“Bah, perkosaan.”
“Bah, bah, bah, mau datang atau tidak? Kalau tidak, jangan lagi pijak rumahku.”
“Aku tak suka di-fait accomply. Cinta tak boleh ber-fait accomply. Kayak kawin hansip saja.”
“Mau datang atau tidak?”
Tak ada jawaban. Semak-semak bersibak. Anton keluar dari gerumbulan semak itu. Dia mengipaskan rumput di celananya. Lalu bersiul meninggalkan tempat itu.
Semak tersibak lagi. Marini membersihkan rumput-rumput yang melekat di roknya yang mini. Dan kemudian merapikan rambutnya.
“Bajingan!” katanya ke arah punggung Anton yang kian menjauh.
Anton tak bereaksi. Marini memungut batu kerikil, dan melempar lelaki itu.
“Bajingan!” serunya. Lemparannya tak mengenai sasaran. Anton cuma melengos sedikit, dan melangkah bergegas.
Gadis itu mengawasi punggung lelaki itu. Dia melangka mengikutinya. Tapi dia teringat. Lalu dia kembali masuk ke gerumbul semak, Mengambil buku-bukunya.
Sembari berjalan, dia menggerundel berkepanjangan. “Dasar lelaki. Tak tahu diri. Dulu bukan main cumbuannya. Sekarang, berlagak alim. Dasar!”
Marini melompati parit, dan keluar dari remputan. Kini ia berjalan di Bulaksumur Boulevard, jalan besar beraspal yang membelah kampus itu. Dia berjalan ke selatan, menjauhi gedung induk universitas Gadjah Mada, berpunggungan dengan Anton yang menuju utara.
***
Marini kecewa terhadap sikap Anton akhir-akhir ini. Dia merasa Anton telah berubah. Marini curiga jangan-jangan ada gadis lain yang sedang dikejar oleh Anton. Dia tidak rela jika itu terjadi. Sudah enam bulan mereka berhubungan. Marini tak rela melepaskan Anton. Dia malah berusaha mengikat kekasihnya itu. Anton sendiri sebenarnya juga menyintai Marini, tapi ia mulai tak tahan dengan desakan Marini untuk menikah. Bahkan ia mulai ketakutan dengan institusi perkawinan, apalagi dengan Marini yang dirasa berpotensi untuk mengontrol dirinya nantinya. Maka ia menjauh dari Marini.
Saat ini Anton belum mau memikirkan soal perkawinan. Anton masih bergelut dengan persoalan kuliahnya yang belum rampung. Padahal orangtuanya hanya mau membiayai kuliahnya selama lima tahun saja. Anton juga merasa bahwa usianya yang kini baru dua puluh lima tahun masih cukup waktu untuk memikirkan masalah perkawinan. Tidak perlu terburu-buru. Belakangan, Marini akhirnya memutuskan menikah menikah dengan Kusno, rekan Anton.
***
Cerita berikutnya adalah perkenalan Anton dengan Erika. Lalu, berkat keluasan wawasan dan kepandaiannya merayu, Erika pun jatuh cinta kepadanya. Anton yang sering datang ke rumah Erika itu membuat ibu Erika curiga. Sang ibu berusaha menghalangi hubungan mereka. Dia berharap agar Anton dapat melupakan Erika, sebab anaknya telah bertunangan dengan Usman yang sedang melanjutkan studinya di Jerman. Sang ibu juga menasehati Erika agar dia tidak mengkhianati Usman. Jadi hubungannya dengan pemuda gondrong itu lebih baik segera diputuskan sebelum berkembang lebih jauh.
Sejak saat itu, Anton tidak pernah lagi datang ke rumah Erika. Hal itu membuat Erika merasa kehilangan. Erika tidak mengetahui bahwa ibunya telah bertemu dengan Anton dan melarangnya untuk bertemu dengannya. Erika mengalami kekecewaan yang berkepanjangan, apalagi setelah mendengar kabar bahwa Usman telah kawin dengan seorang gadis Jerman.
Pada suatu hari Anton bertengkar dengan ibu Yusnita mengenai soal mata kuliah yang diampuh oleh dosen muda itu. Beberapa kali Anton dinyatakan tidak lulus oleh dosen killer itu. Padahal Anton merasa bisa menjawab semua pertanyaan ujian. Bahkan ia menantang dilakukan ujian lisan dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Pertengkaran tersebut membuahkan keputusan dari ibu Yusnita bahwa tidak ada pembicaraan lagi tentang ujian Anton. Kata-kata itu membuat hati Anton menjadi panas. Demikian pula ibu Yusnita. Melalui dekan fakultas, ibu Yusnita meminta agar Anton disidangkan dalam rapat dewan dosen. Sebab Anton, kata ibu Yusnita, telah menghinanya. Apalagi kemudian terjadi demo di fakultas terhadap bu Yusnita, Anton segera dituduh sebagai otaknya.
Dalam suatu kegiatan riset di dataran tinggi Dieng, Anton mendekati Bu Yusnita dengan harapan agar dapat menghasilkan perbaikan bagi dirinya. Bu Yusnita memang terbilang cantik. Anton juga menyadari hal itu. Dalam suasana riset itu, ada saja kata-kata dan tindakan Anton yang berhasil melemahkan hati ibu Yusnita hingga mereka menjadi akrab. Bahkan pada suatu kesempatan, di pinggir telaga, Antron mencium ibu Yusnita. Mereka pun berciuman mesra. Tak ada lagi ketegangan di antara mereka berdua.
Pada kesempatan lain, Anton yang memang mengagumi kecantikan ibu Yusnita, secara terus terang hendak melamarnya. Namun, hasrat hati Anton untuk hidup sebagai suami istri dengan ibu Yusnita tidak dapat diterima karena perbedaan usia mereka terpaut jauh. Apalagi, saat itu Yusnita menyatakan bahwa dia sudah memutuskan akan menikah dengan Gunawan, salah seorang dosen di fakultas itu juga.
***
Suatu hari, Anton berkunjung ke rumah Widyasari, mantan kekasih kakak Erika. Anton mengenal gadis ini karena dikenalkan oleh Erika, lalu dilanjutkan dengan pertemuan di kampus. Seperti biasan, Anton mencoba merayu Widyasari. Singkat cerita, suatu sore, di rumah Widyasari, Anton berhasil merangkul dan mencium gadis itu. Pada saat itu, Erika muncul menyaksikan peristiwa itu.
Karena menyadari di depannya ada Anton, dengan gugup Erika segara meninggalkan tempat itu. Widyasari sadar bahwa selain Usman yang menikah dengan gadis Jerman, Anton itulah yang ikut menghancurkan hati Erika hingga kondisi Erika sangat memprihatinkan. Widyasari rmenganjurkan agar Anton segera menemui Erika. Apalgi dia sendiri memang tidak menyintai Anton. Ibu Erika sendiri sempat menemui Anton di pondokannya dan menyatakan menyesal atas apa yang pernah dikatakannya pada Anton. Ibu Erika meminta Anton untuk datang ke rumah menemui Erika.
Dan novel pun ditutup dengan adegan seperti ini:
Anton berjalan di bawah pohon mahoni. Dentang-dentang gereja semayup. Dan kemudian gaungnya kian keras. Dan rumah yang berpagar warna hijau itu, terpacak dalam senja. Warna merah masih bersisa di langit barat. Lelaki itu memperlambat langkahnya. Dan matanya was-was ke rumah itu. Di teras itu, Erika, Erika, Erika. Anton berdiri di pintu pagar yang terbuka. Dan menyebut nama gadis itu. Erika mengangkat kepalanya. Sesaat terpana.
“Mas Anton,” desisnya. Dia bangkit. Dan menuju pintu pagar itu.
Dia semakin dekat. Dan dalam cahaya langit, Anton melihat wajahnya yang cekung. Ah!
“Kau sakit, Ika?”
Erika menggeleng.
“Tapi tanganmu dingin.”
“Nanti juga panas asal tetap mas Anton pegang,” kata Erika.
Dia kelihatan lebih kecil dari biasa, Anton ingin mendejapnya. Alangkah anehnya, Di depan Widyasari, Anton merasa dirinya hanya murid taman kanak-kanak, sedang di depan gadis ini, dia merasa layak menjadi kakak yang akan selamanya melindungi.
“Kenapa lama tak tak datang mas Anton?” desah gadis itu.
“Sekarang aku datang.”
Mereka masih tegak di pintu pagar itu. Erika memegang tangan lelaki itu.
“Ayo kita jalan-jalan,” kata Anton.
“Sekarang?”
“Ya, sekarang.”
“Begini saja?” Erika melirik sandal jepit di kakinya.
“Ya begini saja.”
Erika merangkul tangan Anton yang kukuh. Dan mereka berjalan di bawah pohon-pohon mahoni yang tak henti-hentinya meluruhkan daun-daunnya.
SELESAI
***
Tentang latar belakang Ashadi menulis novel ini, penjelasan soal warna “biru” yang menjadi bagian judul novel, dan hal-hal lain di luar isi novel, dapat dianggap sebagai faktor ekstrinsik untuk membantu memahami keseluruhan novel ini. Sedangkan faktor intrinsiknya adalah tema cinta mahasiswa yang ditulis dengan bahasa yang hidup, setting yang jelas, alur cerita yang jelas, dan plotnya maju secara logis. Dialog-dialog dalam novel ini menjadi kekuatan tersendiri. Melalui dialog, terutama oleh Anton –yang sering lucu-- itu kita mengetahui karakter masing-masing tokohnya. Mungkin saja ada yang menilai bahwa karakter Anton terasa mustahil dalam dunia nyata, tapi ini memang idealisasi yang sengaja dilakukan oleh Ashadi.
Kehidupan mahasiswa dengan lika-liku percintaanya memang lumrah bagi muda-mudi. Dan kampus merupakan tempat yang paling menyenangkan. Di situ kegelisahan-kegelisahan diredakan dan frustrasi-frustrasi diendapkan. Novel ini secara umum tetap berusaha memotret secara jujur kehidupan orang-orang muda di kampus zaman itu. Jujur dengan aneka problem yang dialami dan jujur pada nuraninya. Karena itu novel ini terasa akrab bagi penikmatnya.
Sedangkan mengenai Herbert Marcuse, yang menjadi idola banyak mahasiswa di era 1970-an itu, adalah salah satu anggota dari “Mazhab Frankfurt”, sebuah Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, ketika lembaga itu dipimpin oleh Max Horkheimer pada 1930. Marcuse diterima di institut itu pada akhir 1932 atas sponsor dari Edmund Husserl. Lembaga itu sendiri didirikan pada 1923 oleh Felix Weil, anak seorang pedagang gandum dan sarjana dalam ilmu politik. Nama-nama lain dalam kelompok ini, misalnya, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Walter Benjamin, dan lain-lain.
Dalam buku One-Dimensional Man (1964) yang laris itu, ia mengeritik masyarakat industri maju pada saat itu, khususnya di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Uni Soviet. Namun demikian, uraiannya mempunyai relevansi juga bagi belahan dunia yang lain. Kesimpulan umum dari buku ini adalah bahwa manusia dewasa ini berdimensi satu saja.
Menurut Marcuse, seperti diringkaskan oleh K. Bertens dalam sejarah filsafat kontemporer, manusia adalah makhluk yang menurut kodratnya mendambakan kebahagiaan. Perwujudan kebahagiaan itu tergantung pada pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, zaman modern ini mempunyai kemungkinan obyektif untuk merealisasikan pemuasan ini. Namun, masyarakat modern tetap terhalang dalam merealisasikan kebutuhannya karena suasana erepresif yang menandai masyarakat di mana ia hidup
Ciri khas yang menonjol dalam masyarakat industri modern adalah peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasionalitas dalam zaman kita ijni adalah rasionalitas teknologis. Segala sesuatu dipandang dan dihargai sejauh dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, dan ditangani.m Dalam pandangan teknologis, instrumentalisasi merupakan istilah kunci. Mula-mula cara berpikir dan bertindak inin hanya dipraktikkan dalam hubungan dengan alam saja, tetapi lama-kelamaan diterapkan juga pada manusia dan seluruh lapangan sosial. Bukan saja benda-benda, alam dan mesin-mesin diperalat dan dimanipulasi, tetapi hal yang sama juga di seluruh wilayah politik, sosial dan kultural. Kita ingat saja istilah social engineering. Manusia dan masyarakt tidak terkecuali dari penguasaan dan manipulasi teknologis.
.Masyarakat industri yang sudah maju adalah masyarakat berdimensi satu. Dan pemikiran yang dipraktikkan dalam masyarat itu adalah pemikiran berdimensi satu. Manusia modern hidup dalam masyarakat yang tidak mengenal oposisi ataupun alternatif. Di Amerika Serikat, entah Partai Republik atau partai Demokrat; dan di Jerman Partai Demokrat Kristen atau Partai Sosialis, praktis tidak ada perbedaan sama sekali. Sama saja siapa yang memegang pemerintahan. Partai-partai politik sudah menjadi mekanisme yang berbelit-belit yang mengumpulkan suara-suara, supaya sejumlah politisi profesional dapat mempertahankan kedudukannya. Partai-partai kiri pun ikut-ikutan saja; mereka diintegrasikan dalam sistem kemasyarakatan yang mantap dan tak tergoyakan.
Cita-cita seperti “kebebasan” dan “demokrasi” telah kehilangan arti kritisnya. Karena pemikiran berdimensi satu secara sistematis disebarkan oleh para manajer politik dan para penguasa yang memonopoli media massa, manusia modern diindoktrinasi dengan slogan-slogan yang didiktekan begitu saja.
Demikianlah sepenggal pemikiran Marcuse yang berkaitan dengan salah satu bukunya itu. Apakah pemikiran itu masih relevan atau tidak, Anda mungkin lebih tahu.
- Atmojo adalah penulis yang meminati bidang filsafat, hukum, dan seni.
###
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Drama Nano Riantiarno: Kejujuran dan Penyesalan
Sabtu, 28 Januari 2023 06:50 WIB
Aum Teater Mandiri: Imajinasi yang Meneror
Senin, 9 Januari 2023 18:24 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0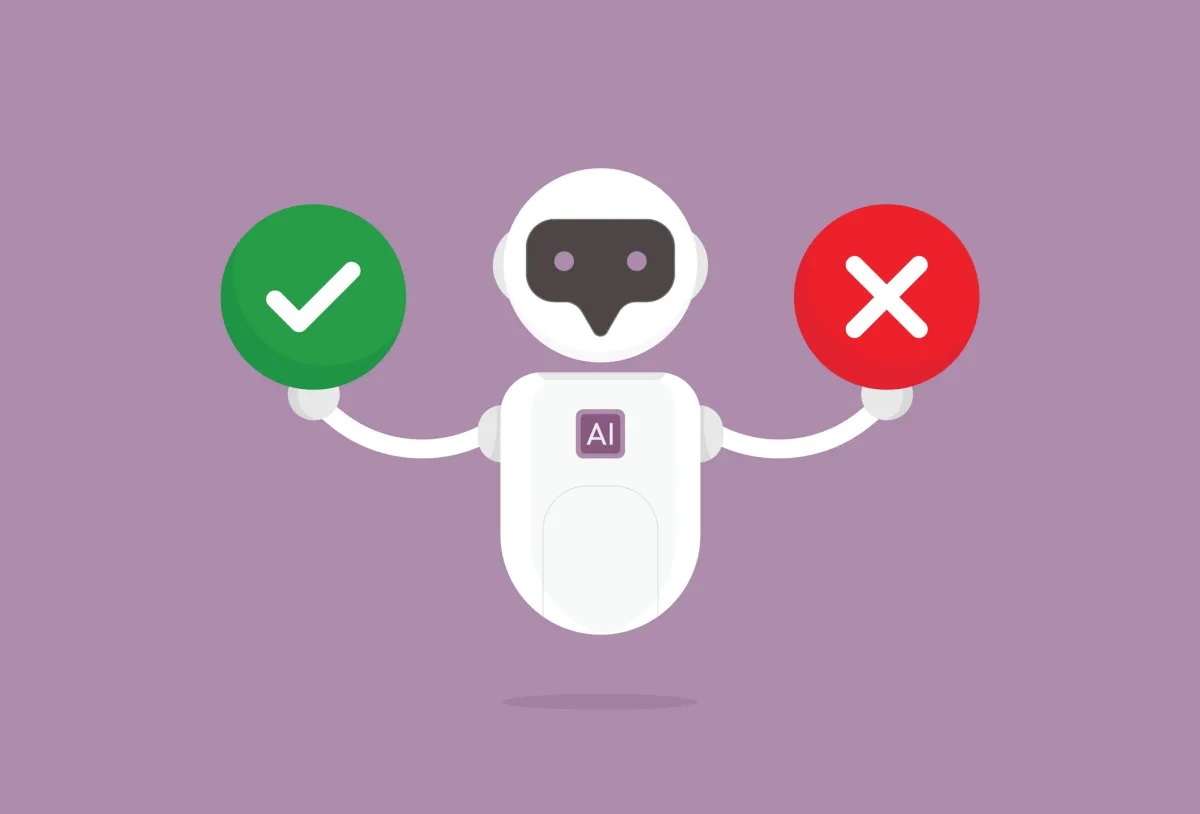









 98
98 0
0












