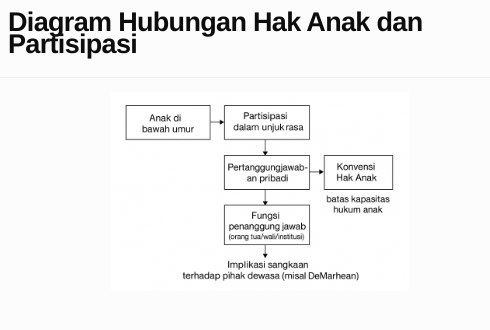Gunoto Saparie lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1955. Aktif dalam dunia literasi, menulis cerita pendek, puisi, novel, dan esai. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit adalah Melancholia (Damad, Semarang, 1979), Solitaire (Indragiri, Semarang, 1981), Malam Pertama (Mimbar, Semarang, 1996), Penyair Kamar (Forum Komunikasi Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, 2018), dan Mendung, Kabut, dan Lain-lain (Cerah Budaya Indonesia, Jakarta, 2019), dan Lirik (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2020). Kumpulan esai tunggalnya Islam dalam Kesusastraan Indonesia (Yayasan Arus, Jakarta, 1986) dan Kiri Islam dan Lain-Lain (Satupena, Jakarta, 2023). Kumpulan cerita rakyatnya Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa Tengah (Pusat Bahasa, Jakarta, 2004). Novelnya Selamat Siang, Kekasih dimuat secara bersambung di Mingguan Bahari, Semarang (1978) dan Bau (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2019) yang menjadi nomine Penghargaan Prasidatama 2020 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.\xd\xd Ia juga pernah menerbitkan antologi puisi bersama Korrie Layun Rampan berjudul Putih! Putih! Putih! (Yogyakarta, 1976) dan Suara Sendawar Kendal (Karawang, 2015). Sejumlah puisi, cerita pendek, dan esainya termuat dalam antologi bersama para penulis lain. Puisinya juga masuk dalam buku Manuel D\x27Indonesien Volume I terbitan L\x27asiatheque, Paris, Prancis, Januari 2012. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Satupena Jawa Tengah juga sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Ketua Komunitas Puisi Esai Jawa Tengah, dan Ketua Umum Forum Kreator Era AI Jawa Tengah. Ia juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, Majelis Kiai Santri Pancasila, dan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Jawa Tengah. Pernah menjadi wartawan, guru, dosen, konsultan perpajakan, dan penyuluh agama madya. Alumni Akademi Uang dan Bank Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang.
Mengunci Ingatan tentang Yudhistira ANM Massardi
6 jam lalu
Yudhistira, sejak awal 1970-an, adalah penyair yang tak pernah betah di satu kotak. Ia menulis puisi, menulis prosa, menulis naskah drama.
Oleh Gunoto Saparie
Di sebuah ruang yang tenang di Kaliurang, 7 September 2025, orang-orang berkumpul untuk sesuatu yang sederhana dan khidmat: membedah buku Mengunci Ingatan. Buku kenangan tentang Yudhistira ANM Massardi itu, meninggal dunia 2 April 2024, yang sejak lama beredar seperti gema yang tak pernah selesai, akhirnya menemukan ruang perjumpaannya sendiri. Ruang Literasi Kaliurang, dengan udara sejuk dan riwayat pertemuan kulturalnya, menjelma semacam altar kecil untuk sebuah perayaan.
Sebelum sampai di lereng Merapi, buku yang sama lebih dulu dipelajari di Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 3 Mei 2025. Jakarta dengan segala gegapnya, dengan debu dan suara lalu lintas yang sulit reda, memberi panggung yang berbeda. Di sana, pameran karya-karya Yudhistira dipasang. Puisi-puisi dibacakan dengan intonasi yang beragam, kadang tergesa, kadang seperti berdoa.
Kaliurang adalah jeda. Kita tahu, bedah buku sering hanya jadi forum akademik. Para pembicara menyiapkan makalah, audiens menyiapkan tanya jawab, panitia menyiapkan snack. Namun dalam peristiwa Yudhistira, yang lahir adalah sesuatu yang lebih halus. Barangkali karena puisinya sendiri tak bisa hanya didekati dengan analisis, melainkan mesti juga dengan rasa kehilangan. Ia menulis seakan hendak merekam detik-detik yang bisa lenyap sewaktu-waktu. Seperti seseorang yang sadar bahwa ingatan pun bisa terbuang.
“Puisi itu bukan sekadar kata,” ujar seorang sahabat Yudhistira ketika membacakan larik-lariknya. “Ia adalah kunci untuk membuka pintu yang tak kita tahu di mana ujungnya.” Suara itu menggema di dinding Ruang Literasi. Para pendengar diam. Ada yang menunduk. Ada yang tersenyum samar.
Yudhistira, sejak awal 1970-an, adalah penyair yang tak pernah betah di satu kotak. Ia menulis puisi, menulis prosa, menulis naskah drama. Tetapi dalam buku Mengunci Ingatan terasa lain. Di dalamnya ada kesadaran akan waktu yang tak bisa ditangkap. Membaca buku itu, kita seakan ikut duduk di sebuah kursi panjang: melihat hari-hari lewat, mendengar orang-orang pergi, merasakan usia yang menua tanpa permisi. Ada cerita dari Siska Yudhistira, sang istri almarhum, tentang produktivitas luar biasa Yudhis setelah pensiun.
Maka pameran karya-karyanya pun jadi semacam perpanjangan teks. Ada manuskrip tua, ada catatan pinggir, ada kliping esai dan puisi, ada poster-poster lawas dari pertunjukan teater yang pernah ia tulis. Seakan ingin berkata: penyair ini bukan hanya milik puisi, ia milik sebuah zaman yang keras kepala ingin dikenang.
Tentu, membaca puisi di depan publik selalu mengandung risiko. Kata-kata yang di atas kertas terasa hidup, bisa kehilangan napas ketika diucapkan. Tetapi justru di situlah letak pesonanya. Seorang penyair sahabat membacakan satu sajak Yudhistira dengan suara hampir berbisik. Tak ada tepuk tangan, hanya senyap. Senyap itu yang jadi musik.
Kita pun bisa bertanya: apa gunanya semua ini? Bedah buku, pameran, pembacaan puisi, musikalisasi puisi, bukankah akhirnya hanya peristiwa kecil dalam kota yang sibuk dengan hal-hal lain? Barangkali memang kecil. Tetapi dari peristiwa kecil itu kita bisa melihat satu hal: bahwa ingatan perlu dijaga. Dalam dunia yang lekas berubah, buku bisa jadi jangkar. Puisi bisa jadi penanda bahwa manusia bukan hanya makhluk ekonomi, melainkan juga makhluk yang ingin dikenang.
Yudhistira tahu itu. Ia menulis bukan untuk abadi, tetapi untuk sejenak berhenti. “Mengunci” berarti menyimpan, menjaga agar sesuatu tidak lepas. Tetapi kunci juga bisa berarti menutup. Ada ambivalensi di sana. Membaca judulnya, kita bertanya: ingatan ini hendak diamankan, atau justru hendak dikubur?
Di Jakarta, suasananya lain. TIM adalah gedung yang sibuk dengan agenda seni dari berbagai arah. Di sana, Mengunci Ingatan seperti berdiri di tengah arus, menunggu pembaca yang sempat menoleh. Kaliurang, dengan hawa dingin pegunungan, memberi ruang lebih intim. Seakan para penyair, pembaca, dan kawan-kawan Yudhistira, seperti Cak Lontong, Renny Jayusman, Ratih Sang, hanya berbincang di ruang tamu rumah sendiri.
Barangkali memang itulah bedanya pusat dan pinggiran. Di pusat, puisi jadi peristiwa budaya. Di pinggiran, ia jadi peristiwa batin. Seseorang di kursi belakang berkomentar: “Kita sedang membaca Yudhistira, tetapi juga membaca diri sendiri.”
Ya, puisi memang begitu. Ia menyalakan cermin. Yang terlihat bukan wajah penyair, melainkan wajah kita yang sedang mencari arti. Maka acara itu berakhir tanpa gegap, tanpa riuh. Hanya dengan janji: puisi-puisi Yudhistira akan terus dibaca.
Pameran ditutup, kursi-kursi ditata ulang, lampu-lampu dimatikan. Tetapi di luar, di Kaliurang yang malamnya dingin, orang-orang masih membawa pulang sesuatu yang lain: semacam keheningan yang tak selesai. Dan mungkin itu yang dimaksud “mengunci ingatan”. Ia bukan soal mengawetkan masa lalu, melainkan menjaga agar keheningan itu tidak dicuri oleh kebisingan dunia.
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah.
Penulis Indonesiana
2 Pengikut

Seusai Penyair Nusantara Bertemu di Jakarta
15 jam laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0