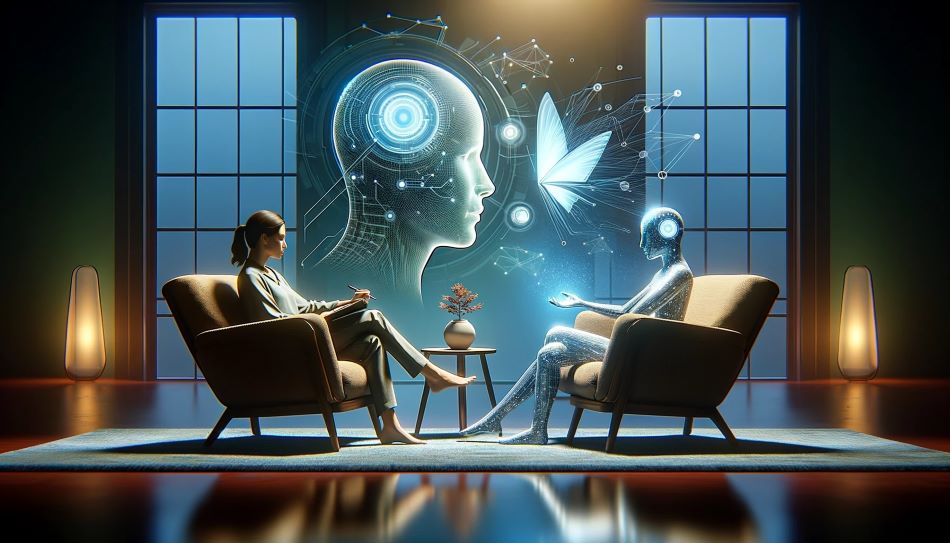Praktisi ISO Management System and Compliance
Sudah Pensiun, Belum Diangkat: Tragedi Guru Honorer di Ujung Usia
1 jam lalu
Guru honorer 20+ tahun gagal PPPK karena passing grade. Diabaikan meski setia mengabdi. Ini jeritan keadilan yang tak bisa dianggap remeh.
***
Pada suatu pagi di ujung timur Nusa Tenggara Timur, Ibu Siti (58) berangkat mengajar seperti biasa. Sepeda motornya menempuh jalan berbatu selama satu jam untuk sampai ke sekolah dasar satu-satunya di desa terpencil itu. Selama 24 tahun, ia menjadi satu-satunya guru yang setia mengajar murid-murid dari keluarga petani dan nelayan.
Gajinya? Hanya Rp 700 ribu per bulan, tanpa tunjangan, tanpa jaminan pensiun. Namun, ketika akhirnya seleksi PPPK dibuka sebagai harapan pengangkatan, ia gagal—bukan karena tidak kompeten, tapi karena usianya melebihi batas dan nilainya tak mencapai passing grade meski telah belajar sekuat tenaga.
Ibu Siti bukan kasus tunggal. Ia adalah wajah dari ratusan ribu guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, menjadi penopang pendidikan di pelosok negeri, namun kini terpinggirkan oleh kebijakan yang justru dimaksudkan untuk melindungi mereka.
Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diluncurkan dengan janji mulia: mengangkat guru honorer menjadi aparatur negara secara bertahap. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini berubah menjadi proses seleksi kompetitif yang justru menyisihkan mereka yang paling berpengalaman. Banyak guru tua yang telah mengabdi lebih dari dua dekade harus bersaing dengan lulusan baru yang lebih mudah memahami soal tes, sementara mereka sendiri kesulitan mengakses pelatihan daring atau menghadapi materi ujian yang jauh dari konteks realitas mengajar mereka.
Data Kemendikbudristek mencatat, hingga 2024, masih ada sekitar 300 ribu guru honorer yang mengabdi tanpa status tetap. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang berhasil lolos dalam beberapa gelombang seleksi PPPK. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu mengajar, tapi karena sistem tidak mempertimbangkan pengalaman nyata sebagai bagian dari kompetensi.
Ironisnya, kebijakan ini lahir dari birokrasi yang sering kali abai terhadap konteks lokal. Tes seleksi nasional dirancang secara seragam, tanpa memperhitungkan keterbatasan akses internet, usia, maupun beban kerja guru di daerah. Seorang guru di Papua mungkin harus menempuh jarak 50 kilometer untuk mengikuti simulasi CAT, sementara rekan-rekannya di Jakarta bisa belajar lewat aplikasi premium. Hasilnya? Guru-guru yang paling dibutuhkan di garis depan pendidikan justru yang paling sulit masuk.
Lebih dari itu, kuota PPPK yang dibatasi tiap tahun—dengan alasan anggaran—menjadi benteng birokrasi yang membuat banyak guru tua tidak sempat diangkat sebelum pensiun. Mereka hidup dalam ketidakpastian: ikut tes tahun ini gagal, ditunda lagi, lalu tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi syarat usia. “Kami tidak minta diistimewakan,” kata seorang guru dalam unggahan viral, “tapi jangan zalimi kami yang sudah puluhan tahun mengabdi.”
Persepsi bahwa guru honorer adalah “tenaga cadangan” harus segera dihentikan. Mereka bukan pekerja kontrak sembarangan—mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Negara-negara lain telah mengambil jalan yang lebih manusiawi. Di Filipina, guru berpengalaman diangkat melalui jalur khusus tanpa tes kompetensi berlebihan. Thailand memiliki skema pengakuan kredit pengabdian, di mana masa kerja menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan. Mereka memahami bahwa pengalaman adalah bentuk kompetensi yang tak terukur oleh soal pilihan ganda.
Di Indonesia, kita masih terjebak dalam dualisme: di satu sisi, kita mengagungkan guru sebagai “pahlawan bangsa”, di sisi lain, kita perlakukan mereka seperti beban administratif. Kita memberi mereka medali simbolik, tapi menolak memberi kepastian status dan kesejahteraan.
Solusi tidak rumit. Pertama, prioritaskan pengangkatan guru honorer lama (minimal 10–20 tahun) tanpa melalui tes, cukup dengan verifikasi rekam jejak mengajar dan rekomendasi kepala sekolah. Kedua, percepat proses pengangkatan secara massal, bukan bertahap lima tahunan, agar tidak ada guru yang pensiun tanpa kepastian. Ketiga, desain ulang mekanisme seleksi dengan bobot pengalaman, portofolio mengajar, dan penilaian kinerja langsung dari sekolah.
Keempat, berikan pelatihan intensif yang benar-benar menjangkau daerah terpencil, bukan hanya secara daring, tapi dengan pendampingan langsung. Terakhir, libatkan serikat guru dan wali murid dalam proses evaluasi kebijakan, agar tidak lagi terasa top-down dan birokratis.
Ketika listrik padam, kita bicara soal ketahanan infrastruktur. Saat harga sembako naik, kita bicara inflasi. Tapi ketika seorang guru yang telah mengajar generasi demi generasi ditinggalkan oleh sistem, kita diam. Padahal, tidak ada pembangunan yang lebih strategis daripada pendidikan, dan tidak ada investasi yang lebih berharga daripada guru.
Menghormati guru bukan hanya soal pidato Hari Guru. Ia adalah soal keadilan struktural. Dan jika kita terus memperlakukan mereka sebagai tenaga pelengkap, maka jangan heran jika mutu pendidikan kita terus tertinggal.
Karena di balik setiap anak yang bisa membaca, ada seorang guru yang rela tak digaji. Dan di balik setiap bangsa yang maju, ada sistem yang menghargai mereka dengan lebih dari sekadar aplaus.
Penulis Indonesiana
1 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





 97
97 0
0