Jejak Rasa dari Lereng ke Cangkir: Dongeng Kopi dan Utang Budi Petani Sumbing
7 jam lalu
Menelusuri kisah kopi dari lereng Sumbing ke Dongeng Kopi Roastery dan Renggo Darsono menjaga keadilan harga dan kesadaran ngopi di Jogja
***
Di Kalasan, aroma kopi dari Gunung Sumbing disangrai dengan hati-hati. Di balik secangkir kopi nikmat, tersimpan perjuangan petani dan utang budi yang jarang disadari para penikmatnya. Inilah cerita di balik Dongeng Kopi, kedai yang mengubah ritual ngopi di Jogja menjadi gerakan kesadaran.
Sore di Kalasan, Cerita dari Gunung
Sore di Kalasan, Sleman. Aroma biji kopi yang baru keluar dari mesin sangrai menembus udara.
Di depan mesin itu, Ayuri Murakabi menatap jarum termometer yang merambat naik. Beberapa detik lagi, biji Arabika dari lereng Gunung Sumbing mencapai suhu sempurna. Ia menarik tuas, menandai akhir perjalanan panjang biji-biji itu dari kebun rakyat hingga ke cangkir-cangkir para penikmat kopi di kota.
“Petani sudah berpeluh keringat di gunung,” ujarnya. “Tugas kami memastikan peluhnya tak sia-sia, menjaga cerita itu tetap hidup di cangkir.”
Ayuri sebagai juru sangrai punya peran penting. Ia adalah penerjemah rasa, penghubung antara kerja keras petani dan kesadaran para penikmat ngopi di Jogja.
Di dapur sangrai yang berada di sisi utara bangunan besar dua lantai Sasana Krida Dongeng Kopi Roastery, setiap batch yang keluar adalah hasil riset rasa, catatan suhu, dan intuisi yang tak bisa digantikan algoritma.
“Kalau salah sangrai, cerita Arabika atau Robusta mereka bisa tamat di sini,” katanya.
Keadilan di Balik Secangkir Kopi
Kopi yang diolah Ayuri berasal dari kebun rakyat di ketinggian Sumbing.
Salah satu petaninya, Bardiman, akrab disapa Bardi, memulai hari sejak pukul 04.30 pagi, bahkan sebelum kabut mengangkat.
Ia memeriksa ranting dan daun satu per satu. “Kopi ini manja,” katanya tersenyum. “Satu hari saja tak disiram, rasanya bisa berubah.”
Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Indonesia memiliki lebih dari 1,2 juta hektare lahan kopi, dan hampir 97 persen di antaranya dikelola oleh petani kecil. Jawa Tengah menyumbang sekitar 26,9 ribu ton per tahun. Namun, di balik angka itu, petani tetap menjadi pihak paling rapuh dalam rantai pasok global.
Harga biji kopi basah petik merah pada panen 2024 sempat naik ke Rp12.000–Rp15.000 per kilogram. Tapi di jogja, biji yang sama setelah disangrai dan dikemas bisa dijual hingga Rp250.000 per kilogram.
Di kedai, secangkirnya bahkan tembus Rp35.000 di kedai kedai yang mendaku sebagai slow bar. Perbandingan yang lumayan.
“Padahal tanpa kerja tangan mereka, aroma kopi takkan pernah sampai ke cangkir kita,” kata Ayuri.
Petik Merah: Ketelatenan yang Tak Tergantikan
Setiap musim panen, keluarga Bardi memetik kopi dengan tangan. Tak ada mesin, tak ada sensor warna. Hanya buah yang benar-benar merah—full ripe cherry—yang diambil. “Yang hijau itu racun rasa,” katanya sambil memperlihatkan ceri mentah.
Dalam sehari, ia bisa memetik 100 kilogram ceri. Setelah dikeringkan, hanya 20 persen yang menjadi biji siap olah.
Tak ada jaminan cuaca, tak ada subsidi memadai, hanya ketekunan dan harapan agar hasilnya cukup untuk hidup.
Rantai Cerita dari Lereng ke Kedai
Biji-biji kering dari Sumbing menempuh ratusan kilometer menuju Kalasan, tempat Dongeng Kopi Roastery menjaga kualitas dan ketelusuran. Setiap batch dicatat dengan teliti—ketinggian tanam, varietas, hingga harga beli dari petani.
Bagi pelanggan seperti Fandy Hafish, transparansi itu punya makna tersendiri.
“Saya ngopi di sini bukan cuma karena rasanya,” katanya. “Saya tahu kopi ini dibeli dengan harga yang adil.”
Komunitas pelanggan Dongeng Kopi yang menamakan diri Kerepdolan menjadikan kedai ini ruang belajar tentang kopi berkelanjutan. Bagi mereka, ngopi bukan sekadar gaya hidup, tapi bentuk kesadaran terhadap keadilan ekonomi desa.
Renggo Darsono dan Filosofi Kopi Berkesadaran
Juru Cerita Dongeng Kopi, Renggo Darsono, meyakini setiap cangkir harus punya cerita. Ia menyebutnya “dongeng yang diseduh.”
Filosofi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
“Kalau kita tahu asal kopi kita, kita akan minum dengan kesadaran penuh,” kata Renggo.
Bagi Dongeng Kopi, keadilan harga dan transparansi bukan jargon, melainkan utang budi pada para petani di hulu. “Makanya, kami punya jargon Pastikan Cangkirmu tidak Berkubang Air Mata Petani!”
Harapan di Lereng, Kesadaran di Cangkir
Malam turun di lereng Sumbing. Di beranda rumahnya, Bardi menyesap kopi tubruk hasil panen sendiri. Ia tahu, sebagian bijinya kini dinikmati di Yogyakarta. Ada rasa bangga, tapi juga getir.
“Kalau harga adil, kami bisa hidup tenang,” katanya.
Bardi mungkin tak mengenal istilah sustainability atau traceability, tapi ia menghidupi keduanya setiap hari. Sementara di kota, para penikmat kopi punya tanggung jawab sederhana: memastikan kisah di balik secangkir kopi tak berhenti di meja kedai.
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Dongeng Kopi Latte, Ketika Kopi Susu Berpadu dengan Rimpang Pilihan
Minggu, 20 Desember 2020 19:14 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





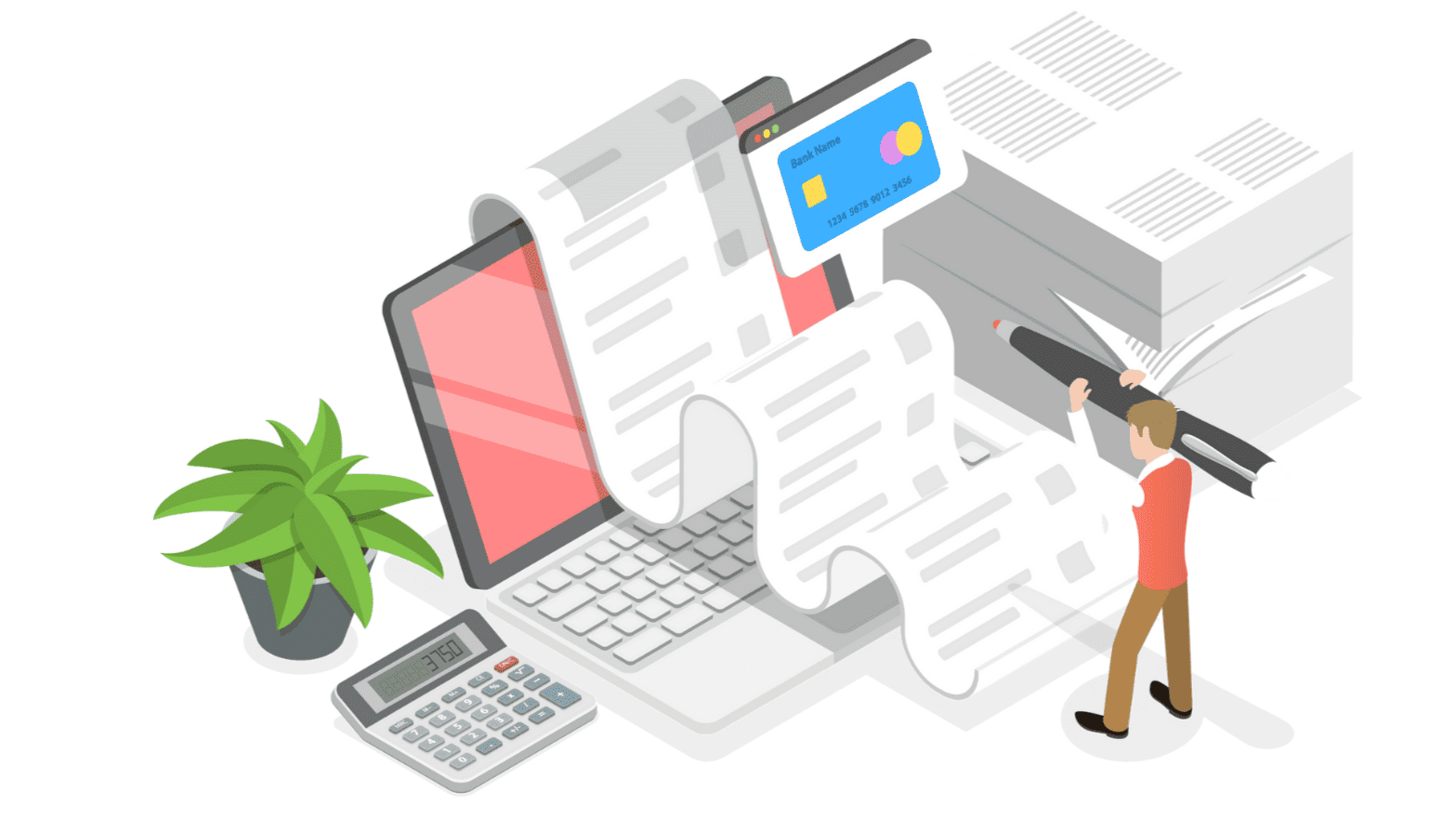

 99
99 0
0













