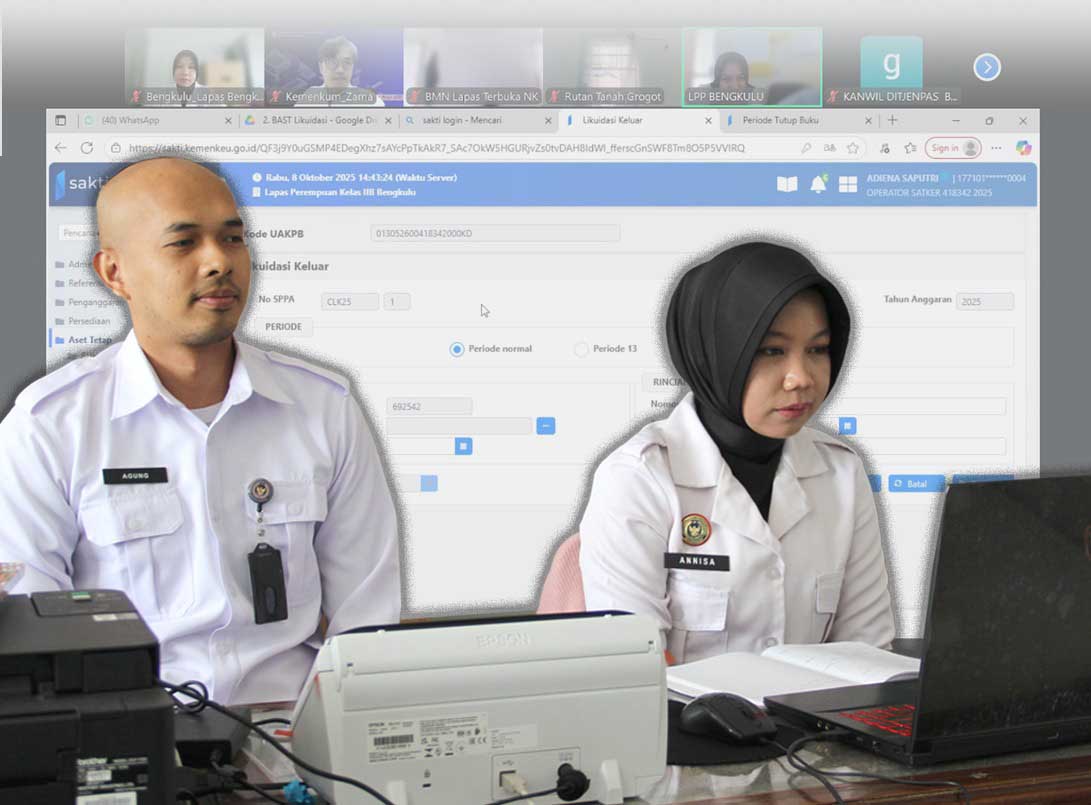Pemula yang menyulam hal-hal sepele menjadi jalinan kisah, cerita, tuturan, dan narasi, agar lahir pencerahan di setiap simpulnya.
Doa Hering Tua
8 jam lalu
Seekor hering tua menatap kematian dengan tenang. Bukan duka, tapi doa alam. Bahwa hidup selalu berakhir memberi bagi yang lain.
***
Langit di atas savana sore itu berwarna tembaga. Matahari tergantung rendah, malas menyingkir. Angin membawa bau tanah panas, darah, dan sesuatu yang tak terpikirkan, aroma kematian yang sangat terasa bagi para pemakan bangkai di atas sana.
Seekor burung terbang berputar perlahan. Ia bukan satu-satunya. Di lidah lama manusia, mereka disebut nasar: penjaga langit bagi yang tak lagi bernafas. Tapi bagi kebanyakan mata, itu hanyalah hering—bayangan hitam di antara cahaya dan kematian.
Di langit senja, kawanan mereka membentuk formasi lingkaran, seperti corak tak kasatmata dalam ritual tarian kuno yang telah terlupakan.
Sementara di bawah, seekor singa jantan terkapar. Surainya kotor oleh debu dan darah. Luka di sisi tubuhnya masih terbuka, mengeluarkan napas hangat yang perlahan berubah dingin. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya hanya bergerak sejengkal. Tak ada lagi kekuatan yang tersisa. Hanya insting yang menolak menyerah, meski tak tahu pada siapa harus bertahan.
Tadi pagi, ia masih menjadi raja di wilayah ini. Ia menandai pohon-pohon, menebar bau di semak-semak, menyingkirkan penantang. Tapi siang itu kawanan jantan muda datang—empat singa yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih buas. Mereka tidak menantang dengan auman kehormatan; mereka menyerang secara bersamaan.
Debu-debu berterbangan, udara dipenuhi bunyi menderu dan debam tubuh yang saling beradu. Cakar-cakar muda mencabik surainya, gigi-gigi tajam menembus kulit leher. Sebuah gigitan di tengkuknya menandai akhir kekuasaan—tanda takdir yang tak bisa dihindari. Ia mencoba melawan, tapi kekuatan itu berpihak pada yang muda.
Ketika debu reda, sang raja terbaring di tanah. Surainya kusut oleh tanah dan darah, matanya terbuka, menatap langit yang mulai memerah. Ia tidak mengaum lagi. Hanya dada yang naik-turun perlahan, seakan menolak kekalahan.
Kini dunia bergerak tanpa menunggu. Para singa muda sedang makan di sisi lain savana, meninggalkan tulang-tulang kecil dari buruannya. Mereka telah mengambil alih wilayah ini—menandai pohon, mencium udara, memastikan aroma mereka menggantikan yang lama.
Mereka tidak peduli pada tubuh yang dulu pernah mereka takuti. Tak ada kemenangan, tak ada perpisahan. Hanya keheningan yang tebal.
Sementara itu, burung-burung di atas sana sudah tahu. Waktunya telah tiba. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya berputar, menunggu napas terakhir terputus. Hering-hering tidak berburu; mereka datang setelah semuanya selesai, ketika hidup perlahan berganti wujud.
Seekor hering tua berada di lingkaran terdepan. Paruhnya bengkok, bulunya kusam. Ia telah menyaksikan banyak kematian: zebra yang diseret hiena, kerbau yang roboh di bawah taring singa, dan kawannya sendiri yang tercabik dalam perebutan bangkai.
Namun tak satu pun seagung yang ini—raja yang akhirnya jatuh.
Ia membungkukkan kepala, menatap singa itu lama-lama. Tidak dengan rasa hormat, juga bukan dengan belas kasih. Ia hanya menilai jarak, menghitung waktu, memastikan kapan daging mulai dingin.
Singa itu mengangkat kepalanya pelan. Matanya masih terbuka, tapi penglihatannya sudah pudar. Di langit, bayangan-bayangan gelap berputar seperti kabut. Mungkin dia mengenal bentuk itu. Mungkin tidak. Napasnya bergetar, kemudian hilang, seperti nyala api yang kehabisan udara.
Sunyi menyebar ke segala arah. Angin berhenti sejenak. Lalu burung hering pertama turun. Sayapnya memotong udara tanpa suara. Disusul yang lain.
Mereka mendarat tanpa tergesa-gesa tanpa aba-aba. Tak butuh penghormatan, tak butuh doa.
Paruh pertama menembus kulit. Bunyi robekan daging terdengar pelan, diikuti bulu dan desis napas. Bau besi darah bercampur debu panas, menciptakan aroma yang hanya dikenal oleh mereka yang hidup dari sisa. Tidak ada rasa berdosa di langit savana.
Yang mati memberi ruang bagi yang hidup. Yang hidup memakan yang mati—begitulah dunia menjaga dirinya sendiri. Dan itu hukum tertua, hukum yang bahkan singa pun harus tunduk padanya.
Sekarang burung tua itu ikut turun. Ia berjalan perlahan, melewati tubuh-tubuh lain yang sudah mulai bekerja. Paruhnya menusuk, mengoyak, menarik. Daging yang dulu bergetar karena kekuatan kini lemas, mudah terlepas dari tulangnya. Tak ada keagungan yang tersisa, hanya kehidupan yang berubah bentuk. Ia makan dengan tenang, seperti seorang biarawan yang menggumamkan doa harian.
Dari jauh, apa yang mereka lakukan tampak kejam. Tapi bagi mereka, itu bukan kebiadaban—melainkan keteraturan tanpa belas kasih, bebas dari penjelasan atau penyesalan.
Setiap bagian mempunyai giliran: kulit untuk yang sabar, organ untuk yang rakus, tulang bagi yang mampu menghancurkannya.Tak ada yang terbuang dan tersia-sia.
Di langit, matahari perlahan jatuh ke balik garis tanah. Warna tembaga berubah biru keunguan. Bayangan burung-burung memanjang di tanah, seperti tanda tangan yang ditulis oleh waktu.
Satu per satu, hering-hering muda kembali terbang setelah kenyang. Hering tua tetap tinggal, berdiri di sisi kepala singa yang kini hanya menyisakan tengkorak di bawah senja. Ia menyantap perlahan—bukan karena kenyang, tapi karena tahu suatu hari nanti tubuhnya sendiri akan menjadi santapan yang sama.
Kini ia tak lapar lagi. Hanya menatap, seakan ingin memastikan bahwa kematian itu lengkap, bahwa tidak ada yang tersisa untuk dihidupkan kembali.
Angin datang membawa bau tanah dan darah yang mengering.
Hering tua itu menutup paruhnya, mengangkat kepala, dan melihat ke langit. Di sana, tak ada janji keabadian—hanya pergantian yang terus bergilir. Tak ada makna maupun kenangan.
Langit tenggelam dalam gelapnya sendiri. Savana tetap bergelombang karena panas. Dunia tidak mengingatnya. Malam tiba perlahan. Bulan muncul tipis, menggantung di atas sisa surai yang telah kehilangan warna. Serangga mulai berdengung di antara tulang-tulang. Hering tua mengepakkan sayap, terbang menembus udara yang gelap.
Di bawahnya, tubuh sang raja telah menjadi bagian dari tanah. Hanya beberapa helai bulu yang tersisa, menempel di rumput kering, bergetar pelan saat angin kembali berembus. Tidak ada kutukan atau keajaiban. Hanya siklus yang menutup dirinya sendiri—kejam, jujur, dan indah dengan cara yang tak mengenal belas kasih.
Dan di savana yang sepi itu, kawanannya melanjutkan tarian kematian mereka. Bukan untuk diratapi. Tapi untuk diingat: bahkan raja pun, pada akhirnya, juga menjadi makanan.
(MZ'16)
Pemula
0 Pengikut

Doa Hering Tua
8 jam lalu
Karpet Terakhir
Rabu, 8 Oktober 2025 17:19 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0