Eksklusivisme dan Pemilu
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Dalam jangka panjang, kemenangan pemilu adalah realisasi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua.
Harus diakui, pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta telah menutup perhatian publik pada lebih dari 100 Pilkada yang diselenggarakan serentak Februari 2017 esok. Pun tak ada yang bisa membantah pemilu Jakarta ramai dengan banyak diskursus, termasuk eksklusivisme. Yaitu, upaya menegasikan kelompok tertentu seperti pendukung dan kandidat. Dan ada banyak kasus yang menunjukkan keberhasilan politik eksklusivisme dalam pemilu. Kemenangan Donald Trump yang anti-Muslim, anti-imigran, dan bias gender pada pemilu presiden Amerika Serikat November 2016 lalu telah menjelaskan bahwa eksklusivisme dapat bekerja di dalam arena elektoral di mana saja: demokrasi mapan maupun demokrasi baru.
Politik Eksklusivisme
Eksklusivisme dalam pemilu bukan barang baru di kawasan Negara Asia Tenggara. Tak bisa dilepaskan dari ‘pembersihan’ etnis Bengal Rohingya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak pada pemilu Myanmar pada November 2015 lalu justru karena alienasi atas Muslim. Walaupun komposisi pemilih Muslim di Myanmar hampir 4%, strategi politik tanpa kandidat Muslim adalah cara NLD meraih simpati mayoritas pemeluk Budha Theravada yang telah banyak terprovokasi anti-Muslim oleh kelompok ekstremis Budha seperti Mabatha pimpinan biksu Wirathu. Contoh lainnya, Malaysia di bawah koalisi Barisan Nasional pimpinan UMNO bahkan melembagakan rasialisme ke dalam konstitusi di mana bumi putera atau Melayu Muslim adalah ‘warga Negara kelas satu’. Dan sekali lagi, pemilu adalah sebab. DPP, Partai yang didominasi oleh Cina keturunan, memenangi pemilu Mai 1969 yang berakhir dengan kerusuhan akibat kekalahan UMNO.
Paling extreme, narasi rasialisme dalam pemilu pernah terjadi hampir seabad yang lalu hingga mengakibatkan bencana besar dalam sejarah pemilu di dunia. Alkisah, pada 19 Oktober 1919 dalam acara orasi rutin sebuah partai kecil di satu bar pinggiran kota Munich, Jerman, seorang pemuda sebatang kara yang akhirnya bertahan hidup usai Perang Dunia I sekonyong-konyong untuk pertama kalinya menyemail narasi eksklusivisme di depan publik: nasionalisme yang bersyarat, nasionalisme anti-Yahudi. Singkat cerita, kepiawaian orasi pemuda tersebut akhirnya mengundang dan menyihir banyak pendengar. Substansi retorisnya sama: nasionalisme anti-Yahudi. Alhasil, partai kecil, Partai Pekerja Jerman, di mana awalnya dia hanyalah ‘tamu’ sebagai intel dari sebuah kantor militer di Munich, akhirnya dia pimpin pada 29 Juli 1921. Dengan narasi rasialisme ini, partai kecil ini pada pemilu nasional 1924 hanya mengantongi 3% suara dengan 12 dari 495 kursi, namun pada akhirnya partai ini meraih hampir 50% suara pada pemilu 1933. Pemuda ini adalah Adolf Hitler dengan kendaraan partainya, Partai Nazi.
Terlepas dari kasus-kasus bekerjanya politik eksklusivisme di atas, masyarakat Indonesia pada dasarnya mempunyai tatanan toleransi yang tinggi. Catatan sejarah menunjukkan tidak ada kerusuhan sosial—selain perdebatan di dalam gedung kongres—ketika bahasa bazaar (baca: pasar) di semenanjung Melayu ‘disumpah’ sebagai bahasa penghubung oleh para perwakilan pemuda dari sudut-sudut pulau kawasan Hindia Belanda pada Oktober 1928. Padahal banyak sarjana bahasa menunjukkan bahwa penutur bahasa Jawa berkisar sekitar 40% waktu itu. Pun tidak ada kerusuhan ketika wakil-wakil dari sebuah komunitas politik besar yang kemudian disebut Indonesia ini memutuskan hanya untuk ber-Tuhan, bukan ber-agama, pada Agustus 1945.
Nasionalisme Partai
Di titik inilah, partai, bukan relawan, justru memainkan peran penting dalam mempertahankan nasionalisme bhineka tunggal ika di Indonesia. Peran ini sulit—jika bukan tidak bisa—dilakukan oleh relawan yang ‘se-rela’ dan seorganisatoris sekalipun. Relawan hanya hadir untuk figur kandidat dan bekerja hanya untuk pemenangan pemilu dan bubar setelah pemilu selesai kembali menjadi individu-individu warga dengan setiap aktivitasnya. Dalam konteks pilkada, skope dan nalar organisasi relawan pun bersifat lokal. Sementara itu, partai politik dilengkapi dengan struktur mesin organisasi, ide, dan platform yang tidak insidental maupun temporer dan bersifat nasional.
UU Partaipun kini mensyaratkan semua partai adalah juga organisasi politik dengan struktur organsiasi yang kuat di seluruh sudut-sudut Indonesia. Pemaparan hasil riset peneliti di Australian National University menunjukkan bahwa level nasionalisasi partai-partai di Indonesia mempunyaitren yang semakin membaik sejak pemilu 1999 hingga 2014 lalu (Kenny dan Gammon, 2016). Artinya, tingkat disparitas perolehan suara partai antardaerah pemilihan dan antara daerah pemilihan dengan agregat suara nasional mempunyai nilai kecil/rendah. Tapi, partai tidak hanya dituntun semakin nasional, tapi juga nasionalis. Jika partai mendorong lahirnya kandidat dengan sentimen dan isu rasial maka partai—dan elit di dalamnya—tak lebih dari tim kampanye yang Machiavellian, penghalal segala cara.
Tentu, kampanye rasis adalah bagian dari cara menang, meski dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, kemenangan pemilu adalah realisasi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi penduduk, bukan hanya pemilih. Menurut logika umum sirkulasi kebijakan dalam sebuah sistem politik, outcome atas terdistribusinya kesejahteraan dan terealisasinya keadilan sosial bagi penduduk sebuah kawasan konstituensi pemilu adalah tingkat penerimaan pemilih yang tinggi terhadap kandidat terpilih maupun partai pengusungnya. Partai tentu sadar atas skema jangka panjang ini. Tapi, hanya saja partai sering terjebak oleh para oligarki pembajak dan kelompok rasial dalam pemilu. Dalam nalar desentralisasi di Indonesia, partai politik tentu juga harus melakukan desentralisasi otoritas untuk beradaptasi dengan tuntutan dan kebutuhan warga (pemilih) yang sangat asimetris di kepulauan yang sangat luas ini. Pada saat yang sama, struktur multilevel organsiasi yang dimiliki partai pada dasarnya mampu mengalirkan denyut nasionalisme bhineka tunggalika hingga ke dalam bilik- bilik suara di daerah. Alhasil, partai sebenarnya mempunyai peran untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia yang telah merancang bangun menjadi sebuah komunitas imajiner (Anderson 1983) hingga menjadi sebuah alkemi (Reid 2010) yang membentuk identitas baru bernama Indonesia.
Oleh Arya Budi
Research Fellow, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM
Mahasiswa Master of Asia Pacific Studies, ANU
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Eksklusivisme dan Pemilu
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0



 Berita Pilihan
Berita Pilihan



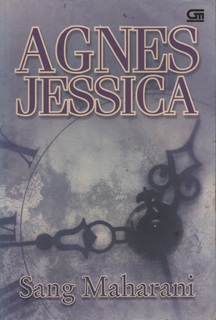

 98
98 0
0















