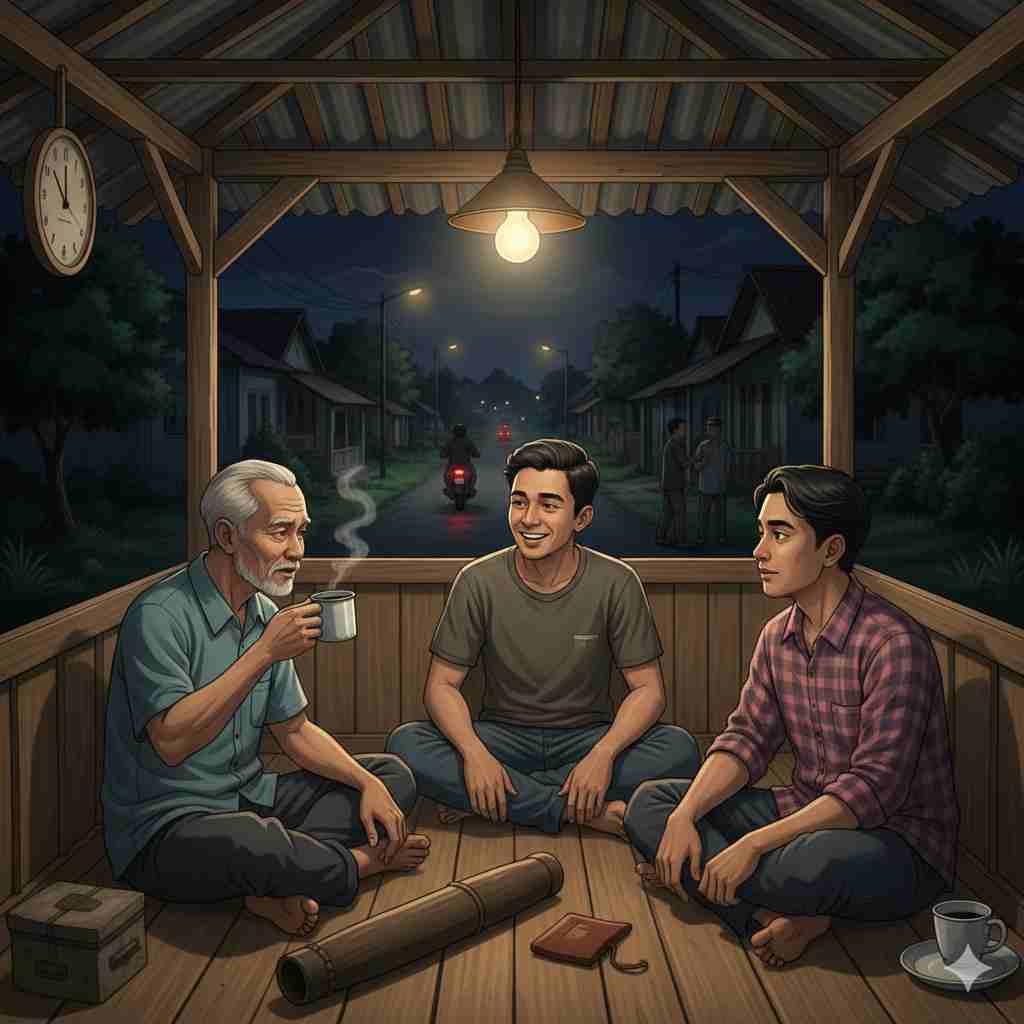Gadis Para Serdadu
Minggu, 28 November 2021 14:12 WIB
Dua bulan sudah aku berada di sini, pagi-pagi sekali dipaksa menjadi budak berempat, silih berganti. Tiap hari juga aku mengumpat. Rasa-rasanya Tuhan pun tak pernah berpihak padaku. Air mataku tak pernah berhenti, Darsana. Sedangkan perjuangan yang bisa kulakukan hanyalah meronta. Selalu ada drama di setiap kamar berukuran dua kali tiga ini. Rumah ini dipenuhi oleh bayang-bayang penindasan. Kami, setiap gadis di sini menjadi sandera yang dipaksa sempurna. Bodohnya, aku masih saja mendambakan diri untuk memakai kebaya putih yang ibumu jahitkan kala itu.
***
Kamu tahu apa yang mengganggu pikiranku, Darsana? Masih samakah hatimu sebelum sepenggal napas terakhirmu kau hembuskan? Oh, sayangku, lihatlah anggrek ungu di ujung pertigaan itu, indah bukan? Masih sangat lekat memori akan tingkahmu dahulu, lucu, selalu saja membuatku tertawa. Hem… Waktu itu, diam-diam kau membawaku bertamasya di sekitar danau yang sangat memesona, tanpa seizin orang tuaku. Pantulan cahaya menembus permukaannya, beningnya mampu menampakkan wajah kita berdua. Di situ parasmu terlihat sempurna, membaur bersama senyumku yang selalu kau puji layaknya candu. Kuakui kau adalah lelaki paling tampan di dunia ini, paling berani, dan paling pandai membuatku tertawa, haha… tentu saja setelah bapakku. Ah, aku malu mengakui itu.
Hari itu aku tak sengaja melihat bunga yang sama di pekarangan, jauh dari titik tangkap mataku di tanah kakiku berpijak. Kau sangat perasa, kau ambil bunga itu dan memberikannya kepadaku. Tahukah kau betapa mongkok-nya hatiku? Aroma yang bahkan tak ada dari bunga itu kucium sampai menusuk kuping ke kupingku. Apalagi, kala kau menggodaku dengan ucapan, “Marsinem, kau cantik hari ini, selalu cantik setiap hari.” Aku tersipu.
Setelahnya, ah sungguh menggelikan. Pemilik rumah itu kau buat murka sebab bunga kesayangannya kau petik paksa. Kita berlari terbirit-birit hingga bakiak kesayanganku lepas dan aku berlari pincang. Anehnya, kau malah membuatku semakin berbunga, sama seperti anggrek ungu yang aku bawa. Semuanya terasa mengasyikkan ketika hal memalukan sekaligus konyol itu terjadi setiap aku bersamamu. Darsana, kau sungguh membuatku kasmaran.
Hueek… maaf.
Sungguh beruntung aku pernah mengenalmu. Andai saja kita tak keluar waktu itu. Pasti serdadu Jepang tidak akan mampu merenggut kebahagiaan kita. Andai saja kau mendengarkan petuahku kala itu, bahwa kurcaci dari negeri matahari serta profesi dambaanmu tak pernah membuat manusia pribumi melepas dahaga, pun membuat keluargamu bahagia. Mereka tak ubah kancil, manis di bibir saja. Malahan membuat kita sengsara, hingga nyawamu direnggut paksa oleh mereka.
Hueeek….
Astaga, mual ini semakin menjadi-jadi. Aku benci dengan diriku. Aku tahu persis apa yang terjadi pada tubuhku. Lihatlah, lama kelamaan perutku akan membesar. Aku akan mengandung kemudian dibuang dengan cuma-cuma. Kamu tau siapa bapaknya? Tentu saja bukan kamu, Darsana. Bahkan aku sendiri tak tahu siapa bapaknya. Terlalu naif untuk mengatakan bahwa, “Kasihan bayi ini tak berdosa.” Kenyataannya, itulah yang terjadi. Siapa yang ingin terlahir dari bapak seperti mereka? beringas tak layak disebut manusia. Bahkan, monyet pun terlalu bagus julukannya.
Kau tahu kenapa ini bisa terjadi? Biar kutebak. Jika kau tahu pun, pastilah nyawamu tetap kandas di tangan mereka, bahkan lebih cepat dari ini. Kau akan membawa celurit dan menebas satu-persatu kepala para lelaki yang haus nafsu itu, tanpa peduli berpuluh-puluh peluru menembus dadamu. Sedangkan aku, sama seperti sekarang, meratapi kepergianmu sampai mataku hampir tak sanggup terbuka.
Tubuhku sudah hina, Darsana. Bodohnya, aku masih saja mendambakan diri untuk memakai kebaya putih yang ibumu jahitkan untukku. Aku ingin benar-benar berada di sana, seperti mimpi kita. Bahwa aku akan duduk di sampingmu sembari mendengarkan mulutmu mengucap mantra janji yang akan menguatkan cinta kita. Namun, semua khayal itu sirna, layaknya dibawa angin yang entah ke mana. Sekalipun dambaan itu tak pernah memenuhi hatiku lagi kala berita kematianmu kutelan mentah-mentah hingga menguasai isi kepala. Tak ada semangat lagi dalam hidupku. Hampa, tak ada daya.
Masih kuingat betul Darsana. Pekan itu kukira akan menjadi kebahagiaan kita sebelum saling melepas lajang, ternyata malah menjadi detik-detik terakhir aku mendengar suaramu. Perpisahan yang direnggut paksa oleh manusia-manusia kerdil tak beradab. Saat itu masih ada senyum yang tertoreh di mulutmu, kebanggaanmu menguar akan lantikan mereka menuju profesi dambaanmu, pasukan Heiho yang kau agung-agungkan. Andai saja kau memilih PETA, Seinendan, atau lainnya. Pasti kematianmu tak akan sia-sia seperti ini, Darsana. Ah, lagi-lagi selalu terselip kata “andai” di setiap bayangan sosokmu.
Hari itu kau membawaku bersepeda, sekadar membagi tawa dan menjamah tempat-tempat menyenangkan. Apalagi, kau suka sekali menggodaku hingga senyum tak pernah luntur dari wajahku. Masih sangat kuingat pakaianmu kala itu, kaos oblong berwarna coklat dan aku memakai kebaya usang warna kuning yang bernoda kopi di bagian lengannya.
“Marsinem, kau ingin tahu apa mimpiku?” tanyamu.
“Bergabung bersama mereka?” jawabku seraya memandangi lekat-lekat para kurcaci itu berpapasan dengan kita.
“Betul, lalu menghalalkanmu dan bahagia bersama, aku akan punya uang Marsinem,” jawabmu dengan tawa yang renyah.
Ah, gombalan itu selalu saja terngiang-ngiang di kepalaku.
Waktu itu kau membelikanku kue cucur di pasar. Katamu, kau membayarnya dari hasil menjual gandum di ladang. Sungguh, itu adalah kue ternikmat sebelum aku memasuki neraka dunia ini.
Kau masih ingat detik-detik terakhir kita saling membagi tatap? Iya, sebelum kita berjumpa dengan mereka. Dua orang berseragam coklat lengkap dengan senapan panjang serta gemertak sepatu yang tinggi-tinggi. Kita berada di tengah jalanan pasar sebelum akhirnya dieksekusi tanpa alasan yang masuk akal. Kamu tahu, setelah kepergianmu aku tak membawa sepedamu untuk pulang sebab aku ditarik paksa oleh mereka dan dimasukkan ke dalam benda beroda empat yang melaju sangat cepat. Aku tak bodoh untuk percaya bualan mereka. Namun, aku tak berdaya untuk menolak ajakan mereka, termasuk meloncat keluar dari benda besar itu.
Jika kau berpikir aku kabur dari rumah setelah itu, kau lebih bodoh, Darsana. Aku sangat mencintaimu, sangat.
Ah, maaf air mataku masih tak bisa berhenti.
Kau tahu Darsana, apa yang terjadi kepadaku? Mereka menjamahku, merenggut keperawananku secara paksa. Waktu itu aku berontak, menangis hingga memukul mereka dengan senjata yang mereka bawa. Namun, lagi-lagi aku tak berdaya. Kau tahu bekas luka ini? Sikuku sakit. Mereka membantingku ke tembok kala aku menolak rayuan mereka. Dahulu, luka ini terbuka hingga warna putih dari tulangku muncul melewati sela-sela kulit. Aku kesakitan Darsana. Namun, mereka tak tinggal diam, aku diobati, tentu saja agar kembali terlihat menawan untuk meladeni mereka. Aku tersiksa. Tersiksa, Darsana.
Dua bulan sudah aku berada di sini, pagi-pagi sekali dipaksa menjadi budak berempat, silih berganti. Tiap hari juga aku mengumpat. Rasa-rasanya Tuhan pun tak pernah berpihak padaku. Air mataku tak pernah berhenti, Darsana. Sedangkan perjuangan yang bisa kulakukan hanyalah meronta. Selalu ada drama di setiap kamar berukuran dua kali tiga ini. Rumah ini dipenuhi oleh bayang-bayang penindasan. Kami, setiap gadis di sini menjadi sandera yang dipaksa sempurna.
Sedangkan kamu, ada di mana Darsana? Mana janji yang kau junjung untuk selalu membuatku bahagia? Mana? Lima belas tahun umurku sia-sia. Lima belas tahun yang harusnya berakhir menjadi isterimu malah harus melayani mereka satu-satu.
Kemarin malam, sayu-sayup kudengar mereka berbicara perihal seorang pasukan baru dari Heiho yang berontak karena tak dipekerjakan dengan baik dan diberi upah sesuai yang dijanjikan. Dia adalah pemuda yang paling lantang menyuarakan pendapatnya walau tak ada satu pun temannya yang berani membela. Mereka menyebut-nyebut namamu. Betapa terkejutnya aku mendengarnya. Apalagi, para serdadu itu memutuskan untuk menghabisi nyawamu sebab kau dianggap pembelot. Mirisnya, cerita itu mereka akhiri dengan tawa lepas bak puas. Sedangkan aku, serasa dibakar hidup-hidup dan dihantam logam panas dalam dada.
Taukah kau, sebulan yang lalu aku bertemu temanku, parasnya cantik, kulitnya putih, di baik, sungguh mencerminkan perempuan Jawa yang diidamkan. Namun, perutnya semakin membesar, mungkin sekitar lima bulan. Nahasnya, para cebol itu tak mau bertanggung jawab. Kabarnya, dia dibuang ke desa seberang. Aku tak tahu bagaimana akhirnya, tapi pelayan di sini bilang dia mati bunuh diri dengan menabrakkan diri di depan mobil perang yang melintas. Kupastikan, nasibku tak jauh berbeda.
Mungkin beberapa menit lagi aku akan kembali menjadi wanita yang tak berharga. Lihat di sana, sebuah mobil baru saja mendarat di bawah pohon. Pemilik sepatu-sepatu itu akan beramai-ramai kemari lalu menyergap kami.
Puingan mimpi kecilku pun tak berarti sama sekali. Aku hilang.
“Biar kupilih yang ini, ayo,” ucap seorang lelaki dengan tubuh krempeng dan tak tinggi tapi cukup lantang mengucap bahasa Jepang yang sedikit kupahami. Dia mencengkram dan menggeret lenganku.
Kali ini aku tak mau berontak. Buang-buang tenaga saja melakukan itu. Toh, aku akan tetap kalah dengan mereka.
Seperti biasa, aku dibanting di atas sebuah kasur. Dia melucuti pakaianku. Sedangkan aku, masih berusaha memejamkan mata dan tak mau melihat parasnya. Mencium baunya saja aku mual, semacam telur busuk yang dicampur air comberan, pasti mereka baru saja berpesta minuman mahal. Jalannya saja sempoyongan. Kalau sudah begini, makhluk ini akan lebih gila dari yang normal.
“Bisa bunuh saja saya setelah Anda melakukan ini?” ucapku ngelantur. Mana bisa mereka berbahasa Jawa? Kendati demikian, kuharap makhluk ini mengerti, walau setengah sadar.
“Diam kau, tak usah banyak bicara,” balasnya dengan bahasa Jepang.
“Jika kau tak mau, akan kubidik jantungku dengan tanganku,” sahutku seraya mengarahkan sebuah benda berpeluru di dadaku.
Dia tak menjawab, bibir itu ditarik sebelah. Dia memicingkan mata seraya mendesah berat.
“Pelayan!” teriaknya menggemakan seisi ruangan.
“Ya Tuan…,” jawab seorang pelayan yang mendekati pintu. Aku cukup akrab dengan dia, berbangsa yang sama denganku. Bedanya, dia laki-laki, di sini hanya sebagai pembantu yang mengantarkan makanan dan minuman.
“Apa yang kau lakukan di situ? Mengintip kami? Aku tahu itu dasar…,” ucapnya tak dilanjutkan.
Entah apa yang dilakukan pelayan itu, aku tak mengamatinya, yang pasti dia telah membuat pria di depanku melotot dan memasang wajah kesetanan. Dengan cepat, cebol ini merenggut pistol yang berada di tanganku. Bibir monyong benda ini mengarah ke pelayan itu. Bodohnya, sang pelayan hanya berdiri mematung sembari memejamkan mata. Tampaknya, aku tahu apa yang akan dilakukan manusia jadi-jadian ini dengan emosinya.
Aku tak bisa tinggal diam. Cepat-cepat aku mendekat, berusaha menurunkan senapan dari tangannya.
DOOR….
Sebuah benda kecil masuk ke dalam kepalaku, melewati pelipis kanan hingga seakan menembus telinga kiri. Aku merasakan ada sesuatu hangat yang mengalir dari sana. Tanganku tak berani menyentuh sebab kutahu, itu pasti sangat anyer dan mengerikan.
Pandanganku kabur, buram, dan menjadi putih seketika. Tubuhku melemas, hembusan napasku tak lagi kurasakan.
Aku salah, ternyata Tuhan sangat menyayangiku. Bapak, Emak, maafkan anakmu yang tak sempat berbakti pada kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Kumohon, jangan cari aku lagi. Marsinem sudah bahagia, lepas dari keadilan yang tak pernah hidup.
Untukmu Darsana, aku akan menjemputmu. Tunggulah aku.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Hakim Hasil Rampasan
Sabtu, 9 April 2022 18:53 WIB
Gadis Para Serdadu
Minggu, 28 November 2021 14:12 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
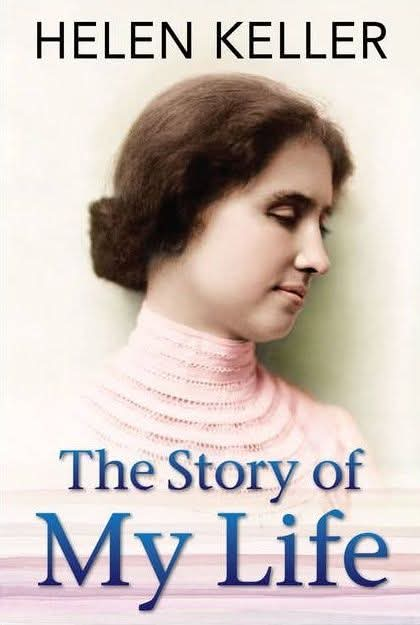
 Berita Pilihan
Berita Pilihan





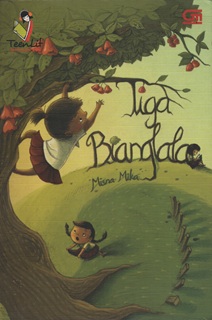

 99
99 0
0