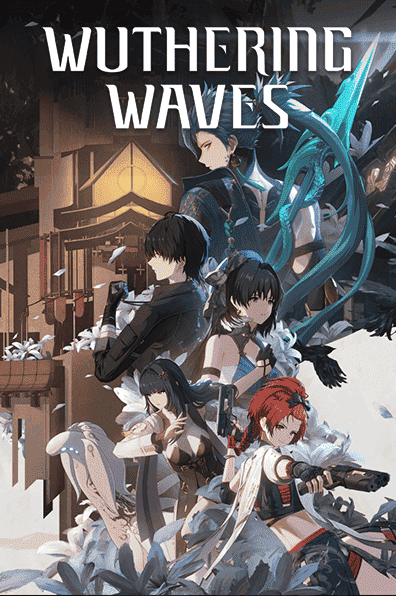Nenek
Rabu, 1 Desember 2021 21:37 WIB
Nenek
Oleh: Manunggal Kusuma Wardaya
Siapa ingin menjadi tua? Aku rasa semua orang, apalagi perempuan seperti aku ingin tetap menjadi muda. Tentu bukan muda seperti bayi atau anak sekolah dasar. Muda dalam arti tetap cantk, berkulit kencang. Akupun ingin tetap muda.
Ya, semua orang ingin tetap muda, segar, dan harum. Namun sang waktu tak bisa diajak kompromi. Dan aku adalah orang yang entah keberapa milyar sepanjang sejarah bumi ini yang mengalami ketuaan. Keriput, kering, peyote, garing.
Ya, aku kini adalah seorang nenek. Engkau tahu? Nenek, Simbah, Eyang putri, Oma, atau apa sajalah!. Tentu saja sebenarnya aku tak cukup pantas menyandang predikat itu.
Aku tak bercucu, dan tak akan mungkin memiliki cucu. Anakku hanya satu orang, Tomo. Dan Tomo telah meninggal tiga puluh empat tahun lalu bersama ayahnya, pada sebuah kecelakaan tunggal. Dan sejak saat itu aku hidup sendiri. Sendiri tanpa Mas Har, suamiku. Tanpa Tomo anak kesayangan kami berdua yang saat itu baru berusia satu setengah tahun.
Pagi ini entah keberapa ribu kali aku mengunjungi makan mereka berdua. Dan entah keberapa ribu kali kutaburkan bunga melati seperti ini di atas pusaran mereka. Mataku yang telah mulai rabun memandangi kedua gundukan itu. Dalam hati aku bertanya, apakah suamiku dan Tomo juga menjadi tua di alam sana? Apakah arwah Mas Har juga keriput sepertiku? Aku tertawa kecil, geli.
Mas Har sangat takut menjadi tua. Ia adalah lelaki yang tampan, dan gagah pada saat ia meninggal. Yang kuingat, ia selalu mengatakan kepadaku walau dengan nada becanda bahwa ia sangat takut menjadi tua.
“Takut taka da noni-noni yang melirik”, demikian biasanya ia menggoda, memancing cemburuku.
Aku tersenyum geli. Segenggam penuh melati kutaburkan di atas pusarannya. Pandangan mataku beralih pada gundukan di sebelah Mas Har. Gundukan yang lebih kecil. Makam Tomo, anak kami. Ahai, apakah Tomo telah tumbuh menjadi lelaki tampan juga di alam baka?! Adakah ia di sana telah memberiku seorang cucu sehingga aku layak bergelar Nenek. Eyang Putri, Oma?!
“Ibu melamu?” sebuah suara mengejutkanku, menggangu lamunanku.
Aku tergeragap karenanya, Nyaris saja keranjang melati tumpahn karena gerak refleks-ku. Hamper saja aku memarahi sumber suara itu, kalau saja ia tak segera menyalamiku dengan ramah. Ia adalah seorang lelaki berusia sekitar 30-35 tahun. Perawakannya tegap, kokoh, berisi. Dadanya bidang bentuk rahang yang kuat. Wajahnya tampan. Mirip ayah Mas Har saat kujumpa 40 tahun silam. Rahang yang kuat itulah daya tarik Mas Har buatku.Ia tak sendiri, bersamanya seorang gadis kecil membawa es krim yang mulai meleleh mengotori roknya.
“Saya perhatikan, sudah hampir dua jam Ibu disini. Sudah siang bu, ibu tidak pulang? Lelaki itu menegurku lagi. “Iya, sebenarnya ibu juga ingin pulang, tapi di rumah ibu juga mau apa?” jawabku seperti bertanya padanya. “Ibu tinggal sendirian?”. “Begitulah.
Laki-laki itu mengajakku ke bawah pohon. Si kecilnya diajak serta. Kami lantas duduk-duduk, melanjutkan pembicaraan. “Anak sendiri tinggal di mana?”, kini aku memulai kembali pembicaraan. “Dekat sini saja, bu”, tangannya menunjuk ke suatu arah. “Ini siapa? Anakmu?”. Ya nek, namanya Lisbeth. Ayo Lisbeth, beri salam pada Nenek!”
Gadis kecil bernama Lisbeth itu menghampiriku. Tangannya yang lembut merahi tanganku. Diciumnya dengan lembut. Kemudian ia kembali ke pangkuan lelaki itu, ayahnya.
Ah, gadis kecil itu teramat cantik. Kulitnya putih bersih. Matanya bulat bercahaya. Aku yakin ia akan tumbuh menjadi gadis yang cerdas, pintar dan berani kelak di kemudia hari.
“Aih anak yang manis. Kelak engkau pasti menjadi seorang gadis yang teramat cantik!”, aku memujinya.
“Ibu belum makan ‘kan?”, lelaki itu bertanya kepadaku. Tanpa menunggu jawaban dariku, ia mengeluarkan bungkusan dari tas bersih. Setelah dibuka ternyata berisi agar-agar.
“Mari nek, kita makan bersama…”
Dan kamipun menikmati agar-agar itu dengan sukacita. Keakraban dengan lelaki yang pantas menjadi anakku dan gadis kecil yang juga pantas menjadi cucuku segera tercipta. Sungguh, siang ini aku merasa sedikit terbebas dari rasa kesunyian. Kesunyian yang berpuluh tahun menghinggapiku. Aku merasa bahagia.
Hari sudah beranjak sore. Agar-agar telah lama habis berpindah dari rantang menuju mulut kami bertiga, untuk akhirnya bersemayam di perut kami masing-masing. Lisbeth bahkan sudah tertidur di pangkuan ayahnya. “Dimanakah gerangan Ibunya?” aku bertanya pada lelaki itu, dan memulai kembali pembicaraan.
Ia terdiam tak menjawab. Dalam hati aku bertanya lagi, apakah aku telah mengajukan pertanyaan yang tidak tepat? Di kota metropolitan ini terlalu banyak pasangan yang bercerai dan seseorang menjadi single parent.
“Maaf, kalau pertanyaan saya menyinggung ananda.” “Tak mengapa bu, Ibu sendiri mengapa sendirian disini?”. “Ibu sudah lama manjadi janda nak, lebih dari tiga puluh tahun yang lalu. Suami ibu meninggal bersama anak ibu satu-satunya.” Jawabku datar.
Kesedihan tiga puluh empat tahun silam sudah mongering dan kulupakan, serta tak perlu membuatku bersedih untuk menceritakannya kepada orang lain. Bukankah Tuhan memberi anugerah “lupa” pada umat manusia..?
“Kalau begitu hampir sama dengan saya, bu. Hanya saja, sejak kecil ayah saya mengajak saya pergi. Dan hingga hari ini saya tak pernah mengenali wajah ibu saya.‘oo..oh..”. “Sudah sore bu, mari kita pulang, tapi saya tidak bisa mengantar ibu. Rumah saya ada dibelakang pemakaman ini. Ibu berani sendiri ‘kan ke pintu gerbang?”. Aku mengangguk. “Semoga kita bisa berjumpa lagi bu, “lelaki itu mengulukan tangannya. Ia Nampak hendak membangunkan Lisbeth yang telah tertidur dipangkuannya. Segera kucegah. “Biar saja, kasihan. Nampaknya ia sedang terlelap.”
Aku tersenyum dan mengulurkan tangan mengusap dahi Lisbeth yang berbintik keringat.
Aku bangkit dan mencium gadis kecil itu. Harum dan wangi, bau anak kecil yang bersih suci, dan tak berdosa.
Kami segera berpisah, Ia berjalan dengan Lisbeth dalam bopongannya. Akupun segera beranjang menuju gerbang kompleks pemakaman itu. Alangkah menyenangkannya seandainya aku mempunyai cucu seperti Lisbeth. Alahkah menyenangkannya jika lelaki itu adalah Tomo, anak kesayanganku dan Mas Har, lebih dari tiga puluh tahun silam.
Pintu gerbang pemakaman sudah semakin dekat. Tak ada lagi orang disitu. Segera kututup pintu itu mataku kuarahkan pada gundukan besar kecil, makam Mas Hard an Tomo. Setelah itu, aku merasakan kepalaku berat… berat. Aku terjatuh.
“Bangun nek, sudah sore. Pemakaman sudah mau tutup”, terdengar suara ditujukan padaku. Terasah sebuah tangan kokoh mengguncang perlahan bahuku. Suara itu ternyata milik Sarkim penjaga makam yang telah lama kukenal. “iya nak Sarkim sebentar, aku menggeragap terbangun. Keranjang yang masih sedikit berisi melati di pangkuanku tumpah karenanya. “sejak tadi nenek tertidur disini, pulanglah nek. Barangkali nenek perlu istirahat di rumah, “Sarkim memberi saran. Ia kemudian membantuku berdiri.
Aku merapikan dandananku, kulihat sekitar. Benar apa yang dikatakan Sarkim. Matahari telah condong kearah barat. Berdua dengan penjaga makam itu, aku berjalan menuju pintu gerbang pemakaman. Sesampainya di gerbang, kuberikan beberapa lembar ribuan kepada Sarkim. “Nak Sarkim. Tolong makam Suami dan anak Nenek dibersihkan selalu, ya. Jangan sampai kotor atau ditumbuhi rumput-rumput, pesanku. “Baik nek, saya tidak pernah lupa untuk meyapu dan mencabut rumputnya”. “Jangan lupa, tolong ikut awasi cucu nenek.” Sarkim mengernyitkan dahinya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia Nampak hendak bertanya. Namun aku segera menyambung. “Ia gadis kecil yang manis. Jangan sampai bermain ke jalan raya, Sarkim. Sanggupkah engkau membantuku mengawasinya?”aku menatap wajah sarkim lekat-lekat. “Sanggup nek” ujar Sarkim. Wajahnya masih menampakkan kebingungan. Beberapa uang ribuan yang kuberikan kepadanya masih di genggam, belum berpindah ke saku celananya. Ia Nampak seperti hendak berkata-kata. Tapi aku tak peduli.
Kutinggalkan Sarkim, berjalan menuju jalan raya. Angin sore menghembus menerpa wajah dan rambutku yang memutih. Beberapa tukang becak menawarkan jasanya padaku. Aku tak mengecuhkan mereka, dan terus berjalan menuju senja.
Hari ini aku sangat bahagia. Hari ini aku tahu, bahwa aku telah menjadi seorang nenek. Dan aku tak ingin kembali menjadi muda. Aku bahagia menjadi nenek. Ya, seorang nenek, kata-kata terindah dalam hidupku hari ini.
Puwokerto 2002
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Terhambatnya Jaringan Bukan Berarti Kamu Bermalas-malasan Mengejar Pendidikan
Rabu, 1 Desember 2021 21:38 WIB
Nenek
Rabu, 1 Desember 2021 21:37 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0