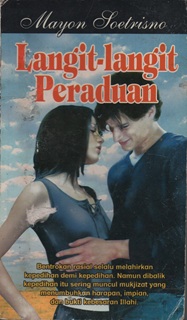Seikat Krisan Merah di Rumah Nenek
Senin, 6 Desember 2021 20:26 WIB
Sejak kecil, aku sering bertanya-tanya mengapa selalu ada seikat krisan merah di rumah nenek. Bahkan saat layu, beliau tidak pernah mau menggantinya dengan jenis lain. Padahal, lili atau anggrek bisa dipertimbangkan. Mereka tidak kalah cantik dan sama-sama bisa bertahan hidup lama dalam vas.
Namun, segala sesuatu yang dijaga dan dirawat baik-baik pasti punya nilai berharga. Aku memang tidak tahu kisah apa yang bersemayam di baliknya, namun aku percaya akan hal itu.
Nama gadis nenekku Ratmi. Beliau dikenal sebagai sesepuh di lingkungan tempat tinggalnya. Usia nenek hampir seabad. Walakin, beliau masih dapat berjalan walau harus dengan bantuan tongkat.
Meski hanya lulusan sekolah dasar, nenek sangat cerdas. Terbukti, di usianya yang tak lagi senja—bisa dibilang sudah malam—daya ingatnya masih kuat. Beliau masih bisa mengeja hari ini Selasa Kliwon dan besok Rabu Legi.
“Kenapa to?” tanya nenek mendapatiku termangu.
“Bunganya cantik, Nek!” pujiku dengan suara keras, sebab fungsi pendengaran nenek tidak sebaik dulu.
“Ya … sudah pasti itu!” sahut nenek.
Nenek lahir tahun 1926. Jangan tanya apakah beliau mengalami zaman pendudukan Belanda atau Jepang. Sebab beliau merupakan seorang mantan veteran perang. Di lemarinya masih tersimpan rapi seragam cokelat susu dengan beberapa tempelan lencana yang dulu menjadi pakaian andalannya.
“Oh iya, Nek. Sarah rindu dibuatkan gambar oleh Nenek,” kataku, bernostalgia.
Saat kecil, aku sering menginap di rumah nenek yang arsitekturnya khas zaman kolonial. Nenek tinggal di rumah berdinding putih kusam ini bersama keluarga Tante Asih, bungsu yang umurnya sudah empat puluhan. Sementara kakek sudah lama wafat karena sakit.
Dari dulu, nenek suka sekali menggambar. Beliau sangat senang jika aku meminta digambarkan. Di selembar kertas, menggunakan sebatang pulpen, beliau menggoreskan sketsa tipis-tipis. Beliau sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambar. Objek yang paling sering digambarnya adalah dokar.
Di sela-sela menggambar, beliau bercerita. Paling sering cerita perjuangan, seperti bagaimana dulu beliau bersembunyi di sungai saat ada tentara Belanda, bagaimana bengisnya tentara Jepang, bagaimana riuh kota saat Indonesia merdeka, dan sebagainya. Sisanya, cerita tentang anak-anaknya. Pernah sekali beliau menceritakan betapa bandelnya ayahku dan bagaimana perjalanan panjang ayahku sampai bisa menikahi ibu.
“Hahaha ….” Nenek tertawa, menunjukkan sederet gigi ompongnya. “Ingin gambar apa?”
“Bunga, Nek,” jawabku.
Nenek membuka laci nakasnya, mengambil selembar kertas. Kemudian beliau berjalan tertatih dan duduk di sampingku.
Nenek membenarkan letak kacamata bacanya. “Kembang apa?[1]”
Aku menatap meja di seberangku. “Bunga yang ada di vas, Nek.”
Nenek mengangguk. Beliau diam sejenak sebelum mulai menggerakkan tangannya yang sudah keriput.
*
Januari, 1942
Sejak pagi buta, radio dan surat kabar ribut memberitakan kedatangan Jepang di Tarakan, Kalimantan Timur. Mereka digadang-gadang akan membasmi keberingasan Belanda, sebab mereka adalah saudara tua Hindia-Belanda. Mereka juga menjanjikan kemerdekaan kepada Hindia-Belanda dengan semboyan andalan mereka.
“Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.”
Di bawah langit yang sama, di atas tanah yang berbeda, Ratmi sedang khusyuk mengganti perban tangan seorang pria usia tiga puluh yang lusa lalu terkena pecahan mortir. Meskipun pria itu tidak mengeluh, beberapa kali beliau mendesis pedih.
Begitulah keseharian Ratmi. Di pengungsian, mereka memiliki sistem berbagi tugas. Perempuan untuk urusan dapur beserta segala tetekbengeknya—mencuci, menjemur, bersih-bersih—, mereka juga dipasrahi urusan medis. Sementara laki-laki di urusan penjagaan. Banyak dari mereka ikut angkat senjata.
Sore itu, Ratmi tentu sudah mendengar kabar bahagia itu, bahwa Belanda akan segera meninggalkan Hindia-Belanda. Sayangnya, kota tempat tinggalnya memiliki kondisi berbeda. Tentara Belanda belum ditarik penuh dari sana, masih ada beberapa dari mereka yang menetap dan membuat ulah.
Sungguh, doanya malam itu hanya satu. Ia ingin kotanya cepat-cepat dimerdekakan dari segala derita.
Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Lepas dari kendang buaya, masuk ke dalam kendang singa. Begitulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan Hindia-Belanda, termasuk kota Semarang di mana Ratmi tinggal.
Pada awalnya, Jepang bersikap sangat baik kepada penduduk lokal. Mereka mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia yang telah lama dilarang pemerintah kolonial, mereka mengizinkan pengibaran Sang Saka Merah Putih, mereka juga menghapuskan sistem kasta sosial yang menginjak-injak harga diri pribumi. Lambat laun, Jepang menunjukkan tabiatnya yang ternyata tidak kalah biadab dari Belanda. Mereka benar-benar binatang.
Sudah sejak lama Ratmi bernasib ngenas, hidup terpisah dari keluarga dan berakhir tinggal di pengungsian. Bukan hal baru ketika suatu hari, ia ditawan dan dibawa ke pengungsian oleh pemerintah Jepang. Istilahnya, ia hanya pindah tempat tinggal.
“Cepat ikut kami!” gertak seorang prajurit Jepang ke muka Ratmi. “Matawa watashi wa anata no atama o uchimasu![2]”
Sebenarnya, Ratmi tidak tahu menahu prajurit Jepang itu berkata apa. Yang jelas, ketika itu kepalanya ditodong sepucuk senapan. Siapa yang tidak mati kutu. Ia juga belum mau bertemu ajal—apalagi dalam keadaan konyol di tangan seorang prajurit Jepang.
*
Ratmi membawa sedikit harta yang ia punya. Beberapa helai pakaian, lima bungkus makanan sisa, kotak P3K, dan cincin pemberian ibunya yang pada akhirnya disita oleh prajurit Jepang yang bertugas.
Ratmi sempat menolak saat benda tersebut akan disita sebab itu satu-satunya peninggalan keluarganya yang ia pegang. Di sisi lain, cincin itu memiliki nilai sejarah. Kata ibunya, cincin itu turun-temurun dari sang buyut yang merupakan seorang ningrat. Sayangnya, Ratmi dibuat tidak berdaya saat dihadapkan pada setali cambuk.
“Hallo, daar[3]! Kamu yang pakai tudung hitam!” panggil seorang gadis berkulit putih yang tubuhnya terbalut gaun bangsawan di suatu Senin pagi.
Ratmi merasa terpanggil. “Saya?”
“Iya, kamu.” Gadis yang jelas seorang keturunan Belanda itu mengangguk. “Apakah kamu masih punya sisa perban?” tanyanya.
Ratmi merogoh kotak P3Knya dan memungut sisa perban yang ada. “Silakan.”
“Puji Tuhan, heel erg bedankt[4]!” ucap gadis itu gembira.
Ratmi hanya tahu sedikit kosa kata Bahasa Belanda sebab ia mentok mengenyam Volkschool[5]. Meskipun begitu, ia paham gadis itu baru saja berterima kasih.
Itu adalah pertemuan pertama dirinya dengan Maria, seorang putri jenderal Belanda yang diculik dan ikut ditawan oleh pemerintah Jepang. Maria berselisih umur tiga tahun lebih tua dari Ratmi. Namun Maria enggan dipanggil dengan embel-embel ‘Zus’, ‘Nona’, atau semacamnya.
Mengesampingkan paras ayunya, bagi Ratmi, Maria adalah definisi putri yang sesungguhnya. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang Hindia-Belanda tulen, pun ia tidak menyombong tentang keturunannya. Tidak seperti beberapa sinyo yang punya darah campuran Belanda yang pernah ditemui Ratmi.
*
Pengungsian di mana Ratmi tinggal tidak pandang bulu. Banyak petinggi masa kolonial Belanda disiksa, diperlakukan semena-mena oleh Jepang. Seolah-olah mereka punya dendam kesumat.
“Ini lauknya aku bagi dua dengan kamu.” Ratmi memelas dengan porsi makan yang didapat Maria. Hanya setengah jatah pribumi.
“Tidak usah, Ratmi. Aku sudah kenyang. Tempe itu untuk kamu saja,” tolak Maria halus, namun tak diindahkan oleh Ratmi.
“Kita masih remaja, harus banyak makan.”
“Ya Tuhan, terima kasih, Ratmi!” Raut wajah Maria menggambarkan kebahagiaan tak berujung.
Ratmi mengangguk, tersenyum.
Entah bagaimana, kendati baru mengenalnya selama dua minggu, Ratmi merasa dirinya memiliki sebuah ikatan dengan Maria. Ikatan yang tidak bisa dijabarkan gadis sawo matang itu melalui kata-kata. Ia merasa telah mengenal gadis berambut pirang itu puluhan tahun lamanya.
Keduanya ditempatkan di barak yang sama. Di penghujung hari, keduanya konsisten bertukar cerita melalui bisik—bisa mampus kalau ketahuan prajurit Jepang yang berjaga.
“Kamu ingin tahu tidak Ratmi, benda berharga apa yang ada dalam ranselku ini?” tanya Maria seraya menepuk ransel merah yang setiap malam dijadikan tempatnya bersandar.
“Sepatu kaca?” tebak Ratmi, asal.
Maria tertawa, namun buru-buru diredam. “Aku bukan Cinderella, Ratmi. Aku hanyalah Maria. Aku tidak punya sepatu kaca.”
“Lalu, apa?” tanya Ratmi, menyerah.
Pada awalnya, Ratmi menebak itu adalah perhiasan. Namun, logikanya menolak. Jika jawabannya perhiasan, sudah pasti benda berkilau itu telah berpindah kepemilikan ke tangan prajurit Jepang sejak jauh-jauh hari.
Maria membuka ranselnya, kemudian mengambil sebuah kantung hitam kecil.
“Ayah dan ibuku suka sekali bunga. Pekarangan rumah kami ditanami puluhan macam bunga,” beber Maria. Pipinya merah tersapu angin malam. “Di dalam kantung ini, ada bibit bunga krisan merah. Hanya barang ini saja yang bisa aku gapai di hari itu—di hari saat aku diculik orang Jepang.”
Maria berhenti sejenak.
Ia menghela nafas panjang. Cerita ini terasa sesak baginya, tetapi ia enggan meneteskan air mata. Ia tidak ingin menyurutkan semangat gadis belia yang sedang duduk di hadapannya.
“Namun, aku bersyukur. Mau tahu kenapa? Itu karena bunga krisan merah melambangkan cinta, persahabatan, dan harapan.” Maria mengeluarkan beberapa biji ke telapak tangannya. “Maukah kau menanam bunga ini bersamaku besok?”
Ratmi mengangguk.
Namun, tak pernah ia dapati hari itu ada. Saat matanya terbuka dari lelap, Maria sudah tidak ada di dalam barak, pun di seluruh pengungsian. Gadis bermata sayu itu bagai hilang ditelan Bumi.
“Nona Belanda kui wis dibekta mbek Jepang, mung aku njuk gung paham dibekta pundi, Nduk.[6].” Begitu pengakuan Bu Mirah yang tidur satu barak dengan mereka berdua.
Beberapa hari setelah itu, samar telinga Ratmi menangkap kabar burung. Gadis-gadis yang hilang di pengungsian adalah gadis-gadis terpilih yang nantinya akan ditempatkan di rumah bordil. Jadi wanita penghibur.
Bahu Ratmi seketika lemas. Malam-malam berikutnya terasa sangat panjang.
*
Agustus, 2020
“Bunga krisan merah melambangkan cinta, persahabatan, dan harapan,” ujar nenek. Beliau khatam menyelesaikan gambarnya, menutup sebuah dongeng panjang yang luar biasa.
Walakin lebih dari setengah abad telah berlalu dan nenek tidak pernah tahu lagi bagaimana kabar Maria setelah penjajahan Jepang—pun usai Indonesia merdeka—, Maria tetap melekat dalam hati dan ingatan nenek.
Nenek menyerahkan kertas penuh oretan itu kepadaku. Sepintas, kulihat setitik air terbit di matanya. Begitulah harga seorang Maria, yang diabadikan oleh nenek dalam wujud seikat krisan merah yang telah dirawatnya baik-baik selama puluhan tahun.
“Ah ….”
Dan dari kisah itu, aku menyadari begitulah cara nenek menyampaikan terima kasihnya kepada Maria, yang selama ini tidak pernah bisa diungkapkannya secara langsung. Dan bagi nenek, menanam dan menjaga krisan merah barangkali sama artinya dengan menanam serta menjaga sebuah harapan. Harapan agar kelak beliau dipertemukan lagi dengan Maria. Meskipun harus menanti hingga kehidupan selanjutnya.
[1] Bunga apa? (Jawa)
[2] Atau saya tembak kepala kamu
[3] Hai, yang di sana!
[4] Terima kasih banyak
[5] Sekolah rakyat
[6] Nona Belanda itu sudah dibawa oleh Jepang, namun aku juga enggak paham dibawa ke mana, Nduk (panggilan anak perempuan (Jawa))
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Seikat Krisan Merah di Rumah Nenek
Senin, 6 Desember 2021 20:26 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0