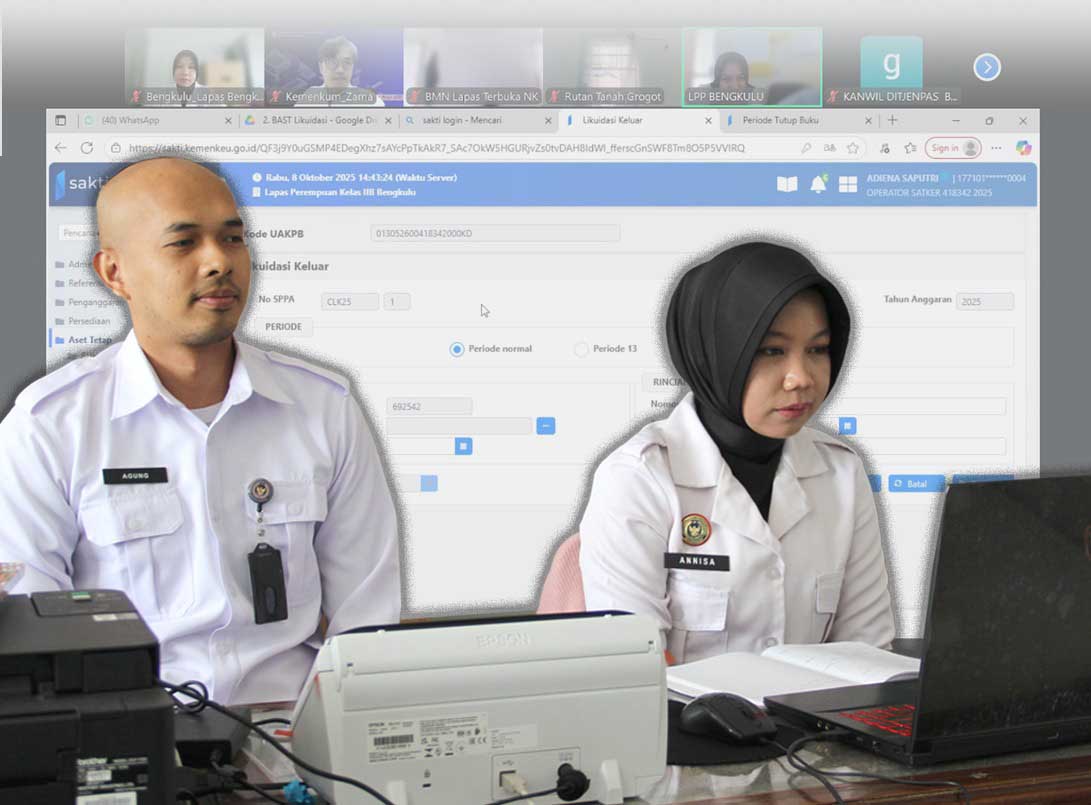Bima yang Tidak Mampu Mengaduk Ksirasagara
Sabtu, 3 September 2022 06:37 WIB
Maka jika memang begitu yang terjadi, bolehlah dengan bangga kita bisa menyebut diri kita “Sang Pemenang.”
Kesaktian Sang Bima dalam kisah Mahabrata sudah tersohor ke seantero negeri. Sehingga namanya diabadikan sebagai nama gugus galaksi tempat bumi kita bernaung, di sudut lengannya yang gagah.
Setiap malam saat suasana menjadi semakin gelap, lengan Sang Bima tampak sangat agung di atas kepala. Berpendar bagai sehelai selendang kabut tebal, bercahaya. Kami menyebutnya Bimasakti. Perkasa yang mampu mengaduk Ksirasagara, lautan susu.
Pak Mandrem guru Biologiku dulu yang juga menyukai lakon pewayangan Jawa mengatakan kita semua adalah pemenang. Seperkasa Bimasakti.
Bagaimana pun, untuk menjadikan kita sehembus nafas bernyawa dan hidup, sperma pejantan yang seperti kecebong itu harus berlarian menjadi yang tercepat. Saling menjungkal, menghalangi satu sama lain. Mengalahkan milyaran kawan untuk menjadi satu-satunya di antara milyaran itu yang akan menjangkau sel selur.
Pertemuan inilah yang menghasilkan kehidupan, yang mana awalnya hanya berupa seonggok daging mentah yang disebut embrio. Tumbuh di dalam Goa Gharba Ibundanya.
Maka jika memang begitu yang terjadi, bolehlah dengan bangga kita bisa menyebut diri kita “Sang Pemenang.”
Sementara untuk mereka yang kalah akan terseleksi dengan sendirinya. Meluruh menjadi darah tanpa arti. Darah yang terbuang. Berbaur kembali dengan zat pertiwi dan ether tempat asal muasalnya sendiri, alam semesta yang agung.
“Sudah hidup saja harusnya kita bersyukur. Peluang sperma untuk masuk ke dalam sel telur hanya satu berbanding semilyar,” lanjut Pak Mandrem.
Aku selalu meresapi kata-kata itu. Menjadikannya semacam alkitab ajaib yang dulu mampu membuatku berusaha lebih keras lagi. Belajar lebih giat lagi, lagi, dan lagi. Lantaran aku merasakan ada naluri pemenang dalam diriku. Ada sosok Bima dalam ragaku.
Namun setelah kesempatan lahir ke dunia yang -kata Pak Mandrem- adalah satu berbanding semilyar ini telah dilalui, nyatanya tidaklah begitu indah. Lama-kelamaan aku menyadari kenyataan bahwa hidup tak sepenuhnya bisa adil.
Di meja Coffee Shop ini aku duduk termangu sendirian. Memikirkan berkali-kali. Tapi toh tetap tak menemukan jawabannya.
Satu jam yang lalu, teman-teman alumni SMA riuh ramai di meja ini. Kami mengadakan reuni kecil. Mereka tersenyum sumringah memamerkan bahwa diri mereka telah menjadi orang sukses. Aku menyimak cerita dengan seksama. Satu-persatu mereka bercerita.
Bryan anak kepala dinas, dia selalu bersaing denganku memperebutkan kursi juara satu kala itu. Namun dia selalu berada di peringkat kedua, kadang ketiga. Aku mati-matian mempertahankan posisi sebagai juara satu setiap semester hanya agar beasiswaku tidak dicabut.
Bryan datang dengan pakaian batik rapi dan sepatu mengkilat. Rupanya dia baru saja menamatkan S2 dengan nilai yang baik. Dia sekarang punya jabatan di salah satu kantor dinas. Mungkin juga hal tersebut adalah peran relasi dari ayahnya. Mencari kenalan pejabat daerah bukanlah hal sulit bagi keluarga Bryan.
Lain dengan Andre yang dulunya dikenal sebagai playboy tengil. Dia duduk di bangku paling belakang kelas. Selalu berbuat gaduh. Sering pula waktu di sekolah dihabiskan dengan menyambangi ruang BK.
Saban hari sepanjang pelajaran, dia akan membuka ponselnya diam-diam. Menggoda siswi-siswi populer untuk dipacari barang satu atau dua hari.
Wajahnya memang tampan. Keturunan dari ayahnya yang memang seorang mantan penyanyi daerah. Kini dia mengikuti jejak itu, merintis karir sebagai influencer dan dengan cepat dia sudah mempunyai ribuan followers.
Tentu juga tak sulit bagi ayah Andre memperkenalkan anaknya kepada produser lagu atau pun film. Atau mengajak Andre sesekali nongkrong dengan rekan-rekan ayahnya sesama public figure itu.
Ada lagi Sutama, generasi ke tiga keluarga Pramono. Salah satu keluarga pebisnis di daerah ini. Orang tuanya mempunya toko oleh-oleh besar yang tersebar di beberapa kota. Kini dia menjadi bos muda melanjutkan usaha keluarga.
Dia bahkan datang ke Coffe Shop ini dengan mengendarai supercar, yang dengan bangga dia katakana, sebagai hasil dari kerja keras selama beberapa bulan saja.
Dulu saat masih sekolah, Sutama dikenal sebagai anak mami yang manja. Selalu berlindung dibalik nama besar keluarganya yang kaya raya.
Anak-anak menggandrunginya karena ingin mencicipi juga keripik-keripik lezat yang dia bawa dari toko oleh-oleh. Dia sangat royal kepada teman-teman.
Kalau soal pelajaran dia tak terlalu pusing. Orang tuanya mendatangkan guru les terbaik untuk menunjang pendidikan anak mereka.
Tetapi meski begitu dia bahkan tidak pernah masuk 10 besar di kelas. Nilainya hanya rata-rata, dan dia tak terlalu punya ambisi untuk menduduki gelar juara.
Dibanding mereka, mungkin hanya hidupku lah yang biasa-biasa saja. Emak dan Bapak tak menuntut banyak dariku. Bahkan kerap menginginkan aku menyudahi sekolah. Tiada fasilitas berbagai macam bimbel seperti halnya teman-teman yang lain.
Bahkan terkadang kedua orang tuaku itu berkata seolah mengkerdilkan mimpiku. Mimpi bahwa suatu saat aku akan sukses dan membanggakan mereka.
Kata-kata itu masih menggema, memantul bagai gaung. Hingga mimpi terpejam aku selalu mengingatnya. Namun ketika terbangun rasanya hati sangat sakit, karena impian itu rupanya sudah berakhir.
“Bapak, Emak, lihat! Bima dapat beasiswa masuk SMA elit. Bima akan rajin belajar dan sekolah yang tinggi agar menjadi orang sukses.”
“Bapak, Emak, lihat! di sekolah Bima juara satu bertahan. Guru dan teman-teman memuji Bima.”
“Bapak, Emak, lihat! Bima lulus dengan nilai ujian terbaik. Bima boleh masuk Universitas kan pak, mak?”
Itu suara-suara kecil yang aku ingat. Wajahku sumringah sambil memamerkan nilai ujian terbaik yang bisa aku raih di sekolah. Mungkin saja waktu itu aku terlalu naif sehingga aku menolak keadaan keluarga yang tidak bisa membantuku melanjutkan mimpi.
“Bima, kalau punya cita-cita ya harus realistis dengan kenyataan. Tamat SMA tak usah kau lanjutkan lagi. Ikut sajalah Pak De Gemblong mengurus jualan baksonya, yang penting kamu punya pekerjaan.” Begitulah ucapan bapak berkali-kali, setiap aku menunjukan prestasiku.
Dadaku seolah terhujam beban yang berat. Bagaimana tidak, mimpi itu patah dan seketika berkeping. Hamburannya seolah menampar kedua pipi untuk terbangun, dan rupanya hanya ada gelap.
Hingga membuatku urung mendaftar di salah satu Universitas ternama dengan jurusan yang aku sukai. Meski dengan beasiswa sekalipun, tapi bapak enggan menyetujuinya.
Emak hanya menurut kata bapak. “Bapak itu kepala keluarga, sudah sepantasnya emak yang perempuan ini patuh apa katanya. Perempuan tidak boleh membantah laki-laki.” Kata-kata emak terngiang seperti sebuah melodi dengan sembilunya.
Perempuan yang tampak lelah itu bahkan tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dia teguh memegang prinsip bahwa istri tidak boleh membantah apapun kata suami.
Menjadi perempuan manut yang legowo. Prinsip yang terbentuk dari lingkungannya di kampung. Prinsip yang lahir dari kaki-kaki para penjajah negeri ini. Prinsip patriarki yang usang.
“Apa benar setidak berdaya itu? Apa benar perempuan harus begitu?”
“Bapak sudah tidak kuat menarik becak. Beasiswa itu tidak akan mungkin menanggung keseluruhan hidupmu di tanah rantau. Pun sesekali, kamu pasti minta dikirimkan uang untuk biaya tugas, tempat tinggal, dan sarana yang lain. Toh, bapakmu ini tamat SD pun tidak. Kamu mau mengejar apa lagi?”
Aku hanya menunduk, dan mengangguk. Aku kubur besarnya mimpiku, lalu pergi mengayuh sepeda tua ke warung bakso Pak De Gemblong.
Dibanding dengan teman-teman yang lain, aku kalah telak sejak awal. Kini aku berpikir meski keras usahaku belajar melebihi mereka, tiada akan mampu kami bersaing. Mereka adalah para pemenang yang saat hidupnya pun telah mencuri permulaan lebih awal.
Untuk apa susah-susah menjadi pemenang jika nasib telah menentukan untuk kalah? Harusnya saat masih berupa kecebong, dengan senang hati aku mengalah saja hingga tiada yang menjadi aku.
Tiada Bima yang lahir sebagai bayi yang menangis. Jika tahu hidup begini maka dengan penuh rasa hormat aku akan mundur.
Ataukah yang sebenarnya terjadi bukanlah sperma itu yang berlomba menjadi yang tercepat? Melainkan mereka saling dorong untuk menumbalkan temannya agar masuk ke bulatan telur itu, lalu menjadi manusia? Ah entahlah.
“Aku tidak pernah mengemis untuk dilahirkan bukan?”
Seharusnya dari awal tak usah kecebong kecil itu berhasrat menjangkau Goa Gharba, yang entah apa dan bagaimana motivasi mereka untuk tetap mendesak masuk. Lalu lahir dan menderita di dunia ini.
Walau kata Pak Mandrem, “Hidup harus sekuat Bimasakti, yang bahkan mampu memanggul dunia. Hingga namanya tetap tersohor hingga kini.” Tapi Pak Mandrem seakan lupa, Bima adalah putra Bhatara Bayu, Dewa dari segala-gala kekuatan. Tentulah buah jatuh takkan jauh dari pohonnya.
Sementara Bima yang ada di dalam diriku ini, hanyalah putra seorang penarik becak. Dia miskin, pun mimpi-mimpi besarnya telah patah oleh seseorang yang dipanggil sebagai orang tua.
Hingga Bima yang ini, tak bisa menjadi sesosok Bimasakti yang dengan gagah memanggul isi dunia di atas lengannya. Memanggul isi dunia di dalam lautan susu, Ksirasagara.
Ni Wayan Wijayanti
Bali, 2 September 2022
*************************
Penulis Indonesiana
4 Pengikut

Seonggok Bayi Usang
Minggu, 5 Januari 2025 14:25 WIB
Sudra
Senin, 27 Mei 2024 13:31 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0