Pahlawan
Sabtu, 20 Mei 2023 09:34 WIB
Aku memang paling tidak tega melihat penjual keliling apalagi yang sudah sepuh. Di kos-ku sendiri pun banyak barang-barang yang sebenarnya tidak begitu aku butuhkan. Karena ya itu, sifat tidak tega ku ini. Ketika ada uang, aku tak akan segan-segan untuk membeli dagangan para penjual keliling yang mampir meski tidak terlalu butuh, apalagi melihat wajah tua dan terlihat letih seperti penjual kaligrafi itu. Namun, apa boleh buat. Kali ini aku memang lagi bokek banget.
"Mas, kaligrafi, Mas. Bagus untuk pajangan di kos," ujar seseorang kepadaku ketika aku tengah asik santai sore di teras sambil ngopi dan baca buku.
Aku menoleh ke asal suara. Seorang lelaki paruh baya dengan wajah berkeringat dan menenteng beberapa barang dagangan.
Ini adalah kali kelima penjual keliling menjajakan barang-barangnya di kos-an ku seharian ini. Ada yang menawarkan sapu, perabotan, kursi, kasur lantai, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Semuanya aku tolak dengan halus. Bukan apa-apa, tapi keuanganku sebulan terakhir ini sangat mengenaskan.
Padahal, biasanya aku paling susah untuk menolak jika ditawari oleh pedagang keliling itu kalau ada uang, karena aku berpikir mereka pasti sangat susah payah, berjalan seharian dan belum tentu ada yang mau beli. Bagiku mereka adalah orang-orang terpinggirkan yang perlahan tergilas penjual-penjual yang lebih melek teknologi jaman.
Aku memang paling tidak tega melihat penjual keliling apalagi yang sudah sepuh. Di kos-ku sendiri pun banyak barang-barang yang sebenarnya tidak begitu aku butuhkan. Karena ya itu, sifat tidak tega ku ini. Ketika ada uang, aku tak akan segan-segan untuk membeli dagangan para penjual keliling yang mampir meski tidak terlalu butuh, apalagi melihat wajah tua dan terlihat letih seperti penjual kaligrafi itu.
Namun, apa boleh buat. Kali ini aku memang lagi bokek banget. Pekerjaanku sebagai penulis lepas lagi sepi nian. Honor di media yang biasa aku nulis pun baru cair semingguan lagi.
Aku merogoh dompet di saku celana. Tinggal sembaran uang 100 ribu teronggok di sana. Sendirian, tanpa teman, dan tampaknya kesepian.
Ini uang harus aku gunakan untuk makan seminggu ini. Entah cukup entah tidak.
"Nggak, Pak. Barangkali lain kali saja, terima kasih," akhirnya aku menolaknya halus seperti penjual yang sudah-sudah.
"Buat Mas, saya kasih potongan harga, deh," rayunya lagi. Tampaknya penjual itu tak mudah putus asa.
Dari balik pagar, terlihat jelas dari sini wajahnya yang memelas. Kulitnya tampak hitam tersengat matahari. Jujur, saja, ini semakin membuatku kasihan.
Aku menghembuskan napas panjang. Tak menyangka masalah sepele ini membuatku berada dalam dilema yang sangat. Memilih membeli dagangan orang tua memelas itu atau kehilangan uang buat makan satu minggu.
"Panas ya, Mas, cuacanya, boleh minta minum, Mas? Nggak beli juga nggak apa-apa, kok," ujarnya lagi sembari mengusap keringat yang membanjiri wajahnya.
"Oh, iya, silahkan, Pak, masuk dulu." Aku bergegas membukakan pintu pagar.
Lelaki paruh baya itu masuk teras, kemudian meletakkan barang-barang dagangannya itu di tiang teras.
"Sebentar, tak ambilkan minuman dulu, Pak," ujarku melangkah masuk rumah.
"Ini, Pak, silahkan," aku menyodorkan segelas besar air putih, "kok saya baru lihat, Bapak, ya? Baru keliling di daerah sini, kah?"
Bapak itu langsung meraih dan meneguk air sampai tandas. Sepertinya dia benar-benar haus.
"Iya, Mas, baru saja saya berkeliling di sini," jawabnya sembari meletakkan gelas yang sudah kosong di atas meja. "Makasih air minumnya, Mas."
Aku mengangguk pelan.
"Ya, sudah, saya lanjutkan keliling dulu, Mas, mumpung belum sore banget," katanya sembari beranjak.
Sekilas aku melihat perban di kakinya. Aku baru ngeh, ternyata bapak ini berjalan agak pincang.
"Kakinya kenapa, Pak?" tanyaku spontan sebelum ia lanjut keluar pagar.
"Oh, ini. Terkilir, Mas, dua hari yang lalu. Biasa udah nggak muda, Mas. Jadi, nggak setangguh dulu, gampang jatuh."
Aku makin merasa kasihan.
"Bapak rumahnya di mana kalau boleh, tau?" lanjutku. Tiba-tiba aku penasaran.
Ia menyebutkan suatu wilayah yang cukup jauh sekali dari sini.
Di situ lengkap sudah rasa kasihanku padanya.
"Ya, sudah, Pak, saya beli satu. Harganya berapa?" tanyaku spontan sembari menunjuk kaligrafi ukuran tanggung. Rasa iba itu tampaknya membuatku bernyali untuk memutuskan.
Dalam hati terbesit rasa bangga luar biasa. Akhirnya aku bisa membuat bapak ini pulang dengan senang. Pasti anak dan bininya pun ikut bahagia ketika ia kembali ke rumah.
"Harganya 120 ribu, Mas, yang ini. Tapi buat Mas 100 ribu saja. Tadi, kan, saya sudah bilang, diskon," tukasnya dengan mata berbinar-binar.
Pas bener. Di dompet tinggal 100 ribu. Persetan dengan nanti makan apa. Gampang nanti aku pinjam si Angga, temen kost-ku, untuk makan.
"Aku segera meraih dompet butut dari saku. Dan mengeluarkan selembar uang merah satu-satunya dari dompetku. Ada rasa kehilangan sebenarnya, tapi ini sudah aku putuskan.
Apakah kau tahu rasanya ketika aku melakukan ini? Rasanya itu seperti aku ini adalah pahlawan. Ya, pahlawan! Pahlawan penolong jutaan umat manusia.
"Oh, iya, Mas. Berarti pas ya uangnya," jawabnya sembari membuka dompet kecil di pinggangnya. Lalu ia menyelipkan uang 100 ribu hasil 'jarahannya' ke tas kumal itu.
Begitu melihat isi tas biru tua itu. Aku menelan ludah. Tampak jelas sekali uang dilipat-lipat berwarna merah, biru, dan pecahan lainnya yang cukup tebal.
"Pak, laku keras ya hari ini?" tanyaku spontan sembari menelan ludah.
"Alhamdulillah, Mas. Sudah 30 kaligrafi, tambah Mas berarti 31 hari ini. Lumayan banget, Mas."
Aku menelan ludah lagi yang makin terasa asam.
"Ya, sudah, saya pamit, ya, Mas," Suara pak tua itu kini di telingaku terdengar seperti perampok yang baru saja membegal korbannya.
"Pak, uangku," kataku seperti tak rela digondol penjual itu.
"Uangnya, Pas, ya, Mas," tegasnya lagi sambil tersenyum. Namun, kini senyumnya bagiku seperti menjelma menjadi senyum licik seorang perampok.
"Pak, uangku," lirihku lagi sembari menggapai-gapaikan tangan. Namun, pak tua itu seperti tak mengidahkan suaraku dan terus bergegas.
Ia bersiul-siul kecil melangkahkan kaki keluar pagar setelah sebelumnya mengucap salam perpisahan.
Kulihat ia semakin menjauh dengan langkah girang.
Aku terdiam mematung dengan tangan masih tergapai, sembari mengamati kaligrafi dan pak tua itu bergantian sampai akhirnya sosoknya lenyap di tikungan.
Rasa ibaku kini telah berganti sempurna menjadi rasa sesal, sesal melihat kenyataan bahwa yang sebenarnya pantas dikasihani bukan pak tua itu, tapi diriku sendiri.
***
Tamat.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Penulis yang Menemukan Kembali Gairahnya
Minggu, 21 Mei 2023 17:13 WIB
Pergulatan di Kereta Senja
Minggu, 21 Mei 2023 17:01 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





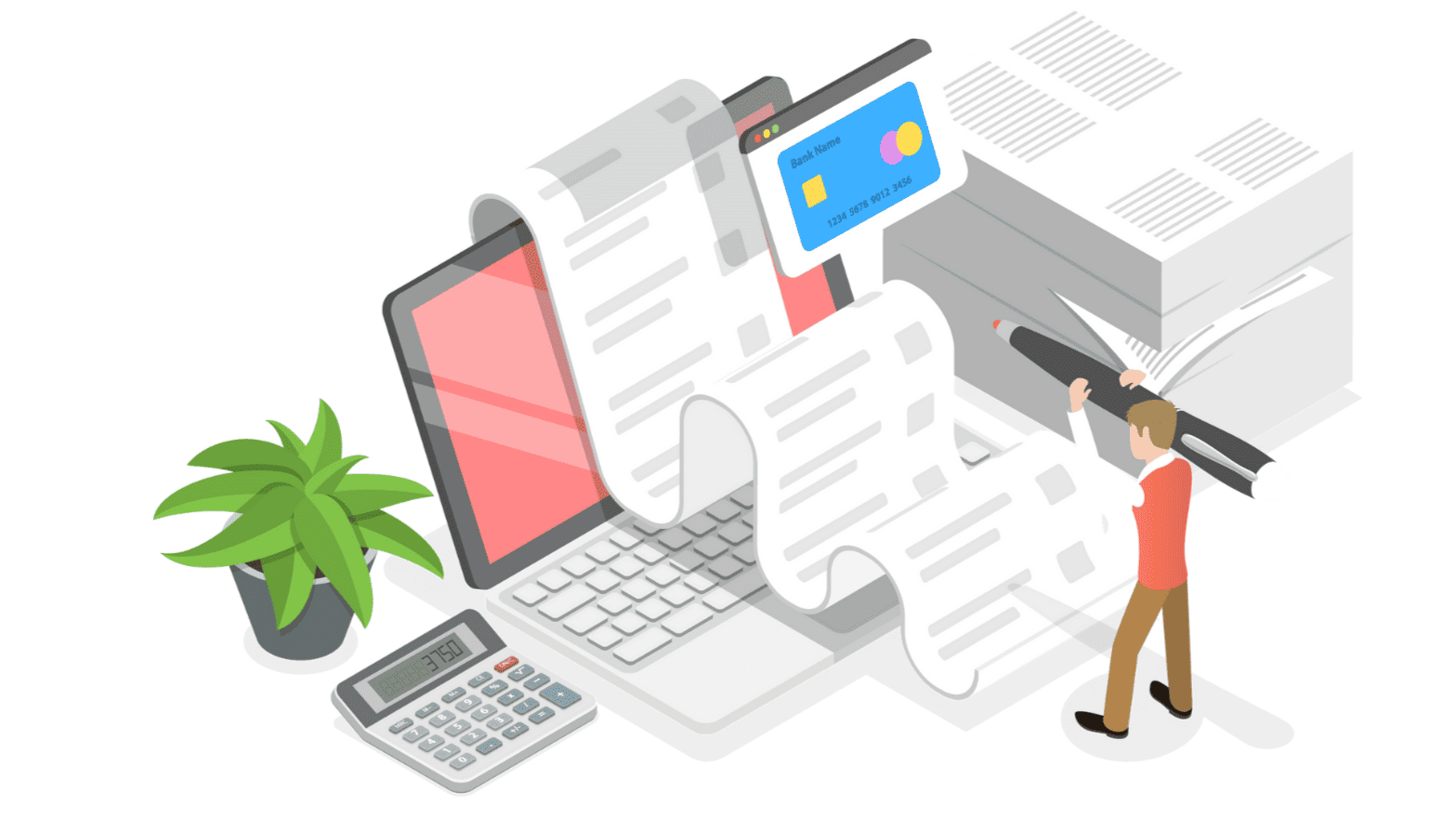

 98
98 0
0















