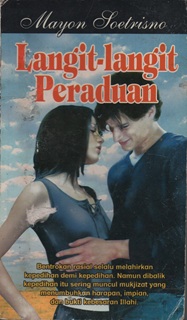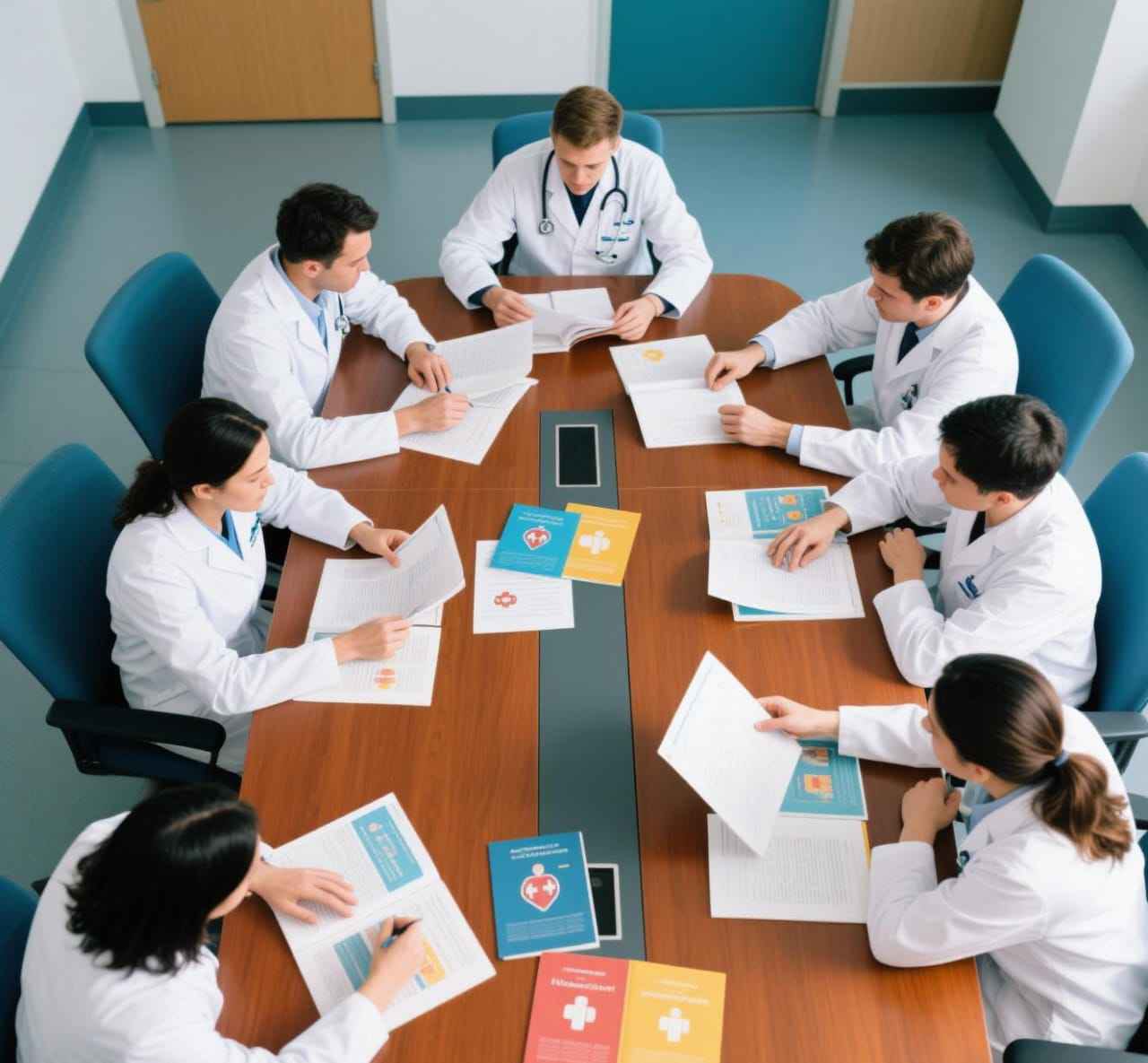Sastra Jawa di dalam Arus Modernitas
Senin, 5 Juni 2023 08:13 WIB
Dari dua kalimat itu saja dapat dilihat sastra jawa kuno memiliki kualitas puitik yang tak tertandingi. Erotik sekaligus brutal. Kalimat itu begitu pas untuk menarasikan peperangan –kebrutalan perang memanglah sejenis erotisme tanpa aturan. Karena dalam panas peperangan, norma-norma tiada.
“Sebab hidup, Gusti, Kadaluarsa. Jika hanya berisi nasehat mama-papa” adalah penggalan lirik lagu yang berjudul Doa 1 yang dipopulerkan oleh grup musik Silampukau. Seperti namanya, kekuatan lirik dari grup musik indie asal Surabaya ini memang memukau. Bagi orang Melayu, silampukau berarti burung kepodang yang bersuara merdu. Silampukau juga terdiri dari dua kata yaitu silam yang berarti masa lampau dan pukau yang berarti memesona, mengagumkan. Mungkin nama itu terinspirasi dari kisah-kisah masa silam yang lebih memesona dan mengagumkan. Begitu juga dengan sastra jawa.
Berdasarkan tahun penulisannya, sastra jawa dibagi menjadi dua. Pertama, sastra jawa kuno. Sastra ini ditulis diantara abad ke-6 sampai dengan abad ke-14. Karya-karya yang terkenal pada periode ini antara lain Ramayana, Bharatayudha, Arjunawiwaha, Gatotkacasraya dan lain-lain. Kedua, sastra jawa klasik yang ditulis sekitar abad ke-14 sampai dengan abad ke-19. Periode ini melahirkan karya-karya seperti Wedatama, Wulangreh, Centhini, Kalatidha dan lain sebagainya.
Periodisasi sastra jawa berakhir sampai abad ke-19 ditandai dengan meninggalnya Ranggawarsita, pujangga terakhir keraton Surakarta. Karena setelah masa itu, tidak ada pujangga keraton lagi. Namun ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Mengapa abad ke-14 dipilih sebagai batas pembeda antara yang kuno dan yang klasik? Atau lebih tepatnya apa yang terjadi di jawa pada abad ke-14 sehingga mempengaruhi periodisasi sastranya ?
Jika kita lihat lebih lanjut dalam sastra jawa klasik seperti Wedatama dan Wulangreh, misalnya. Kita hanya akan menemukan kumpulan “nasihat mama-papa”, –meminjam istilah dari Silampukau. Yang satu nasehat tentang cara mencapai kesempurnaan hidup sedangkan yang satunya nasehat tentang bagaimana seorang pangeran muda dapat berwatak luhur agar pantas menggantikan ayahnya, sang raja.
Kedua sastra tersebut terlalu dibebani fungsi didaktis. Membuka sepuluh halaman saja, pembacanya mungkin akan merasa bosan karena kumpulan kalimat nasehat itu –walaupun membahas hal yang berbeda– tetap terkesan monoton dan stagnan. Kurang lebih isinya sama, kalau mau menjadi orang yang memiliki karakter A, maka harus melakukan B, C, D. Singkatnya, dua serat itu berisi nasehat yang diulang-ulang. Jika ada, kekuatan literer dari kedua serat tersebut hanya tampak pada bunyi, pilihan kata dan kekayaan sinonim.
Lain halnya dengan sastra jawa kuno. Kualitas aliterasi sastra jawa kuno dalam Bharatayudha yang menggambarkan keadaan senja di padang Kurusetra seperti ini saya rasa tidak akan ditemukan dalam sastra jawa klasik manapun :
Panjang garis awan bercampur ke dalam merah menyala cakrawala,
bagaikan darah merendam pakaian merah pengantin yang diperkosa.
Dari dua kalimat itu saja dapat dilihat sastra jawa kuno memiliki kualitas puitik yang tak tertandingi. Erotik sekaligus brutal. Kalimat itu begitu pas untuk menarasikan peperangan –kebrutalan perang memanglah sejenis erotisme tanpa aturan. Karena dalam panas peperangan, norma-norma tiada.
Selain itu dalam masa jawa kuno, seks bukanlah hal yang semata-mata vulgar seperti sekarang. Dalam Sanggamatantra misalnya, puncak dari hubungan suami-istri adalah penyatuan spiritual, layaknya hubungan alam dan manusia.
Di dalam pemikiran masyarakat jawa kuno, alam dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Alam itu bersifat feminim sedangkan manusia bersifat maskulin. Bumi misalnya disifati dengan sifat feminim, maka dari itu bumi sering kita sebut ibu pertiwi. Tugas manusialah sebagai pihak yang maskulin untuk menanam benih kepada bumi yang feminim, layaknya sepasang pengantin. Dan kesadaran akan adanya penyatuan semacam itulah yang mendasari spiritualitas orang jawa kuno dalam bercocok tanam.
Di abad ke-8, para sufi dari Timur Tengah juga memaknai penyatuan-penyatuan semacam ini. Penyatuan antara seorang hamba dan Yang Maha di dalam cinta yang begitu besar yang dikenal dengan sebutan Isyq. Ketika memasuki kondisi Isyq maka seorang salik (pejalan dalam laku tarekat) akan kehilangan dirinya. Sehingga dalam beberapa kisah kita mengenal ada yang sampai menari berputar-putar. Ada juga yang sujud sampai 40 hari lamanya. Dunia modern menamai kondisi Isyq ini dengan sebutan ekstase.
Dugaan saya pada abad ke-14, setelah Islam datang dan Eropa meraih kemenangannya, erotisme dan gairah manusia pada alam tergantikan dengan dogma. Kekakuan dogma ini yang akhirnya melahirkan sebatas doktrin dan nasehat. Sejak saat itu, sastra jawa menempuh arah yang berbeda dari para pendahulunya. Sejak itu pula hidup menjadi kadaluarsa.
Penulis Indonesiana | Author of Rakunulis.com
1 Pengikut
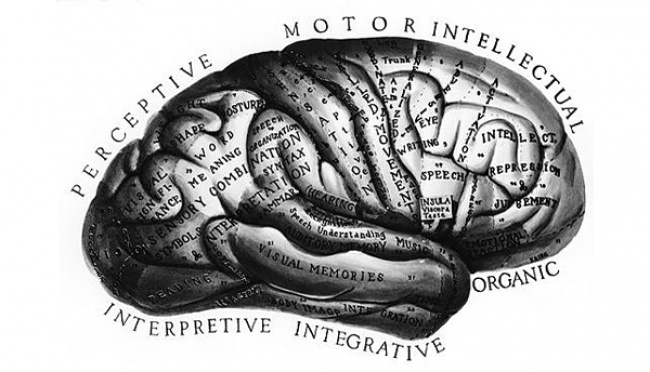
Hukum-hukum Akal dan Pertanyaan-pertanyaan Aneh yang Menyertainya
Sabtu, 7 Juni 2025 12:20 WIB
Menyoal Lampu Motor Siang Hari, Sertifikasi Halal dan PPN 12%
Selasa, 15 April 2025 21:18 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0