Seni dan Sastra dalam Keindonesiaan
Kamis, 11 Januari 2024 06:20 WIB
Kesusasteraan Indonesia berakar dan tumbuh dari keragaman, sejak masa prakolonial sampai saat ini. Berbagai pengaruh lintas budaya, keragaman bahasa, aliran dan orientasi budaya mewarnai bahwasaanya kesusasteraan yang berkembang di Indonesia. Dalam keragaman itu keindonesiaan terus menerus didialogkan dan dibangun.
Kesusasteraan Indonesia berakar dan tumbuh dari keragaman, sejak masa prakolonial sampai saat ini. Berbagai pengaruh lintas budaya, keragaman bahasa, aliran dan orientasi budaya mewarnai kesusasteraan yang berkembang di Indonesia. Dalam keragaman itu keindonesiaan terus menerus didialogkan dan dibangun. Meskipun demikian keragaman itu tidak bisa tidak mengandungi relasi kuasa yang tidak seimbang.
Kesusasteraan dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh masyarakat di wilayah Indonesia Timur kurang terekam dalam sejarah kesusasteraan, kesusasteraan daerah kurang mendapat ruang untuk mendapat perhatian dan dukungan. Dengan mengoptimalkan akses terhadap kesusasteraan yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun daerah, kita bukan saja membangun kesusasteraan yang lebih mendunia, melainkan juga membangun keindonesiaan yang lebih inklusif.
Penelitian filologi, sastra lisan dan sastra modern yang ditulis dalam aksara Latin sejak masa pra-kolonial tidak bisa tidak menunjukkan keragaman dalam kesusasteraan yang tersebar di kawasan Nusantara. Beribu naskah ditulis di atas lontar, deluwang dan kertas dalam macammacam aksara: aksara Pegon, Bugis, Batak, Jawa. Huruf Latin hanyalah salah satu jenis aksara yang setelah masuknya modernitas melalui berbagai hal ± terutama kolonialisasi ± menjadi dominan dan kemudian menggusur berbagai huruf tersebut.
Ragam lisan dan tulis, yang hidup berdampingan, kemudian saling menunjang dalam proses yang disebut literasi sekunder ± ketika yang lisan dituliskan, kemudian dilisankan kembali. Tetapi sekali lagi karena tuntutan modernitas, sastra lisan yang luput direkam dan dituliskan, dan kemudian tidak diturunkan pada generasi berikutnya, juga terancam kepunahan. Kita melihat bahwa keragaman tidak berada di ruang hampa, melainkan dalam suatu konteks sosial, politik, ekonomi yang mau tidak mau berpengaruh pada keragaman sastra. Pendidikan, yang berfungsi menyiapkan pembaca dan penulis, sangat berperan dalam memilih karya apa yang dibaca dan yang diproduksi.
Dalam masa kolonial, sekolah Belanda mengajarkan dan menyediakan bacaan karya sastra Belanda, khususnya dari abad ke-19. Tidak mengherankan jika kemudian para sastrawan kita yang menulis di majalah Pujangga Baru mendapat pengaruh kuat dari penyair aliran romantik di Belanda yang disebut de tachtigers. Kebijakan budaya yang memprioritaskan hal yang satu dari yang lainnya, ikut berdampak pada perkembangan sastra. Satu lagi contoh dari masa kolonial adalah kebijakan pemerintah Belanda melalui badan kebudayaannya yang kemudian menjadi Balai Pustaka untuk memilih sastra dalam bahasa Melayu tinggi sebagai medium bersastra.
Kebijakan ini mengandung kepentingan politik Belanda, karena sastra popular yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit swasta dari berbagai kalangan itu sulit untuk dikontrol. Iklim politik pada waktu Perang Dingin di tahun 1960-an ikut tercermin dalam polarisasi sastrawan di Indonesia dalam aliran seni untuk seni dan seni untuk masyarakat (Moelyanto dan Taufiq Ismail, 1995).
Ketika Orde Baru berjaya, maka karya sastra dan sastrawan dari aliran yang dianggap kekiri-kirian menjadi terpinggirkan. Keberagaman sastra Indonesia yang mulikultural dan kontribusi mitologi Melayu Nusantara itu tidak menyurutkan semangat membangun keindonesia yang lebih baik, yang lebih beradab, dan yang lebih bermartabat. Perkembangan sastra di Indonesia secara nyata menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbudaya, dan bernegara itu pun berkaitan erat dengan kehidupan bersastra.
Suatu keniscayaan bahwa sastra Indonesia merefleksikan kehidupan masyarakat Indonesia yang multimajemuk sehingga secara nyata dapat menjadi cerminan hidup berbangsa, bernegara, berbudaya, dan bermasyarakat yang beradab, bermartabat, serta berkarakter mulia. Di negara yang sedang dalam keadaan krisis multidimensi seperti saat ini, kehidupan sastra kita pun ikut terimbas dengan keadaan tersebut. Sastra yang bercorak reformasi dan keadaan negeri yang dilanda berbagai kerusuhan, disintegrasi bangsa, teror informasi hoak, dan kekacauan politik, ikut pula mewarnai sastra Indonesia modern sehingga banyak orang mengatakan Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia (Ismail, 2008).
Dengan demikian, kalau ditanyakan adakah keindonesiaan dalam sastra Indonesia? Jawabnya tentulah ada. Hanya saja, keindonesiaan atau identitas Indonesia itu bukan bersifat tunggal, melainkan sangat beragam, majemuk, sebagaimana dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat Indonesia itu sendiri adalah keberagaman, plural, dan multikultural. Selain hal tersebut, masyarakat Indonesia sudah sejak lama berada dalam transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang mulai menunjukkan karakter yang responsif, artikulatif, formulatif, dan argumentatif.
Transisi ini ikut berpengaruh dalam perkembangan sastra Indonesia ke arah sastra yang bersifat multikultural. Sastra Indonesia berkembang sejalan dengan dinamika sosial politik, sebagaimana tampak dalam dua buku yang sangat berngaruh di dunia, Modern Indonesia Literature (Teeuw, 1967) dan Modern Indonesia Literature II (Teeuw, 1996). Sastra tidak semata dilahirkan oleh dinamika sejarah dan budaya. Namun sesungguhnya, sastra turut membentuk dinamika sejarah dan buadaya (Greenblatt, 2005). Hubungan sastra dan sejarah sosial politik, dan budaya terjadi timbal-balik. Kajian dan kritik sastra Indonesia tidak pernah lepas dari hubungan ini, misalnya yang dilakukan oleh Malna (2000) terhadap puisi Indonesia secara menyeluruh. Sastra Indonesia selalu dibicarakan dalam kerangka sejarah, ideologi, politik, atau kebudayaan; sebut saja satu studi yang dilakukan oleh Scherer (2012) terhadap Pramoedya Ananta Toer.
Sastra berperan dalam membentuk sejarah, membangun keindonesiaan dengan keanekaragaman budaya (multikultural) sebagai energi dan semangat berbangsa. Sastra Indonesia bukan sebatas dokumen budaya, politik, atau sejarah tetapi babitus keindonesiaan bertumbuh dengan warna-warni lokal. Sastra wujud keindonesiaan yang multikultural. Menulis sastra, mengkonstruksi keindonesiaan multikultural walaupun tidak disadari oleh sastrawan. Pun membaca sastra, memasuki keindonesiaan multikultural.
Novel Indonesia awal mengungkap persoalan tuan dan nyai (kuli, babu, gundik) representasi hubugan domestik menindas dan diskriminatif, seperti diceritakan oleh G. Francis dalam Tjerita Njai Dasima (1896), selanjutnya terbit Njai Painah (1900), Njai Alimah (1904), Njai Aisyah (1915), hingga Njai Marsina (1923). Hal ini juga muncul dalam Max Havelaar (Multatuli, 1868) atau pada novel Anak Semua Bangsa (Pramoedya Ananta Toer, 1980). Roman Balai Pustaka mengangkat kesadaran baru hubungan perlawanan pribumipenjajah. Pada satu sisi, penjajah dipandang pembawa modernisasi dunia Barat menuju negeri Timur, yang tampak pada roman Siti Nurbaya dan roman lain pada masa ini.
Roman Balai Pustaka gemar menampilkan konflik dalam diri pribumi menghadapi modernisasi. Walaupun tidak mudah bagi para pengarang Balai Pustaka menganjurkan pilihan yang tegas: modernisasi atau adat, kuatnya sikap mempertahankan adat, wujud resistensi dan perlawanan kultural terhadap penjajah. Muatan multikultural dalam sastra Indonesia berperan sebagai resistensi atau penolakan budaya penjajah. Memasuki tahun-tahun penentu nasib bangsa, sastra Indonesia bergulat dalam perang melawan penjajah untuk mecapai Indonesia merdeka (lihat cerpen perlawanan terhadap Jepang, Perempuan karya Mochtar Lubis atau Vicker Djepang karya Nugroho Notosusanto).
Semasa pemerintahan Presiden Soekarno sastra terlibat di dalam pertarungan ideologi yang berujung pada kekalahan Komunis dan kemenangan Angkatan Darat, kekuatan yang tidak masuk konstelasi Nasakom (Artika, 2014). Secara politis, pemerintahan Presiden Soeharto menjadi akhir sastra terlibat (realisme sosialis) di dalam dinamika sejarah sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan (Malna, 2000:472-503; Putra, 2008). Sastra dipinggirkan dari kehidupan politik dan dipandang sebagai kemenangan aliran seni untuk seni atau humanisme universal (lawan kubu Lekra).
Kemenangan ini tidak bermakna ketika sastra berhadapan dengan kekuatan politik represif Orde Baru, menabukan sastra, kesenian, dan kebudayaan sebagai gerakan politik. Sastra pun hanya berurusan dengan kertas dan kata, bersih politik dan mengasingkan diri dalam filsafat (lihat karya-karya Iwan Simatupang, Budidarma, Putu Wijaya, Sutardji, dan Danarto). Namun, di luar keadaan tersebut benih sastra realisme sosialis tetap bertumbuh karena hubungan sastra dan kenyataan sebagai keniscayaan (Artika, 2016); akrab dengan persoalan pembangunan Indonesia Orde Baru, namun sastra yang antipemerintah selalu dikekang.
Sampai kini nasib Wiji Thukul misalnya belum jelas, sebagaimana terungkap di dalam sejumlah puisi antologi Akar Rumput. Kehidupan politik tidak demokratis juga mengerdilkan peranan sastra ”tirani dan benteng” atau sastra protes sosial Angkatan 66 yang pada dekade 1960-an mencapai puncak kejayaan. Walaupun kelompok ini jemawa menerima kemenangan atas kubu Lekra (Moeljanto dan Ismail, 1995) sebagai imbas tragedi 1965 dan keluarnya Tap MPRS XXV/1966, toh semasa Pemerintah Orde Baru, mereka pun tercerai berai dan mencoba mendekati media koran.
Pengajaran sastra model ini juga terhambat oleh pendekatan teoretis dan struktural dengan tujuan untuk menyiapkan siswa menjawab tes teori sastra, berbentuk pilihan ganda. Minimnya atau bahkan minat sastra guru yang rendah, gayung bersambut dengan pendekatan teoretis dan struktural, satu-satunya pilihan pengajaran sastra. Harapan untuk lepas dari masalah ini ada pada pengajaran bahasa berbasis teks. Perlu niat baik guru agar sudi mengubah paradigma pengajaran, dari teori ke teks.
Dalam Kurikulum 2013 teks fiksi memperoleh kedudukan yang sangat penting. Basis teks tidak harus dimaknai dengan pengajaran mengenai teori struktur dan kebahasaan teks, yang akan menyimpangi ide besar pengajaran bahasa Kurikulum 2013. Hal ini memang sudah menggejala di sekolah. Jika ini berlanjut maka sekali lagi siswa tidak membaca sastra dalam pengajaran sastra tetapi mereka mengetahui teori teks sastra. Harapan terakhir, pengajaran sastra di universitas. Mata kuliah sastra harus berdasar karya. Mahasiswa calon guru bahasa sepanjang semester-semester yang diikuti harus diperkenalkan dan ”dipaksa” membaca secara langsung khazanah sastra bangsa dan dunia. Di sinilah literasi sastra dibentuk. Semua ini dilakukan untuk menyiapkan guru yang berwawasan sastra dan membukakan pintu kepada siswa menuju dunia sastra, berpetualang di dalamnya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Seni dan Sastra dalam Keindonesiaan
Kamis, 11 Januari 2024 06:20 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
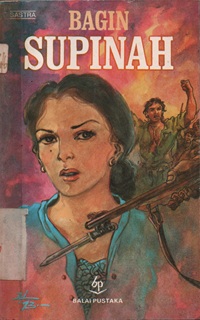






 99
99 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan








