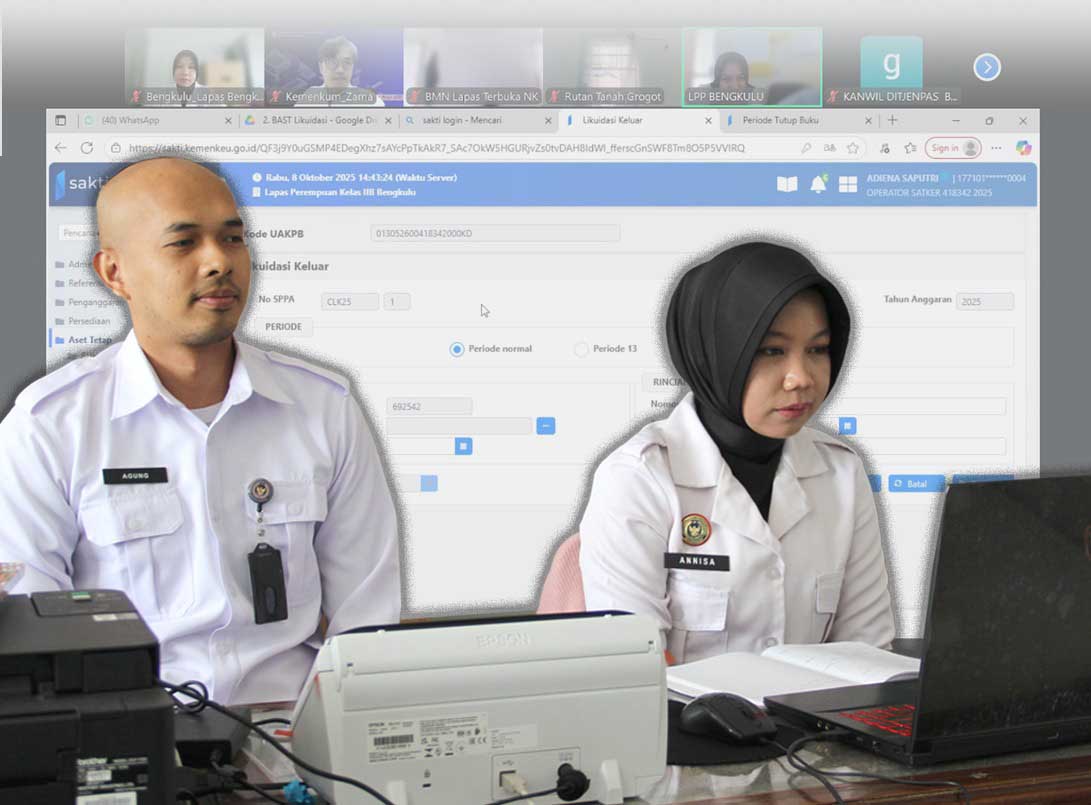Menaiki Pedati yang Ditarik Kuda Lumpuh
Kamis, 10 April 2025 14:19 WIB
Di tangan pemimpin lemah, hirarki jjadi agama baru. Mereka duduk di menara gading, menatap tim dari kejauhan dengan kacamata silinder birokrasi,
***
Bayangkan Anda tengah menaiki pedati yang elegan, penuh penumpang dengan harapan besar menuju tujuan bersama. Namun, pedati itu ditarik oleh seekor kuda yang lumpuh. Ia tak bisa berlari, bahkan untuk berjalan pun terseok-seok. Itulah gambaran yang tepat untuk organisasi yang dalm sistem kepimpinan yang lemah—gerak lambat, tujuan kabur, dan semangat pun mandek. Itulah nasib banyak organisasi yang—penuh rencana, strategi, dan jargon motivasi, tapi ditarik oleh kepemimpinan yang lebih cocok mengatur lalu lintas siput ketimbang mengomando revolusi.
Pemimpin lemah tidak kekurangan kata-kata, hanya kekurangan makna. Mereka rajin membuat rapat, tapi jarang hadir secara maknawi. Seperti filsuf palsu yang fasih berbicara tentang etika tapi memarkir mobil di trotoar, pemimpin seperti ini menyebarkan ilusi arah. Mereka tidak memimpin, mereka hanya berada di depan, berharap tim mengikuti suara sandal mereka yang seret tanpa gairah.
Organisasi semacam ini adalah meditasi kolektif tentang absurditas. Semua terlihat sibuk, semua tampak produktif, tapi tidak satu pun bergerak ke depan. Ini bukan stagnasi, ini adalah gerak semu: seperti treadmill, penuh peluh tapi tak menghasilkan jarak. Sartre mungkin akan menyebutnya sebagai being-for-nothing, kita ada, tapi untuk apa?
Mereka punya “visi”, tentu saja. Tetapi visi itu seumpama lukisan kabut di atas kertas minyak yang tidak jelas, tidak konkret, dan ketika disentuh, malah basah. Di bawah kepemimpinan seperti ini, anggota tim merasa seperti pemeran dalam sandiwara absurd: tahu perannya, tapi tak tahu ceritanya. Seperti kata Kierkegaard, “Kecemasan adalah pusing yang lahir dari kebebasan.” Namun dalam organisasi ini, kecemasan muncul karena tak ada yang tahu siapa yang seharusnya memimpin siapa.
Di tangan pemimpin lemah, hierarki menjadi semacam agama baru. Mereka duduk di menara gading, menatap tim dari kejauhan dengan kacamata silinder birokrasi. Ketika karyawan mencoba bicara, mereka hanya mendengar gema dari ruang kosong. Inilah hierarki bukan sebagai struktur efisien, tetapi sebagai pelindung ego yang rapuh. Seperti yang dikatakan Nietzsche, “Manusia lebih takut kehilangan kekuasaannya daripada kehilangan moralnya.”
Jika Tuhan menciptakan dunia dalam tujuh hari, pemimpin mikro akan butuh empat belas hari, dua belas spreadsheet, dan enam belas pertemuan daring hanya untuk menyetujui bentuk awan. Kepemimpinan lemah percaya bahwa kontrol adalah bentuk cinta. Padahal yang dirasakan tim justru belenggu digital dan survei kelelahan berkedok “check-in harian.” Inilah cinta yang menyedihkan—yang menghitung setiap detak jantung, tapi lupa makna hidup. Dan, Stephen Covey bilang, “Organisasi yang gagal biasaya terlalu banyak dikelola dan kurang dipimpin”.
Salah satu ironi terbesar dari pemimpin lemah adalah mereka percaya bahwa mengatakan “terima kasih” adalah bentuk umpan balik yang utuh. Tidak ada koreksi, tidak ada dorongan. Hanya pujian yang menggantung, seperti lampu taman yang mati di malam buta. Bahkan dalam drama Shakespeare pun, pujian tanpa makna adalah racun berbalut madu. Dan di ruang rapat kita, racun itu disajikan setiap Jumat sore menjelang pulang.
Pemimpin lumpuh sering memiliki fleksibilitas moral yang luar biasa. Janji adalah semacam puisi korporat, indah untuk didengar tapi tak pernah dimaksudkan untuk ditepati. Mereka bicara tentang “nilai perusahaan” saat memotong anggaran. Mereka berbicara soal integritas dari balik invoice yang di-mark-up. Dan kita semua tersenyum, karena tahu bahwa etika dalam kepemimpinan lemah hanyalah alat selfie demi citra LinkedIn.
Marissa Mayer di Yahoo, Travis Kalanick di Uber, Jeff Skilling di Enron semuanya pernah mengendarai pedati indah yang ditarik oleh ambisi buta dan etika pincang. Mungkin kuda mereka bahkan sempat berlari, tapi ke jurang. Maka, kita belajar bahwa bukan hanya kepemimpinan yang gagal, tapi juga struktur yang membiarkan mereka tetap duduk di bangku kusir, bahkan setelah pedatinya terbakar.
Di organisasi yang ditarik oleh kuda lumpuh, ide adalah makhluk yang asing. Jika ada yang berani mengusulkan sesuatu, maka ia akan dikremasi dalam rapat evaluasi tanpa naskah. Tak ada tempat bagi kreativitas, karena pemimpin lebih sibuk mengatur distribusi laporan bulanan ketimbang menyiapkan masa depan. Akhirnya, ide terbaik hanya berakhir di pojok whiteboard, dikelilingi oleh tanda tanya dan ketakutan.
Begitulah. Di lingkungan dengan kepemimpinan lumpuh, inovasi adalah makhluk asing. Setiap gagasan baru diperlakukan seperti virus: dikarantina, dipelintir, lalu diarsipkan. Pemimpin takut pada hal yang tak bisa dikontrol, dan ide adalah makhluk paling liar. Maka kreativitas pun mati muda, tidak karena ditolak tapi karena dibungkam dalam kerangka prosedur.
Organisasi ini bisa jadi memiliki “nilai-nilai organisasi” yang ditempel di dinding. Tapi seperti semua dekorasi palsu, ia hanya jadi latar belakang selfie. Nilai-nilai itu bukan untuk dihayati, tapi untuk disalin ke presentasi tahunan. Seperti kata Camus, absurditas bukan terletak pada dunia, tapi pada manusia yang terus berharap pada sistem yang tak pernah belajar dari dirinya sendiri.
Haruskah kita terus menaiki pedati ini? Ataukah saatnya kita merancang ulang kendaraan dan mengganti kusirnya? Dalam dunia ideal, organisasi akan memilih pemimpin yang sadar diri, rendah hati, dan cukup bijak untuk tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Mereka yang tak hanya paham peta, tapi juga membaca cuaca, kondisi roda, dan kelelahan kudanya. Kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal keberanian filosofis untuk menyadari bahwa semua ini absurd dan tetap mencoba memperbaikinya.
Dalam dunia yang bergerak cepat, menaiki pedati yang ditarik kuda lumpuh adalah tindakan eksistensial: kita tahu ia tak akan sampai, tapi tetap berharap. Namun, harapan tanpa tindakan adalah candu. Maka, pilihannya hanya dua: turun dari pedati, atau bangunkan kuda dengan semangat kepemimpinan yang baru yang jujur, adaptif, dan tidak takut belajar dari kekeliruan. Karena jika tidak, kita semua hanya akan menjadi penumpang dalam cerita lucu yang tragis, tertawa atau menangis sambil jalan di tempat.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita rela duduk manis di pedati yang ditarik kuda lumpuh? Apakah karena takut kehilangan kenyamanan ilusi? Ataukah karena kita tak berani bertanya siapa yang sebenarnya mengendalikan arah? Kadang, tindakan paling rasional adalah turun dari pedati, membuka kandang, dan mulai merakit kendaraan baru. Karena jika tidak, kita akan terus menjadi bagian dari parade kebodohan yang lamban tapi pasti yakni menuju “kematian organisasi” itu.
Penggiat literasi dan penikmat kopi susu
55 Pengikut

Absennya Integritas dalam Masyarakat Bermuka Dua
Jumat, 30 Mei 2025 13:48 WIB
Dedi Mulyadi dan Krisis Kepemimpinan di Indonesia
Kamis, 29 Mei 2025 07:37 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 98
98 0
0