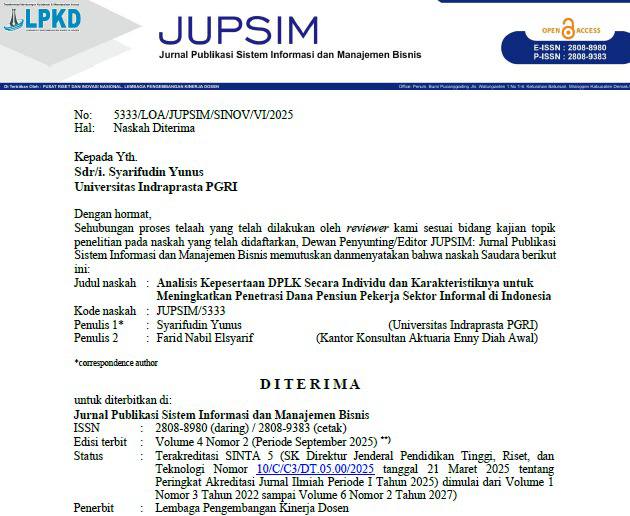Mahasiswa Universitas Nurul Huda
Sebiduk Sehaluan
Kamis, 3 Juli 2025 10:06 WIB
Bersama untuk bangkit dari segala trauma, luka, dan putusnya harapan.
Perahu melaju sehaluan
Kepada jiwa-jiwa yang terancam kematian
Matahari menyingsing di sebelah timur. Cahayanya berpendar menerobos kulitku yang putih, begitu hangat setelah cuaca dingin menerpa tubuhku dan juga penduduk lain yang tengah mengungsi di tenda-tenda darurat. Mataku menyelisik diantara robohan bangunan-bangunan besar berharap serpihan kenangan bisa terus selalu mengingatkanku kepada Ubak dan Umak.
Apa yang harus kulakukan, sudah dua jam mencari serpihan-serpihan itu namun tak kunjung kutemukan. Aku merasa baru kemarin saat Umak membuat Pindang Ikan Gabus beraroma tempoyak yang begitu sedap, saat Ubak membuat pancing tradisional untuk menangkap ikan di sungai, saat Mama Irin memberiku sepotong kue beraroma durian yang begitu legit disertai potongan strowberi sebagai hiasan.
Seketika tubuhku terhuyung, rasa sesak ini semakin menusuk hatiku. Kuremas bajuku yang sudah kusut. Ketidakpastian adalah hal yang paling menakutkan. Apakah Ubak, Umak dan Mama Irin masih hidup atau telah menghadap Sang Kuasa. Setidaknya tinggalkanlah tanda agar aku bisa mencari mereka meskipun kenyataan begitu menyakitkan. Lamat-lamat kudengar seseorang memanggilku, segera kuhapus air mataku dengan tangan yang kotor oleh debu dan lumpur.
"Oyy, Laila!" teriak Edo di seberang jalan yang terhalang oleh reruntuhan bangunan. Aku menatapnya berlarian kesana kemari saat melintasi reruntuhan itu.
"Aku sudah yakin kamu ada di sini Laila. Jadi aku langsung kesini setelah mengantar logistik ke pengungsian bagian selatan. Tenang saja, aku sudah meminta izin Pak Rizal," jelas Edo napasnya masih tersengal. Aku hanya tersenyum menanggapinya.
"Apa yang kamu bawa?" tanyaku. Edo segera membuka palstik hitam yang ia bawa. Seketika mataku terbuka lebar setelah menangis di antara reruntuhan yang berdebu."Bagaimana kamu mendapatkan buku-buku ini?"
Edo menyerahkan tiga buku ciptaan sastrawan yang paling kukagumi. Dua buku karya Chairil Anwar dan satu buku karya Pramoedya Ananta Toer. Di jaman yang serba modern ini sangatlah sulit mendapatkan buku fisik, buku fisik telah berubah menjadi chip transparan yang tertempel di tangan dan bisa menampilkan hologram berbentuk buku dengan tulisan yang bahkan bisa diterjemahkan oleh lebih dari seribu bahasa.
Indonesia telah mencapai kejayaannya lebih dari lima puluh tahun yang lalu. Bahkan desaku yang terletak di pelosok Sumatera Selatan telah berubah menjadi perkampungan yang modern. Rumah-rumah berbentuk bulat perak bekilau saat tertimpa cahaya matahari maupun rembulan. Namun hanya satu-satunya rumahku, peninggalan Akas yang masih murni menjadi warisan budaya.
Rumah panggung dengan material kayu jati dengan ukiran di setiap kusen pintu dan jendela. Saat musim liburan tiba, rumahku sudah seperti tempat wisata. Banyak turis yang berdatangan menggunakan mobil terbang demi melihat rumahku, kerap kali Ubak yang galak mengusir turis yang datang karena enggan sekali dengan keramaian.
Buku yang di bawa Edo benar-benar mengingatkanku pada masa-masa itu. Masa di mana saat liburan tiba dan banyak turis berdatangan. Sementara Umak dan Mama Irin sibuk menyambut mereka, aku mengunci pintu kamarku rapat-rapat dan bercengkrama bersama buku-buku fisik yang ada di rak buku kamarku. Seharian kuhabiskan waktu untuk membaca, aku tak menghiraukan teriakan Umak karena sangat asik membaca, sampai tertidur dan bangun setelah keadaan rumah sepi dari para turis.
"Aguyy, budak sikok ini rajin betul. Anak gadis kesayangan Ubak baru terbangun dari Istananya," sindir Mama Irin yang tengah sibuk membantu Umak menyiapkan makan malam. Aku hanya tertawa kecil menampilkan wajah seolah-olah bersalah.
"Ada Bimbim, Mama Irin sayangku," ucapku meledek Mama Irin. Bimbim adalah robot kucing yang bisa membantu pekerjaan rumah dengan cekatan. Pekerjaan menyambut para turis semakin mudah dengan adanya Bimbim si robot kucing.
Namun semua itu tinggallah kenangan. Saat Gunung Purba menampakkan kegagahannya satu tahun yang lalu, seluruh perkampungan modern luluh lantak oleh kepulan abu vulkanik, guncangan gempa bumi yang begitu dahsyat dan juga aliran banjir dari danau yang turut menghanyutkan bangunan bulat perak di beberapa daerah, dan ironisnya rumah panggung peninggalan Akas yang menjadi satu-satunya objek budaya hancur lebur oleh gempa.
"Apa kamu sudah mengisi formulir masuk perguruan tinggi Laila?" Suara Edo tiba-tiba menghancurkan lamunanku.
"Belum," jawabku singkat.
Kini Edo memboncengku menaiki motor terbang. Akan tetapi motor terbang ini tidak bisa terbang, Edo beberapa kali mengaktifkan mode terbang namun hanya si pemilik motor yang bisa menerbangkannya, yaitu Pak Rizal. Edo meminjam motor terbang yang tidak bisa terbang ini dari Pak Rizal sebagai penanggung jawab di wilayah pengungsian kami. Pak Rizal yang tengah sibuk mengurusi pernikahan salah satu pasangan di pengungsian langsung saja memperbolehkan Edo meminjamnya.
"Baiklah, kalau begitu akan kutemani kamu mengisi formulir itu. Ada tempat baru yang kutemukan, sangat indah Laila. Apa kamu mau kesana?"
"Dimana memangnya? Bukankah kamu sudah membawaku mengelilingi wilayah ini?" tanyaku penasaran.
"Tidak. Belum Laila. Ada sebuah tempat yang sangat indah, bahkan itu sangat dekat dengan pengungsian kita. Aku menunggu waktu yang tepat untuk membawamu kesana." Edo menambah laju gas pada motor terbang yang tidak bisa terbang ini. Melaju kesana kemari sembari melewati reruntuhan yang belum ditindak lanjuti oleh Pemerintahan.
Selama hidup di pengungsian, Edo selalu membantuku. Aku bertemu dengannya saat terjebak di dalam angkutan terbang yang terpelanting jatuh saat bencana besar itu terjadi satu tahun yang lalu. Sama halnya denganku, keluarga dan orang tuanya menghilang. Bedanya, Edo akan selalu mensyukuri apa yang terjadi padanya. Ia menikmati hidup di pengungsian dengan memperbanyak bekerja membantu para petugas sehingga ia dengan mudah beradaptasi.
Sedangkan Aku, hanya bisa terpuruk dan menyalahkan keadaan. Lima tahun yang lalu saat pemerintahan mendeklarasikan pembuatan segel pembatas untuk semua gunung di Indonesia agar tidak terjadi bencana : baik itu gempa, tsunami, maupun letusan gunung yang bisa menghancurkan Indonesia yang sudah jaya. Ubak benar-benar mengutuk program pemerintah ini yang seolah-olah mendahului takdir Sang Kuasa. Hasilnya apa? Kehancuran. Wilayah Indonesia bagian Lampung hingga daerah perkampunganku di pelosok Sumatera Selatan hancur. Lantas siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa yang bisa mengembalikan Ubak dan Umak yang hilang? Aku benar-benar sudah seperti Ubak yang mengutuk Pemerintahan.
Edo telah menghentikan laju motor. Aku terpana melihat pemandangan yang begitu indah di depan mataku. Sang Kuasa telah menyisakan salah satu keindahan alam agar aku bisa terus selalu ingat akan Kuasanya.
"Bagaimana? Indah bukan?"
"Ini adalah sungai satu-satunya yang tidak terdampak abu vulkanik. Entah bagaimana bisa seperti ini. Alirannya sangat jernih bukan? Mungkin banyak ikan di sana, kamu mau memancing Laila?"
"Memangnya kamu bawa alat pancingan?"
"Tidak." Edo tertawa melihat wajah sebalku menanggapi jawabannya itu.
"Kemarilah, akan kuceritakan sesuatu," ucap Edo yang sudah duduk di tepi sungai yang tenang. Aku turut duduk di sampingnya, sesekali cipratan air sungai mengenai wajahku, begitu segar sekali.
"Apakah kamu sudah tahu Laila. Sungai ini dahulunya dijadikan bendungan, namanya Bendungan Perjaya. Umbayku dulu pernah menceritakannya saat aku masih kecil," jelas Edo. Sesekali melempar kerikil ke sungai. Aku juga mengikuti gerakannya melempar kerikil ke sungai, cukup seru.
"Bagaimana? Apa kamu sudah menentukan mau memilih perguruan tinggi dimana? Menurutku sih ... kamu masuk saja ke Universitas Nurul Huda"
"Bukankah kamu menyukai menulis? Perguruan tinggi itu sangat maju di bidang kepenulisan dan sastra. Mereka juga masih menyimpan buku-buku fisik di perpustakaannya. Buku yang kuberikan kepadamu itu dari sana Laila." Edo terus melanjutkan lemparan kerikilnya itu. Kali ini lebih jauh dan bertenaga.
"Perguruan tinggi itu juga sudah dilengkapi sistem pengaman di setiap asramanya. Sehingga aman untuk berlindung. Saat aku mengirim logistik kesana banyak sekali pengungsi dan juga banyak informasi yang kudapat," jelas Edo. Aku mulai tertarik dengan percakapan ini. Apakah aku harus masuk ke perguruan tinggi itu?
"Kamu tahu Laila. Umakku telah di temukan, seseorang memberi tahuku bahwa sekarang ia berada Kalimantan, di Ibu Kota, Laila. Tapi hanya Umakku saja yang selamat, tiga kakak lelakiku telah tiada." Edo menghentikan lemparannya, kemudian ia menatapku.
"Aku senang tapi juga sedih. Umakku selamat tapi tiga kakakku tiada. Umakku selamat tapi sepasang kakinya diamputasi, sekarang Umakku berada di Rumah Sakit Kalimantan bersama saudara jauhku Laila."
"Bagaimana Umakmu bisa berada di Ibu Kota?" tanyaku.
"Iya, saudara jauhku menemukan Umak saat berada di Rumah Sakit darurat kemudian membawanya ke Kalimantan. Kemudian ia meninggalkan pesan untukku," ucap Edo. Ia kembali melemparkan kerikil.
"Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu akan ke Kalimantan menemui Umakmu?" Saat ini aku benar-benar penasaran apa yang akan Edo jawab.
"Sepertinya aku akan kesana Laila, sampai Umakku sembuh. Saudaraku sudah mendaftarkanku di perguruan tinggi ternama di sana. Aku juga bisa bebas belajar dan bereksperimen jika kuliah di sana," jelas Edo.
Entahlah, apa yang saat ini kurasakan benar-benar rancu. Aku senang tapi juga ... aaah entahlah. Apa hakku jika harus melarang Edo pergi? Siapa diriku jika harus ikut dengannya? Yang ada aku hanyalah beban bagi Edo. Di pengungsian saja sudah banyak merepotkannya, apalagi jika harus ikut ke Kalimantan.
Edo telah menemukan cahayanya meski itu samar. Sedangkan aku masih terkurung dalam gelapnya kesedihan yang kuciptakan. Satu tahun bencana ini berlalu, namun belum juga usai aku menghilangkan kesedihan ini. Tetap mencari serpihan kenangan foto atau apalah itu di rumah panggung yang sudah hancur lebur, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Aku sebatangkara.
"Apa yang akan kamu lakukan di dunia yang hancur ini Laila?"
Mengapa Edo menanyakan hal seperti ini. Aku bahkan tidak tahu apa tujuanku sebenarnya, bahkan menentukan pilihan masuk perguruan tinggi sangat sulit bagiku. Hal sekecil menentukan mana lauk yang akan kuambil saat makan di pengungisan pun aku tidak bisa, dan pada akhirnya Edo lah yang mengambilkan. Lalu mengapa kamu menanyakan hal seperti ini? Jelas aku tidak bisa menjawabnya.
"Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kamu isi saja formulir pendaftaran itu. Kamu mau perguruan tinggi mana? Atau mau ikut bersamaku ke Kalimantan?"
"Tidak!" jawabku mantap. "Hidupmu ada di Kalimantan Edo, Umakmu ada di sana. Aku akan tetap berada di sini, tempat kelahiranku. Dan masalah perguruan tinggi, aku akan menuruti saranmu. Aku akan menjadi penulis hebat berasal dari Sumatera Selatan. Tulisanku akan melintasi pulau, menyebrangi lautan, dan banyak daerah agar sampai kepadamu. Jangan lupa untuk membaca tulisanku."
"Baiklah kalau begitu." Edo tersenyum. Wajahnya kali ini terlihat lebih tenang.
***
Sukaraja, 20 April 2080
"Lailaa! Lihatlah! Sini-sini." Mira tiba-tiba saja menarikku saat sedang menyiapkan perlengkapan wisuda.
Tidak terasa saat Edo menyarankanku masuk perguruan tinggi itu, dan lihatlah sekarang aku menjadi mahasiswi Universitas Nurul Huda yang besok akan di wisuda.
Edo benar, asrama milik perguruan tinggi ini dilengkapi sistem pengaman sehingga kami terhindar dari cuaca ektrem maupun bencana seperti guncangan gempa dengan skala tidak terlalu besar. Aku aman berada di sini, dan selebihnya aku mengenal teman baruku, Mira.
Saat pertama kali melihatnya kukira dia adalah orang turunan wilayah timur Indonesia. Kulitnya sangat coklat, rambutnya benar-benar kribo, tapi jika dilihat wajahnya begitu manis.
"Ada apa siih?" tanyaku risih. Mira menarik-narik bajuku. Inilah alasan mengapa bajuku molor.
"Kau jingok ini dulu. Bukankah ini karyamu Laila? Aku sepertinya pernah membaca kalimat-kalimat ini, dan aku tidak salah lagi. Ini adalah karyamu Laila. Karyamu di plagiat!" Mira memberikan chip yang menampilkan hologram buku.
Kubaca prolog yang ada di buku hologram itu lalu kemudian ku cocokkan dengan kalimat yang ada di laptopku. Benar sekali, ini adalah tulisanku tapi sama sekali tidak tertera akulah penciptanya. Susah payah kutulis, kurangkai kata demi kata menjadi kalimat yang indah, lalu kukirim ke penerbit. Lalu apa ini?
Segera kukirim surel ke penerbit menindak lanjuti plagiarisme ini. Wajahku kalut, seharusnya hari ini menjadi hari paling menyenangkan bagiku. Edo mengirim pesan akan datang ke wisudaku. Namun sialnya mengapa harus ada masalah seperti ini.
"Sudah kau kirim surel itu Laila?" Mira bertanya. Aku hanya mengangguk menanggapinya.
"Kalau tidak segera di balas, lebih baik kau laporkan saja ke pihak berwajib." Mira kini duduk di ranjangku.
"Mungkin...," gumamku. Aku terlalu bodoh, mengapa aku tidak mengecek surat perjanjian dengan teliti. Aku baru menyadarinya saat kubaca ulang, penerbit itu tidak bertanggung jawab atas plagiarisme. Kata-kata yang tertuang dalam kontrak ini sangat tidak jelas. Arrghh bagaimana ini!
Dulu aku terlalu senang saat tulisanku diterima penerbit, jadi asal-asalan saja menandatangani kontrak itu. Tulisanku yang di plagiat adalah kisahku saat di pengungsian. Kutulis kisah itu agar aku bisa terus selalu mengingat setiap detik kejadian yang kualami. Dan dengan entengnya orang-orang itu memplagiat tulisanku.
"Laila, ada panggilan masuk tuh. Aku ke kantin dulu ya, mau ikut?" ajak Mira, aku menggeleng menjawabnya. Lantas kulihat ponselku, benar sekali seseorang meneleponku. Edo meneleponku. Enggan sekali rasanya menjawab panggilan itu. Aku terlalu malu dengan wajahku yang kusut ini.
Beberapa detik kemudian ia mengirim pesan jika sudah berada di depan pintu gerbang asrama. Secepat kilat aku bersiap-siap menemuinya, terlebih berusaha menghilangkan raut wajah yang kusut ini. Aku segera menaiki lift asrama menuju lobi, pintu keluar ada di sana.
Jantungku seperti roler coaster yang terus naik turun. Detak jantungku tak karuan. Lima tahun kami tidak saling bertemu. Sesekali hanya mengirim pesan menanyakan kabar, terkadang Edo juga mengirimkan paket buku fisik untukku. Edo akan mengirim permintaan maaf jika ia tidak sempat mengabari ataupun tidak mengirimkan buku-buku kepadaku. Aku pun memakluminya, seharusnya aku yang meminta maaf karena sudah berada di kejauhan dari Edo aku masih merepotkannya.
Gerbang asrama terbuka. Jantungku sepersekian detik terenti melihat Edo yang tersenyum ramah padaku. Auranya begitu berbeda, wajahnya yang dulu kusam oleh debu sekarang bersinar oleh pancaran aura kepintarannya.
"Hai! Laila," sapa Edo. Ia membawa motor terbang berwarna merah. Kali ini motor yang ia bawa bisa terbang, memungkinkan bisa mengelilingi tempat-tempat indah dengan cepat.
"Ha - hai, Edo," jawabku. Tanganku dingin sekali. Coba lihatlah, apakah wajahku memerah? Malu sekali.
"Ayo naiklah! Aku akan melihatkanmu tempat yang indah," ajak Edo. Aku pun menuruti perintahnya menaiki motor terbang ini. Dahulu aku dibonceng menggunakan motor yang dipinjam Edo dari Pak Rizal, motor itu tidak bisa terbang sehingga sangat lamban. Tapi kali ini, aku dibonceng lagi menggunkan motor terbang yang bisa terbang, seru sekali.
Beberapa menit kemudian laju motor mengurangi kecepatannya. Edo membawaku ke sebuah tempat, sepertinya aku tidak asing dengan tempat ini. Sebuah rumah panggung berdiri kokoh di dekat anakan sungai kecil. Beberapa rumah bulat juga turut ada di sana meski masih dalam proses pembangunan. Ini adalah desaku. Lama sekali aku tidak mengunjunginya. Telah kuikhlaskan kepergian Ubak, Umak dan Mama Irin, dan mencoba menjalani hidup dengan tenang. Desaku sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya, mungkin beberapa tahun kemudian barulah dihuni.
"Mengapa kamu membawaku kesini?" tanyaku.
"Aku tahu kamu pasti akan menanyakan hal ini. Pertama Laila, maaf aku tidak bilang kepadamu. Sebenarnya satu tahun yang lalu aku kemari. Aku mencoba kembali membangun rumah panggung ini untukmu," tutur Edo, ia berbalik menatapku.
"Kedua, aku sudah membaca semua bait-bait puisi indahmu. Aku sudah berjanji akan membaca semua tulisanmu itu Laila, dan boleh aku jujur itu sangat indah. Namun aku juga mengetahui dan menyimpulkan apa yang kamu rasakan, perih memang. Tapi inilah kehidupan," ucap Edo. Entah mengapa mataku tiba-tiba berair. Suara gemericik air sungai dan suara burung-burung di pagi hari begitu mendukung suasana hatiku.
"Ketiga, Laila. Aku tahu ini milikmu." Edo memunculkan hologram buku, itu adalah kisah ciptaanku yang di plagiat. Edo melanjutkan, "Aku meminjam chip ini ke Chika, anak Wali Kota. Maaf karena selama ini aku tidak bercerita padamu. Sebenarnya di Kalimantan hidupku bergantung pada Wali Kota," jelas Edo yang masih belum bisa kumengerti.
"Sebelum bencana ini terjadi, aku mengirimkan surel ke Wali Kota di Kalimantan agar merekrutku menjadi bagian dari penelitian Pemerintah mengenai segel gunung itu. Saat bencana itu terjadi, Wali Kota menyetujuinya dan mengharuskanku segera ke Kalimantan. Wali Kota memerintahkan agar tidak ada satu pun berita bocor mengenai penelitian ini, maaf jika aku harus berbohong padamu menyatakan bahwa di Kalimantan aku bersama saudara jauhku."
"Sebagai gantinya Umakku akan dirawat semaksimal mungkin. Dan sekarang ia sudah sehat seperti biasanya, Laila," ucap Edo. Ia menatapku lekat.
"Selain itu Wali Kota juga memintaku untuk menjadi pasangan anaknya, Chika. Tapi terus terang aku tidak bisa. Dan asal kamu tahu, orang yang memplagiat tulisanmu ini adalah Chika, Laila."
Sungguh, aku tidak bisa berkata apapun. Semua hal yang dikatakan Edo sangatlah di luar nalarku. Bagaimana bisa seperti ini.
"Aku sangat mengenali ini adalah karyamu Laila. Setiap detik, menit, hari yang kamu lalui bersamaku, aku ingat semua itu. Kamu menuliskannya dengan sangat indah." Air mataku menetes begitu saja. Benar, aku menuangkan segenap isi hatiku ke dalam tulisan itu. Kuhabiskan setiap malam menulis kata, kalimat, menjadi paragraf yang bermakna.
Kepada burung, angin yang bertiup
Kepada ikan, dan air yang mengalir
"Laila, dunia ini akan hancur. Aku melakukan penelitian dengan dalih kuliah. Aku memang kuliah dan masuk perguruan tinggi ternama di sana, tapi hanya butuh satu tahun aku bisa menyelesaikannya." Aku terkejut mendengar perkataan Edo.
"Aku selalu sibuk melakukan penelitian. Pagi, siang, malam, sampai pagi lagi. Bahkan bisa dihitung jam aku tertidur, itulah sebabnya aku tidak menghubungimu Laila," ucap Edo. Ini juga menjadi alasanku untuk tidak membalas ataupun menghubunginya, aku takut ia akan terganggu dengan pesan-pesanku.
Kepada gelap yang tak berpenghujung
Kepada cahaya yang setia bersinar
"Saat melakukan penelitian yang begitu panjang, kami telah berhasil membuat segel yang pas untuk semua gunung. Gunung-gunung itu akan meletus secara normal dan tidak akan terjadi pemusnahan seperti dahulu. Namun setiap perbuatan pasti ada pertanggung jawaban Laila. Bumi ini secara perlahan akan mati, tumbuhan tidak akan lagi bisa hidup, begitu juga dengan manusia. Saat ini Pemerintah sedang mencari solusi untuk masalah ini. Aku menolak perintah penelitian ini Laila, aku tidak ingin lebih jauh tenggelam di dalamnya."
Aku berdiri menatap mega-nya langit
Sampaikanlah salamku kepada jiwa-jiwa yang berpulang
Sampaikanlah salamku kepada jiwa-jiwa yang bertatap
"Aku telah berpikir dua langkah ke depan, menduplikat isi pikiran dan gagasanku ke dalam robot yang akan membantu penelitian itu lebih lanjut adalah pilihan yang tepat," ucap Edo sembari menatap anakan sungai dengan aliran yang begitu jernih. Itu adalah tindakan yang tepat namun penuh resiko hilang ingatan.
"Apa kamu tidak takut melakukan itu semua?”
"Tidak," jawabnya singkat.
"Apakah kamu masih mengingat pertanyaannku, apa yang akan kamu lakukan di dunia yang hancur ini? Sejujurnya aku juga tidak tahu Laila," ucap Edo. Ia berbalik memandangku.
"Tapi itu semua terjawab setelah membaca bait puisimu. 'Perahu melaju sehaluan', 'kepada jiwa-jiwa yang terancam kematian.' Kita berada di ambang kematian Laila. Lalu aku memutuskan ...," ucap Edo menatapku lekat. Semudah itukah ia menafsirkan puisi-puisiku?
"Aku akan berada pada satu perahu bersamamu. Menahkodainya hingga ke titik dimana kita akan menuju." Edo benar-benar dengan perkataannya. Perkataannya bagai jarum-jarum kecil yang dilepaskan dari busur, melenting di udara dan menancaap satu demi satu di sanubariku. Air mataku kembali meluncur.
"Aku mengetahui perasaanmu setelah membaca bukumu yang di plagiat. Namun kamu tidak pelu khawatir, aku telah mengurusnya. Chika akan mempertanggungjawabkan perbuatannya." Edo menggenggam erat jemariku, mencoba menenangkan.
"Besok akan kubawa Umakku ke hadapanmu Laila. Kamu akan segera memiliki Ibu, kamu tidak sendirian lagi Laila. Ada aku dan Umak yang akan menjadi bagian dari hidupmu. Aku akan menikahimu Laila."
***
Kata-kata itu telah menjadi penutup kisahku. Kini pemerintah sudah melakukan regulasi mengenai segel gunung itu. Dengan bantuan Edo aku sukses menjadi penulis yang tidak dibodohi oleh penerbit, karena sekarang akulah pemilik perusahaan penerbit ternama di Sumatera Selatan. Dan Edo kini menjadi Dosen di Universitas Nurul Huda. Ia tak ingin kembali menggeluti penelitian itu, lebih baik menularkan ilmunya ke generasi selanjutnya itu adalah pilihan yang terbaik.
Inilah kisahku.
Selesai
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Tugas Mencari Hewan
Kamis, 3 Juli 2025 10:39 WIB
Sebiduk Sehaluan
Kamis, 3 Juli 2025 10:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




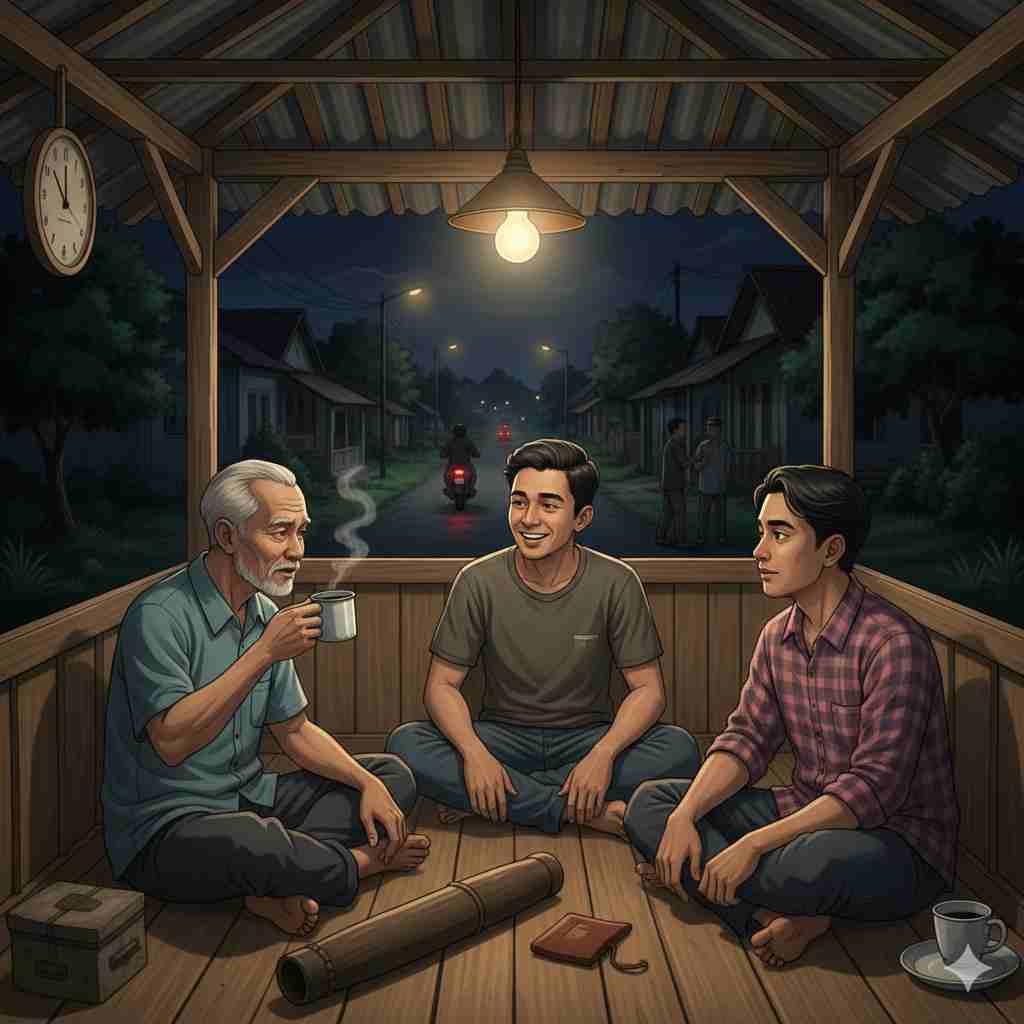

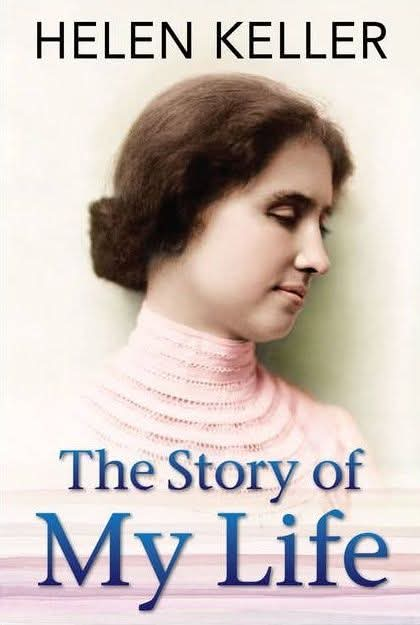
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0