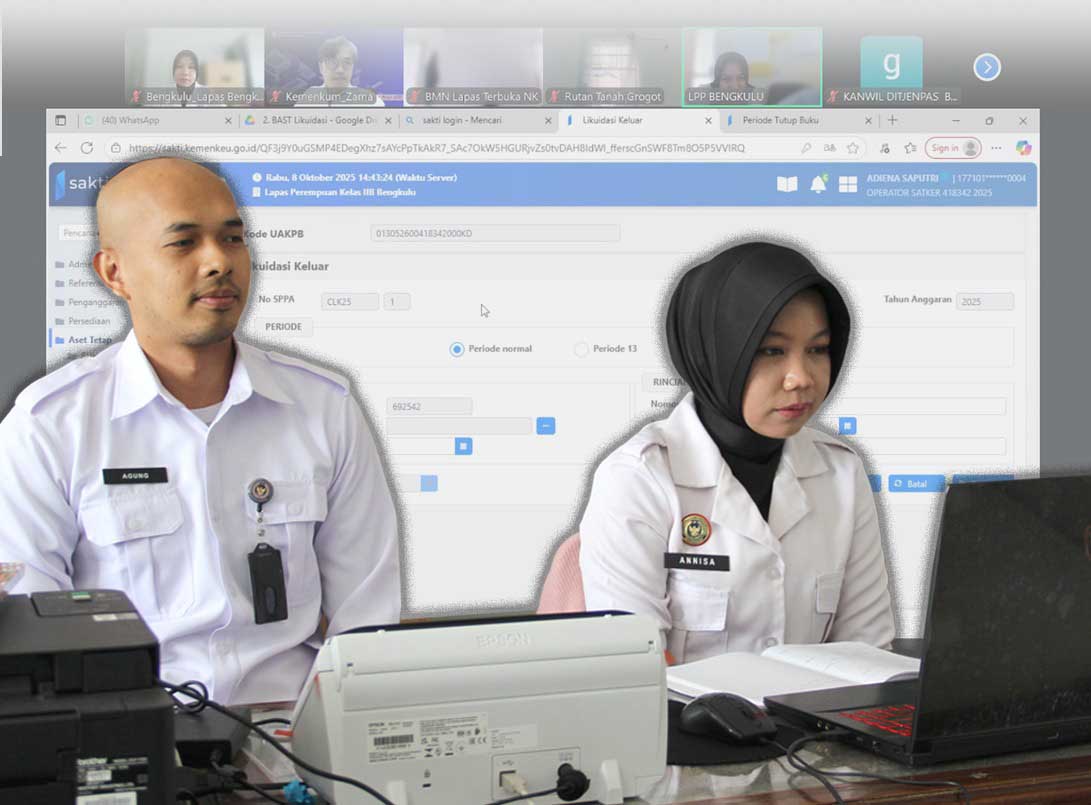Tata Kelola Batubara dan Kaburnya Hak Menguasai Negara
Minggu, 10 Agustus 2025 20:13 WIB
Kebijakan DME batubara boros subsidi, minim transparansi, dan abai konstitusi, jauh dari prinsip keadilan energi berkelanjutan.
***
Ketika pemerintah meletakkan batubara sebagai bahan baku strategis proyek hilirisasi energi nasional, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar tentang untung rugi fiskal atau efisiensi investasi. Ini adalah soal arah ke mana sesungguhnya kita sedang digiring dalam membangun kemandirian energi nasional menuju ketahanan energi berkeadilan atau sekadar melanggengkan ketergantungan pada energi fosil yang makin ditinggalkan dunia?
Proyek DME (dimethyl ether) berbasis batubara yang digadang-gadang sebagai substitusi elpiji 3 kg menjadi kasus penting yang patut dibedah bukan hanya dari sisi keekonomian, tetapi juga dari perspektif konstitusional dan keberlanjutan sumber daya.
Ketika PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama Air Products and Chemicals Inc mundur dari proyek ini, dan kemudian negara menghadirkan PT Danantara sebagai entitas pembiayaan pengganti, muncul rentetan pertanyaan baru, adakah kehati-hatian fiskal negara? Bagaimana bentuk pengawasan publik? Dan yang tak kalah penting, apakah semua ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945?
Subsidi yang Membengkak, Risiko yang Dikesampingkan
Hilirisasi batubara dalam bentuk proyek DME telah sejak awal menuai kritik. PTBA sendiri menghitung kebutuhan subsidi negara untuk proyek ini mencapai Rp41 triliun, jauh di atas prediksi awal. Biaya produksi DME yang mencapai Rp9.100 per kilogram dibanding harga jual elpiji 3 kg yang disubsidi sekitar Rp4.250/kg menimbulkan gap yang terlalu besar. Dalam skema ini, pemerintah harus menanggung selisih harga agar produk DME bisa terserap di pasar.
Skema subsidi ini bukan hanya memberatkan APBN, tetapi berpotensi menjadi subsidi permanen untuk industri batubara. Dalam konteks keadilan energi, subsidi semestinya didistribusikan untuk mempercepat transisi ke energi bersih, bukan justru memperpanjang usia energi fosil.
Lalu, hadirnya Danantara sebagai penyandang dana proyek ini, justru menambah kompleksitas tata kelola. Danantara didirikan tanpa transparansi publik yang memadai, dan wewenangnya sangat besar mendanai proyek-proyek hilirisasi energi, termasuk DME. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi Danantara? Apa saja instrumen akuntabilitasnya? Dan apakah publik dapat mengetahui dampak pembiayaan ini terhadap fiskal nasional?
Jika kita tarik ke hulu, perdebatan ini menyentuh langsung pada jantung konstitusi ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan, seperti Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, telah mengembangkan doktrin “Hak Menguasai oleh Negara” (HMN) yang bermakna lebih dari sekadar penguasaan administratif. Negara wajib hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengurus dan pengawas, yang menjamin agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi semata.
Dalam konteks DME batubara, kita justru melihat indikasi bahwa proyek ini tidak mengedepankan prinsip kemanfaatan untuk rakyat. Pertama, karena biaya produksinya jauh lebih mahal dibanding elpiji impor. Kedua, karena sumber batubara yang digunakan adalah batubara kalori tinggi, yang langka dan dibutuhkan industri lain. Ketiga, karena proyek ini hanya dinikmati oleh segelintir pelaku industri besar, tanpa ada jaminan bahwa rakyat kecil akan merasakan manfaat langsung.
Ironi Transisi Energi di Era Krisis Iklim
Kritik terhadap proyek DME batubara juga tak bisa dilepaskan dari konteks global Indonesia telah berkomitmen terhadap target penurunan emisi melalui Paris Agreement, dengan dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) yang mencanangkan transisi menuju energi bersih.
Alih-alih mendorong pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, bioenergi atau panas bumi, pemerintah justru mendorong hilirisasi Batubara yang jelas memperpanjang masa hidup energi kotor. Bahkan Kementerian ESDM baru-baru ini memperluas daftar perusahaan yang diwajibkan melakukan hilirisasi batubara, termasuk dalam bentuk DME, metanol, dan produk turunan lainnya.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional masih dikuasai oleh logika industri ekstraktif, bukan oleh visi pembangunan berkelanjutan. Padahal, keberlanjutan dan keadilan energi seharusnya menjadi prioritas, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki beban ganda: kebutuhan pembangunan dan krisis iklim.
Salah satu problem serius dalam proyek DME dan pembiayaan Danantara adalah minimnya partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Hingga hari ini, tidak ada dokumen kelayakan proyek DME yang dipublikasikan secara terbuka. Rencana bisnis yang dibiayai Danantara pun tidak dapat diakses oleh publik, padahal dana yang dikelolanya berasal dari penyertaan modal negara dan BUMN yang notabene milik rakyat.
Di sinilah urgensinya membangun keterbukaan informasi di sektor energi dan sumber daya alam. Tanpa keterbukaan, publik tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif. Tanpa pengawasan, potensi penyimpangan dan korupsi makin besar. Proyek sebesar DME dengan subsidi puluhan triliun dan dampak ekologis yang tidak kecil dan tidak boleh berjalan dalam ruang hampa demokrasi.
Dalam hal ini penulis tak menolak hilirisasi. Kita juga tidak mengingkari peran batubara dalam sejarah pembangunan energi Indonesia. Tapi sudah waktunya Indonesia membangun arah baru memprioritaskan hilirisasi energi terbarukan, bukan hilirisasi energi fosil.
Pemerintah perlu menghentikan glorifikasi proyek DME batubara sebagai solusi energi. Padahal, data menunjukkan proyek ini boros subsidi, tidak efisien, dan berisiko tinggi secara fiskal. Lebih baik, anggaran negara dan dukungan kebijakan difokuskan untuk transisi energi berbasis rakyat seperti pengembangan PLTS atap di desa, subsidi insentif untuk bioenergi, hingga revitalisasi koperasi energi.
Danantara pun perlu diaudit secara publik. Rencana kerja, skema pembiayaan, dan seluruh proyek yang akan didanainya harus diumumkan secara terbuka. Karena sumber dananya berasal dari publik, maka akuntabilitasnya pun harus tunduk pada logika publik, bukan semata logika bisnis.
Menagih Tanggung Jawab Konstitusional Negara
Membaca ulang Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar nostalgia terhadap semangat ekonomi kerakyatan. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional agar pengelolaan sumber daya alam tidak dibajak oleh logika komersial semata.
Negara dalam pengertian pemerintah dan seluruh aparatusnya bertanggung jawab penuh untuk menjamin agar setiap kebijakan energi berakar pada prinsip keadilan antargenerasi dan kelestarian lingkungan.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan panduan yang jelas. Doktrin hak menguasai oleh negara bukan hanya izin untuk mengatur, tapi mandat untuk mengelola, menjaga keberlanjutan, memastikan pemerataan manfaat, serta menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan strategis.
Jika proyek DME dan pembiayaan oleh Danantara tidak memenuhi asas-asas ini, maka sesungguhnya ia bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Maka, pemerintah harus memikirkan ulang arah kebijakan energi kembali pada cita-cita keadilan sosial yang menjadi fondasi republik ini.
Penulis :
Rifqi Nuril Huda
Email : [email protected]
Instagram : @rifqinurilhuda
Direktur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies (IEDS), Ketua Umum Akar Desa Indonesia
Penulis Indonesia, Pegiat Desa, Pengamat Energi
0 Pengikut

Ketika Hari Pangan Diselimuti Radiasi
8 jam laluBaca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 996
996 0
0