Praktisi ISO Management System and Compliance
Diskon Tagihan, Listrik Padam: Siapa yang Dibohongi?
2 jam lalu
Subsidi listrik murah, tapi mati-matan. Apa rakyat benar-benar makmur, atau cuma ilusi? Ganti diskon dengan solusi struktural!
***
Ada satu momen yang sering terulang setiap kali pemerintah mengumumkan kebijakan subsidi listrik: riuhnya sorotan media, narasi “keberpihakan kepada rakyat”, dan tagline menyejukkan seperti “tagihan turun, beban berkurang”.
Namun di balik euforia itu, di sudut-sudut rumah warga, di antara dinding kontrakan sempit atau di tengah desa terpencil, ada yang bertanya pelan,“Kalau listriknya mati-mati, murah pun jadi sia-sia.”
Subsidi listrik memang selalu menjadi primadona dalam bingkisan kebijakan populis. Murahnya tagihan bulanan dipamerkan sebagai bukti negara hadir untuk rakyat kecil. Tapi apakah benar-benar membuat rakyat makmur? Atau justru hanya menciptakan ilusi kesejahteraan—sementara akar masalah sistem energi kita tetap tak tersentuh?
Ambil contoh program diskon tarif listrik beberapa waktu lalu. Pemerintah menyuntik APBN triliunan rupiah untuk meringankan beban masyarakat di tengah tekanan inflasi. Secara angka, kebijakan ini berhasil: tagihan turun, keluhan berkurang, dan elektabilitas naik. Tapi jika kita melongok lebih dalam, kita akan menemukan bahwa yang dirasakan rakyat bukan sekadar harga per kWh, melainkan keandalan, akses, dan keadilan dalam mendapatkan listrik.
Di banyak daerah pedesaan, listrik padam hingga enam jam sehari. Di wilayah perkotaan, meski aliran stabil, kenaikan daya dari 900 VA ke 1.300 VA bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan prosedur yang berbelit. Sementara itu, rumah mewah di kompleks elite menikmati listrik tanpa gangguan, bahkan turut menikmati subsidi yang sama. Inilah ironi dari sistem subsidi yang tidak tepat sasaran: yang paling butuh, sering dapat pelayanan paling buruk; yang tidak butuh, malah menikmati manfaat penuh.
Kebijakan subsidi listrik selama ini lebih mirip diskon politik daripada solusi struktural. Seperti promosi akhir tahun di pusat perbelanjaan, yang menawarkan harga murah tapi stok barang langka atau kualitas turun. Murah di kertas, mahal di realita. Anggaran besar dialokasikan untuk menekan tarif, tapi minim investasi untuk memperbaiki jaringan transmisi, mengurangi technical loss, atau memperluas akses ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Fenomena ini bukan baru. Dalam literatur ekonomi publik, praktik semacam ini dikenal sebagai fiscal illusion—ilusi fiskal—di mana masyarakat merasa pemerintah murah hati karena membayar sedikit, padahal biaya sebenarnya ditanggung secara tidak langsung lewat defisit, utang, atau pembiayaan siluman lainnya. Subsidi listrik yang membengkak—dari Rp 60 triliun di 2020 menjadi lebih dari Rp 150 triliun di 2023—bukan hanya memberatkan APBN, tapi juga menggerus ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transisi energi.
Yang lebih mencemaskan, subsidi yang tidak tepat sasaran justru menciptakan distorsi pasar. Rumah tangga mampu yang menggunakan AC, water heater, dan peralatan listrik boros, menikmati tarif rendah yang seharusnya dikhususkan bagi yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, mereka tidak punya insentif untuk berhemat. Sebaliknya, keluarga miskin yang hanya bisa menyalakan lampu dan kipas angin, justru kesulitan saat ingin menaikkan daya karena proses administratif yang rumit dan biaya tambahan yang masih terasa berat.
Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural dalam distribusi energi. Kita memberi subsidi kepada semua, tapi tidak memastikan bahwa semua mendapat manfaat yang setara. Lebih parah lagi, kita mengorbankan masa depan demi ketenangan sesaat. Dana yang bisa digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara atau jaringan mikrogrid di Papua, malah habis untuk membayar subsidi silang yang tidak efisien.
Masalah ini bukan soal tidak mau membantu rakyat, tapi soal cara membantunya. Subsidi listrik harus direformasi bukan dihapus—dengan pendekatan yang lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan. Pertama, subsidi harus tepat sasaran. Alih-alih memberi diskon universal, pemerintah bisa menerapkan skema cash transfer langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan, seperti yang dilakukan Malaysia dengan Bantuan Elektrik. Uangnya bisa digunakan untuk bayar listrik, atau kebutuhan lain, tanpa mengganggu insentif efisiensi energi.
Kedua, transparansi dan partisipasi publik dalam penentuan tarif sangat penting. Saat ini, keputusan tarif listrik sering diambil di balik pintu rapat kementerian, tanpa keterlibatan ahli energi, regulator independen, atau suara masyarakat. Padahal, tarif yang adil harus mencerminkan biaya nyata produksi, distribusi, dan dampak lingkungan, bukan kompromi politik anggaran.
Ketiga, investasi pada infrastruktur dan transisi energi harus jadi prioritas. Daripada terus mengucurkan uang untuk subsidi jangka pendek, lebih bijak jika alokasi fiskal difokuskan pada perbaikan jaringan listrik, pengurangan kebocoran teknis, dan percepatan energi baru terbarukan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kedaulatan energi dan komitmen terhadap net zero emission.
Negara-negara seperti Jerman dan Denmark telah membuktikan bahwa sistem energi yang adil dan berkelanjutan bukan mimpi. Mereka menerapkan tarif dinamis, subsidi hijau, dan insentif bagi rumah tangga yang memproduksi listrik sendiri lewat panel surya. Di Thailand, pemerintah menggunakan data terpadu untuk memastikan subsidi hanya menyentuh 20 persen penduduk termiskin, sementara sisanya membayar sesuai kemampuan.
Indonesia bisa belajar dari sana. Kita butuh keberanian untuk berhenti menjadikan subsidi listrik sebagai alat pencitraan, dan mulai membangun sistem yang kuat, adil, dan mandiri. Kesejahteraan bukan diukur dari murahnya tagihan bulanan, tapi dari apakah listrik menyala terus, bisa diandalkan, dan tersedia untuk semua—tanpa harus menunggu kebijakan populis datang setiap lima tahun sekali.
Ketika lampu padam di tengah malam, diskon 30 persen tidak bisa menerangi gelap. Yang dibutuhkan bukan sekadar harga murah, tapi sistem yang benar-benar menerangi masa depan.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
Artikel Terpopuler


 0
0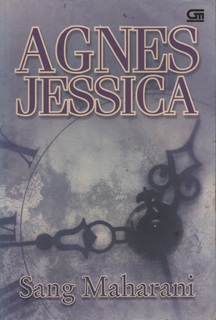
 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 97
97 0
0















