Petani-petani Kendeng dan Kebebasan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Aksi Dipasung Semen Jilid 2 dan pro kontranya, menggelitik saya untuk bertanya, siapa yang (sebenar-benarnya) sedang terpasung?
Siapa yang Sedang Terpasung?
Aksi Dipasung Semen Jilid 2 dan pro kontranya, menggelitik saya untuk bertanya, siapa yang (sebenar-benarnya) sedang terpasung? Dan siapa yang (sebenar-benarnya) paling bebas?
Dipasung itu sakit, memang. Para petani dan aktivis yang ikut aksi dipasung dibantu oleh relawan-relawan untuk tetap dapat berativitas (sekadarnya). Tetapi dengan melalui cara tersebut, mereka telah mengambil langkah perlawanan yang begitu santun untuk mempertahankan hak dasar hidup: air, tanah, dan udara di Pegunungan Kendeng Utara. Petani-petani yang berjuang dengan beragam cara untuk menolak pabrik semen, adalah yang merdeka jiwanya meski terpasung fisiknya. Mereka memiliki kebebasan gabungan dari Guru Isa dan Hazil. Mereka merdeka nalar, logika, dan nuraninya saat aksi pasung semen, dan merdeka pula jiwanya saat menjadi petani. Membiarkan gerak kaki mereka terpenjara karena dicor atau karena aksi-aksi perjuangan bentuk lain yang menguras fisik, selalu jauh lebih baik ketimbang diam tanpa perlawanan dan terpasung oleh kepengecutan.
Lalu siapa yang sebenar-benarnya sedang terpasung?
Mereka lah orang-orang pro korporasi dan pejabat berwenang yang dililit oleh kalkulasi-kalkulasi laba pabrik semen. Orang-orang yang termakan manisnya janji industrilisasi meski dengan cara melecehkan kehidupan dan inkonstitusional. Buzzer yang kontra aksi Kendeng Lestari yang terbelenggu nalar dan nuraninya demi konversi rupiah dari tulisannya yang mampu membodohi-bodohi orang.
Konflik agraria tentang pembangunan pabrik semen bukan hal yang baru. Perlawanan petani dalam menolak pabrik semen bukan baru terjadi dalam setahun dua tahun belakangan. Tapi telah satu dekade. Sebuah perjuangan berantai yang panjang, mulai dari awal 2006 di Sukolilo, Pati, penolakan pabrik semen oleh dilakukan Jaringan Masyaratkat Peduli Pegudungan Kendeng (JMPPK) dan Sedulur Sikep. Kemudian di Kayen, Tambakromo, hingga ke Rembang. Dari perusahaan semen swasta maupun milik pemerintah. Alasan penolakannya pun sama, cacat AMDAL, tumpang tindih terhadap konstitusi kawasan perlindungan daerah Karst, dan ketidaktransparan rencana pembangunan. Bahkan terakhir, aksi Dipasung Semen 2 dipicu oleh izin baru yang terbitkan Ganjar Pranowo pada 23 Februari lalu , izin tersebut mencederai Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 99 PK/TUN/2016 yang telah membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 juni 2012 serta Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 064/G/2014/PTUN SMG.
Penolakan di Rembang pun dimulai dengan aksi mendirikan tenda di depan lokasi pembangunan pabrik, jalan kaki ratusan kilometer menuju kantor guberneran Jawa Tengah, Dipasung Semen Jilid 1 hingga Jilid 2. Konsistensi, masifitivitas, dan panjangnya perjuangan petani-petani Pegunungan Kendeng pada satu dekade terakhir akan mengingatkan kita pada kasus Kedung Ombo. Proyek pembangunan waduk yang harus menggusur di 3 keresidenan dan 9 kabupaten di Jawa Tengah tersebut dimulai pada tahun 1981. Warga menolak uang penggantian pergusuran yang sangat murah. Dengan dikawal berbagai macam LSM, solidaritas masyarakat, media, kelompok-kelompok mahasiswa bahkan dari luar Jawa Tengah, kasus Kedung Ombo berhasil menjadi perhatian publik. Dengan bantuan LBH Semarang, pada tahun 2002 akhirnya masalah ganti rudi tanah di Kedung Ombo terselesaikan dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 174/Menhut/VII tahun 2002.
Maka mereka yang kontra terhadap aksi petani-petani Kendeng, meragukan sikap kritis petani, menuduh adanya provokator di balik aksi, mengindikasi adanya eksploitasi petani perempuan, bahkan menuding bahwa petani-petani dan koalisi solidaritasnya dimobilisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan, adalah orang-orang mendahulukan berbicara ketimbang berpikir. Saya bahkan mencurigai mereka bukan hanya cacat nalar maupun buta sejarah, tapi juga orang-orang yang dengan sengaja memelihara amnesia akut.
Betapa pun terpasungnya petani-petani Kendeng karena kaki yang dicor, mereka lah orang-orang yang merdeka dengan akalnya. Dan memilih untuk menolak terpasung oleh janji-janji industrilisasi yang kelak justru akan berbalik memasung kemerdekaan sebagai manusia yang (semestinya) sebagai subyek.
Petani-petani Kendeng dan Khittah Manusia
Khittah manusia sebagai subyek sudah lama menjadi buah pemikiran revolusioner dari seorang tokoh pendidikan yang kontroversial, Paulo Freire. Dalam mahakarya-nya yang fenomenal berjudul “Pendidikan yang Membebaskan”, ia menulis:
“Manusia sempurna adalah manusia sebagai subyek. Sebaliknya, manusiayang hanya beradaptasi adalah manusia sebagai obyek. Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena ia tidak mampu mengubah realitas.”
Freire mengkritisi tentang konsep beradaptasi, bahkan lebih frontal ia menulis bahwa adaptasi dengan lingkungan adalah sikap binatang, bukan sikap manusia. Petani-petani Kendeng yang mempertahankan khittahnya sebagai petani, dan menolak menjadi buruh pabrik semen adalah cara mereka mengukuhkan dirinya sebagai subyek. Mereka hanya melakukan upaya untuk terus menjadi manusia: humanisasi. Ketika mereka pasrah tanpa perlawanan dan justru berubah mengikuti kekuatan-kekuatan sosial yang penuh kuasa, maka sikap tersebut justru adalah pemerosotan sebagai obyek: dehumanisasi.
Sehingga jelas bahwa pengebirian terhadap peran dan partisipasi aktif petani, kecurigaan terhadap sikap kritis petani dan malah berbalik menggugatnya, adalah sikap manusia-manusia yang terlalu modern hingga tak menyadari kemerosotan khittah kemanusiannya sendiri. Mereka lah manusia obyek. Bahkan mereka bagaikan orang lumpuh jika meminjam apa yang dikatakan Erich Fromm dalam Escape from Freedom (buku yang juga menjadi rujukan Freire):
"(Manusia) menjadi bebas terhadap ikatan-ikatan yang berasal dari luar, yang mencegahnya bertindak dan berpikir menurut apa yang mereka anggap cocok. Ia akan bertindak dengan bebas jika ia tahu tentang apa yang diinginkan, dipikirkan, dan dirasakan. Tapi masalahnya ialah bahwa ia tidak tahu. Dan karena itu ia akan menyesuaikan diri dengan penguas-penguasa yang tidak kenal dan ia akan mengiyakan hal-hal yang tidak disetujuinya. Semakin ia bertindak demikan, semakian ia tidak berdaya untuk merasa semakin ia ditekan untuk menurut. manusia modern, meskipun dipulas dengan optimisme dan inisiatif, dikuasai oleh perasaan amat tidak berdaya bagaikan orang lumpuh yang hanya mampu menatap malapetaka sebagai tak terhindarkan."
Babak Baru Perlawanan
Dua perwakilan petani yang telah menemui presiden di Istana Negara pada 22 Maret lalu dan menerima jawaban nan begitu birokratif, bahwa Jokowi tidak mencampuri urusan izin baru yang diterbitkan Ganjar Pranowo. Tanggapan itu bukan hanya melecehkan kehidupan dan perjuangan menahun para petani, tetapi sekaligus membunuh marhaenisme.
Seperti yang disampaikan oleh salah seorang relawan Solidaritas untuk Kendeng Lestari ketika saya menghadiri acara doa bersama untuk (Alm) Yu Patmi pada 22 Maret 2017 lalu, bahwa aksi untuk melawan pembangunan pabrik semen akan terus berlanjut, dengan strategi yang berbeda sampai tuntutan petani dipenuhi. Solidaritas dan konsistensi dari perjuangan petani-petani Kendeng bahkan diharapkan bisa menjadi resonan bagi perlawanan untuk konflik agraria di berbagai wilayah lainnya.
Aksi akan terus menyebar. Petani, aktivis dan relawan aksi akan terus memberikan kesadaran kepada orang-orang yang masih terpasung nalarnya. Aksi petani-petani Kendeng adalah aksi yang memberi warna baru dalam cara melawan. Bahwa melawan tidak melulu dengan konfrotasi, bahwa melawan bisa dilakukan juga dengan sehormat-hormatnya. Sebagaimana petani-petani Kendeng melakukan pencerahan dari mata air ke mata air kepada petani-petani lain. Sebagaimana petani-petani memanggil peneliti, aktivis lingkungan, untuk belajar mendata mata air dan memahami ekologi kawasan perlindungan Karst. Sebagaimana petani-petani Kendeng ‘memanggil’ ahli hukum dan mempelajari cara melawan tanpa membentur konstitusi. Sebagaimana petani-petani ‘merangkul’ ahli-ahli semen dan pihak-pihak lain yang mulanya kontra terhadap mereka hingga merangkulnya menjadi bagian dari barisan perjuangan mereka. Dan benar saja, pada 24 Maret 2017, Aksi Solidaritas Kendeng telah memasuki babak baru, menyebar ke beberapa kota seperti Jogja, Bandung, Jambi, Medan, Cilegon, dll.
Represi negara yang telah banyak “memotong” kewarasan rakyatnya menggunakan berbagai macam tameng sebenarnya membuktikan bahwa ketakukan negara adalah ketika kita –rakyatnya- menjadi waras. Membuka diri sebebas-bebasnya untuk 'membaca' dan memahami situasi sosial seperti yang dialami petani-petani Kendeng, adalah langkah awal untuk mengecup kewarasan. Selama masih memakan nasi, saya pikir menyikapi apa yang dialami petani-petani Kendeng (atau lebih luas lagi: terhadap seluruh konflik agraria) hanya dengan diam dan seolah persoalan tersebut terpisah dari kehidupan kita hingga begitu remeh untuk membuat sulit tidur, adalah kesengajaan untuk memasung kewarasan.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Melimpah Hadiah di Bekasi Wedding Exhibition #4
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Petani-petani Kendeng dan Kebebasan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0



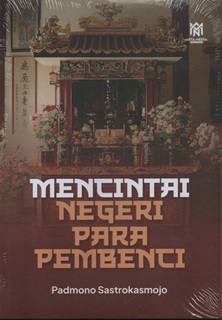





 98
98 0
0














