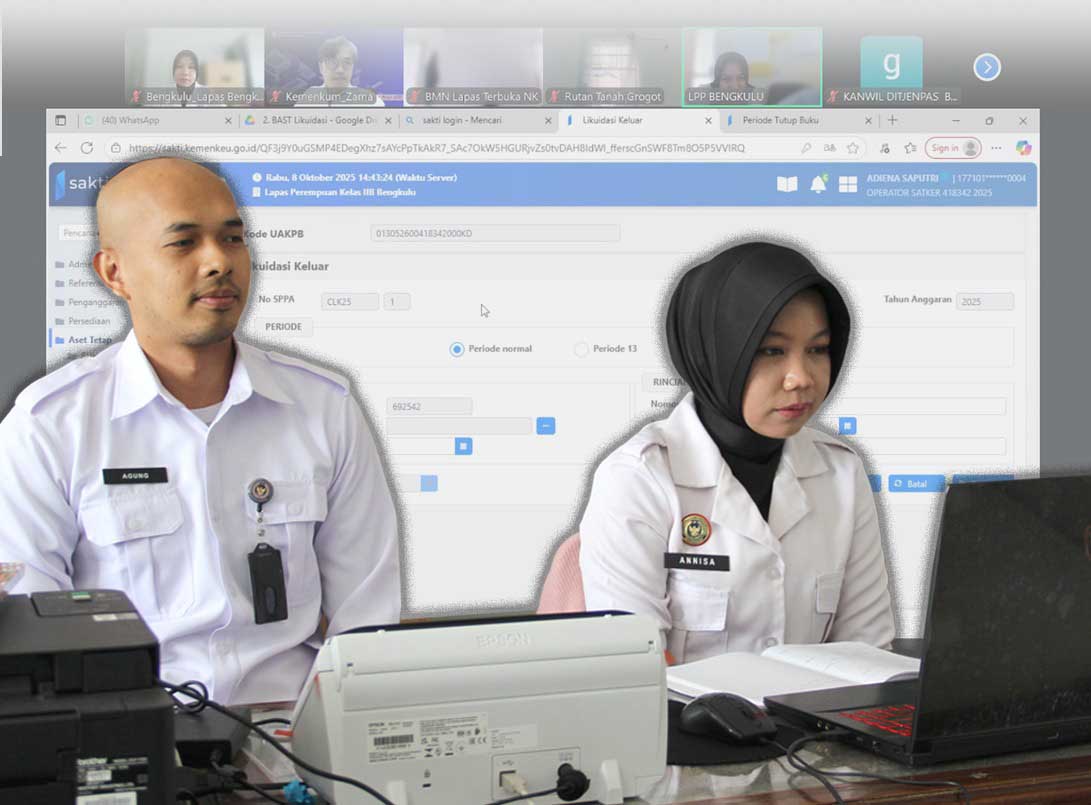Romantisme Sukarno-Hatta dan Wajah Semu Demokrasi Kini
Minggu, 1 September 2019 13:23 WIB
Romantisme Sukarno-Hatta agaknya harus dijadikan refleksi historis oleh aktor politik yang hadir di ruang publik
Wajah demokrasi di negeri ini tak lagi diwarnai oleh pertarungan-pertarungan ideologi maupun konsep bernegara yang mengemuka seperti saat awal berdiri. Orientasi kekuasaan yang teraktualiasi dalam kedudukan menjadi tujuan. Politik kompromi lebih memainkan kunci dalam sebuah transaksi. Kemewahan ideologi, pada akhirnya, tergerus dan menuju mati suri.
Kisah Dwitunggal, Sukarno dan Hatta, yang mengiringi perjalanan bangsa saat masih muda, agaknya tak lagi menginspirasi aktor-aktor politik yang kini hadir di ruang publik. Persahabatan, perseteruan, serta perbedaan pandangan merupakan pasang-surut hubungan antara keduanya. Tak semua pandangan Sukarno diamini oleh Hatta, dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, di titik tertentu dimana tujuan besar bangsa ini harus diupayakan, mereka mengesampingkan egoisme individual.
Sukarno menjadi pionir Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan menawarkan nasionalisme sekuler dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Partai yang terbentuk di Bandung pada 4 Juli 1927 tersebut setidaknya mampu menyatukan beberapa organisasi kedalam sebuah konsep nasionalisme yang multi-rasial dan lebih egaliter. Tercatat, Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Study Club Surabaya, serta organisasi-organisasi kedaerahan dan kristen melebur ke tubuh PNI dalam wadah PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). PNI mjuga memperoleh dukungan dari kalangan komunitas Cina dan Arab dengan konsep yang ditawarkannya.
Berjarak ribuan kilometer dari Sukarno, Hatta aktif dalam sebuah organisasi bernama Perhimpunan Indonesia (PI) saat masih menempuh studi di Belanda. Ia memimpin PI sejak 1926. Sejurus dengan Sukarno, ia menentang romantisme kolonialisme melalui paham sosialisme. Hatta menerima banyak penafsiran Marxis mengenai belenggu imperialisme. PI bergerak ke arah yang cederung radikal ketika para pemimpin PKI yang diasingkan seperti Tan Malaka dan Semaun memberikan pengaruhnya dalam pidato-pidato yang disampaikan dalam rapat-rapat organisasi.
Keduanya saling memberikan dukungan ketika salah satu pihak mengalami permasalahan. Aktivitas politik yang dijalankan Hatta dalam kapasitasnya sebagai ketua PI dengan menghadiri Kongres Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Jenewa pada 10-15 Februari 1927, mengakibatkan ia dan kawan-kawannya ditangkap oleh pemerintah sekembalinya ke Belanda, tujuh bulan berselang. Sukarno yang mengetahui kabar tersebut, memberikan dukungan dengan melakukan penggalangan dana bagi para aktivis di negeri Belanda dalam rapat-rapat PNI di Bandung. Dua warsa berselang, tepatnya pada Desember 1929, Sukarno ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Pemerintah Kolonial akibat pergerakannya dalam tubuh PNI. Salah satu bentuk dukungan Hatta dituangkan dalam sebuah artikel berjudul “De Vernietiging der PNI” (Penghancuran PNI) pada 2 Januari 1931. Hatta mengkritisi para hakim kolonial sebagai pelayan kekuasaan, bukan pelayan keadilan.
Pertautan Sukarno-Hatta tak selamanya berjalan mulus. PNI mulai kehilangan sosok pemimpin setelah banding yang diajukan Sukarno ditolak oleh Raad van Justitie dan memaksanya untuk mendekam di balik jeruji besi dengan vonis selama empat tahun. PNI harus dibubarkan. Elite PNI kemudian terpecah ke dalam dua faksi yakni Partai Indonesia (Partindo) dan PNI Baru. Hatta menyayangkan pembubaran PNI dan menganggap hal tersebut begitu memalukan karena ia sebenarnya berharap banyak pada PNI untuk menggalang pergerakan rakyat. Namun, perseteruan keduanya tak mampu melunturkan semangat dalam menentang kolonialisme hingga mampu mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan dalam lantunan proklamasi.
Hubungan Sukarno-Hatta kembali diuji dalam mengawal berlangsungnya kehidupan rumah tangga negeri ini. Berbagai problematika muncul pada setengah dasawarsa awal Indonesia merdeka, yang begitu mengancam integrasi. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa memaksa terjadinya perlawanan bersenjata di beberapa daerah seperti Medan, Ambarawa, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Belum lagi, adanya rongrongan dari dalam tubuh sendiri akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah pusat seperti Pemberontakan PKI di Madiun, DI/TII di Jawa Barat, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), serta Pemberontakan Andi Aziz. Percobaan demokrasi juga terkesan mengalami kegagalan dengan berbagai permasalahan yang mengiringi mulai dari korupsi, terancamnya kesatuan wilayah, keadilan sosial yang tak kunjung tercapai, serta permasalahan ekonomi yang belum terpecahkan. Klimaksnya, pada 20 Juli 1956, Hatta mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden dan berlaku sejak 1 Desember 1956. Dalam pidatonya yang terakhir, ia mengecam praktik partai politik yang didasarkan atas kepentingan pribadi. Terlebih, Sukarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pasca ditinggalkan oleh Hatta.
Romantisme Sukarno-Hatta agaknya harus dijadikan refleksi historis bagi aktor-aktor politik yang berjejal di ruang publik saat ini. Sukarno dengan nasionalismenya yang berfokus pada penggalangan massa dan Hatta dengan sosialismenya yang mengutamakan jalan pendidikan mampu menyatu mengupayakan kemerdekaan, meski berujung perpisahan. Reformasi yang berhasil digaungkan lebih dari dua dasawarsa nyatanya belum mampu menihilkan praktik politik transaksi, orientasi jabatan semata, maupun kompromi antar elite. Ideologi tak lagi menjadi barang istimewa yang layak diperjuangkan. Wajah demokrasi kini masih saja terlihat semu.
Sumber gambar: wikimedia.org
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Romantisme Sukarno-Hatta dan Wajah Semu Demokrasi Kini
Minggu, 1 September 2019 13:23 WIB
Mitos dan Kuasa Pasar: Dewi Sri sebagai Penguat Subsistensi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0