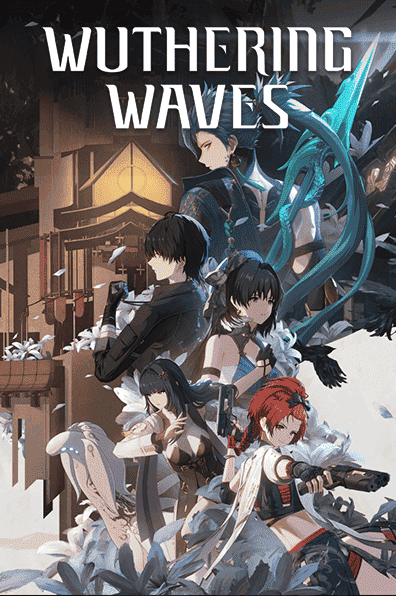Keterlibatan Akademisi di Balik Bencana Ekologis
Senin, 16 September 2019 09:42 WIB
Artikel ini mendeskripsikan sisi lain dari peran akademisi yang selama ini dianggap selalu netral dan objektif
Jika hari ini kita bertanya tentang siapa yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya berbagai bencana ekologis di Indonesia, maka mayoritas akan menuding korporasi. Ini benar belaka, karena pemodal selalu mencari cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan untung, maka pertimbangan ekologis sering diabaikan.
Namun, menurut saya, tudingan ini cenderung menyederhanakan masalah. Berjalannya suatu usaha korporasi pasti melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak. Artinya, setiap pihak memberikan andil terhadap terjadinya bencana ekologis. Salah satu pihak yang berperan besar namun terkadang luput dari sorotan adalah akademisi.
Sebelum terlalu jauh, saya ingin terlebih dahulu memberikan beberapa batasan terhadap istilah yang saya gunakan. Pertama, istilah akademisi yang saya gunakan terbatas pada mereka yang berasal dari perguruan tinggi, karena mereka ini adalah pemegang mandat undang-undang sebagai pengusung kebenaran ilmiah, kejujuran, dan keadilan. Kedua, pengertian bencana ekologis mengacu kepada bencana-bencana yang disebabkan ulah manusia, seperti banjir, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, longsor, dan konflik.
Ketiga, tulisan ini tidak bermaksud mengkerdilkan peranan pihak lain, karena itu sama pentingnya, baik sebagai penyebab maupun penerima dampak bencana ekologis tersebut. Ini hanya dimaksudkan untuk melihat peranan akademisi secara lebih khusus dan mendalam.
Keterlibatan akademisi dalam bencana ekologis dapat ditelusuri melalui berbagai peranan mereka dari “hulu” sampai “hilir”. Tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap keahlian dan kepakaran akademisi membuatnya diperlukan dimana-mana, sehingga akademisi sangat mewarnai pengelolaan lingkungan hidup di negeri ini. Sayangnya, peran-peran yang menuntut kejujuran dan keluhuran budi ini terkadang tidak luput dari berbagai penyimpangan, hal tersebut lah yang menjadi garis besar tulisan ini.
Banyak yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan hidup kita saat ini sangatlah progresif, hal tersebut ditandai dengan beragamnya instrumen yang harus disusun guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kita mengenal instrumen yang cukup populer seperti Amdal, UKL-UPL, dan KLHS. Instrumen lainnya masih sangat banyak, sebut saja misalnya instrumen ekonomi lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, emisi gas rumah kaca, kerentanan perubahan iklim, dan lain sebagainya.
Pertanyaannya adalah, bagaimanakah penerapan instrumen-instrumen tersebut? Jika dilihat kondisi hari ini, pepatah yang paling cocok menggambarkan hal tersebut adalah “jauh panggang dari api”. Untuk instrumen-instrumen lama (seperti Amdal dan UKL-UPL) relatif tidak mengalami kendala berarti.
Sementara, untuk instrumen yang baru cenderung lambat, contohnya pada penerapan KLHS yang memiliki perjalanan sangat panjang, mulai dari penyusunan konsep pada 2006-2007, kemudian dibunyikan di dalam UUPPLH 32/2009. Setelah terjadi tarik ulur kewenangan antara KLHK dan Kemendagri, maka keluarlah PP 46/2016 tentang Pedoman Umum KLHS, sampai akhirnya dikeluarkan peraturan menteri sebagai tindak lanjut PP tersebut.
Sedangkan untuk instrumen lainnya, sependek pengamatan saya, belum memiliki perkembangan yang berarti, peraturan turunan yang mengatur teknis instrumen masih belum dikeluarkan. Jika ditelisik lagi, ada jarak bertahun-tahun sampai kemudian regulasi tersebut bisa diterapkan.
Mengapa penerapan instrumen-instrumen tersebut cenderung lambat? Tanpa bermaksud meniadakan pengaruh dinamika politik, keterlambatan ini juga ada kaitannya dengan peran akademisi. Aspek keilmuan menjadi salah satu faktor penting dalam perumusan regulasi. Hal ini menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kepakaran dan keahlian para akademisi, mulai dari perumusan, penerapan, sampai evaluasi regulasi, sehingga menyebabkan terjadinya dominansi peran akademisi.
Padahal di sisi lain, akademisi juga memiliki tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak ringan. Pada akhirnya, proses perkembangan instrumen-instrumen tersebut menjadi lambat.
Selain membantu di dalam merumuskan suatu kebijakan, para akademisi ini juga “turun gunung” menjadi pelaksana regulasi tersebut. Kita lihat pada proses penyusunan KLHS, walaupun di dalam regulasi disebutkan bahwa KLHS disusun oleh tim yang disebut Kelompok Kerja (POKJA) KLHS, namun nyatanya, KLHS justru disusun oleh akademisi yang di dalam tim ini sebenarnya berperan sebagai tenaga ahli. Alasannya, supaya proses KLHS bisa dilaksanakan dengan cepat.
Contoh yang agak klasik namun sangat kental peran akademisi adalah pada proses penyusunan Amdal. Para akademisi tersebut terkadang “menyamar” sebagai konsultan Amdal, bahkan tidak sedikit yang memiliki perusahaan konsultan sendiri. Sementara itu, tim teknis Amdal juga diisi oleh para akademisi yang terkadang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Maka tidak mengherankan jika sidang Amdal tak lebih seperti “perbualan kedai kopi”. Kalau sudah begini, tidak salah rasanya jika kita mempertanyakan kualitas Amdal tersebut.
Para akademisi yang biasa terlibat dalam pekerjaan seperti ini biasanya bukanlah “akademisi biasa” karena mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, pada akhirnya mereka dibantu oleh asisten yang acapkali secara keahlian dan pengalaman masih minim. Pekerjaan semakin menumpuk, sementara waktu dan kemampuan intelektual semakin terbatas, maka berbagai cara pun dilakukan, termasuk copy paste, manipulasi data, analisis dangkal, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang terjadi adalah pekerjaan asal jadi.
Pada situasi yang agak ke “hilir”, lazim terjadi akademisi menjadi pembela korporasi untuk melancarkan praktik-praktik buruk yang selama ini dilakukan korporasi tersebut. Pembelaan ini bisa dilakukan secara halus maupun terang-terangan. Untuk cara yang halus, biasanya menggunakan arena perdebatan ilmiah sebagai wadah menawarkan wacana mereka yang sarat akan kepentingan bisnis, misalnya workshop yang dilaksanakan untuk menguji suatu kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan korporasi. Seluruh fasilitas workshop disediakan oleh korporasi-korporasi tersebut, perguruan tinggi sebagai penyelenggara kemudian mendatangkan pembicara dan peserta yang “sependapat” dengan mereka. Sehingga rumusan rekomendasi bisa dikondisikan.
Selain itu, ada pula yang memang terang-terangan membela korporasi, misalnya dengan menjadi saksi ahli bagi korporasi di persidangan. Kesediaan dan motif para akademisi ini tentu sesuatu yang subjektif. Namun, sebagai pihak yang seharusnya membela kepentingan publik, maka prilaku para akademisi ini sangat mengundang tanda tanya besar.
Pada akhirnya, hal ini tidak saja memberikan keburukan bagi akademisi tersebut secara individu, tetapi membawa keburukan pula pada perguruan tinggi tempat dimana ia bernaung. Sudah sering kita menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada perguruan tinggi, karena dianggap jarang berpihak pada kepentingan massa yang sedang berjuang mempertahankan alam mereka. Ini adalah suatu ironi yang sangat memilukan.
Upaya-upaya kritik “dari dalam” sudah banyak dilakukan, salah satunya dari Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, sebagaimana diceritakan oleh Hariadi Kartodihardjo, dalam suatu tulisannya yang berjudul “Perguruan Tinggi dan Kebajikan Publik”. Para guru besar tersebut mengalami kerisauan terhadap peran ahli dari perguruan tinggi yang semakin langka, terutama yang bersedia secara terbuka membela kepentingan negara.
Para guru besar tersebut setuju bahwa adalah tidak etis apabila dosen dari perguruan tinggi negeri membela kepentingan korporasi. Apalagi jika ada motivasi kesaksiannya sebagai sumber mata pencarian. Sebab, pada dasarnya mereka tengah menghadapi negara, yang memberinya gaji, anggaran penelitian, serta fasilitas kerja. Semestinya, setiap dosen selalu mengaitkan pengabdiannya kepada kebajikan publik dengan tanggung jawab membela kepentingan orang banyak.
Kerisauan para guru besar ini adalah kerisauan kita bersama. Hari-hari ini, kepakaran dan keahlian para akademisi telah menjadi semacam “komoditas” dalam “pasar” yang semakin spesifik. Sulit untuk mengabaikan faktor peningkatan finansial yang signifikan sebagai motif utamanya.
Jika praktik ini terus berlangsung, maka akademisi akan semakin berjarak dengan kepentingan khalayak ramai. Pada tataran yang lebih ekstrim, praktik-praktik seperti ini akan menggerus kejujuran ilmiah mereka sendiri, demi membenarkan yang dibela. Walaupun agak berat, tapi saya percaya kita akan bisa mengetuk pintu hati para akademisi yang sedang tersesat ini.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Keterlibatan Akademisi di Balik Bencana Ekologis
Senin, 16 September 2019 09:42 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0