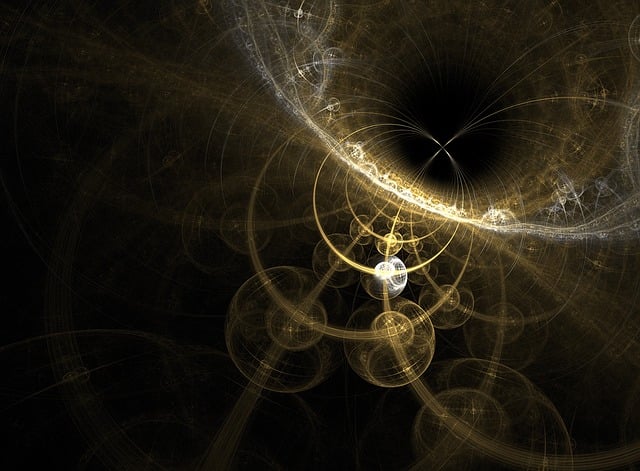Ingat-ingatlah kataku ini, "Ada kalanya dalam suatu waktu, kita perlu mencintai langit yang berawankan doa. Maka, saat hujan turun, luruhlah segala dusta,"
"Kata-kata yang indah, kamu dapat dari mana?" Gadis Teratai tersenyum.
"Kakek," jawabku, lirih.
Saat aku berusia tujuh tahun dan rumah kecil kami dibangun dekat Sungai Kuning, Kakek selalu meniup seruling tanah liat yang dibuatnya. Kami adalah keluarga yang menjaga tradisi dan budaya nenek moyang. Tanpa kuceritakan bertele-tele pun, tentu saja kalian bisa menebak bahwa kami lahir dari Suku Hui. Koloni terbesar selain bangsa Han.
Langit di Jalur Sutera akan selalu indah kala dipandang secara lamat. Membiru, luas, memayungi tanah padang berbukit Ningxia. Terpaan angin jelas kencang, nah, kalau kalian melihat kincir angin di daerahku tak perlu terkejut. Listrik mengalir ke desa kami karena kontribusi perputaran kincir-kincir tersebut.
Alam adalah sumber segalanya bagi kami, orang kampung yang tinggal jauh dari Shanghai juga Beijing. Ada banyak saudara pindah ke kota karena relokasi, tapi aku memutuskan untuk tinggal dan hidup di desa sebisa mungkin.
"Pernah mendengar senandung khas Pangeran Huaer?" tanyaku, pada Gadis Teratai.
"Sebuah puisi yang disenandungkan?" dia balik bertanya.
"Aku lebih menyebutnya sebagai syair. Karena tidak begitu terikat dengan pola, tetapi seorang penyanyi Huaer selalu memiliki majas-majas terbaik di awal lagu," sembari menyeruput secangkir teh hangat. Aku menjelaskan pengetahuan sempitku. Sore itu, menjadi sore singkat kami sebelum Gadis Teratai kembali ke kota dalam beberapa hari ke depan.
"Aku mau beli seruling tanah liatmu. Mau kucoba suaranya nanti di balkon rumah, boleh?" tanya Gadis Teratai lagi.
Sudah seminggu terakhir ini, Gadis Teratai hampir tidak pernah absen mengamatiku bermain seruling den menyenandungkan lagu-lagu Huaer. Sepertinya dia benar-benar tertarik. Dalam benak aku berharap agar tidak ada rasa kecewa yang menyelimuti bisnis kecil-kecilan ini.
"Boleh-boleh saja. Pilihlah sesukamu, ada banyak varian warna, bentuk. Pula varian suara dan nada-nada tertentu. Pilih dengan perasaanmu yang paling jujur," kataku padanya, sembari mengajaknya bergegas menuruni bukit di tepi Sungai Kuning yang mengurai keterbenaman mentari. Magrib akan segara tiba.
Huaer tradisional disenandungkan tanpa alat musik. Musik hadir dari lantunan nada-nada yang disuarakan para penyanyi hingga terdengar merdu. Suara yang baik, adalah suara yang dapat menjangkau telinga para pendengar dari jarak jauh. Arah terpaan angin, kemudian posisi para penyanyi menghadap, menjadi tatanan utama yang perlu diperhatikan ketika menyenandungkan Huaer.
Begitupun seruling dari tanah liat. Kami perlu menghadap ke arah yang tepat sebelum memainkan seruling. Selain, tentu saja, pilihan menutup beberapa lubang dengan jari jemari agar suara seruling bernada.
Suara seruling yang kumainkan tidak berdasarkan pada sebuah lagu tertentu. Kami menciptakannya sendiri, sesuai dengan apa yang ingin disuarakan dari nurani. Semacam improvisasi bebas. Sebebas-bebasnya, asal enak saja didengarkan alias tidak sumbing.
"Simpan baik-baik. Mungkin tidak seberharga ponsel yang tanganmu genggam. Tetapi bila kamu merawatnya sungguh-sungguh, aku bakal merasa senang sekali," pesanku kepada Gadis Teratai setelah dia memilih seruling yang menurutnya bagus.
"Aku tidak punya harga khusus kepada teman baik. Bayar saja sesukamu. Kutambahi seruling kesayanganku, ya. Hitunglah sebagai kenang-kenangan," kuteruskan, sambil tersenyum kepada dia.
Gadis Teratai tertawa kecil, "Seharusnya kamu bisa lebih banyak belajar tentang cara berbisnis,"
Kubalas dengan garukan-garukan kecil di kepala bagian belakang. Aku kikuk di hadapan dia.
Gadis Teratai jarang membawa kantong plastik. Seruling yang dibeli dariku ditatanya rapi dalam saku tas selempang. Dia pernah bercerita kepadaku, akan sangat merepotkan membawa-bawa kantong plastik, terlebih kalau sudah jadi sampah, bahan plastik itu dalam proses kimiawinya akan sangat yang susah terurai. Tentu saja, plastik-plastik itu kalau mencemari lingkungan juga akan merusak kualitas tanah yang kujadikan bahan baku seruling.
Seruling yang bagus, dihasilkan melalui proses yang sangat panjang serta berkelanjutan. Seorang kuli pembuat seruling tanah liat sepertiku ini, perlu bekerja keras untuk menghasilkan puluhan cetakan berkualitas. Aku membentuknya dengan berbagai rupa.
Ada yang mirip kepala kerbau. Rumah siput, ada juga yang hanya berbentuk persegi dengan presisi tertentu. Menyesuaikan letak lubang serta suara yang dihasilkan. Juga, tentu saja untuk proses membakar, perlu menakar secara lebih jelas soal cuaca.
Ketika suhu di dekat rumahku mencapai di atas suhu rata-rata, proses pembakaran tembikar seruling tidak akan menghasilkan keidealan. Berlaku sama bila suhu di bawah rata-rata, tembikar akan jadi lembab dan membuat tekstur tanah berbeda dari yang diinginkan. Hanya dengan ukuran suhu ruangan yang pas, serta waktu yang tepat, akan membuat tembikar terbentuk secara sesuai dan tepat.
Aku kurang begitu tahu sejak kapan seruling tanah liat mulai ada dan digunakan orang-orang desa. Jelasnya, sejak dilahirkan, aku hidup dari hasil penjualan seruling tanah liat sebagai industri rumahan yang dikelola keluargaku. Beberapa sepupu, sudah tidak lagi merawat usaha semacam ini karena mereka pindah ke kota. Di desaku saja, kini bisa dihitung dengan jari yang masih bertahan mengelola usaha alat musik tradisional seruling tanah liat.
Beberapa kerabat yang pulang dari kota setelah bertahun-tahun. Tidak jarang memberi bahan candaan bagi usaha kami yang masih membuat seruling tanah liat. Mereka bilang, "Anda sudah melewati zaman, namun semangat berjualan tetap seperti seorang remaja yang baru lulus dari sekolah menengah," dan kebanyakan memang dari anak-anak mereka, menyebut kami sedikit kolot.
Tetapi aku juga tidak mau kalah begitu saja, ketika tanpa basa-basi kusebut mereka sebagai anak-anak pencakar langit. Tinggal di gedung-gedung tinggi yang jauh dari tanah, sampai-sampai lupa menginjakkan kaki di lantai tingkat ke berapa dan di ruangan mana mereka menaruh pot tanamannya.
Hanya memang, yang kusukai dari mereka adalah kedermawanan. Kebanyakan tidak hanya membawa sekaligus memberikanku minuman-minuman soda yang nikmat, namun juga makanan terkini yang nihil ditemui bila berbelanja di pasar desa.
***
Sudah hampir tiga bulan. Tidak lagi ada kabar. Gadis Teratai mungkin sudah tidak memikirkan untuk kembali ke sini.
Ya, setidak-tidaknya aku paham bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Aku sangat senang bisa membantu sekaligus menemani hari-harinya di sini menyelesaikan skripsi.
Kami berdua bisa sama-sama saling belajar, dan aku juga tambah tahu banyak hal tentang apa-apa saja yang mereka bahas di Universitas. Aku bangga sekali setelah tahu bahwa mereka ternyata memperhatikan kerabat-kerabatku di sini.
Gadis Teratai pernah berujar, "Universitas sangat menghargai nilai-nilai kebudayaan nasional Tiongkok, dan mereka pasti tertarik dengan sesuatu yang aku lakukan," bahwa aku menganggap, sepertinya yang kulakukan selama ini tidak bermuara pada kesia-siaan.
Fung Jiao, nama asli dari Gadis Teratai. Dia bermarga Han, dan sejak lahir tinggal di Beijing. Aku memanggil dia Gadis Teratai karena saat pertama kali kita bertemu, dia membawakanku Bunga Teratai, sebagai benda keberuntungan yang semoga dapat memperlancar rezeki.
Namaku sendiri Ma Koay, Ma diambil dari nama Rasulullah. Sedang Koay berarti rembulan dalam bahasa suku kami. Aku lahir di malam hari, saat tiba peringatan hari istimewa Israj Mi'raj. Bapak wafat saat aku masih dalam usia kandungan 4 bulan karena serangan jantung mendadak, sejak kecil, aku dirawat oleh Kakek dan Ibu. Bulan depan, usiaku mencapai angka ke-29.
Bagiku Lao Tzu ada benarnya juga. Dia pernah bilang, "Jika kamu tidak mengubah arah, kamu mungkin bisa berakhir ke arah yang kamu tuju," sampai akhir-akhir ini aku merasa, telah berada ke arah yang kutuju tanpa perlu mengubah arah. Aku mengikuti naluri sesuai keinginan hati.
Supaya tidak perlu berpindah tempat guna menjual ratusan seruling tanah liat. Selalu bersetia dengan adat istiadat, hingga melawan segala bentuk upaya relokasi demi beberapa bidang tanah yang terus-menerus memberi kehidupan. Menyemai kebahagiaan.
Aku amat bahagia, meski nasib tidak membawaku kepada gemerlap serta megahnya perkotaan di luasnya dataran Tiongkok. Namun desa di tepi Sungai Kuning ini telah menyediakan segala yang kucintai. Harapan bagi kami orang-orang Hui melestarikan Huaer, harus tetap tumbuh. Sekecil apapun kemungkinan, kesempatan, peluang yang memadai.
Ikuti tulisan menarik Resza Mustafa lainnya di sini.