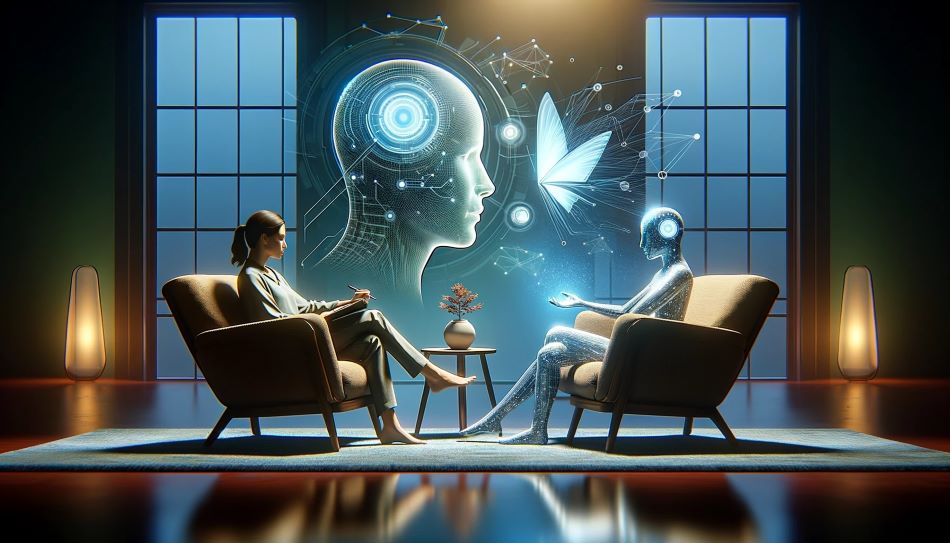Jalan Pulang Cinta
Senin, 29 November 2021 05:52 WIB
Kasus mafia tanah mencuat ke permukaan di berbagai media massa belakangan ini. Para pelaku kejahatan ini bisa melakukan sendiri atau menjadi bagian jaringan mafia tanah. Kejahatan mengambil alih lahan milik orang lain ini bisa dilakukan secara terorginisir. Mafia tanah biasanya memiliki kedekatan dengan korbannya.
Jarum jam panjang menunjuk angka dua dan pendek tepat di angka tiga. Itu artinya kurang dari satu jam lagi, maka kereta api tiba di stasiun terakhir. Cinta sengaja memilih jadwal keberangkatan kereta api yang tiba di tujuan menjelang pagi. Ia ingin menikmati kesejukan kota kelahirannya sebelum terbit matahari. Selain itu, gadis dua puluh tiga tahun juga mempunyai alasan lain.
*****
“Kenapa ngga pilih keberangkatan kereta yang agak malaman sih? Biar sampai di rumah sudah terang,” saran Tera sebelum Cinta memutuskan membeli tiket kemarin.
“Aku penyuka pagi dan kesunyian, Tera, Berjalan menyusuri jalanan lengang menuju rumah itu sesuatu banget,” jawab Cinta.
“Ah, sok penyair lu! Hei, gimana kalau pas keluar stasiun lu jadi korban kejahatan, hayo?”
“Kejahatan apa?”
“Ya misalnya dipalak, dirampok atau diperkosa, hayo?”
Cinta memandang Tera dengan tersenyum. Kemudian gadis berpenampilan tomboy itu mengulurkan tangannya ke dalam backpack miliknya, Ia mengeluarkan benda berwarna hitam mengkilat dari backpack dan ia menunjukkannya pada Tera. Seketika wajah Tera menunjukkan keterkejutannya.
“Hah, pistol? Lu punya pistol, Cinta?”
“Gua bakal sikat siapa aja yang coba berniat jahat ama gua dengan ini!”
“Beneran itu? Lu dapat dari mana?”
“Hei, biasa aja kali! Lagian kan emang gua ikutan club menembak, jadi wajar dong gua punya ini, hellooo?”
Tera memegang dan mengamati pistol di tangan Cinta.
“Eh,iya, asli, beneran lho ini”
“Asli! Beneran! Cuman ini buat olah raga doang.”
“Oh, ini yang dibilang air softgun itu ya?”
*****
Cinta melangkah keluar dari pintu utama stasiun. Ia mengenakan sarung tangan mungkin karena udara masih dingin pagi itu. Ia berhenti sejenak memandang sisi lain kota yang sepuluh tahun ia tinggalkan. Cinta selalu menggelengkan kepala sambil tersenyum, setiap kali sejumlah pengemudi taksi menawarkan jasa mereka. Perempuan lajang ini memilih berjalan kaki menyusuri jalanan yang masih lengang. Lampu-lampu jalanan masih menyala dan sebagian sinarnya menyatu dengan kabut. Setiap sudut kota ini menyimpan kenangan di ruang kepala Cinta. Gambar-gambar masa lalu kembali memenuh di ruang kepalanya setiap kali Cinta menghirup udara segar pagi itu.
“Kenapa kamu harus pergi, Cin,” tanya Bram dalam perjalanan ke stasiun sepuluh tahun lalu.
“Itu pertanyaanmu kesekian dan aku sudah ku jawab berkali-kali,” jawab Cinta.
“Yah, jadinya kasihan ibumu karena anak wedok satu-satunya pergi.”
“Kan Mami sudah ada yang nemanin. Kan sekarang sudah ada Om Hendra.”
“Maksudmu Pak Hendra, Papi barumu? Ya, tapi….”
“Hei, ingat ya! Aku ngga punya papi baru. Satu-satunya papi ku adalah almarhum Papi Sena. Paham?”
Lelaki bernama Bram hanya terdiam menerima ucapan Cinta itu. Mereka berdua menjadi membisu sepanjang perjalanan menuju ke stasiun kereta api. Dalam diam, Bram sebenarnya masih menyimpan gelisah di dadanya yang ia ingin ungkapkan kepada Cinta. Keduanya sudah menjadi sahabat dekat sejak lama. Bram merasa bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan membuat suasana tidak nyaman menjelang kepergian Cinta dengan percakapan itu. Padahal ia sebenarnya ia mengungkapkan sesuatu yang penting kepada Cinta saat itu.
****
Seiring waktu berjalan, hubungan Cinta dan Bram kembali mencair. Keduanya kembali saling bicara justru saat mereka berjauhan. Masing-masing sering saling bercerita atau sekedar menyapa.
“Jadi sebenarnya kamu keberatan mami menikah ya, Cin?”
“Ya begitulah. Karena pikirku bahwa cinta papi itu tergantikan oleh lelaki lain. Kupikir mami juga punya pikiran macam itu. Tapi ternyata….ya sudahlah.”
“Gimana mami lihat sikapmu waktu itu?”
“Yah, gitulahh Bram. Mami berusaha meyakinkan bahwa Om Hendra itu baik dan dia juga masih tetap tak bisa melupakan cinta almarhum papi dan….yah banyaklah. Yah, tapi sudahlah. Aku sadar bahwa mami mungkin membutuhkan seseorang dalam hidupnya.”
“Hmmm….kamu itu ternyata punya konsep tentang cinta sejati, Cin.”
Ucapan terakhir Bram itu terdengar lirih dan di telepon hamper tidak terdengar jelas.
“Apa? Gimana, Bram? Ngga jelas?”
“Ah, nggak, eh, ya udah aku mau ngelanjutin kerjaan dulu, bye!”
Klik.
****
Waktu menjelang terang tanah ketika Cinta berdiri di depan sebuah rumah yang ia tidak asing. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh halaman rumah itu. Pohon-pohon sudah tampak menua tapi tidak ada kenangan terhapus di sana. Cinta bisa mengingat kembali masa kanak-kanaknya di luasnya tempat itu. Taman kelihatan tak terawat dengan rumput-rumput liar yang menutupi keindahan beragam bunga yang ada. Cinta kecil dan teman-teman suka memetiknya dan mereka menggunakan untuk pasaran.
Setelah Cinta melintasi halaman luas itu, ia melangkah perlahan memasuki teras rumah. Cinta membuka perlahan pintu depan tanpa ia merasa perlu mengetuknya. Ruang tamu masih seperti dulu. Dinding sudah mulai berwarna kusam. Sebagian perabotan lama masih ada dan tampak semakin lusuh. Pandangan Cinta tertuju pada kursi santai yang dinaungi lampu baca di mana papinya almarhum suka menghabiskan waktu di sana dulu. Cinta melihat jajaran buku yang tertata di rak di belakang kursi tadi. Semua tampak berdebu dan beberapa sarang laba-laba menempel di sana. Cinta mengambil salah satu buku dari sana, tapi ia rupanya tanpa sadar menariknya terlalu kuat sehingga buku-buku lain jatuh berserakan di lantai.
Gedubrak!
“Cinta?” ucap seorang perempuan seusianya tiba-tiba di hadapannya.
“Feli? Aku tidak bermaksud membangunkanmu sepagi ini.”
“Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu begitu saja masuk? Kenapa ngga beri kabar dulu kalau mau datang?
“Tidak perlu. Ini toh rumahku juga. Suka-suka aku, Feli!”
“Aku juga punya hak di rumah ini, Cinta!”
“Hanya kau jadi istri Om Hendra? Hei, aku adalah anak dari pemilik sesungguhnya rumah ini, yaitu almarhum papi dan mami! Jadi jangan bicara soal hak, hai pengkhianat!”
“Pengkhianat? Apa maksudmu? Aku tidak pernah merusak rumah tangga Om Hendra dan mamimu. Kami menikah setelah Om Hendra berstatus duda, beberapa waktu setelah mami mu meninggal dunia.”
“Kamu mengkhianati Bram demi mendapatkan Oh Hendra!”
“Oh sok tahu sekali kamu, Cinta. Tahu apa kamu dengan hubungan kami? Hei, tapi jujur aku ngga bisa hidup dengan Bram jika masa depannya belum jelas.”
“Itu dulu. Tapi coba lihat Bram sekarang. Dia punya hidup yang lebih baik di kota ini.”
“Tunggu…tunggu…kenapa kamu tahu banget ya soal Bram? Ah, jangan-jangan kalian punya hubungan ya sebenarnya selama ini?”
*****
Suatu hari, Bram memang pernah mengutarakan isi hati pada Cinta. Mereka berharap bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekedar sahabat.
“Aku nggak mudah menyatakan ini padamu, Cinta. Tapi aku harus sampaikan sesuatu yang lama terpendam ini.”
“Terima kasih untuk keberanian dan kejujuranmu, Bram. Kamu lelaki yang baik yang kukenal. Aku juga membayangkan akan bahagia jalan bareng kamu lebih sering. Tapi aku mau kita seperti dulu saja.”
“Hmm, baiklah. Terima kasih juga untuk jawabanmu. Setidaknya aku masih punya harapan, Cinta”
“Ah, ngga usah juga terlalu berharap kali. Kalau kamu ketemu yang lain juga nggak apa-apa kok.”
Keduanya tertawa bahagia.
*****
“Cinta! Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini?”
Seorang lelaki paruh baya muncul dari kamar tidur dan penampilannya masih bau bantal. Ia merasakan suasana tegang dari dua perempuan di hadapannya. Dahinya berkerut ketika dia melihat buku-buku yang berserakan di lantai.
“Hai, Om Hendra. Sepertinya keributan pagi ini membangunkanmu, ya?”
“Nggak apa-apa, tapi kenapa Cinta ngga memberi kabar mau datang. Setelah sekian lama, aku pikir kamu…”
“Lupa? Nggalah, Om. Aku selalu mengingat tempat di mana Keluarga Bimasena pernah hidup berbahagia. Dan kini, aku mau mulai membangun kembali kebahagiaan itu.”
“Iya itu dulu. Sekarang, di tempat ini akan berdiri sebuah keluarga bahagia juga. Keluarga Hendra Ludira.”
Cinta mengambil langkah mendekati Hendra. Wajahnya menampilkan gambaran yang bergejolak riuh dari batinnya. Bibirnya tersenyum tetapi kedua sorot matanya menyinarkan kemarahan. Gadis itu semacam mendapat peneguhan bahwa semua kisah-kisah yang ia dengar tentang mama dan suami barunya itu adalah kebenaran. Ruang pikiran gadis itu telah menumpuk rangkaian lakon hidup mamanya yang telah menjadi korban kecurangan Hendra. Salah satu episode yang mengemuka adalah Hendra berupaya melakukan pengambilalihan harta mamanya lewat jalan culas. Ketika mama Cinta sakit, Hendra setengah memaksa istrinya itu menandatangani persetujuan memberikan hak kepemilikan rumah pada sang suami. Tentu saja, hal itu tidak butuh persetujuan anak kandung karena Cinta sudah menyerahkan kepemilikan rumah pada mamanya setelah papanya meninggal dunia.
“Dan sekarang aku mau minta balik semuanya, Om Hendra.”
“Hahaha, enteng sekali kamu bicara. Tidak semudah itu, Cinta!”
“Aku mau secara legal Om Hendra menyerahkannya kepadaku.”
“Ah, sudahlah! Ngga usah macam-macam. Lagipula aku memiliki semua ini secara sah!”
“Iya secara legal, tetapi Om Hendra mendasarinya dengan kebusukan.”
“Cukup! Pergi kamu dari rumah ini!”
“Mau atau tidak?”
“Tidak! Tidak sudi!”
Dor! Dor!
Ahhhh!
Hendro Ludira terkapar di lantai. Ada dua luka menganga di dada lelaki itu. Feli, istrinya berteriak histeris. Ia melihat pistol berwarna hitam mengkilat di tangan Cinta. Ia tidak menduga bekas sahabatbya itu menghabisi nyawa suminya dengn senjata itu. Cinta mendekati dan menenangkan Feli yang tampak ketakutan. Cinta memeluk erat Feli dan tak lama terdengar letusan untuk ketiga kalinya: dor! Feli jatuh terkulai dan tubuhnya telungkp di atas jasad suaminya. Kemudian, Cinta melihat kedua tubuh tak bernnyawa itu sejenak. Setelah ia memasukkan pistol ke dalam backpack, ia meninggalkan rumah itu dari pintu belakang. Ketenangan pagi itu terusik oleh peristiwa pembunuhan terhadap sepasang suami-istri.
*****
“Halo, Cinta?”
“Ya, Bram.
“Kamu sudah dengar belum? Om Hendro dan Feli meninggal ditembak orang.”
“Ha? Perampokan?”
“Tapi nggak ada barang-barangnya yang hilang.”
“Oh, gitu ya. Eh, tapi polisi sudah tahu siapa pelakunya?”
“Belum. Katanya belum ditemukan petunjuk apapun termasuk sidik jari.”
“…….”
S E L E S A I
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Jalan Pulang Cinta
Senin, 29 November 2021 05:52 WIB
Pembunuh Bayaran
Rabu, 10 November 2021 06:16 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 99
99 0
0