Matahari Tenggelam Lima Tahun Silam
Rabu, 8 Desember 2021 23:34 WIB
Suara debur ombak yang bertalu-talu memecah karang terdengar tak asing di telingaku. Di bawah bayang-bayang pohon ek tua yang berdahan rindang, aku terbaring menatap senja dari kejauhan. Menikmati senja sembari mencoba untuk memanggil kembali memoriku dari lima tahun silam.
Semburat jingga kemerahan di hadapanku, angin yang menerpa halus wajahku, serta suara kawanan burung yang bersahutan. Semuanya persis sama seperti dulu dan seakan-akan berkonspirasi untuk membawaku ke masa lalu. Satu hal yang berbeda sore ini; sejengkal tempat kosong di sampingku. Lima tahun lalu ada seseorang yang sering menempati tempat kosong itu. Mendengarkan keluh kesahku atau sekadar berdiam menanti matahari tenggelam.
Kala itu usiaku menginjak delapan belas tahun, duduk di tahun terakhir sekolah. Semua orang mengenalku: Guru, murid, dan bahkan hampir seluruh karyawan sekolah tahu siapa aku. Mereka mengenalku bukan karena aku pintar, namun karena kenakalanku. Entah sudah berapa kali kakiku melangkah keluar masuk ruangan kepala sekolah. Entah sudah berapa banyak kekacauan yang terjadi karena ulahku. Mulai dari kaca-kaca yang pecah, meja yang rusak, pintu yang terlepas dari engselnya, serta properti-properti sekolah lain yang kubuat tak berfungsi.
Rasanya, tak ada lagi guru yang mampu menasihatiku. Mereka semua sudah angkat tangan, tidak mau tahu lagi apa yang kuperbuat. Satu-satunya yang masih mau tahu adalah kepala sekolah yang tanpa lelah menasihati.
Sebelumnya, aku tidak seperti itu. Aku cukup baik di sekolah. Semua kenakalanku berawal ketika perusahaan ayah bangkrut, dan yang tersisa saat itu habis untuk membayar hutang-hutang ayah. Bahkan, rumah kami pun disita oleh bank dan kami harus pindah ke rumah kontrakan yang sangat sempit.
Sejak saat itu ibu mulai sakit-sakitan, sedangkan ayah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ayah jadi sering mabuk-mabukan dan menjadi temperamen. Ia akan pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat. Tak ada lagi ayah yang hangat dan penyayang, ayah benar – benar telah berubah. Beberapa kali kudengar dari balik dinding, suara ayah yang sedang memukuli ibu. Kemudian tangisan ibu akan mulai memenuhi kamar. Waktu itu aku hanya berani mendengar dari balik dinding. Saat itu aku baru berusia lima belas tahun, aku tidak memiliki nyali untuk menghentikan ayah. Hatiku teriris tiap kali aku mendengar ibu menangis, tapi nyaliku ciut untuk menghentikan ayah.
Ketika ayah di rumah aku selalu bertanya kepada ibu.
Apakah ibu baik – baik saja?
Namun hanya senyuman disertai anggukan kecil yang menjadi jawabannya. Ibu tidak pernah mengeluh kepadaku atau siapa pun akan perbuatan ayah. Ia terlihat sangat kuat di mataku. Tetapi aku salah, ternyata ibu tak sekuat itu.
Satu hari sepulang sekolah, aku menemukan ibu tergeletak di lantai kamar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar banyak busa. Di sampingnya terlihat pil-pil obat bertebaran di lantai. Nahas, ibu menenggak terlalu banyak pil dan tidak terselamatkan.
Aku hancur sejadi – jadinya, perasaan bersalah menyelimuti hatiku. Seharusnya aku tahu apa yang ibu lalui terlalu berat untuk dilaluinya sendiri. Seharusnya aku lebih peduli dengan ibu. Aku tak bisa berhenti berandai-andai. Membayangkan jika sebelumnya aku melakukan sesuatu hal ini tidak akan terjadi.
Penyesalanku berujung pada rasa benciku terhadap ayah. Mulai saat itu aku tidak lagi menganggap ayah ada. Dia bahkan tidak peduli sedikitpun ketika ibu pergi.
Akhirnya, aku pun berubah menjadi anak nakal dan tidak mengacuhkan orang lain. Aku hidup semauku, datang ke sekolah hanya untuk bermain dan tidur. Aku pun tidak memiliki teman. Karena aku kerap berkelahi dengan siapa saja. Semua orang menjauhiku dan tak ingin mendekat. Sebagian besar takut kepadaku dan sebagian lainnya mencibir diriku. Aku tidak peduli, toh tidak ada untungnya untukku.
Suatu hari, usai sekolah, aku merasa seseorang mengikutiku. Sehingga, aku mempercepat langkah kaki. Namun, suara langkah yang terdengar dari belakang pun terdengar semakin cepat pula. Akhirnya, tanpa berani melihat ke belakang aku berlari kencang, berusaha untuk menyelamatkan diriku. Sayangnya, orang yang mengikutiku jauh lebih cepat dariku. Mereka menyergapku dari belakang, lantas menyeretku beberapa meter ke dalam sebuah gang sempit.
Di dalam gang itu sudah ada beberapa orang yang menunggu. Tubuhku dilempar dengan mudahnya ke dalam gang, sehingga kepalaku membentur keras tembok. Kuperhatikan dengan saksama siapa yang kuhadapi. Ternyata, yang ada berada di depanku adalah seorang murid di sekolah yang kukalahkan saat berkelahi tempo hari. Aku tak menyangka dia menyimpan dendam kepadaku sampai seperti ini.
Belum sempat aku bangkit, orang-orang yang sebelumnya menyeretku sudah menahan kedua tanganku. Sedangkan murid tersebut dan satu orang lainnya memukulku tanpa ampun. Darah segar keluar dari mulut dan hidungku. Setelah beberapa lama memukulku mereka berhenti sebentar dan membiarkanku begitu saja.
Saat mereka sedang lengah aku segera melarikan diri. Dengan sisa kekuatan yang ada dan darah yang mengalir deras dari pelipis kanan, aku berlari dengan sangat cepat, tak menoleh sedikitpun. Dari belakang, aku mendengar suara mereka mulai mengejarku kembali.
Setelah berlari cukup jauh, aku tiba di jalan menuju bukit. Jalan itu hanya mengarah ke bukit atau aku harus kembali dan berhadapan dengan murid-murid tadi. Maka, tanpa berpikir panjang aku mengarahkan langkahku ke arah utara. Menanjaki jalan ke arah bukit dengan tertatih-tatih. Bukit itu terkenal angker, kami para murid dan warga sekitar dilarang untuk mendatanginya. Selain karena menakutkan, di ujung bukit tersebut terdapat tebing curam yang menjorok ke arah lautan. Tepat di bawahnya terdapat karang – karang tajam yang siap menerkam.
Pikiranku yang sedang tak karuan ditambah dengan sakit di sekujur tubuh membuat ku terus berjalan. Perlahan tapi pasti aku memasuki pepohonan rimbun di kaki bukit. Entah mengapa aku yakin mereka tidak akan mengikutiku sampai kesini. Tapi ternyata tidak, mereka benar-benar mengikutiku sampai ke kaki bukit. Aku mulai panik, segala usaha kukerahkan agar dapat berlari ke atas. Sejujurnya aku pun sedikit takut, namun aku lebih takut ditangkap mereka. Bagai orang kesetanan aku berlari tanpa henti.
Tanpa kusadari aku sudah sampai di puncak bukit. Aku menahan napas sambil bersembunyi. Namun, setelah sekian lama kutunggu, tampaknya mereka sudah tidak mengikutiku. Sembari mengatur napas yang sudah tak karuan aku menengok ke arah lautan. Aku terkesima melihat pemandangan yang ada di hadapanku. Matahari terlihat hampir tenggelam sempurna, menyisakan sedikit warna oranye di langit. Aku melangkah lebih jauh ke arah tebing untuk melihat langit lebih jelas lagi.
“Melompat ke bawah sana tidak akan menyelesaikan masalahmu, Nak.” Tiba-tiba aku mendengar suara serak dari sampingku.
Aku tertegun.
Siapa orang yang ada di atas sini juga?
Kemudian, aku memalingkan wajahku untuk melihat siapa yang tadi berbicara. Di bawah sebuah pohon ek besar, duduk seorang laki-laki tua yang sedang bersandar pada batangnya. Guratan-guratan tegas terlihat di wajahnya dan tubuhnya cukup kekar. Pakaiannya terlihat compang – camping. Wajahnya terlihat tidak terurus, terlihat dari rambut panjangnya yang sangat amat tidak teratur.
Mungkin umurnya sekitar enam puluh tahun? entahlah.
Aku berjalan terseok mendekat lalu ikut duduk bersandar di sampingnya.
“Aku tidak ingin melompat, Pak Tua,” ucapku getir.
“Dari wajahmu, jelas terlihat keinginanmu untuk melompat anak muda”. Katanya sambil terkekeh dengan suara seraknya.
Sebenarnya apa yang dikatakan lelaki tua itu tak sepenuhnya salah. Di dalam kepalaku terbesit keinginan untuk melompat ke bawah sana. Lagi pula, tak ada satupun yang peduli akan keberadaanku. Sejenak, aku terdiam mengamati warna langit yang perlahan pudar dan menjadi gelap.
“Masa depanmu terlalu panjang untuk dibuang begitu saja”. Ujar lelaki tua itu, memecah keheningan di antara kami berdua.
“Sudah kubilang aku tak ingin melompat!” balasku ketus.
Lelaki tua itu kembali terkekeh. Kemudian, aku bangkit dari tempat dudukku dan pamit pulang padanya. Keesokan harinya, aku kembali mendatangi bukit itu di sore hari. Aku ingin sekali melihat matahari tenggelam seperti kemarin. Kali ini aku datang lebih awal. Aku ingin menyaksikannya dari detik-detik sebelum tenggelam. Setibanya aku di atas, aku melihat lelaki tua itu lagi di tempat yang sama. Aku duduk di sampingnya, bersandar santai di pohon ek, menatap lautan. Pemandangan ini seperti memberikan kedamaian tersendiri untuk hatiku.
Beberapa lama setelah aku merebahkan diriku di tanah, lelaki tua itu mulai berbicara. Kami pun akhirnya saling berbincang. Tanpa sadar, aku menceritakan seluruh keluh kesahku padanya. Kuceritakan semua masalahku selama ini. Menceritakan kepadanya berapa banyak anak yang sudah kukalahkan saat berkelahi. Lelaki tua itu lalu terdiam sebentar.
“Banyak yang dapat kau lakukan lebih dari itu, nak”. Ucapnya.
“Maksudnya?”, tanyaku tak mengerti.
“Belajarlah, ibumu pasti tidak ingin melihatmu seperti ini,” ujarnya.
“Apakah kau ingin berakhir begini sepertiku?”, lanjutnya tertunduk.
“Jangan jadikan keadaanmu ini sebagai pembenaran atas semua perilakumu.”, ia kembali melanjutkan ucapannya.
Aku terdiam. Tak bisa menjawab perkataannya. Tidak ada yang pernah ada yang mengatakan hal seperti itu kepadaku sebelumnya. Sampai langit berubah gelap aku hanya terdiam, tak mengucapkan satu kata pun. Hingga akhirnya aku pun pamit.
Sepanjang perjalanan pulang aku memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Memang benar sudah lama sekali aku hidup seenaknya sendiri menatap ke belakang. Meskipun aku berusaha untuk tidak memikirkannya, perkataan lelaki tua itu terus terngiang di kepalaku.
Esoknya, aku kembali datang ke puncak bukit. Lantas, merebahkan diriku di tempat biasa. Pak Tua sudah menunggu seperti biasa, namun kali ini aku memulai pembicaraan terlebih dahulu.
“Aku akan mulai belajar sekarang,” ujarku bersemangat.
Lelaki tua itu hanya tersenyum dan menepuk-tepuk pundakku pelan.
“Aku juga berjanji akan menjadi sukses,” ujarku lagi.
“Aku ingin buat ibu bangga,” gumamku kecil.
Semenjak hari itu aku mulai tekun belajar. Awalnya agak sulit untuk mengerti. Tak ayal, aku hampir tidak pernah belajar selama ini. Namun seiring waktu aku dengan mudah mengerti semua yang kupelajari. Sejujurnya, aku tak mengira aku dapat menguasainya. Semua guru di sekolah tercengang dengan perubahan dan performaku yang meningkat pesat. Tak ubahnya guru-guru, murid-murid kelas pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadaku.
Semakin dekat dengan ujian aku semakin giat mengerjakan soal. Aku bahkan hampir hafal seluruh isi buku yang kubaca. Biasanya aku belajar di atas bukit. Sembari berbincang singkat dengan pak tua dan menutupnya dengan menyaksikan matahari tenggelam sampai habis di ujung sana.
Hari ujian akhirnya tiba, aku berusaha untuk tidak gugup. Aku sudah melakukan semua sebisaku dan berusaha semampuku. Setelah bel selesai berdering aku melangkahkan kakiku keluar ruangan. Mencoba untuk pasrah untuk hasil yang akan kudapat nantinya.
Selang beberapa waktu sejak hari ujian, kepala sekolah memintaku untuk datang ke ruangannya. Sedikit gugup aku mendatangi ruangannya, bertanya-tanya ulahku yang mana lagi yang membuatku dipanggil. Kepala sekolah tersenyum lebar ketika aku muncul di ruangannya. Beliau mendekat kepadaku lalu memelukku sangat erat. Aku terheran-heran dengan sikapnya yang tidak biasa. Namun, yang diucapkannya setelah itu memperjelas semuanya.
“Selamat kamu diterima di universitas terbaik di negeri ini. Bapak tahu kamu mampu,” ujar kepala sekolah.
Aku termangu mendengar perkataannya. Untuk beberapa saat aku terdiam mematung. Tanganku gemetar, tak percaya dengan perkataan beliau. Lalu, kepala sekolah melepaskan pelukannya dan kembali tersenyum haru kepadaku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar aku menyambut amplop putih yang diulurkan kepala sekolah.
Hal yang pertama kali kulakukan adalah berlari ke arah bukit. Aku ingin segera mungkin menyampaikan berita ini kepada Pak Tua. Seperti biasa ia sedang duduk di bawah pohon ek menghadap ke laut. Aku langsung memberitahunya hasil ujianku; nilai sempurna dan bahwa aku diterima di universitas terbaik di negeri ini. Senyuman tersungging di wajah tuanya. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasa sebahagia ini.
Waktu berlalu dan aku pun harus pergi dari kotaku untuk menuntut ilmu. Aku cukup sedih karena akan meninggalkan pak tua. Belum lagi tidak bisa melihat pemandangan sore dari atas bukit. Tetapi, Pak Tua meyakinkanku untuk pergi. Kami berjanji untuk saling bertukar kabar lewat surat. Dan aku berjanji untuk kembali saat sudah sukses nanti.
Lima tahun telah berlalu dan aku telah menyelesaikan studiku. Memperoleh dua gelar sekaligus dalam kurun waktu lima tahun, dengan nilai nyaris sempurna. Kuputuskan untuk kembali ke kota asalku.
Begitulah bagaimana aku dapat kembali duduk lagi di sini setelah sekian lama. Di bawah pohon ek tua ini, menghadap matahari tenggelam. Kemarin, sesaat aku tiba di kota asalku aku mendapat kabar bahwa Pak Tua telah tiada. Kesedihan merasukiku, aku belum sempat memenuhi janjiku. Belum sempat mengabarkannya kalau aku telah sukses. Sambil menyaksikan matahari tenggelam aku masih terisak pilu. Disaksikan oleh langit sore dan matahari yang sama dengan lima tahun silam.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Matahari Tenggelam Lima Tahun Silam
Rabu, 8 Desember 2021 23:34 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





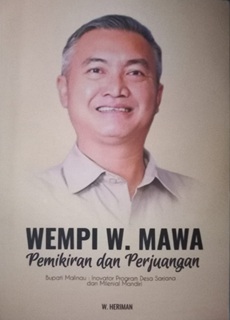

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 96
96 0
0

















