Perempuan Penakluk Lautan
Rabu, 8 Desember 2021 23:47 WIB
Dam, ombak berteriak pada pasir untuk menahannya lebih lama di sini—begitu juga aku padamu—kupanggil-panggil namamu namun kau terus melaju dengan perahu cadik mendiang ayahmu. Deru mesin kian redup menjauh. Suaraku ditelan oleh kelam dan malam yang rindang karena bulan sedang bertelanjang bulat di atas sana. Sama sepertiku beberapa waktu lalu kau rayu untuk bertelanjang di hadapanmu. Perutku dari hari ke hari terlihat semakin membesar, maka aku meminta pertanggungjawaban. Tapi kau lebih memilih untuk berlayar, menghadapi ganasnya gelombang membelah gelap daripada mengucurkan setetes kata padaku.
***
“Oi, Memei! Sebaiknya kau angkat kaki dari sini. Kau perempuan pelihara anak haram. Sama seperti Ibumu dahulu yang membawa petaka untuk kita semua.”
Aku memilih mengusap perut daripada bunyi mulut karena keadaan begini sudah akrab sejak kanak. Kulihat Ibu bolak-balik menyambut tamu-tamunya yang pemarah. Jeritan hingga ayunan tangan kepada Ibu kupandang dengan kenyang. Mereka menganggapnya jalang yang suka menggoda lelaki orang. Mereka tahu kalau Ibu salah satu korban selamat dari pembantaian Nanking yang dilakukan tentara Jepang. Namun, Ibu bilang kalau semasa itu ia lebih baik mati terpenggal daripada ikut rombongan menaiki kapal. Saat itu ia baru sadar, semua yang berada di dalam kapal adalah gadis-gadis sebaya dengannya yang lencir, ranum, dan siap dipetik. Ketika sampai di dermaga Vietnam, di sana kelamin-kelamin mereka mulai diedarkan. Genap setahun kemudian, angin menghantar pesan—perang saudara pecah, lantas kapal memutar kemudi, menyerahkan diri pada jarum kompas dan nasib yang mengantar pelayaran tiba pada suatu dermaga di Indonesia.
Ibu terjun ke laut—tepat kapal menjatuhkan sauh—ia melesat, merasakan asin air mengorek luka pada rahimnya yang terus bergerak untuk berenang menjauh. Di kepalanya hanya ada sinar lemah agar menggoyangkan kaki dan tangan tanpa menoleh ke belakang. Hingga akhirnya, Ibu didera keram dan gigil, membuatnya tak kuasa menahan—perlahan, tubuhnya mulai berangsur tenggelam—semua pecahan ingatan yang selama ini ia lupakan tiba-tiba dikebas ombak kembali. Kematian mulai menjulurkan tangannya melalui buih-buih. Tetapi setidaknya Ibu telah bahagia bila semua harus terhenti di sini. “Ibu pikir saat itu tangan malaikat yang menyambut tangan Ibu, tapi ternyata itu tangan ayahmu, Mei. Laki-laki tak bertanggungjawab. Tiap malam berjudi di pelabuhan dan mabuk-mabukan. Kata teman-teman Ayahmu, suatu malam ia tiba-tiba tersungkur dari meja saat menjatuhkan kartu terakhir dan langsung meninggal. Ibu pikir itu karena penyakit dadanya.
Aku selalu menangis ketika mengingat kenangan tentang Ibu. Kutemukan Ibu berpamit dengan mulut penuh busa petang itu.
Dari kejauhan, suaminya menunjuk langit sambil diayunkan, tampak mesin perahunya telah berhasil dihidupkan. Wanita tua ini menghadap ke belakang sebentar, menyebabkan perhiasan yang menumpuk di lengannya berdenting. Ia melayangkan ancaman melalui pandangan. “Awas ya kamu coba-coba menggoda suamiku.”
Sejak kabar kehamilanku menyebar ke seluruh pesisir pantai, orang-orang menerbangkan cemooh yang mengoyak diriku dengan berbagai cerita. Di pos ronda, di dermaga tempat pelelangan ikan, di atas perahu, di pasar, di mana pun asal mereka sedang berkumpul, aibku adalah hal yang bagus untuk membunuh kebosanan.
Sinar matahari menerobos pintu di mana aku sedang duduk menanti perahu cadikmu. Separuh cahayanya membuat sudut rumah persegi panjang ini meremang. Hari telah matang, kulihat para nelayan pulang dari menjaring yang pergi sejak semalam. Saat-saat seperti ini, aku langsung mengganjal pintu dengan sebongkah batu—menghalau angin mengantar jerit—satu per satu, perahu bersandar di bibir pantai. Bila nelayan pulang dengan langkah sangat pelan, beraut wajah masam, dapat dipastikan pada jala yang dipikul, hanya sedikit ikan yang terkait atau tak tersentuh sama sekali. Dan mereka akan mendatangi rumahku, meminta ganti rugi. Kata mereka, akulah penyebab ikan jadi sulit ditangkap. “Tuhan tak sudi memberi rezeki kalau pendosa besar sepertimu masih berada di pesisir ini.” Kata-kata seperti ini berulang kali aku dengar, aku lupa siapa yang memulainya.
“Memei, kau sembunyikan di mana kekasihku?” Semburat di wajahnya membara. Dia sahabatku, Wen’ri. Kami tumbuh bersama-sama seperti selayaknya gadis kecil, tetapi ketika kami mulai mendapati darah tiap bulan, kutemukan diriku jauh lebih menarik darinya. Aku mematut diri berlama-lama di depan kaca, menyisir rambut, memberi bedak pada wajah, membayangkan tiap lelaki di pesisir ini sempurna menginginkanku. Aku tidak mau lagi keluar rumah untuk menjaga kulitku tetap secantik mutiara. Kurasa itu sebabnya Wen’ri jadi suka menyendiri, nekat mendayung sendiri perahunya sampai melebihi garis batas dalam mengais ikan. Para nelayan yang melihat Wen’ri sudah berulang kali memberi teguran, namun ia tetap pada pendiriannya yang sekeras batu karang. Orang-orang jadi tidak peduli lagi kepada Wen’ri.
“Ayo jawab Memei! Di mana kau sembunyikan kekasihku? Sejak kecil, aku tidak pernah mau mengambil apa yang kau miliki. Aku mencari jalan kebahagiaanku sendiri, tapi mengapa kebahagiaanku satu-satunya kau rebut juga? Pantas saja kau dinamai perempuan jalang!”
Aku berlulut, memeluk kaki Wen’ri, butiran pasir pantai berguguran dari kulitnya, “Wen’ri sayangku, demi Tuhan dan laut, aku menyesal, tolong maafkan. Mohon beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku ingin kita kembali karib.” Aku sudah tidak tahan, airmataku akhirnya melesak. Aku memang perempuan jalang! Bermain mata dengan kekasih orang, kekasih sahabatku sendiri, astaga! Menegak racun nyamuk sekali pun seperti Ibu tak akan menyelesaikan masalah, malah runyam bertambah.
Hening di antara kami telah membatu, hanya terdengar debur ombak dan sisa sedu sedan dariku. Tiba-tiba Wen’ri mendorong bahuku perlahan, aku mendongak penuh pengharapan, “Ini sudah terlalu malam, aku lupa membawa lampu cublik, aku harus segera pulang, ada yang perlu kupersiapkan.” Setelah itu Wen’ri benar-benar berbalik arah dan tubuhnya menghilang ditelan malam.
Nyeri menjalar dari perut ke selangkangan, mungkin aku terlalu lama membungkuk hingga tak sadar kalau perutku yang seperti bulan ikut tertekan. Angin di luar sangat kencang, membuat pasir terbang dan sebagian memasuki rumah, dengan susah payah aku berjalan sambil menahan nyeri dan beban di perutku. Batu yang tadi mengganjal pintu harus disingkirkan. Aku keluar terpincang-pincang sambil meraba papan-papan rumah. Pasir terbang menghantam wajahku, mataku perih. Dari kejauhan, samar-samar suara perempuan terus memanggil, makin lama aku dapat mendengar jelas apa yang ia serukan. Cahaya kuning kecil hidup di tengah gelap. Semakin lama semakin membesar, “Memei, lekas kenakan pakaian tebalmu, aku tahu keberadaan ayah anakmu.” Seketika aku tertegun dengan kalimat terakhirnya. Dan itu diserukan olehnya! Aku menghambur ke arahnya.
“Harus ke mana kita mencarinya?”
“Kujelaskan nanti. Bergegaslah ke perahuku.” Wen’ri menyerahkan satu tangannya, sementara satu tangannya lekat pada lampu cublik. Ia menuntunku sangat pelan, sudah lama aku merindukan sikap Wen’ri yang seperti ini.
“Tapi aku takut, Wen’ri. Sepertinya akan ada badai.”
“Apa kamu sudah lupa dengan julukan perempuan penakluk lautan? Hanya aku perempuan di pesisir ini yang masih berburu ikan dengan cara lama.”
Kami telah sampai di depan perahu Wen’ri yang tidak dilumuri pewarna. Laut langsung menyambut dengan menjilat-jilat seperempat kaki kami. Sejak dulu kemampuan Wen’ri dalam mengarahkan tombak, bertahan melawan ombak, membaca arah angin, melihat rasi bintang, mengetahui tempat ikan berkumpul dengan mengetuk permukaan laut. Banyak nelayan datang ke rumah Wen’ri dengan membawa sejumput uang atau ikan. Waktu itu aku memberanikan diri bertanya mengapa enggan menerima. “Ini warisan dari leluhur. Aku tidak akan mengajarkan kepada orang lain, karena mereka berburu ikan dengan cara menebar jala. Jika digabungkan dengan caraku, maka habislah ikan di lautan.”
“Memei, mengapa malah melamun? Cepat sambut tanganku sebelum Damang pergi menjauh,” Wen’ri telah berada di atas perahu, meleraikan tangannya kepadaku. “Aku mendengar kabar dari nelayan yang barusan pulang, kalau melihat perahu cadik milik Damang. Saat ini, laut mempunyai tekanan tinggi dibandingkan daratan, berarti kalau perahu Damang hanya mengikuti arus gelombang, maka angin laut akan mengantarnya ke tepian. Jangan sampai Damang menghidupkan kembali mesinnya menyusur arus.”
Belum sempat Wen’ri menghunuskan dayungan pertamanya, perahu kayu bewarna biru dengan kedua cadik yang membentang bewarna kelabu beradu dengan ujung perahu Wen’ri. Aku dan Wen’ri saling menatap tak percaya, itu adalah perahu cadik milik Damang! Wen’ri langsung melompatinya, aku mencoba mengikuti namun tiba-tiba nyeri yang sangat ngeri berdenyut di selangkangan, kemudian sesuatu terasa mengalir dari sana, kakiku basah.
“Memei, mesin tempelnya sudah tidak ada. Damang juga entah ke mana. Pakaian dan wadah airnya lenyap, tapi Memei, coba kamu lihat ini, aku menemukan selembar kertas, apa isinya, tak ada selain namamu yang ditulis besar-besar.”
“Wen’ri, maafkan aku telah mengotori perahumu.”
“Astaga, kamu mau melahirkan?”
Lompatan Wen’ri dari perahu cadik Damang membuat perahu ini berguncang, kepalaku jatuh dari papan dudukan dan penglihatanku melayang-layang. Wen’ri langsung membenarkan posisiku, menarik celana dalamku. Menangkup air laut di sisi kapal dengan kedua tangannya lalu menumpahkannya ke dalam kelaminku.
“Apa yang kamu lakukan, Wen’ri? Sama saja kamu mencoba membunuh bayiku. Tolong hentikan, ini sangat perih!”
“Maafkan aku, Memei. Tapi sebagai keturunan dari Tetua adat pesisir sini, aku harus menjaga agar lautan ini bebas dari malapetaka. Sejak kanak aku diperingatkan untuk tidak lagi bermain bersamamu.”
“Sudah cukup, Wen’ri! Bayi ini suci, sama sekali tidak ada hubungannya dengan seluruh malapetaka yang nantinya akan menimpa.” Tetapi wen’ri tidak mendengarkanku, ia terus saja mencoba mengoyak janinku.
Sambil menahan rasa sakit, aku bergumam dalam hati, “Biarpun kamu dijuluki sebagai wanita penakluk lautan, tetapi bila anak ini lahir, kamu tidak mungkin bisa menaklukan takdir Tuhan.”
Malang, 20 November 2020
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Perempuan Penakluk Lautan
Rabu, 8 Desember 2021 23:47 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





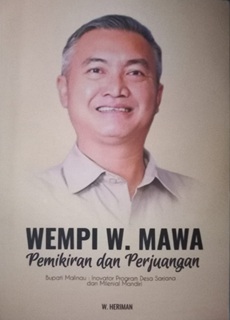

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 96
96 0
0

















