Pemerhati demokrasi dan politik lokal, mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, serta penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menjadi Manusia Indonesia
Jumat, 18 Juli 2025 10:23 WIB
Refleksi atas lunturnya jati diri bangsa akibat politik.
***
Sering kali kita mendengar pujian tentang siapa manusia Indonesia. Kita dikenal ramah, gotong royong, penuh semangat kebersamaan, spiritual, dan santun. Cerita-cerita ini kita pelajari sejak kecil, di sekolah atau dari orang tua, dan sering kita banggakan ketika tamu asing memuji kehangatan kita dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan pencitraan semata, melainkan sesuatu yang telah menjadi narasi kolektif, yaitu citra diri yang diyakini sebagai fondasi kita bersama.
Namun, jika kita menengok ke cermin kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah politik dan sosial, wajah yang tercermin seringkali berbeda. Kita mendapati ketidaksesuaian tajam antara kisah indah itu dengan kenyataan yang kita hadapi. Keramahtamahan kadang menguap di bawah panasnya konflik politik, gotong royong terkikis oleh sekat-sekat kepentingan kelompok, dan santun berubah menjadi suatu sikap diam yang pasif.
Pertanyaannya sulit, dan menyakitkan: ke mana sebenarnya manusia Indonesia sejati itu ketika negara dan bangsa sedang dalam ujian? Apakah kita telah kehilangan jati diri kita, ataukah kita hanya tersesat sejenak di tengah derasnya arus zaman?
Jika kita amati lebih dekat, kita akan melihat ironi yang jelas mencabik semangat gotong royong. Dalam sejarah kita, gotong royong adalah jantung dari kebersamaan: membangun rumah, menyelenggarakan acara adat, bahkan menjaga keamanan kampung. Namun sekarang, gotong royong justru sering tampil dalam bentuk yang sempit dan tersita oleh logika kepentingan politik. “Kita” tak lagi berarti bangsa, melainkan kelompok pendukung yang saling berseteru.
Media sosial, yang dulu diharapkan bisa menjadi ruang sosialisasi positif, berubah menjadi arena pertempuran verbal yang menguras energi dan memupuk permusuhan. Daripada membangun, kita malah terjebak dalam destruksi lewat pertentangan yang sering tak berujung.
Hal lain yang menarik untuk direnungkan adalah bagaimana sopan santun yang selama ini kita anggap sebagai ciri budaya luhur, justru menjadi paradox yang melumpuhkan sikap kritis kita. Budaya “ewuh pakewuh”, rasa segan yang menahan kita untuk menyakiti perasaan orang lain, seolah dipahami ulang sebagai larangan menyampaikan kritik kepada pemimpin. Ketika kritik dianggap sebagai ketidaksopanan atau kurang ajar, maka kita memilih untuk diam dan berkompromi dengan ketidakadilan.
Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kritik bukanlah pengkhianatan, melainkan bukti kecintaan dan perhatian yang dalam terhadap negeri ini. Di sinilah titik di mana kedewasaan berpolitik kita diuji: apakah kita siap menjadi warga negara yang berani berkata tidak ketika ada hal yang salah, ataukah kita akan terus nyaman dalam keheningan yang melemahkan?
Lebih jauh lagi, luka yang lebih dalam hadir pada bagaimana spiritualitas dan konsep kekeluargaan, yakni dua hal yang biasanya jadi penopang kuat identitas kita, kini terjerumus ke dalam wilayah abu-abu politik praktis. Spiritualitas, seharusnya menjadi cahaya penuntun yang memupuk rasa kasih dan keadilan, sering kali diselewengkan menjadi alat untuk mendiskreditkan lawan atau men justifikasi kepentingan tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada nilai kekeluargaan.
Semangat membantu sesama dalam lingkup keluarga atau komunitas kini berubah menjadi praktik “prioritas keluarga” yang tidak sehat, yang merayakan nepotisme dan KKN sebagai norma yang dapat dimaklumi. Jabatan publik dan sumber daya negara dialokasikan bukan berdasarkan kemampuan dan integritas, tetapi pada kedekatan dan relasi pribadi. Fenomena ini menghadirkan tantangan serius yang memanggil kesadaran kolektif kita semua.
Namun, dari semua itu, kita tidak perlu tenggelam dalam keputusasaan. Justru, keresahan dan luka inilah yang harus kita jadikan titik tolak, bahan bakar untuk menyalakan kembali semangat menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Menjadi Indonesia hari ini bukan soal kembali ke masa lalu dan mendaur ulang kisah lama, melainkan tentang memaknai ulang nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman sekarang.
Gotong royong harus kita kembalikan sebagai kekuatan kolektif untuk melawan ketidakadilan, korupsi, dan kepentingan sempit. Santun harus diartikan sebagai wujud keberanian yang berbasis data dan dialog, bukan diam pasrah yang mengabaikan kebenaran. Spiritualitas harus menjadi kompas moral yang menuntun kita dalam memilih pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan adil. Dan kekeluargaan semestinya tidak eksklusif menjadi jargon “keluarga saya dan kawan saya”, melainkan prinsip meritokrasi yang adil, di mana semua warga bangsa diperlakukan sebagai bagian keluarga besar yang setara dan memiliki hak yang sama.
Menjadi Indonesia bukan hanya tentang warna kebangsaan yang tertulis di KTP atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ini adalah tentang bagaimana kita bertindak, berbuat, dan bermimpi bersama sebagai sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Masa depan Indonesia akan terbentuk dari kolektivitas kita, bukan dari sekadar individu yang mengisi posisi tinggi. Oleh karena itu, mari kita berhenti sejenak, berintrospeksi, dan tanya pada diri sendiri, dengan jujur, tanpa pura-pura, “Manusia Indonesia seperti apa yang aku hadirkan hari ini?” Jawaban atas pertanyaan sederhana namun dalam ini akan menentukan arah langkah dan nasib bangsa yang kita cintai.
Mari menjadi Indonesia, kembali. Bukan dengan nostalgia, tapi dengan langkah tegas dan hati yang penuh kesadaran. Bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan tindakan nyata yang membumikan nilai luhur bangsa. Karena sejatinya, menjadi Indonesia adalah perjalanan yang kita jalani bersama, dengan percaya, dengan kerja keras, dan dengan harapan tanpa batas.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Demokrasi dalam Kepungan Asap
Senin, 1 September 2025 17:13 WIB
Negara yang Seharusnya Melindungi, Justru Melindas
Sabtu, 30 Agustus 2025 13:56 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0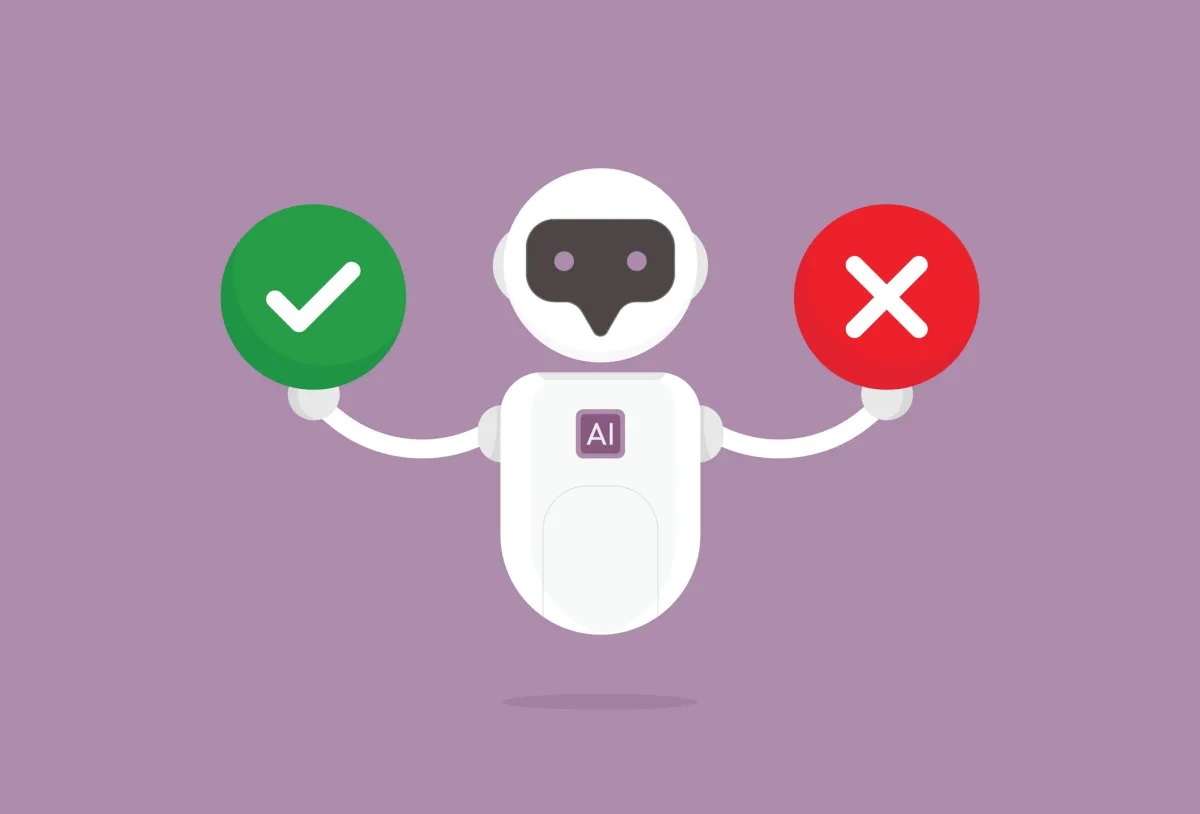









 98
98 0
0












