Pemerhati demokrasi dan politik lokal, mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, serta penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Negara yang Seharusnya Melindungi, Justru Melindas
Sabtu, 30 Agustus 2025 13:56 WIB
Ketika instrumen kekuasaan berubah menjadi mesin pemusnah, keamanan bukan lagi hak warga, melainkan ilusi yang bisa dilindas sewaktu-waktu.
***
Keamanan adalah janji paling mendasar yang diberikan negara kepada warganya. Ia bukan sekadar slogan birokratis, melainkan fondasi dari kontrak sosial yang membentuk republik ini. Pada malam gulita 28 Agustus 2025, negara mempertontonkan wajahnya yang paling brutal dan absurd. Di atas aspal Jakarta, tubuh Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online lumat di bawah roda Barakuda, kendaraan taktis milik aparat keamanan yang semestinya menjadi simbol perlindungan, bukan predator bagi rakyatnya sendiri.
Peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan sebuah pertunjukan teatrikal yang mengerikan tentang patologi kekuasaan. Ini bukan lagi sekadar berita duka, melainkan sebuah epitaf: nisan yang menandai kematian keamanan publik, dilindas secara harfiah oleh negara yang seharusnya menjaganya. Menyederhanakan insiden mematikan ini sebagai “kesalahan oknum” adalah kemalasan intelektual sekaligus pengkhianatan terhadap akal sehat. Sebab, yang kita saksikan bukanlah kecelakaan, melainkan manifestasi telanjang dari penyakit kronis yang menggerogoti tubuh republik: krisis legitimasi negara.
Monopoli Sah yang Menjadi Ilegal
Sosiolog Max Weber, dalam esainya yang monumental, mendefinisikan negara sebagai institusi yang berhasil memonopoli “penggunaan kekerasan fisik yang sah” (legitimate use of physical force). Kata kunci yang menjadi fondasi peradaban modern adalah “sah”. Legitimasi ini bukanlah hak buta yang datang dari langit, melainkan mandat rapuh yang dianugerahkan oleh rakyat. Ia terikat pada koridor hukum, prinsip proporsionalitas, dan diabdikan sepenuhnya untuk melindungi warga negara.
Legitimasi dibangun melalui konsistensi dan akuntabilitas; ia luntur ketika kekerasan menjadi eksesif, arbitrer, dan gagal membedakan antara ancaman nyata dan warga sipil. Ketika roda Barakuda melindas Affan, kekerasan itu seketika menjadi ilegal dan biadab. Monopoli itu telah disalahgunakan secara telanjang, mengubah negara dari penjaga menjadi penindas.
Pengerahan kendaraan taktis lapis baja untuk pengendalian massa di ruang sipil sudah merupakan kegagalan doktrin. Ia menunjukkan cara pandang militeristik yang melihat warga bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, melainkan sebagai objek atau musuh yang harus ditaklukkan. Rasionalitas instrumental, di mana kehadiran alat (Barakuda) mendikte Tindakan, telah mengalahkan rasionalitas humanis dan konstitusional.
Pengkhianatan Kontrak Sosial
Dalam sanubari setiap negara modern bersemayam sebuah perjanjian tak tertulis: kontrak sosial. Para filsuf pencerahan seperti Thomas Hobbes dan John Locke menguraikannya sebagai pertukaran fundamental: warga negara menyerahkan sebagian kebebasan individualnya kepada negara, dan sebagai gantinya, negara wajib menjamin hak paling asasi, hak untuk hidup dan merasa aman.
Perjanjian ini diperbarui setiap hari melalui tindakan nyata negara. Affan Kurniawan adalah arketipe warga negara di era ekonomi gig: seorang pejuang urban yang menggantungkan hidupnya pada kerja informal, minim proteksi sosial, namun tetap taat pada aturan main. Ia adalah perwujudan rakyat kebanyakan yang menaruh kepercayaan pada janji perlindungan negara.
Malam itu, kontrak tersebut dikhianati secara paling brutal. Tembok pelindung yang dijanjikan tidak hanya roboh, tetapi berbalik menjadi mesin penghancur. Leviathan, monster negara yang digambarkan Hobbes, yang seharusnya hanya menakutkan bagi musuh-musuh ketertiban, justru memangsa anaknya sendiri. Peristiwa ini adalah metafora sempurna dari relasi kuasa yang timpang secara patologis: kerapuhan seorang warga biasa dihadapkan pada kekuatan negara yang masif, mekanis, dan tanpa wajah. Negara, alih-alih menjadi solusi atas kerentanan warganya, justru menjadi sumber utama dari ketidakamanan itu sendiri.
Kekuasaan yang Sekarat, Kekerasan yang Merajalela
Filsuf politik Hannah Arendt secara tajam mengingatkan kita untuk tidak mencampuradukkan antara kekuasaan (power) dan kekerasan (violence). Kekuasaan sejati, menurutnya, lahir dari legitimasi, persetujuan, dan kemampuan kolektif warga untuk bertindak bersama. Sebaliknya, kekerasan justru menjadi pertanda keruntuhan kekuasaan itu sendiri. “Kekuasaan dan kekerasan berbanding terbalik; di mana yang satu berkuasa secara absolut, yang lain absen”, tulisnya.
Sebuah rezim yang harus bersandar pada intimidasi, represi, dan pengerahan alat tempur di jalanan kotanya sesungguhnya tidak sedang menunjukkan kekuatan. Ia justru sedang berteriak dalam kerapuhannya, mengaku telah gagal meyakinkan, gagal berdialog, dan gagal memimpin dengan otoritas moral. Barakuda di jalanan sipil bukanlah simbol supremasi, melainkan lonceng kematian bagi otoritas yang legitimasinya sedang sekarat.
Lebih dalam lagi, tragedi ini adalah manifestasi fisik dari apa yang disebut sosiolog Johan Galtung sebagai kekerasan struktural. Ketimpangan yang tersembunyi dalam sistem hukum, ekonomi, dan politik kita, yang membuat nyawa seorang pekerja informal terasa begitu murah, kini meledak dalam bentuk kekerasan langsung yang paling mengerikan. Affan, seperti jutaan warga lainnya, mungkin sudah menjadi korban dari struktur yang tidak adil jauh sebelum malam nahas itu. Roda Barakuda hanyalah eksekutor brutal dari sebuah hukuman yang telah lama dijatuhkan oleh sistem.
Menuntut Kembali Republik
Keadilan untuk Affan dan keluarganya tidak bisa ditawar. Namun, keadilan sejati melampaui penghukuman para pelaku di lapangan. Ia menuntut pembongkaran dan reformasi struktur yang memungkinkan tragedi ini terjadi: institusi keamanan yang akuntabel di bawah supremasi sipil yang kokoh, serta paradigma baru yang menempatkan nyawa dan hak setiap warga sebagai hukum tertinggi.
Negara harus dipaksa kembali ke khitahnya: sebagai pelayan dan pelindung. Tragedi ini harus menjadi titik api yang menyulut kesadaran kita untuk merebut kembali republik dari ambang krisis legitimasi yang berbahaya. Sebab jika tidak, kita semua hanya sedang menunggu giliran, di atas aspal yang sama, di bawah roda-roda kekuasaan yang lain.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Demokrasi dalam Kepungan Asap
Senin, 1 September 2025 17:13 WIB
Negara yang Seharusnya Melindungi, Justru Melindas
Sabtu, 30 Agustus 2025 13:56 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 99
99 0
0


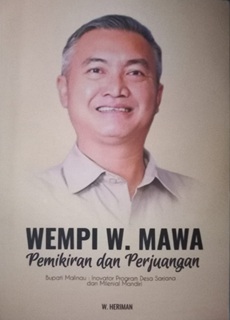



 Berita Pilihan
Berita Pilihan












