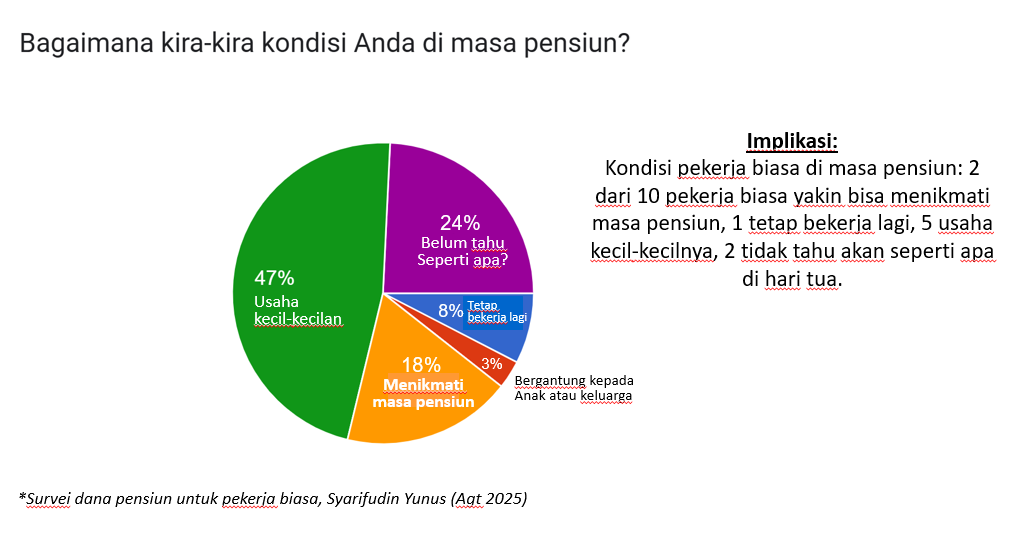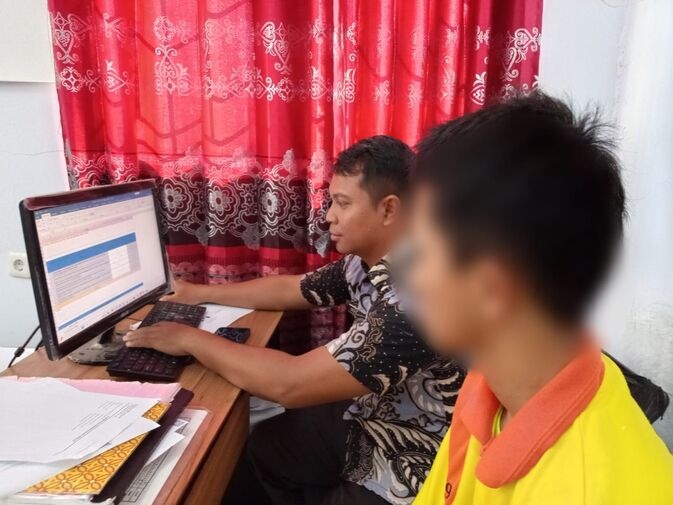Gunoto Saparie lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1955. Aktif dalam dunia literasi, menulis cerita pendek, puisi, novel, dan esai. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit adalah Melancholia (Damad, Semarang, 1979), Solitaire (Indragiri, Semarang, 1981), Malam Pertama (Mimbar, Semarang, 1996), Penyair Kamar (Forum Komunikasi Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, 2018), dan Mendung, Kabut, dan Lain-lain (Cerah Budaya Indonesia, Jakarta, 2019), dan Lirik (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2020). Kumpulan esai tunggalnya Islam dalam Kesusastraan Indonesia (Yayasan Arus, Jakarta, 1986) dan Kiri Islam dan Lain-Lain (Satupena, Jakarta, 2023). Kumpulan cerita rakyatnya Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa Tengah (Pusat Bahasa, Jakarta, 2004). Novelnya Selamat Siang, Kekasih dimuat secara bersambung di Mingguan Bahari, Semarang (1978) dan Bau (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2019) yang menjadi nomine Penghargaan Prasidatama 2020 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.\xd\xd Ia juga pernah menerbitkan antologi puisi bersama Korrie Layun Rampan berjudul Putih! Putih! Putih! (Yogyakarta, 1976) dan Suara Sendawar Kendal (Karawang, 2015). Sejumlah puisi, cerita pendek, dan esainya termuat dalam antologi bersama para penulis lain. Puisinya juga masuk dalam buku Manuel D\x27Indonesien Volume I terbitan L\x27asiatheque, Paris, Prancis, Januari 2012. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Satupena Jawa Tengah juga sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Ketua Komunitas Puisi Esai Jawa Tengah, dan Ketua Umum Forum Kreator Era AI Jawa Tengah. Ia juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, Majelis Kiai Santri Pancasila, dan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Jawa Tengah. Pernah menjadi wartawan, guru, dosen, konsultan perpajakan, dan penyuluh agama madya. Alumni Akademi Uang dan Bank Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang.
Tokoh Lintas Agama Jateng: Republik Lahir dari Kebebasan dan bukan Kekerasan
2 hari lalu
Para tokoh lintas agama dan kepercayaan di Jawa Tengah menyerukan sesuatu yang terdengar lembut: moralitas, tanpa kekerasan, hati nurani.
Oleh Gunoto Saparie
Di depan Gedung DPR, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, mati dilindas kendaraan taktis. Kita tak pernah benar-benar tahu bagaimana tubuhnya rubuh, bagaimana suaranya padam di tengah kerumunan. Tetapi kita tahu: sejak saat itu, sesuatu di dalam tubuh republik ini ikut remuk.
Di hari-hari itu, bulan Agustus, bulan yang selalu diingat sebagai bulan proklamasi, berubah jadi bulan yang getir. Orang turun ke jalan bukan membawa bendera merah putih dengan perayaan, melainkan membawa kemarahan. Mereka tak lagi mendengar pidato, mereka mendengar sirene. Mereka tak lagi menyanyikan Indonesia Raya, mereka berteriak, melempar, membakar.
Dan kemudian datang suara lain: para pemuka lintas agama dan kepercayaan Jawa Tengah yang berkumpul di Keuskupan Agung, Jalan Pandanaran, Semarang, 1 September 2025. Mereka menyebut nama mereka Pelita (Persaudaraan Lintas Agama). Kata itu sederhana: pelita, sebuah lampu kecil di ruang yang gelap. Mereka menyerukan sesuatu yang terdengar lembut: moralitas, tanpa kekerasan, hati nurani.
Tentu kita bisa sinis. Kata-kata “moralitas” sudah lama jadi retorika dalam rapat-rapat, jadi poster di dinding kementerian, jadi khutbah di podium politik. Tetapi mungkin justru karena itu, seruan ini terdengar janggal, sekaligus penting. Sebab negeri ini sedang tenggelam dalam logika kekerasan. Di mana polisi menghadapi warga dengan peluru karet dan gas air mata, warga menjawab dengan batu dan api. Di mana tubuh orang banyak berubah jadi angka statistik.
Moralitas: mungkin ia kini tak lebih dari bisikan samar. Tetapi, bukankah dalam sejarah, bisikanlah yang sering lebih kuat daripada pekik?
Pelita yang dipimpin Setyawan Budy menyebutkan tujuh butir seruan dan ditandatangani 30 tokoh lintas agama dan kepercayaan. Ada apresiasi kepada Presiden, ada imbauan pada aparat agar tak represif, ada ajakan pada mahasiswa agar waspada provokasi, ada kecaman terhadap perusakan. Semua terdengar normatif, dan barangkali tak akan menghentikan batu melayang di udara.
Namun, seruan itu bisa jadi pengingat: republik ini lahir dari gagasan tentang kebebasan, bukan dari kekerasan. Dari kalimat yang ditulis di atas kertas, bukan dari selongsong peluru.
Kita ingat, 80 tahun yang lalu, Soekarno membaca teks proklamasi dengan suara bergetar. Tidak ada tembakan salvo, tidak ada sorak sorai massa yang membakar gedung. Hanya sebuah teks, dan sebuah suara. Tetapi dari situlah lahir sebuah negara.
Mungkin, seruan Pelita ingin mengingatkan kita kembali pada kesederhanaan itu: bahwa republik hanya akan bertahan jika ia kembali berbasis pada kata, bukan kekerasan; pada nurani, bukan privilese. Namun bisakah ia?
Di hadapan kenyataan bahwa kursi parlemen diisi orang-orang yang menaikkan tunjangan mereka sendiri di tengah kemiskinan rakyat, kata “moralitas” bisa terdengar seperti doa yang tak sampai. Tetapi mungkin doa memang begitu: lirih, tak terdengar, namun ia bisa menggerakkan hati seseorang di tengah keramaian. Dan jika hati yang satu itu bergerak, ia bisa menyalakan yang lain, sebagaimana pelita kecil bisa memecah gelap.
Barangkali, di tengah tubuh republik yang memar, kita memang tak punya pilihan lain. Selain percaya pada sesuatu yang samar: bahwa suara yang lirih pun bisa menjadi jalan pulang.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah
Penulis Indonesiana
2 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0






 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 98
98 0
0