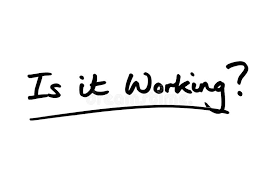Tanah Singgah; Sebuah Monolog
23 jam lalu
Naskah Monolog "Tanah Singgah" merupakan Naskah Karya Rafdisyam, Pernah dipentaskan dalam FLS3N Kota Padang, 2025
TANAH SINGGAH
Monolog
Karya Rafdisyam
SET
Sebuah halte di perbatasan kota, menjelang senja. Cahaya oranye matahari terbenam menyinari sebuah kursi panjang berwarna cokelat kusam. Suara-suara kendaraan berlalu lalang terdengar samar. Langit mulai mendung dengan awan-awan kelabu yang bergerak perlahan.
TOKOH
SARI - Perempuan, 25 tahun. Mengenakan pakaian sederhana namun rapi, blus berwarna biru muda dan rok panjang hitam. Rambut hitam panjang diikat rapi. Wajahnya memancarkan ketegaran meski terlihat lelah.
MAMAK - Laki-laki 50 tahun
AYAH - Laki-laki 45 tahun
MBAK MAISAROH - Perempuan 40 tahun
(SARI memasuki panggung dari sisi kiri dengan langkah pelan namun mantap. Ia membawa sebuah koper besar berwarna cokelat tua dan tas selempang kecil. Tatapannya lurus ke depan.)
SARI
Tanah… (Menggenggam tanah dengan lembut)
Kita semua berasal dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Ada banyak jenis tanah di dunia ini. Tanah lembut, tanah keras, tanah subur, tanah gersang...
Di tanah inilah aku dilahirkan. Di sinilah aku dibesarkan. Di sini pulalah aku diayun dibuai ibuku. Di sini juga aku dimanja oleh ayahku.
Lihat, di sana. Rumah sederhana berhalaman luas itu. Rumah yang dibangun ayahku dengan tangannya sendiri. Dari hasil keringatnya. Dari air matanya.
Ya, walaupun tanahnya punya ibu. Begitu kata mereka. Tepatnya kata Mamakku dulu.
MAMAK
"Rosna, bangunlah di sini, kau. Jadikan tempat berteduh, tempat berlindung, tempat membesarkan Sari. Sasuai jo adaik kita, Ros. Ambo hendak merantau Ros, silakan Ros batagak rumah, Laki kau juga bisa bekerja di ladang kita. Ambo rila jo hati nan lapang, mungko nan janiah."
SARI
Ya, begitulah kata beliau. Aku masih ingat jelas. Ketika itu aku masih kelas 1 SMP. Mamak mempercayakan tanah itu kepada ibu untuk ditempati, untuk dibangun rumah.
(Kembali duduk di kursi, melihat jam tangannya lagi dengan cemas)
Kapan bus itu akan datang?
(Terdengar suara motor mendekat)
Maaf, Pak. Saya tidak memesan ojek.
(Suara klakson mobil)
Maaf, Bang. Saya tidak ikut mobil Abang.
Tujuan? Ya, saya memang tidak punya tujuan.Tidak semua perempuan punya tujuan, Bang. Kami hanya akan merantau ke sumur, ke kasur, ke dapur, Bang. Terima kasih atas tawaran Abang sebelumnya (melambaikan tangan)
Sejujurnya, selain saya memang membela kaum perempuan, kata orang sih feminisme. Tapi saya juga kasihan dengan laki-laki... terutama Ayah.
(Ekspresi berubah lembut, menirukan percakapan dengan ayahnya)
AYAH
"Nak, bantu pijitkan punggung Ayah ini."
"Waktu kita tidak lama lagi, Nak. Besok kita harus berangkat dari rumah ini. Ayah ini seperti abu di atas tungku, tidak punya hak lagi. Meskipun Ayah yang membuat tiang-tiang ini. Ayah yang menjalin setiap besi. Bahkan Ayah juga yang menjalin setiap kenangan di dalamnya."
"Lihat rumah kita, Nak. Sekarang atapnya akan menampung lebih banyak hujan lalu menjatuhkannya ke tanah ini. Atap hanya persinngahan saja agar orang di dalam tidak basah. Namun airnya akan kembali ke tanah.
"Kamu tidak usah menangis lagi... Ayah sudah cukup menangis untuk kita berdua, seperti Ibu, kita juga akan pulang ke tanah. Tidak perlu risau perkara tanah.”
"Besok, semua pusako harus ditinggalkan. Di sini, Ayah hanya meminjam-pakai, tidak ada hak milik Ayah lagi. Ayah titipkanpadamu sebuah pusako yang harus selalu dijaga.. Tidak lebih dan tidak kurang dari budi baik dan elok laku yang sudah Ayah dan Ibu ajarkan selama ini."
(Terdengar suara hujan mulai turun perlahan)
SARI
Dingin ini bukan karena hujan. Bukan juga karena petir barusan. Dingin ini terasa karena terlalu banyak ruang yang kosong tapi berantakan. Hujan atau tangisan, sama saja.
Hari itu memang berat bagiku. Tiga hari yang lalu aku menyelimuti mayat ibu. Aku meneteskan air mata tanpa henti. Banyak orang datang. Mereka menyalami, memeluk, membisikkan kata-kata penghiburan. Tapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan ini.
"Bu, aku dan Ayah ikhlas. Semoga kepergian ini akan menjadi jalan pertemuan kita lagi nanti."
(mamak datang dari rantau)
"Mak... Ibu sudah duluan pulang."
"Apa? A-apa maksud Mamak? Mengapa Aku dan Ayah tidak boleh tinggal di sini lagi?"
"Tapi Mak Dang! Ayah yang membangun rumah ini! Ayah yang bermandi keringat dan air mata membangun semua ini! Apa salahnya kalau kami tetap tinggal di sini?”
"Lantas mengapa Aku tidak berhak mempertahankan hakku juga? Aku hanya butuh kebijaksanaan Mak Dang! Aku tidak ingin melawan mamak di depat mayat Ibu. Tolong hargai Ibu mak, hargai Ayah dan hargai kami yang membangun ini.”
“Mak dang, aku tidak mau mengungkit hal seperti ini, apalagi sekarang. Bahkan modal merantau Mak Dang dulu dicarikan Ayah dan Ibu dari sawah dan ladang yang mereka garap! Ini tidak adil, Mak Dang!"
"Baiklah. Jika kami tidak boleh di sini lagi, bahkan sebelum kering tanah kubur Ibu, kami akan berangkat. Silakan, Mak Dang! Ambil saja semuanya! Dunia punya karma, pusako punya dandi. Tidak akan kuinjak lagi tanah ini.”
Setelah itu aku dan Ayah berkemas. Bersama perasaan yang tercampur rasa kelat. Terasa pahit di mulut, tapi tetap harus ditelan. Meski berdarah-darah, meski tercabik-cabik hati ini.
Di kampungku, tanah adalah pusako tinggi. Diwariskan turun temurun dari nenek moyang. Dari mamak ke kemenakan, dari ibu ke anak perempuan. Laki-laki yang tinggal di rumah istrinya tidak berhak memiliki. Mereka hanya "sumando", orang datang. "Abu di atas tunggul,” bisa diterbangkan kapan saja. Mamak juga tidak berhak memiliki namun boleh mengaturnya.Tapi, aku ini perempuan satu-satunya anak Ibuku. Aku juga tidak tau harus mengajukan tuntutan kepada siapa. Lantas terpaksa aku harus pergi bersama Ayah.
Mungkin kalian bertanya-tanya...
Ya, Ayahku tidak di sini sekarang. kemenakannya datang menjemput pagi tadi.
Aku? Tentu aku tidak ikut. Ayah masih punya kemenakan di kampungnya. Mereka juga berhak atas ayahku. Aku cukup senang dengan itu. Ya, meskipun hanya Ayah satu-satunya yang kumiliki.
Mungkin memang tidak ada tempat untuk anak pisang sepertiku. Makanya aku terdampar di sini, di kursi halte ini. Bukankah seharusnya aku memohon lagi kepada Mak Dang? Mungkin saja, atau kebalikannya. Lihatlah, Sekarang aku tonggak babeleang
Tapi aku tidak berhenti sampai di sini. Sejak kecil ibu mengajarkan untuk selalu mencari jalan, membuka pintu, melompati pagar bila perlu.
(Melihat jam)
Sebentar lagi busnya datang.
Oh iya, tadi Mbak Maisaroh tiba-tiba menelponku.
MBAK MAISAROH
"Sari, Mbak udah dengar semuanya. Yowes, koe kesini wae. Iso kok kerjo nengkene. Kalau mau, jadi mantu juga boleh. Iyo, di sini mantu perempuan boleh kok tinggal di rumah lanang.”
(Terdengar suara klakson bus dari kejauhan)
Ah, itu dia busku.
Aku berharap menemukan rumah yang bukan sekadar singgah, aku ingin rumah untuk pulang, tanah yang bukan sekadar singgah.
Di sini, perempuan tidak merantau. Tapi lihat aku sekarang. Merantau ke tempat yang mungkin bisa kupanggil rumah. Merantau untuk menemukan harga diri. Merantau agar kapalku tidak terombang-ambing di sungai kecil. Tidak semua yang pergi adalah pelarian. Tidak semua yang merantau karena adalah kekalahan. Kadang, merantau adalah pembuktian prinsip. Selamat tinggal Ranah Bundo
SELESAI
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Tanah Singgah; Sebuah Monolog
23 jam lalu
Makan Tubuh
Minggu, 7 Agustus 2022 16:41 WIBArtikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 97
97 0
0