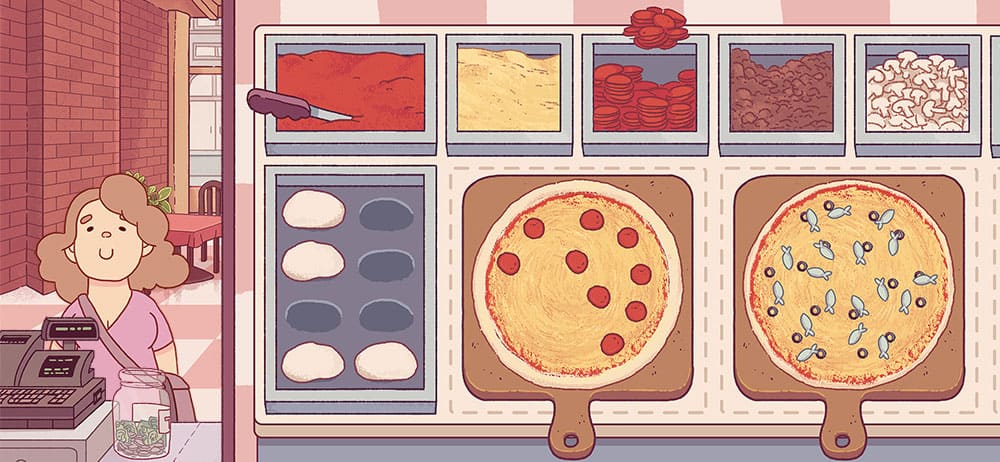Flexing Pejabat di Media Sosial dan Operasi Buzzer
9 jam lalu
Strategi pencitraan atau pelecehan etika?
***
Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi arena utama bagi pejabat publik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, praktik "flexing" atau pamer kekayaan dan gaya hidup mewah oleh pejabat serta keluarganya, serta operasi buzzer—kelompok akun berbayar yang menyebarkan narasi tertentu—telah memicu perdebatan sengit. Apakah ini sekadar strategi pencitraan yang efektif untuk membangun dukungan publik, ataukah bentuk pelecehan etika yang merusak kepercayaan masyarakat? Tulisan ini akan mengupas kedua sisi, berdasarkan fenomena yang marak di Indonesia, di mana kedua praktik ini sering dikaitkan dengan politik dan pemerintahan.
Flexing pejabat merujuk pada kebiasaan memamerkan aset mewah seperti mobil, jam tangan, atau liburan eksklusif di platform seperti Instagram atau X (sebelumnya Twitter). Di Indonesia, kasus ini sering melibatkan pejabat tinggi dan keluarganya, yang dianggap tidak sensitif terhadap kesenjangan sosial. Sementara itu, buzzer adalah akun media sosial berbayar yang digunakan untuk mengamplifikasi pesan, sering kali dengan cara terstruktur untuk memengaruhi opini publik. Mereka bisa menyebarkan narasi positif tentang pejabat atau menyerang kritik, dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah dari proyek pemerintah.
Menurut laporan investigasi, proyek buzzer di Indonesia bisa bernilai hingga Rp 1,4 triliun untuk periode 2024-2025, dengan perusahaan pemenang tender sering kali beroperasi dari lokasi sederhana dan mencurigakan, seperti ruko kosong. Buzzer ini tidak hanya untuk branding produk, tapi juga untuk politik, di mana mereka menciptakan "perang informasi" yang tak terlihat, memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak.
Di satu sisi, flexing dan operasi buzzer dapat dilihat sebagai alat modern untuk pencitraan diri. Pejabat menggunakan media sosial untuk menunjukkan pencapaian, seperti proyek infrastruktur atau kegiatan sosial, yang bisa membangun citra sebagai pemimpin yang sukses dan relatable. Dalam konteks demokrasi digital, buzzer membantu mengcounter serangan informasi palsu atau kritik tidak berdasar, mirip dengan kampanye PR di bisnis. Sebuah postingan di X menyebutkan bahwa buzzer adalah "ikhtiar" untuk mengintervensi pandangan publik terhadap topik tertentu, terutama ketika media tradisional tidak lagi dominan.
Contohnya, buzzer bisa mencapai reach maksimal dengan analisis data canggih, meskipun efektivitasnya tergantung pada kreativitas pesan. Jika dilakukan secara transparan, ini bisa menjadi bentuk engagement yang positif, seperti mempromosikan kebijakan pemerintah tanpa melanggar hukum. Di Indonesia, di mana media sosial adalah sumber informasi utama bagi jutaan warga, strategi ini bisa memperkuat dukungan elektoral, asal tidak berlebihan.
Di sisi lain, praktik ini sering dikritik sebagai pelecehan etika yang merusak. Flexing pejabat dianggap tidak peka terhadap kemiskinan rakyat, menciptakan antipati dan memperlebar kesenjangan sosial. Sebuah postingan di Instagram menyebut flexing sebagai "tumpukan daun kering di musim kemarau," yang bisa memicu ketidakpuasan publik. Rekam jejak digital sulit dihapus, dan flexing bisa menjadi bumerang di kemudian hari, terutama bagi pejabat yang seharusnya menjaga integritas.
Untuk buzzer, isu etika lebih dalam. Mereka sering menyebarkan narasi keraguan, adu domba, atau hoax menggunakan akun bot dengan ciri khas seperti nomor di nama pengguna. Wawancara dengan pengelola agensi buzzer mengungkap bahwa admin mengoperasikan ribuan akun untuk menyerang akun organik yang kritis terhadap penguasa. Ini bisa melanggar hukum jika melibatkan penyebaran informasi palsu, dengan sanksi pidana di Indonesia. Buzzer politik juga membungkam kritik, seperti serangan terhadap akademisi yang mengkritik pemerintah, menciptakan echo chamber di mana pesan hanya bergaung di kalangan pendukung.
Lebih parah, jika dibiayai dana publik, ini menjadi pemborosan dan korupsi terselubung. Investigasi menunjukkan perusahaan buzzer sering anonim, dengan pemegang saham tidak jelas, menimbulkan bau amis. Dalam demokrasi, ini mirip Orde Baru 4.0, di mana buzzer digunakan untuk memoles citra lembaga sambil membungkam suara rakyat.
Dampak negatifnya jelas: erosi kepercayaan publik terhadap pejabat dan pemerintah. Masyarakat semakin antipati terhadap flexing, terutama di tengah ketidakadilan sosial. Buzzer juga gagal jika publik semakin kritis, karena pesan kaku mudah terdeteksi. Namun, buzzer bisa efektif untuk distraksi sementara.
Untuk mengatasi ini, diperlukan regulasi ketat: transparansi anggaran buzzer, larangan flexing bagi pejabat, dan pendidikan literasi digital bagi masyarakat. Pejabat seharusnya fokus pada kanal langsung dengan rakyat, bukan propaganda.
Flexing pejabat dan operasi buzzer bisa menjadi strategi pencitraan jika dilakukan secara etis dan transparan, tapi dalam praktiknya di Indonesia, sering kali melampaui batas menjadi pelecehan etika. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menjaga etik untuk menghindari pelanggaran lebih besar. Pada akhirnya, publik yang semakin sadar akan menentukan: apakah ini alat demokrasi atau senjata manipulasi? Di era informasi terbuka, kejujuran tetap menjadi kunci utama.
Penulis Indonesiana, komisaris dpk gmni up45 Yogyakarta,
2 Pengikut

Keganjilan Logika Keagamaan dalam Fatwa Haram Sound Horeg oleh MUI
Selasa, 29 Juli 2025 09:15 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 93
93 0
0