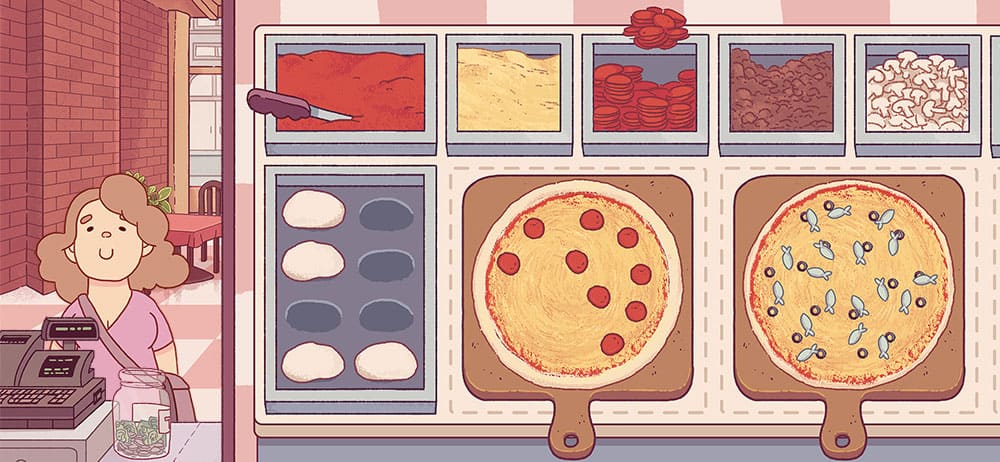Gunoto Saparie lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1955. Aktif dalam dunia literasi, menulis cerita pendek, puisi, novel, dan esai. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit adalah Melancholia (Damad, Semarang, 1979), Solitaire (Indragiri, Semarang, 1981), Malam Pertama (Mimbar, Semarang, 1996), Penyair Kamar (Forum Komunikasi Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, 2018), dan Mendung, Kabut, dan Lain-lain (Cerah Budaya Indonesia, Jakarta, 2019), dan Lirik (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2020). Kumpulan esai tunggalnya Islam dalam Kesusastraan Indonesia (Yayasan Arus, Jakarta, 1986) dan Kiri Islam dan Lain-Lain (Satupena, Jakarta, 2023). Kumpulan cerita rakyatnya Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa Tengah (Pusat Bahasa, Jakarta, 2004). Novelnya Selamat Siang, Kekasih dimuat secara bersambung di Mingguan Bahari, Semarang (1978) dan Bau (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2019) yang menjadi nomine Penghargaan Prasidatama 2020 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.\xd\xd Ia juga pernah menerbitkan antologi puisi bersama Korrie Layun Rampan berjudul Putih! Putih! Putih! (Yogyakarta, 1976) dan Suara Sendawar Kendal (Karawang, 2015). Sejumlah puisi, cerita pendek, dan esainya termuat dalam antologi bersama para penulis lain. Puisinya juga masuk dalam buku Manuel D\x27Indonesien Volume I terbitan L\x27asiatheque, Paris, Prancis, Januari 2012. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Satupena Jawa Tengah juga sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Ketua Komunitas Puisi Esai Jawa Tengah, dan Ketua Umum Forum Kreator Era AI Jawa Tengah. Ia juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, Majelis Kiai Santri Pancasila, dan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Jawa Tengah. Pernah menjadi wartawan, guru, dosen, konsultan perpajakan, dan penyuluh agama madya. Alumni Akademi Uang dan Bank Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang.
Membaca Perkembangan Ekonomi Syariah
8 jam lalu
Indonesia punya potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Penduduk muslim di republik ini terbesar di dunia.
Membaca Perkembangan Ekonomi Syariah
Oleh Gunoto Saparie
Ada sebuah angka yang tertulis di laporan resmi: 47,05 persen. Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional. Angka itu tampak seperti kabar baik. Sebuah pencapaian yang meneguhkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekadar alternatif, melainkan pilar. Tetapi, seperti semua angka, ia hanya penanda. Ia menunjuk, namun tak pernah bisa bercerita sepenuhnya.
Kita bisa berlama-lama dengan grafik yang naik, dengan presentase yang menanjak. Dari 44,13 persen di 2021, naik menjadi 45,66 persen di 2022, lalu 46,71 persen di 2023. Angka-angka itu memberi keyakinan, memberi kesan ada arah yang jelas. Namun, apakah angka itu cukup untuk menyatakan bahwa ekonomi syariah sungguh hidup di keseharian, sungguh berakar di masyarakat, atau sekadar tumbuh di laporan tahunan lembaga?
Ekonomi syariah, sesungguhnya, bukan sekadar tentang sistem finansial. Ia adalah bahasa. Ia lahir dari keyakinan bahwa keadilan bisa dan harus hadir dalam pertukaran. Ia menyiratkan sebuah janji: bahwa pasar tidak perlu tercerabut dari moralitas, bahwa laba tidak perlu dipisahkan dari halal. Maka, ketika sektor ini tumbuh, yang kita saksikan bukan hanya triliunan rupiah aset, melainkan sebuah cita-cita: bahwa perdagangan, investasi, bahkan spekulasi bisa tunduk pada etika. Tetapi pasar selalu punya logikanya sendiri. Ia bergerak mencari efisiensi, mengejar celah, memanfaatkan peluang.
Dari situlah muncul pertanyaan yang tak nyaman: Sejauh mana praktik syariah benar-benar berbeda dari praktik konvensional yang digantikannya? Apakah akad murabahah dalam bank syariah sungguh membedakan dirinya dari kredit biasa, ataukah hanya permainan istilah yang rapi, sekadar mengganti bunga dengan margin?
Di titik inilah kita bisa belajar dari sejarah. Islam klasik mengenal hisbah, sebuah lembaga yang mengawasi pasar. Ia bukan sekadar regulator yang mengatur angka-angka, melainkan juga penjaga moral. Ia memastikan timbangan adil, memastikan harga tidak dimanipulasi, memastikan bahwa yang kuat tidak menindas yang lemah. Pertanyaannya kini: Siapa yang memegang peran itu dalam dunia ekonomi syariah Indonesia? Apakah KNEKS yang bekerja dengan laporan resmi, otoritas pasar modal yang sibuk dengan regulasi, atau algoritma fintech yang bekerja tanpa wajah?
Optimisme tentu sah. Indonesia punya potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Penduduk muslim di republik ini terbesar di dunia. Industri halal yang meluas. Aset keuangan syariah yang mencapai Rp9.927 triliun pada akhir 2024. Semua tampak meyakinkan. Tapi globalisasi datang dengan caranya sendiri: membawa peluang sekaligus residu. Pasar halal internasional bukan sekadar soal makanan dan minuman. Ia juga industri sertifikasi. Ia adalah perdagangan label, perebutan standar, dan kadang permainan politik dagang.
Di titik ini, syariah bisa tumbuh sebagai spiritualitas yang merangkul, atau justru membeku sebagai merek dagang yang dijual. Ada kenyataan lain yang tak selalu terlihat dalam laporan. Seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang meminjam dari koperasi syariah. Seorang anak muda yang memakai aplikasi fintech syariah bukan karena paham akadnya, tapi karena prosesnya lebih cepat. Seorang buruh migran yang menabung di bank syariah karena mendengar katanya “lebih aman”, tanpa pernah benar-benar mengerti bedanya.
Mereka ini tidak muncul di grafik PDB, tetapi merekalah wajah sesungguhnya dari “ekonomi syariah” yang kita rayakan. Dan wajah itu sering kali menyimpan pertanyaan. Apakah koperasi syariah benar-benar memberi ruang adil bagi pedagang kecil, atau sekadar mengganti bunga dengan istilah margin dan bagi hasil? Apakah fintech syariah sungguh memberi peluang bagi yang tak terjangkau bank, atau hanya mempercepat mekanisme utang dengan balutan aplikasi digital? Maka yang paling penting bukanlah angka yang terus naik, melainkan sejauh mana sistem ini menyentuh martabat manusia. Ekonomi syariah bisa hidup sebagai moralitas, bisa juga membeku sebagai industri. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa besar kontribusinya terhadap PDB, melainkan apakah ia benar-benar membawa keseimbangan bagi mereka yang paling rentan.
Sejarah mencatat, pada masa awal Islam, Nabi Muhammad memuji seorang pedagang yang jujur, yang menimbang dengan benar, yang tidak menipu pembeli. Itu adalah potret sederhana ekonomi syariah: sebuah etika yang melampaui angka. Jika hari ini kita bicara tentang Rp980,3 triliun aset perbankan syariah, atau Rp8.559,5 triliun pasar modal syariah, kita tetap harus ingat potret sederhana itu.
Karena pada akhirnya, ekonomi syariah, seperti ekonomi apa pun, tidak hanya tentang pertumbuhan. Ia adalah tentang keadilan. Ia adalah tentang janji bahwa jual-beli tidak melahirkan penindasan, bahwa investasi tidak hanya menambah kekayaan segelintir orang, bahwa keuntungan tidak harus berarti kerugian orang lain. Statistik bisa menandai arah. Tetapi suara hati manusia kecil, yang sehari-hari bergulat dengan harga, utang, dan rezeki, yang menentukan apakah arah itu sungguh berarti.
Ekonomi syariah bisa menjadi pusat baru global. Tetapi ia hanya akan menjadi berarti jika tetap berpijak pada hal yang paling sederhana dan paling sulit: keadilan yang hidup dalam keseharian.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah
Penulis Indonesiana
3 Pengikut

Membaca Perkembangan Ekonomi Syariah
8 jam lalu
Catatan atas Program Paket Ekonomi 2025
3 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 91
91 0
0