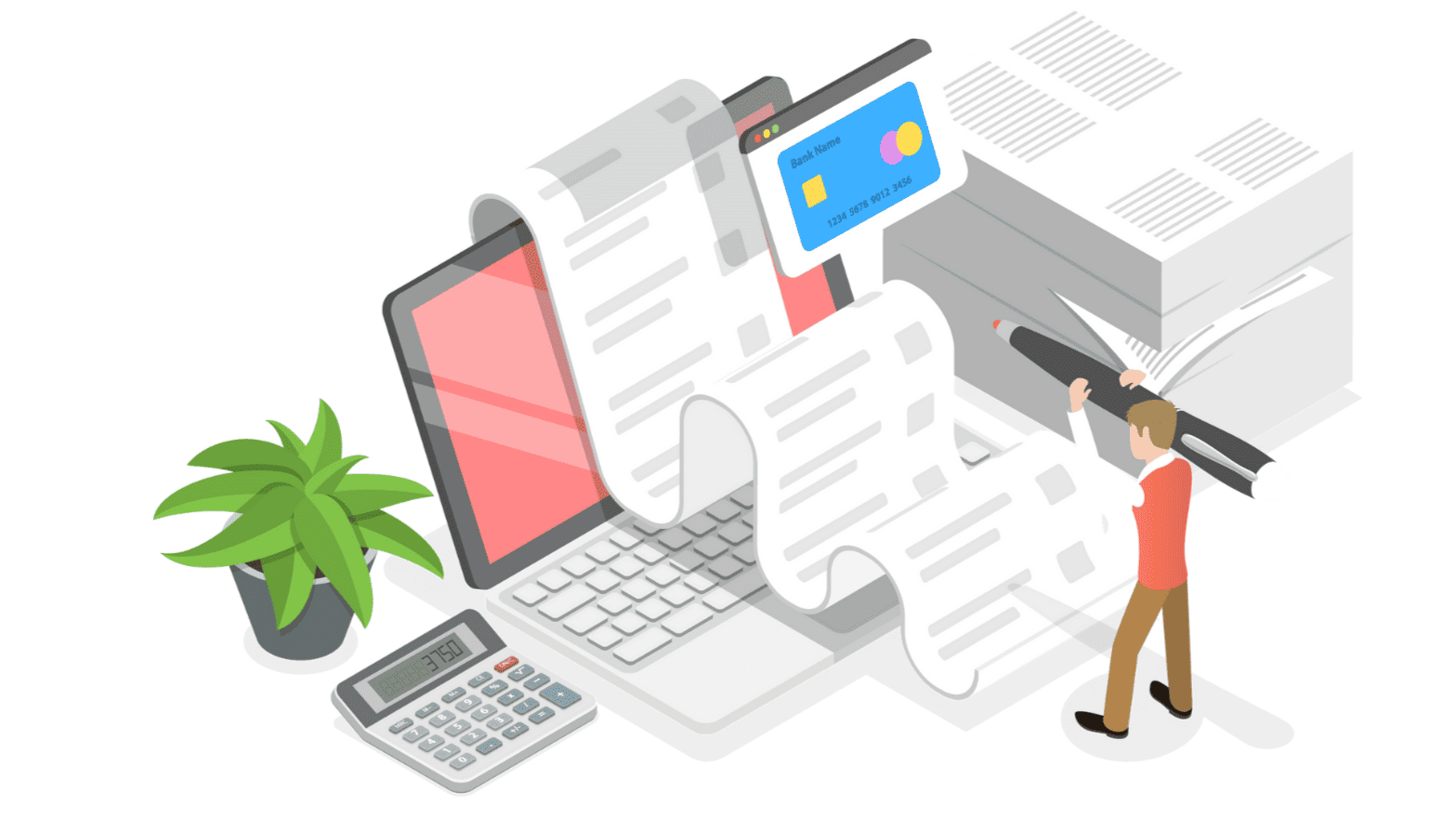Gunoto Saparie lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1955. Aktif dalam dunia literasi, menulis cerita pendek, puisi, novel, dan esai. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit adalah Melancholia (Damad, Semarang, 1979), Solitaire (Indragiri, Semarang, 1981), Malam Pertama (Mimbar, Semarang, 1996), Penyair Kamar (Forum Komunikasi Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, 2018), dan Mendung, Kabut, dan Lain-lain (Cerah Budaya Indonesia, Jakarta, 2019), dan Lirik (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2020). Kumpulan esai tunggalnya Islam dalam Kesusastraan Indonesia (Yayasan Arus, Jakarta, 1986) dan Kiri Islam dan Lain-Lain (Satupena, Jakarta, 2023). Kumpulan cerita rakyatnya Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa Tengah (Pusat Bahasa, Jakarta, 2004). Novelnya Selamat Siang, Kekasih dimuat secara bersambung di Mingguan Bahari, Semarang (1978) dan Bau (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2019) yang menjadi nomine Penghargaan Prasidatama 2020 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.\xd\xd Ia juga pernah menerbitkan antologi puisi bersama Korrie Layun Rampan berjudul Putih! Putih! Putih! (Yogyakarta, 1976) dan Suara Sendawar Kendal (Karawang, 2015). Sejumlah puisi, cerita pendek, dan esainya termuat dalam antologi bersama para penulis lain. Puisinya juga masuk dalam buku Manuel D\x27Indonesien Volume I terbitan L\x27asiatheque, Paris, Prancis, Januari 2012. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Satupena Jawa Tengah juga sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Ketua Komunitas Puisi Esai Jawa Tengah, dan Ketua Umum Forum Kreator Era AI Jawa Tengah. Ia juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, Majelis Kiai Santri Pancasila, dan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Jawa Tengah. Pernah menjadi wartawan, guru, dosen, konsultan perpajakan, dan penyuluh agama madya. Alumni Akademi Uang dan Bank Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang.
Komunitas Sastra Bulan Purnama 14 Tahun
3 jam lalu
Masa 14 tahun bukan waktu singkat bagi komunitas sastra yang hidup tanpa banyak sponsor, tanpa agenda politik, tanpa pamrih...
Oleh Gunoto Saparie
Ada sesuatu yang selalu datang dengan kesetiaan pada waktu tertentu: bulan purnama. Ia datang tanpa gegap gempita, tapi cukup untuk membuat langit jadi terang dan manusia berhenti sejenak, memandang, merenung. Barangkali karena itu, sebuah komunitas sastra di Yogyakarta memilih nama itu: Sastra Bulan Purnama (SBP). Di bawah kepemimpinan Ons Untoro, komunitas ini telah berumur 14 tahun.

Gunoto Saparie. Foto: Tulus Wijanarko
Tidak muda lagi, tetapi juga belum tua. Umur yang cukup matang untuk melihat ke belakang dan bertanya: apa yang sesungguhnya telah kita lakukan bagi kesusastraan? Setiap bulan, sejak 2011, SBP menggelar acara pembacaan puisi, peluncuran buku, diskusi, dan dialog kebudayaan. Kadang di panggung terbuka Tembi Rumah Budaya, kadang di ruang-ruang yang lebih kecil tapi akrab, tetapi kini lebih sering di Museum Sandi. Dari sanalah, nama-nama penyair, cerpenis, dan esais dari berbagai kota datang, membawa kata-kata yang ingin dibagikan ke langit Yogyakarta. Mungkin di antara mereka tak semua besar namanya, tetapi semua percaya bahwa sastra adalah ruang yang memberi napas bagi hidup.
Goenawan Mohamad pernah mengatakan bahwa yang disebut “komunitas” adalah tempat di mana kata-kata bisa hidup bersama waktu. SBP adalah salah satu buktinya. Ia bukan sekadar forum pembacaan puisi; ia adalah ruang ingatan kolektif, tentang bagaimana sebuah masyarakat kecil masih percaya pada kekuatan kata. Di tengah dunia yang makin berisik oleh algoritma dan komentar singkat, mereka masih percaya pada kalimat panjang, pada bait yang dicipta dengan kesabaran. Tetapi setiap komunitas juga membawa beban: antara gairah dan keletihan, antara idealisme dan kenyataan.
Kekuatan SBP adalah konsistensinya. Empat belas tahun bukan waktu singkat bagi komunitas sastra yang hidup tanpa banyak sponsor, tanpa agenda politik, tanpa pamrih lain selain mempertemukan orang-orang yang mencintai kata. Ons Untoro, dengan ketekunan yang jarang, memelihara api itu. Di tangan orang lain, barangkali api itu sudah padam sejak lama.
Namun kekuatan itu juga sekaligus menjadi sumber kelemahannya. Ketergantungan pada figur sentral bisa menjadi persoalan. Komunitas yang tumbuh karena satu sosok sering kehilangan arah ketika sosok itu letih atau pergi. Dalam SBP, Ons Untoro adalah roh yang menjaga keseimbangan antara estetika dan keorganisasian. Tetapi seperti bulan purnama, ia pun punya fase: kadang penuh cahaya, kadang redup. Dan komunitas yang sehat seharusnya bisa bersinar juga ketika bulan itu tak lagi muncul di langit.

Lastri Fardani Sukarton. Foto: Tulus Wijanarko
Di luar persoalan itu, SBP menghadapi tantangan lain: perubahan cara orang berhubungan dengan sastra. Di era media sosial, banyak penulis muda lebih tertarik menulis status puitis di Instagram daripada membaca puisi di panggung. Mereka mengukur karya dengan jumlah “like”, bukan kedalaman makna. Dalam situasi semacam itu, komunitas sastra tradisional seperti SBP sering tampak berjalan lambat. Tetapi justru dalam kelambatan itu, mungkin tersimpan nilai. Ia memberi ruang bagi kontemplasi, bagi kesetiaan kepada bentuk, bagi hubungan manusia yang lebih nyata.
Namun tentu saja, tak cukup hanya setia. Komunitas juga harus hidup, harus beradaptasi. SBP perlu membuka diri terhadap cara-cara baru dalam memaknai sastra: digitalisasi karya, pementasan daring, kolaborasi lintas disiplin: musik, film, rupa, bahkan teknologi. Sastra tak harus tinggal di panggung; ia bisa hadir di layar, di jalan, di ruang publik mana pun yang bersedia mendengarkan. Tetapi yang paling penting bukan bentuknya, melainkan semangatnya. SBP harus terus menjaga semangat keterbukaan: menerima siapa pun yang ingin menulis, membaca, atau sekadar mendengarkan.
Karena yang membuat komunitas hidup bukan karya besar, tapi keberlanjutan percakapan. Dalam percakapan itu, lahir rasa saling percaya. Kreativitas, seperti bulan, membutuhkan siklus: muncul, redup, lalu muncul kembali. Ia tak bisa dipaksa, tapi bisa disiapkan.
Komunitas seperti SBP sebaiknya menjadi tempat di mana siklus itu dijaga. Tempat di mana penulis muda tak sekadar tampil, tapi juga belajar. Di mana kritik hadir bukan untuk menjatuhkan, namun untuk mengasah. Di mana para penyair senior tak hanya dibacakan karyanya, tetapi juga mendengarkan yang muda.
Empat belas tahun adalah waktu yang cukup untuk menegaskan jati diri. SBP telah membuktikan bahwa sastra masih bisa hidup tanpa hiruk-pikuk industri. Tetapi di masa depan, SBP dan komunitas sastra lain harus berani menyeberang: dari sekadar peristiwa menjadi gerakan, dari pembacaan menjadi penciptaan bersama. Karena pada akhirnya, sastra adalah tentang manusia. Tentang kesanggupan kita menyuarakan yang tak bisa dikatakan dengan cara lain.
Komunitas hanyalah wadah, tempat kata-kata mencari makna kolektifnya. Jika SBP bisa terus menjadi tempat di mana makna itu tumbuh, maka 14 tahun hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Seperti bulan purnama yang datang setiap waktu, semoga SBP terus bersinar, kadang terang, kadang temaram. Tetapi selalu hadir, menjadi penanda bahwa kata-kata masih punya tempat di bawah langit Yogyakarta.
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah.
Penulis Indonesiana
3 Pengikut

Komunitas Sastra Bulan Purnama 14 Tahun
3 jam lalu
Sastra, Kesehatan Mental, dan Harapan
2 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 97
97 0
0