Praktisi ISO Management System and Compliance. Blog tentang ISO 9001, SIO 14001, ISO 45001 dan ISO 45001 pada https://www.effiqiso.com/. Menulis Buku :Best Practice for Maintaining ISO 50001 Certification, \xd\xd ISO 9001:2015 A Practical Storytelling Guide for Newcomers, \xd\xd Maintaining Mental Health in the Digital Era.
Merasa Pikiran dan Tubuh Terpisah? Begini Rasanya Saat Kita Menjadi Utuh
2 jam lalu
Di tengah kesibukan, banyak dari kita hidup terpisah dari tubuh. Simak refleksi tentang bagaimana kembali merasa utuh di dunia yang serba cepat
Oleh Bambang RIYADI
Saat duduk di kantor, saya mengetik laporan. Tapi rasanya seperti hanya tangan saya yang bergerak. Saya tidak benar-benar hadir. Seperti ada jarak antara diri saya yang duduk di kursi dan “saya” yang menyaksikan dari kejauhan. Seolah pikiran saya melayang, sementara tubuh sekadar menjalankan rutinitas.
Anda pernah merasa seperti ini?
Banyak dari kita mengalaminya — tanpa sadar. Perasaan terputus dari tubuh, seolah hidup dalam kepala sendiri, memandangi dunia melalui jendela pikiran. Ini bukan gangguan aneh. Ini adalah gejala umum dari dunia modern: stres kronis, digitalisasi berlebihan, dan gaya hidup yang mengutamakan produktivitas di atas kemanusiaan.
Dalam artikel yang dimuat The Guardian, psikolog dan penulis Sarah Wilson menyebut fenomena ini sebagai “living in your head” — hidup di kepala, bukan di tubuh. Dan jalan pulang menuju keutuhan, katanya, bukan lewat lebih banyak kerja keras, tapi lewat kehadiran, ketenangan, dan pengalaman menjadi manusia secara utuh.
Tubuh Bukan Kendaraan, Tapi Rumah
Kita sering memperlakukan tubuh seperti mobil: bensinnya (makanan), oli-nya (istirahat), dan mesinnya (otot) harus diganti saat rusak. Tapi kita jarang mendengarkannya saat ia berbicara — lewat rasa pegal, sesak napas, atau insomnia.
Padahal, tubuh adalah sistem komunikasi paling canggih yang kita miliki. Ia menyimpan ingatan emosional, merespons stres sebelum pikiran menyadarinya, dan memberi tanda bahaya jauh sebelum penyakit muncul.
Namun, dalam budaya kerja yang mengagungkan multitasking, kita dilatih untuk mengabaikan tubuh:
- Makan sambil bekerja.
- Tidur dengan ponsel di tangan.
- Menahan buang air demi rapat online.
- Berpura-pura baik-baik saja padahal hati sedang hancur.
Akibatnya? Disosiasi ringan: perasaan terpisah dari diri sendiri, seperti sedang menjalani hidup dalam mode otomatis.
“Saya bisa bekerja 12 jam tanpa istirahat. Tapi begitu pulang, saya kosong. Tidak merasa apa-apa,” kata Dina, pekerja kreatif di Jakarta.
Ini bukan kekuatan. Ini alarm darurat dari sistem saraf kita.
Ketika Otak Mengambil Alih, Jiwa Tertinggal
Otak kita, terutama bagian prefrontal cortex, sangat hebat dalam merencanakan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Tapi ia juga mudah jadi tiran.
Ia terus-menerus berkata:
- “Harus lebih produktif.”
- “Jangan gagal.”
- “Orang lain pasti lebih baik dari kamu.”
Dalam prosesnya, emosi, intuisi, dan rasa nyaman dihilangkan dari persamaan. Kita menjadi makhluk rasional tanpa akar — seperti pohon yang tumbuh tinggi, tapi akarnya dangkal.
Psikoterapis sensorik-integratif seperti Dr. Peter Levine menyebut bahwa trauma, stres, dan tekanan sosial membuat kita ‘melarikan diri’ dari tubuh. Tubuh dianggap tempat sakit, malu, atau kelemahan. Maka kita mundur ke zona aman: pikiran.
Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Ia akan bicara — lewat migrain, maag, nyeri punggung, atau gangguan tidur.
Jalan Pulang: Menjadi Utuh Lagi
Menjadi utuh bukan berarti selalu merasa bahagia. Ini tentang kembali ke hubungan yang sehat dengan diri sendiri — pikiran, tubuh, dan jiwa yang bekerja bersama, bukan saling bertentangan.
Bagaimana caranya?
1. Mulai dengan Napas
Napas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Coba sekarang: tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan perlahan selama 6 detik.
Ulangi lima kali. Apa yang terjadi? Anda mulai hadir. Dunia sekitar terasa lebih nyata. Ini bukan meditasi ajaib — ini ilmu saraf: napas lambat menenangkan sistem saraf simpatis (fight-or-flight).
2. Sentuh Dunia Nyata
Gosok ujung jari Anda di permukaan meja. Rasakan teksturnya. Pegang secangkir kopi. Perhatikan panasnya yang merambat ke telapak tangan. Inilah yang disebut grounding: teknik sederhana untuk kembali ke tubuh.
Penelitian membuktikan, orang yang rutin melakukan grounding — menyentuh tanah, memegang objek, merasakan angin — memiliki tingkat kecemasan lebih rendah.
3. Gerakkan Tubuh, Tanpa Tujuan
Tidak harus olahraga berat. Cukup gerakkan tubuh tanpa tujuan performa: goyangkan pinggul, regangkan tangan, berjalan pelan tanpa tujuan.
Dalam budaya Barat, gerak selalu dikaitkan dengan hasil: bakar kalori, bentuk otot, capai target. Tapi tubuh butuh gerak untuk menyalurkan energi emosional, bukan untuk prestasi.
4. Biarkan Emosi Ada, Tanpa Harus Memperbaikinya
Ketika sedih, jangan buru-buru mencari solusi. Duduk saja bersamanya. Rasakan di mana ia berada di tubuh Anda: di dada? tenggorokan? perut?
Emosi bukan musuh. Ia adalah informasi. Ia berkata: “Ada sesuatu yang perlu diperhatikan.”
5. Batasi Konsumsi Digital yang Memicu Disosiasi
Scroll media sosial tanpa henti, binge-watching serial, atau kerja berjam-jam di depan layar — semua ini membuat kita semakin terpisah dari tubuh.
Cobalah digital detox singkat: 30 menit tanpa ponsel setelah bangun tidur, atau makan siang tanpa layar.
Keutuhan Bukan Tujuan, Tapi Proses
Menjadi utuh bukan berarti kita akan selalu merasa “baik”. Ada hari-hari ketika kita kembali terjebak di kepala, stres, atau ingin kabur dari realitas. Itu manusiawi.
Yang penting, kita punya jalan pulang.
Seperti yang ditulis Sarah Wilson: "We are not broken. We are fragmented. And fragments can be gathered."
Kita tidak rusak. Kita terpecah. Dan pecahan-pecahan itu bisa dikumpulkan kembali.
Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk cepat, produktif, dan sempurna, menjadi utuh adalah bentuk perlawanan yang lembut. Ia adalah pilihan untuk:
- Merasa lapar, dan makan.
- Merasa lelah, dan berhenti.
- Merasa sedih, dan menangis.
- Merasa senang, dan tertawa tanpa malu.
Penutup: Hidup Bukan di Layar, Tapi di Dalam Tubuh
Kita hidup di era di mana identitas dibentuk oleh likes, followers, dan pencapaian digital. Tapi kehidupan yang sesungguhnya — rasa hangat matahari pagi, pelukan yang menenangkan, napas lega setelah menangis — semuanya terjadi di dalam tubuh.
Maka, jika Anda merasa terpisah dari diri sendiri, itu bukan kegagalan. Itu adalah undangan.
Undangan untuk kembali.
Untuk merasakan.
Untuk hadir.
Karena manusia sejati bukan yang paling pintar atau paling sukses. Tapi yang berani merasakan hidup sepenuhnya — sampai ke ujung jemari kakinya.
Penulis Indonesiana
1 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0









 98
98 0
0


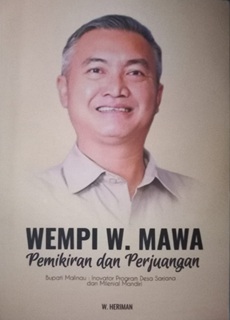


 Berita Pilihan
Berita Pilihan







