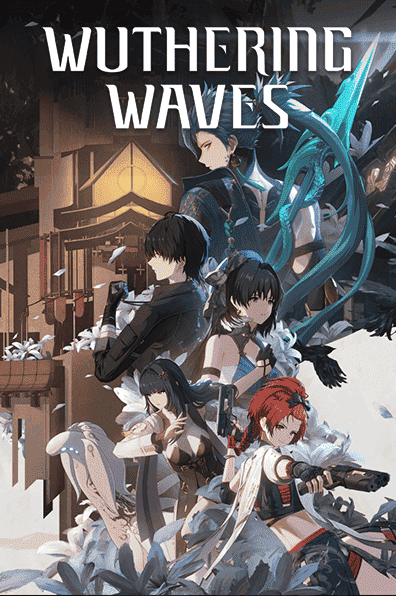Menari di Hadapan Maut
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Catatan tentang sosok, kiprah dan pikiran sastrawan Gerson Poyk.
Bagi seorang yang berusia senja, lawatan ke berbagai tempat barangkali serupa nostalgia mengenang masa-masa yang telah lewat. Ingatan akan pengalaman-pengalaman yang lalu bermunculan. Terlebih bila bertemu karib lama, peristiwa-peristiwa indah di waktu dulu seolah hadir kembali dan belum sekalipun dilupakan. Mungkin, hal itu pula yang dialami Gerson Poyk, sastrawan kelahiran Ba’a, sebuah kota kecil di pedalaman Pulau Rote NTT, dalam kunjungannya ke Bali pada akhir bulan Januari 2012.
“Saya menyadari, hadirnya saya di sini adalah bagian dari proses berkesenian saya. Beruntung saya pernah mukim di Bali, dan bertemu kawan-kawan yang memperkaya kreativitas saya,” tambahnya sambil menyebut beberapa nama sahabat seperti dramawan Abu Bakar, cerpenis Agus Vrisaba, kartunis Wayan Sadha, penyair Umbu Landu Paranggi, budayawan Jean Couteau serta lain sebagainya.
Namun, tentu amat terlampau sederhana bila kita memaknai kehadiran Gerson sebagai nostalgia semata. Selama diskusi di Bentara Budaya Bali, yang dilanjutkan kembali pada dialog di kediaman dramawan Abu Bakar, Gerson bukan hanya menguraikan pertemuannya dengan para sahabat, akan tetapi juga memberikan perspektifnya terkait hakikat menulis. Baginya, menulis adalah cerminan kepedulian terhadap kehidupan. “Menjadi pengarang yang baik, itu mudah sekali. Cukuplah dengan memahami dan menghayati keseharian, hingga akhirnya kita menemukan, apakah masalah-masalah manusia yang paling utama. Hal itulah yang harus kita tulis,” ungkap Gerson.
Adalah menarik bila pendapat ini disampaikan oleh seorang pengarang yang belum lama merayakan usianya yang ke-80 tahun. Setiap pandangannya tentulah merupakan buah dari pergulatan kreatifnya selama ini. Dan Gerson memang dikenal sebagai seorang penulis yang total berkesenian, baik dalam laku sehari-hari ataupun tecermin melalui karya-karyanya. Tokoh-tokohnya bukan sekadar melakoni kisahan rekaannya, namun juga hadir menjadi refleksi atas kenyataan sebenarnya yang dialami manusia: kemiskinan, sosok-sosok terpinggirkan, hingga renungan-renungan akan absurditas dunia kita.
Gerson mengakui bahwa hampir semua karya-karyanya merupakan hasil kontemplasi atas pengalamannya selama ini. Lahir tahun 1931 di pedalaman Pulau Rote, sebuah daerah terpencil di bagian timur Indonesia, Gerson tumbuh dalam kondisi serba sulit. Mulai dari tak mudahnya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, melewati masa-masa penjajahan, hingga keterlambatan menamatkan pendidikan oleh karena perubahan sistem kolonial. Belum sampai di situ, upayanya meraih eksistensi juga diuji ketika Gerson merantau ke luar NTT. Ia jadi jurnalis, yang kemudian ditinggalkannya demi pilihan sebagai penulis.
Dari pengalaman tersebut, diperkaya oleh pengetahuan melalui buku-buku, Gerson menyadari panggilannya sebagai pengarang. “Menulis untuk eksistensi tidak sama dengan menulis demi menyelami persoalan-persoalan esensial manusia. Selama ini kita telah lupa akan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kehidupan, serta terlalu banyak mengejar keinginan. Nurani dikalahkan naluri. Akal sehat dikesampingkan demi tujuan sesaat,” ujarnya sembari menambahkan kondisi berbangsa Indonesia era kini sebagaimana yang ditampilkan di media-media massa.
Pandangan dari peraih Hadiah Adinegoro tahun 1985 dan 1986 ini boleh jadi merupakan respon atas kondisi sosial budaya Indonesia selama kurun waktu belakangan. Seolah sebagai bagian dari penegakan demokrasi, elite politik saling adu pendapat. Kerap juga disertai bantah, kilah dan dalih, dan bahkan kemudian saling beradu konflik. Di sisi lain, silang pandangan itu ditampilkan dengan sudut pandang media masing-masing, yang seakan-akan menghadirkan kenyataan yang sesungguhnya, namun sejatinya dirancang demi kepentingan tertentu. Demokrasi hadir bagaikan sasana tinju, yakni siapa yang paling kuat bertarung, ke sanalah lampu panggung menuju.
Namun demokrasi adalah proses panjang. Ia bisa terkesan menjemukan oleh karena jauhnya jalan guna sampai ke tujuan, demikian Frans Magnis Suseno pernah menulis. Bertarung dalam sasana seperti ini tentu masih lebih baik dibandingkan pertikaian di jalan-jalan yang pasti lebih banyak memakan korban. Demokrasi, tambahnya, harus ditempuh setahap demi setahap, bukan dengan revolusi yang seolah bagaikan jalan pintas, namun berdampak kontraproduktif bagi negeri ini.
Dalam dua kali dialog, Gerson selalu menekankan pentingnya kesadaran manusia untuk berpegang pada hukum moral dan kemanusiaan. “Bila Kant mengutarakan bahwa kekuatan iman menjembatani akal dan pengalaman manusia untuk sampai kepada Tuhan, saya punya rumus sendiri. Iman diperkuat oleh cinta. Dan cinta akan diperteguh karena kerja. Yang melandasi semuanya adalah moral dan martabat luhur sebagai manusia,” tambah Gerson.
Absurditas Gerson
Di usianya yang ke-80 tahun, hal apakah yang hingga kini masih dirasa membayangi setiap pikiran dan tindakannya?
“Ada dua hal, yakni maut dan waktu,” katanya. “Setiap pagi datang, kita dikepung sensasi absurd. Ada kecelakaan mobil menewaskan sekian orang, dan kita tak pernah tahu di mana letak salah para korban. Mereka hanya tewas, begitu saja. Inilah keabsurdan kita, yang tak pernah bisa ditolak.”
Gerson kerap mempertanyakan, mengapa manusia harus bertambah tua. Namun, dengan ringan ia menambahkan bahwa mungkin di sanalah letak hakikat sebagai umat Tuhan. Dengan menyadari kenyataan itu, ujarnya, manusia tak harus merasa bersedih dan berputus asa.
“Ya, kita tertawa saja. Untuk apa kita punya laut kaya dan bumi subur kalau tidak kita hayati dan nikmati? Manusia memang mesti meraih segala sesuatu yang diinginkan, entah itu eksistensi, kekayaan ataupun sebagainya. Namun, saya kira, hendaknya itu tidak dilakukan secara berlebih. Tujuannya agar kita sama-sama bisa berbagi,” ujarnya riang sembari menuturkan pengalaman kebersamaannya selama di Bali pada era 1970-1980-an dengan para seniman ataupun sahabat-sahabatnya yang lain.
Agaknya, Gerson memang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Pengalaman-pengalaman pahitnya di masa lalu, tidak mendorongnya untuk mengabaikan kenangan-kenangan indah ataupun membagikan kebahagiaan tak bersudah kepada semua orang. Karya-karya Gerson memang mengangkat tema-tema sosial, seperti ditunjukan kumpulan cerpennya Di Bawah Matahari Bali (1982). Namun, peliknya kehidupan tokohnya dituturkan dengan sedemikian unik, sehingga mengundang pembaca untuk menertawakan pelbagai masalah, dan juga dirinya sendiri. Ya, Gerson barangkali telah sampai pada hakikatnya sebagai penulis, dan sembari mengakhiri diskusi ia berujar lagi, “Kalau memahami dan memaklumi apa yang terjadi sehari-hari, batin kita akan tenteram. Dan kita pun kemudian merasa ringan, hingga seolah-olah bisa menari di depan maut.”
(Sumber foto: purnamarisa.wordpress.com)
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Di Ketinggian Penjara Lampau
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Lumut Mengikis Batuan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0