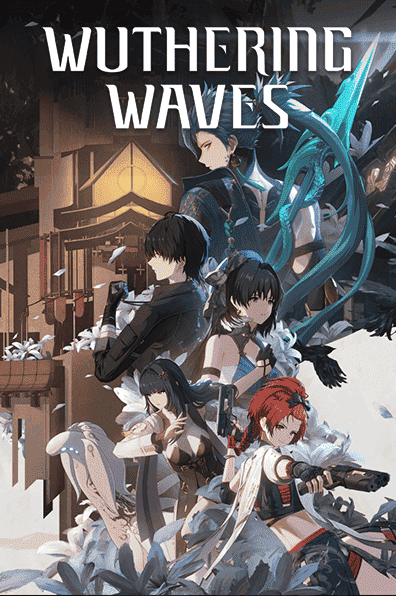Kapitalisme Terjebak Krisis?
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Berulang kali ekonomi kapitalistik menghadapi krisis. Paham ini dianggap memiliki kelemahan fundamental di dalam dirinya sendiri.
"Under capitalism, man exploits man. Under communism, it's just the opposite."--John Kenneth Galbraith (Ekonom, 1908-2006)
“Keserakahan itu baik,” kata Gordon Gekko. Frasa yang terucap dari mulut tokoh antagonis yang diperankan oleh Michael Douglas dalam film Wall Street (1980-an) ini adalah cermin tegas dari perangai orang-orang kaya yang menambang uang dari bursa saham dan pasar uang dunia itu. Di dunia Manhattan yang gemerlap, keserakahan yang terang-terangan bukan lagi hal yang memalukan. Keserakahan dikenakan dengan bangga bak kemeja, dasi, dan jas bermerek terkenal.
Keserakahan itulah yang telah menjerembabkan Lehman Brothers dan Merrill Lynch (ambruk pada 2008 dalam usia hampir 160 tahun) dan sejumlah perusahaan besar lain di dunia keuangan. Ambruknya sejumlah korporasi ini menyeret pemerintah AS untuk mengambil langkah penyelamatan, seolah “apa yang baik bagi Wall Street, baik pula bagi Amerika.” Di tengah krisis, keserakahan yang menjadi watak para kapitalis besar tak juga lenyap. Ketika itu, para eksekutif puncak sibuk memasukkan dolar dana talangan pemerintah ke kantong mereka sendiri.
Berusaha bangkit dari keterpurukan tak ubahnya mengangkat batu ke puncak bukit. Ratusan juta orang tak kunjung menikmati kepulihan, dihadang oleh interes politik dan bisnis. Kesabaran pada akhirnya mencapai batasnya. Puluhan ribu orang Amerika turun ke jalan-jalan di kota New York dan kota-kota lain di AS, dan bagai virus menyebar ke Eropa.
Mereka menentang keserakahan korporasi. Mereka menyebut diri “kaum 99 persen”, sebuah representasi dari mayoritas warga AS yang menderita akibat perbuatan “kaum 1 persen”, yakni para politikus, pengusaha, dan pemimpin perusahaan—orang-orang yang direpresentasikan oleh tokoh Gordon Gekko.
Gerakan “Occupy Wall Street” adalah respon masyarakat kebanyakan atas situasi yang digambarkan oleh Richard Posner telah beranjak dari resesi menuju depresi. Sebagian ekonom mencemaskan bahwa situasinya bahkan lebih buruk dari Depresi Besar 1930. Ada kecemasan, krisis akan segera merembes ke wilayah-wilayah lain jika Eropa tak mampu melokalisasi masalahnya dan negara lokomotif ekonomi dunia (China, India) tak sanggup menanggung bebannya.
Sangat menarik bahwa dalam bukunya, A Failure of Capitalism (2009), Posner berargumen bahwa “penyebab utama depresi bukanlah pemerintah, politikus, atau pun para bankir, melainkan cacat di dalam sistem kapitalis itu sendiri.” Sebagai penganjur pasar bebas yang mashur, Posner menyampaikan pernyataan yang mengagetkan: “Krisis finansial ini lebih merupakan krisis kapitalisme ketimbang kegagalan pemerintah.”
Thomas Piketty dalam bukunya yang terbit tahun ini, Capital in the Twenty-First Century, juga menyebutkan bahwa kapitalisme mengandung kelemahan di dalam dirinya sendiri sehingga kesenjangan di negara-negara yang menganut paham ini semakin melebar. Di Indonesia, Indeks Gini terus meningkat, yang menandakan kesenjangan semakin tinggi. Badan Pusat Statistik menyebut angka 4,1 pada 2013, lebih tinggi dibandingkan sebelum 2010 (berkisar 0,33-0,38). Maknanya, yang kaya bertambah kaya meninggalkan yang miskin semakin jauh.
Krisis finansial yang melanda AS dan Eropa memicu kembali perdebatan tentang sistem ekonomi apa yang mampu memberikan manfaat terbesar kepada sebanyak-banyaknya orang. Barangkali benar apa yang dikatakan Nobelis ekonomi Joseph Stiglitz bahwa boleh jadi tidak ada pemenang dalam krisis ekonomi sekarang. Yang ada hanyalah pecundang. Dan di antara pecundang terbesar, kata Joseph Stiglitz, ialah yang mendukung kapitalisme gaya-Amerika.
Sebagaimana Posner, Stiglitz mengatakan bahwa pelajaran yang dapat ditarik oleh negara-negara Dunia Ketiga dari krisis finansial ialah bahwa kapitalisme secara fundamental cacat (Vanity Fair). Keserakahan kelompok 1 persen bukan hanya menyulitkan kehidupan kelompok 99 persen, tapi juga menimbulkan malapetakan di belahan lain Bumi ini. Kaum miskin sangat menderita di bawah rezim “fundamentalisme pasar”. Tidak ada trickle-down economics, yang ada trickle-up economics.
Krisis berkepanjangan kali ini membuat banyak orang mempertanyakan ketepatan apa yang diproklamasikan oleh Francis Fukuyama sebagai “akhir sejarah”. Sejak Tembok Berlin dirobohkan pada 1989, yang menandai runtuhnya Komunisme di Eropa Timur, seolah-olah ini berarti kemenangan Kapitalisme, khususnya dalam kapitalisme bentuk Amerika. Seandainya pun ini disebut sebagai kejayaan Amerika, maka kejayaan ini membentang dalam periode yang pendek karena pada 2007 negeri adidaya ini memperlihatkan tanda-tanda kemundurannya. Ini bukan sekedar kegagalan pemerintah (jika memang harus ada yang disalahkan), melainkan—seperti dikatakan oleh sejumlah very mainstream economists di AS—sebuah krisis kapitalisme.
Krisis ini, dalam pandangan Richard Sennett, pendiri The New York Institute of the Humanities, merupakan konsekuensi dari pergeseran ke arah kapitalisme keuangan sebagai unsur primer dalam aktivitas ekonomi. Dalam 30 tahun terakhir, kata Sennett, “Aktivitas ekonomi menjadi lebih bersifat monokultur.” Perusahaan cenderung fokus pada pasar ketimbang pada bisnis intinya.
Orang kaya memburu keuntungan jangka pendek. Gagasan memperoleh manfaat melalui ikhtiar jangka panjang semakin tidak populer. Kapital dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Fleksibilitas ini jauh lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi mereka yang ada di puncak, namun menebarkan ketidakstabilan, kerentanan, dan ketidaksetaraan bagi mereka yang ada di bawah.
Di dalam apa yang diistilahkan oleh Sennett sebagai “flexible capitalism”, mayoritas pekerja kehilangan kesempatan untuk melihat kapasitasnya berkembang. (Sebuah poster dalam aksi Occupy Wall Street berbunyi: Wall Street steals our jobs, homes and futures). Pasar bebas telah melemahkan ikatan komunitas, menciptakan kevakuman moral, dan membuat masyarakat lebih rentan terhadap resesi.
Mendahului para ekonom sekarang, Karl Marx mengatakan kapitalisme sangat tidak stabil. Ketidakstabilan itu ada di dalam dirinya. George Soros, orang kaya yang menambang banyak uang dari sistem ini, mengakui cacat itu dikarenakan kapitalisme sangat memanjakan kapital finansial. Kapital ini bebas pergi ke tempat-tempat yang memberikan reward terbaik. “Sepanjang kapitalisme berjaya,” tulis Soros dalam The Crisis of Global Capitalism, “perburuan uang akan mengalahkan pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya.”
Kepentingan bersama (common interest) tidak menemukan eskpresinya di dalam perilaku pasar. Meminjam gagasan Adam Smith, korporasi tidak bertujuan menciptakan lapangan kerja; mereka memperkerjakan orang (sesedikit orang dan semurah mungkin) untuk mencetak keuntungan.
“Takutlah ketika orang lain serakah dan serakahlah ketika orang lain takut.” Frasa ini bukan berasal dari Gordon Gekko, melainkan Warren Buffet. (sbr foto: ocuppywallstreet.net) ***
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Di Musim Corona, Hati-hati Jangan Sampai Menghina
Selasa, 14 April 2020 05:33 WIB
Bila Jatuh, Melentinglah
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0